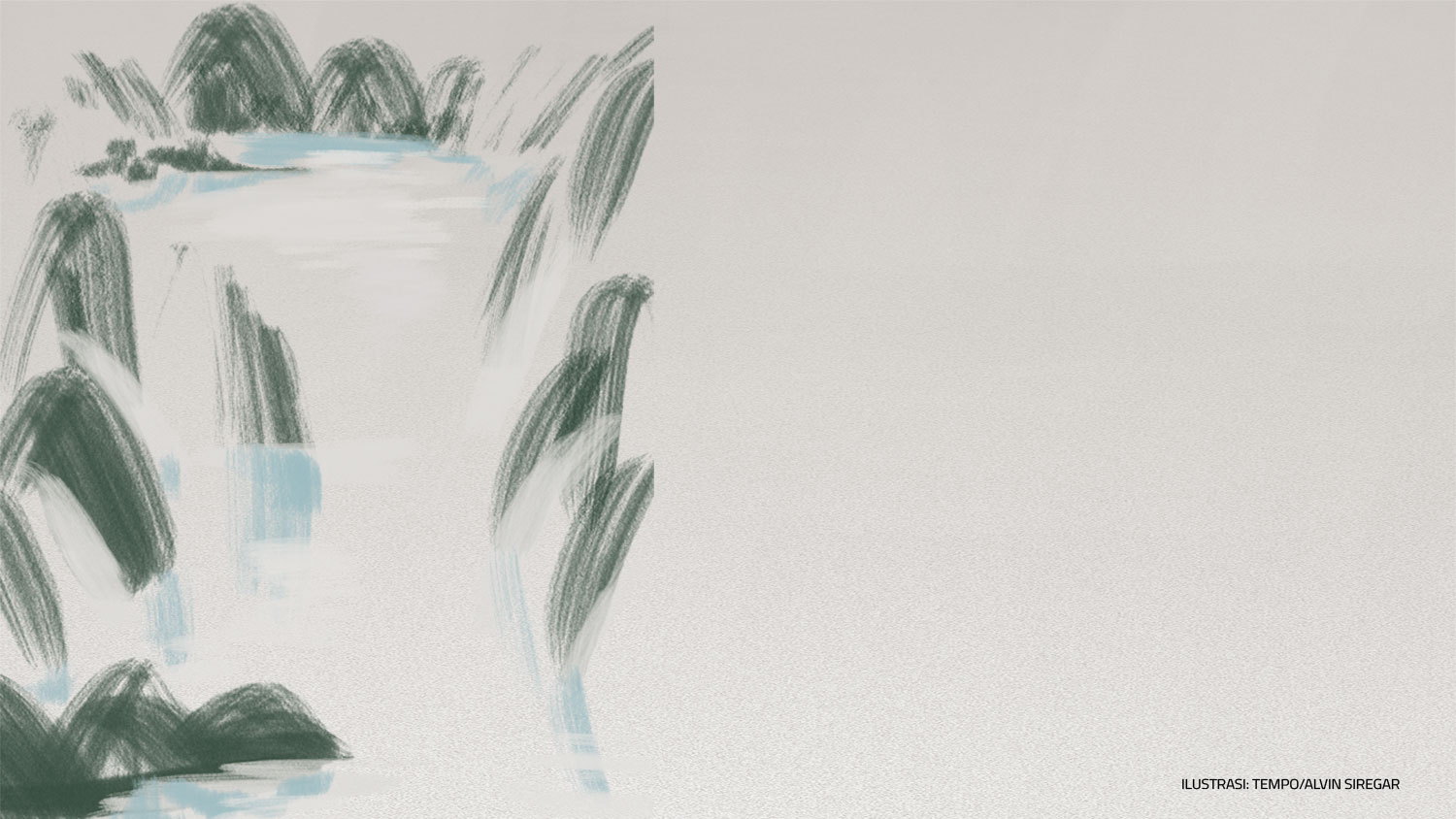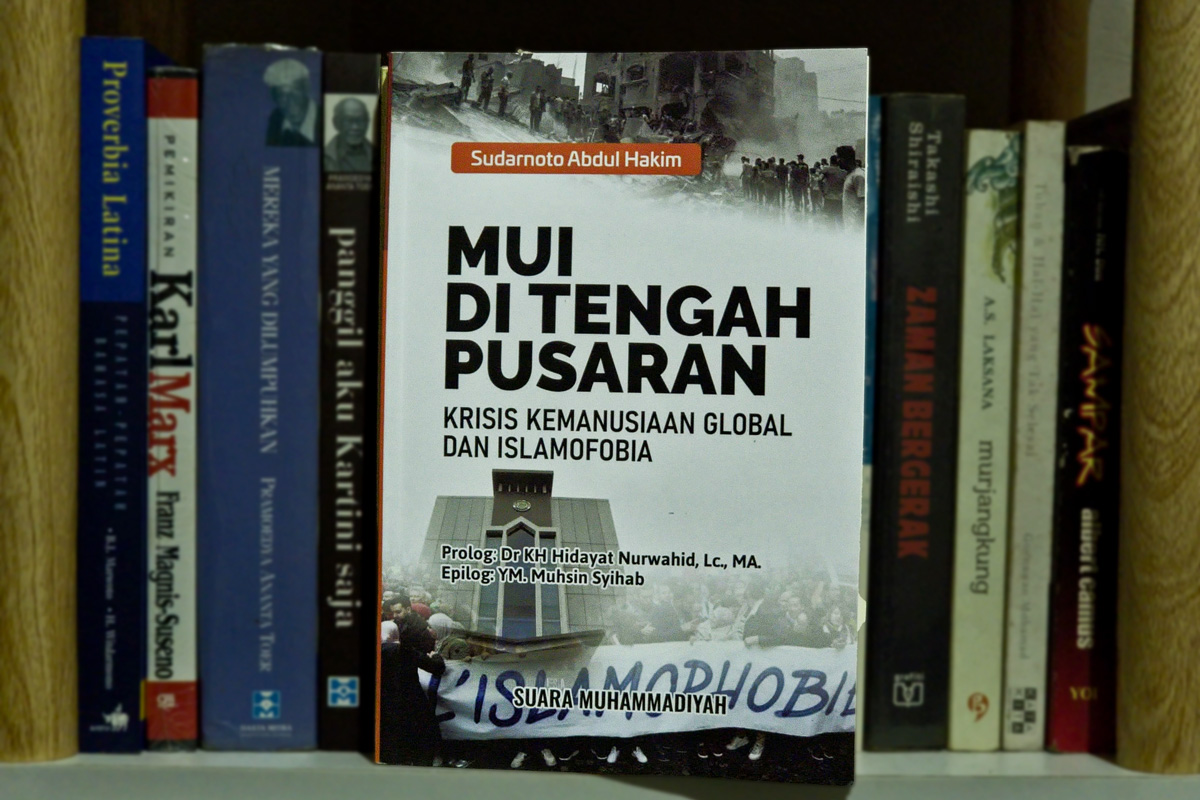HAMLET MENJELANG PEMILU
Teater Sae | | Naskah | : | Afrizal Malna |
| Sutradara | : | Busyra Q.Yoga |
| Tempat | : | Gedung Kesenian Jakarta |
| Waktu | : | 29-30 Mei 1999 |
|
Adakah Hamlet yang bukan pangeran Denmark, dan bukan tokoh rekaan Shakespeare? Teater (neo) Sae punya jawabannya. Dalam pertunjukan Hamlet Menjelang Pemilu, yang kali ini disutradarai oleh Busyra Q. Yoga, Hamlet versi Teater Sae tampil berbeda dengan karakter seorang pangeran peragu yang membayang dalam maskulinitas Lawrence Olivier, Kenneth Brannagh, atau Rendra. Hamlet dalam lakon Afrizal Malna ini lebih mengesankan kepincangan identitas sebuah generasi yang dibohongi. Generasi yang hidup dalam negara transisi, kerajaan yang hendak berubah menjadi republik, dengan pemilu yang direkayasa Raja Baru. Hamlet menyambutnya dengan caranya sendiri, membuat pemilu berlangsung dengan kegilaan. Di situ, Hamlet dicitrakan sebagai tokoh yang punya ketegasan sikap, yang tak hanyut melainkan melawan arus euforia massa. Kegilaan itu akhirnya gagal. Ia dibunuh oleh kekuasaan.
Ketegasan Hamlet di situ paradoksal dengan temperamennya yang lembek, feminin, dan gaya bicara seorang ABG (istilah masa kini untuk anak baru gede), bahkan kekanakan. Memasang Wahyu Priadi sebagai Hamlet, dengan akting yang payah dan artikulasi yang belepotan, merupakan kesembronoan yang fatal: karakter sentral lakon ini lenyap ditelan keluasan ruang. Apalagi dramaturgi naskah yang memang lemah tak diimbangi dengan sajian elemen artistik yang memadai.
Ini sangat disayangkan karena beberapa tahun lalu Teater Sae punya posisi cukup penting di panggung teater mutakhir Indonesia. Di bawah pengarahan Boedi S. Otong dan berdasar teks Afrizal Malna, kelompok ini berhasil menawarkan "konsep" yang unik. Komunikasi antarperan, atau yang lazim disebut dialog, dilonggarkan dari ketunggalan tema, menjadi sengkarut komentar, diucapkan dengan nada riuh oleh peran-peran yang tanpa identitas. Kata-kata dibebaskan dari bangunan makna yang utuh dan jelas. Pemain leluasa menghidupkan ruang dalam bloking tak lazim, dengan intensitas dan energi tubuh yang menciptakan kolase gerak dan memancarkan histeria. Perkakas rumah tangga dihadirkan sebagai properti yang menautkan dunia imajiner dengan dunia sehari-hari. Sebuah kombinasi estetis yang mengesankan kegilaan, lebih menyentakkan sensasi daripada logika.
Keunikan itu seakan tak membekas pada pertunjukan ini. Setelah beberapa tahun vakum dan sejak ditinggalkan sutradara Boedi S. Otong, Teater Sae seperti memulai dari titik nol. Padahal, sebagian pendukung pentas itu adalah orang-orang yang cukup berpengalaman, misalnya Afrizal Malna (penulis naskah dan juru bicara kelompok), Busyra Q. Yoga (sutradara), Sonny Sumarsono dan Iskandar Loedin (artistik), dan Aam Singalayu (musik). Pementasan itu sungguh jauh dari pencapaian artistik Teater Sae sebelumnya. Momen-momen puitis yang berkelindan secara asosiatif dalam penyutradaraan Boedi tak dapat ditemukan lagi. Ini seolah menegaskan bahwa Teater Sae, sebagaimana umumnya teater di Indonesia, masih menjadikan sutradara sebagai pusat orientasi kreatifnya.
Mereka sendiri seakan sadar atas kelemahannya. Melalui penjelasan dalam leaflet (yang terkesan apologis), mereka sengaja tak hendak mengulang estetika teater yang pernah digelutinya. Lantaran situasi sosial politik yang berubah oleh reformasi, mereka membutuhkan jawaban atas pertanyaan: "teater seperti apakah yang akan dihadapi?". Dan mereka memilih Hamlet untuk menjawabnya.
Namun, Hamlet yang mereka usung bukanlah karya William Shakespeare, juga bukan saduran atau tafsir atas jiwa bahasa simbolis, karakter, dan setting sosial budaya Kerajaan Denmark, yang tentu saja boleh diabaikan. Ini kisah yang dituliskan kembali. Nama Hamlet, juga beberapa nama tokoh lain dan kerangka dasar karya Shakespeare, sekadar dipinjam untuk mengingatkan bahwa mungkin ada sisi lain yang hidup dalam diri tokoh-tokoh tersebut. Selebihnya adalah upaya merefleksikan kegelisahan sebagai warga negara yang gamang menatap masa depan.
Repetisi dialog dan adegan yang kurang memedulikan efektivitas pencitraan menegaskan kemiskinan visi artistik penulis naskah dan sutradara. Keseluruhan lakon sekitar 90 menit itu tak lebih dari serentetan ungkapan verbal dan pengadeganan yang majal. Sebagai sebuah refleksi, daya gugahnya terasa lunglai ketika pada layar diproyeksikan fakta tentang pembantaian massa. Maka, seperti nasib Hamlet yang konyol, kegilaan yang hendak ditawarkan menjelang pemilu hanya menghasilkan sebuah kegagalan. Memprihatinkan.
Sitok Srengenge
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini