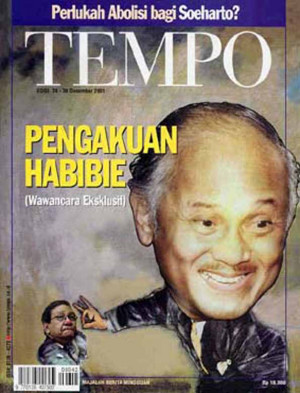Seandainya saja Joko Pinurbo adalah sebuah balon yang penuh sesak dengan ego, tahun 2001 akan menjadi tahun yang melambungkannya ke angkasa ruang. Bayangkan, di tahun 2001 itu Joko meraup tiga penghargaan sekaligus: dari Dewan Kesenian Jakarta untuk kumpulan puisinya Di Bawah Kibaran Sarung, kemudian ia juga dinyatakan sebagai pemenang SIH Award (lembaga yang dimotori pelukis Jeihan) untuk trilogi puisi Celana, dan dari Yayasan Lontar, juga untuk Celana. ”Terus terang, saya kaget,” kata Joko.
Dia kaget karena pada dasarnya dia adalah sosok yang pemalu, pendiam, dan sederhana dengan ego yang luar biasa di bawah tanah. Itulah sebabnya, karena Joko Pinurbo—tak seperti seniman Indonesia umumnya yang sibuk dengan ego dengan ukuran XL—bukan sebuah balon, dia tak melayang ke angkasa ruang, tapi hanya terpana karena ”tak menduga akan mendapat penghargaan Lontar”.
Maklum, menurut dia, kumpulan puisi Celana adalah, ”buku puisi saya yang pertama dan merupakan buku puisi percobaan,” tutur Joko dengan rendah hari. Lahir di Sukabumi, 11 Mei 1962, sebagai anak sulung dari lima bersaudara, Joko menulis sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Karena orang tuanya tak punya cukup uang untuk membelikannya kertas, Joko menulis di awang-awang dengan jarinya. Hobi membacanya hanya tersalur lewat koran bekas pembungkus yang dibawa ayahnya. Setelah duduk di bangku SMA Mertoyudan, kegemarannya membacanya bisa disalurkan dengan jauh lebih baik karena perpustakaan sekolahnya memiliki koleksi yang mengagumkan. Tergelitik oleh buku-buku yang dibacanya, Joko keranjingan menulis di majalah dinding sekolahnya. Akibatnya, rapornya jeblok.
Sebagai penyair, Joko menjelajahi banyak tema. Namun, tahun-tahun terakhir, ia banyak menggeluti obyek keseharian seperti celana, kamar mandi, atau bagian dari tubuh manusia. Semua diungkapkan dengan bahasa sederhana tapi tetap kaya imajinasi (juga parodi), yang akhirnya jadi ”merek dagangnya”. Apa sebetulnya alasan Joko memilih tema keseharian tersebut? ”Saya orang yang kuper (kurang pergaulan) karena sejak kecil sakit-sakitan,” kata Joko. Dari kesendiriannya itulah ia jadi makin peka dengan hal-hal kecil yang mungkin tak tak terlalu memancing minat penyair lainnya.
Lulusan IKIP Sanata Dharma Jurusan Pendidikan dan Sastra ini tak cuma menggeluti puisi. Bersama teman-temannya di Yogya, Joko menggerakkan Komunitas Senthong Seni Bangun Jiwo, yang kegiatannya antara lain menggelar festival selawat, wayang kampung, ketoprak, dan dongeng anak-anak. Penyair yang juga aktif di Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar—didirikan mendiang Y.B. Mangunwijaya—ini memiliki hasrat untuk membentuk acara kesenian yang bisa menjadi jembatan dialog antarmasyarakat lewat kesenian.
Meski pemalu, lelaki bertubuh tipis karena digerus penyakit di masa kecilnya ini memiliki bahasa yang witty, yang cerdas tanpa pretensi. Beberapa tahun silam, dia mempresentasikan sebuah makalah tentang puisi di Indonesia di Teater Utan Kayu, dan menyatakan, ”Begitu banyak puisi di dalam cerita pendek dan novel Indonesia yang jauh lebih baik dan puitis daripada di dalam ’puisi resmi’,” demikian ia bertutur santai. Dan ucapan itu memancing tawa gemuruh.
Kini, meskipun sudah mengantongi tiga hadiah, ayah dua anak yang sehari-hari bekerja sebagai editor bank naskah Grup Gramedia di Yogyakarta itu mengaku masih punya rasa ”iri”. Joko penasaran kenapa puisi tidak bisa menjaring puluhan ribu pembaca seperti novel Saman karya Ayu Utami, misalnya. ”Ini tantangan buat saya,” kata Joko, yang tahun 2002 ini akan menerbitkan kumpulan puisi Pacarkecilku.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini