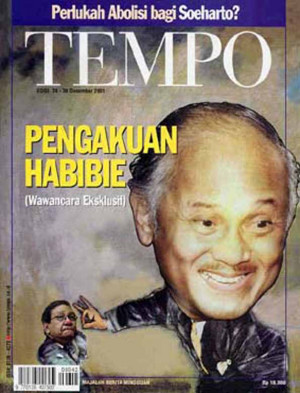AKADEMI Seni Rupa Indonesia. Tulisan dari kawat besi itu masih bertengger di sana, di atas pintu gerbang. Patung R.J. Katamsi, pendiri akademi di Yogyakarta itu, juga masih utuh di halamannya. Tapi di sekeliling patung itu kini hanya ada tanaman jagung, singkong, pisang, pepaya, dan bahkan kangkung yang tumbuh subur.
Tak ada yang bisa mengaitkan kebun palawija itu dengan sebuah ekspresi kesenian jika Anda tidak menyaksikan mural hitam-putih di dinding kusam bangunan bertingkat kampus yang tak terpakai itu. Ditorehkan dengan teknik realis, karya kolaborasi seni rupa publik itu menyajikan kritik sosial menyengat, dengan pembelaan kuat pada petani.
Dan jika Anda tidak bertemu dengan Tony Volentero, bekas Ketua Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi, sebuah kelompok perupa yang bermarkas di situ. Tony adalah salah satu pelukis mural tadi. Dia juga petani. "Kami ini pembela rakyat," katanya, "Kami pembela petani, maka kami harus pula melakukan apa yang dilakukan para petani."
Taring Padi adalah salah satu fenomena seni rupa di paruh akhir 1990-an. Sebentar setelah Orde Baru jatuh, pada 21 Desember 1998, sejumlah mahasiswa Institut Seni Indonesia di Yogyakarta mendirikan lembaga itu. Mencipta karya secara kolektif, mereka mengusung "ideologi kesenian bercorak demokrasi kerakyatan." Persisnya mereka punya tujuan "mengembangkan seni dan budaya lokal dengan orientasi kerakyatan yang digali dari kebutuhan rakyat."
Dalam praktek, mereka menggabungkan seni rupa dengan aktivisme politik: menyisihkan hasil penjualan karya mereka untuk membiayai unjuk rasa memperjuangkan hak-hak petani, persamaan gender, kampanye perdamaian, dan menolak militerisme. Bersama sebuah organisasi lain, Aliansi Petani, mereka juga pernah mengampanyekan dihentikannya penggunaan pestisida serta pupuk kimia.
Pada awalnya, mereka bertekad untuk berkarya secara kolektif, menjunjung kebersamaan, dan tidak mengedepankan sikap materialistis. Tapi terbukti itu tidak mudah.
Beberapa anggota Taring Padi kini menggelar pameran di galeri-galeri komersial Jakarta atas nama sendiri-sendiri. Menurut Hestu Ardianto, koordinator badan penerbitan lembaga itu, hanya 10 persen dari hasil penjualan karya pribadi itu yang masuk ke kas organisasi. Setelah dipotong 30-40 persen oleh pemilik galeri, sisanya menjadi milik anggota yang berpameran.
Taring Padi tidak sendirian gagal menegakkan benang basah semangat kolektivisme di tengah gerusan kapitalisme individualistis. Kelompok perupa lain dari institut seni yang sama di Yogyakarta, bernama Apotik Komik, membentur tembok serupa.
Apotik Komik didirikan oleh 12 perupa jurusan seni grafis setahun sebelum Taring Padi. Mereka tidak berpretensi mengusung tema sosialistis. Mereka hanya mengerjakan karya bersama-sama: menggelar seni rupa publik dengan nada eksperimental.
"Tujuan kami bukan untuk mencari uang, tapi menjadi wadah kolaborasi seni yang menyegarkan," kata Samuel Indratma, salah satu pendirinya. Mengambil nama Apotik Komik, mereka ingin menyembuhkan berbagai penyakit publik. Pada satu kesempatan, misalnya, mereka menggambari dinding sepanjang 200 meter yang menghadap Maliboro, menjadikannya santapan segar bagi orang yang lalu-lalang di jalan terkenal Kota Yogyakarta itu.
Tapi bahkan Samuel kini mengakui Apotik Komik sendiri tengah "meriang". Dalam dua tahun terakhir, kelompok itu absen menggelar karya kolaborasinya. Anggotanya masing-masing sibuk berkesenian secara individual, yang ternyata lebih menjanjikan penghasilan. Karya mural yang kini digelar di tembok rumah kontrakan Samuel pun bukan lagi karya para perupa Apotik Komik.
Beruntung Apotik Komik tak menanggung beban misi seberat Taring Padi. Hestu Ardianto mengakui bahwa semangat kolektif telah mulai luntur dalam kelompoknya dan imbas hasrat kapitalistis mulai terasa. Tapi, "Pada dasarnya kami tidak pernah berpaling dari idealisme Taring Padi," katanya, "Katakanlah ini strategi kapitalisme melawan kapitalisme."
Mudah mengatakannya. Secara perlahan selera komersial galeri yang begitu dominan tak bisa dicegah mengubah tema-tema kerakyatan para anggota Taring Padi menjadi sekadar bentuk glamor dari romantisisme kerakyatan. Dan sekaligus melucuti fungsinya sebagai alat perjuangan rakyat sebagaimana diinginkan pada awalnya.
Tapi apa boleh buat. Seperti telah ditunjukkan oleh Djoko Pekik, romantisasi kehidupan rakyat jelata memang bisa sangat mahal harganya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini