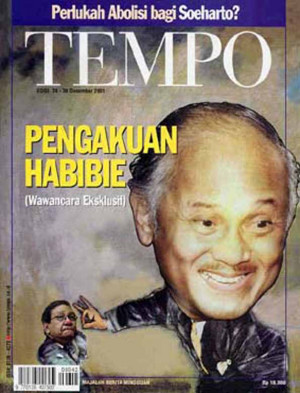HERI Dono adalah monster yang memukau. Melalui moncong hewan-hewan digital (tapi juga purba), ia menyihir kita dengan teror sekaligus humor yang ganjil. Heri Dono adalah tukang sulap yang memakai ilmu sihir sederhana, tapi hasilnya mengesankan.
Di tangannya, barang-barang rongsokan yang dibeli secara kiloan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, berubah wujud menjadi monster-monster yang kesurupan, primitif, dan me-ledek masyarakat modern. Kritikannya, meskipun tajam, selalu dibarengi dengan optimisme dan kemampuan menertawai diri sendiri.
Dunia bagi Heri Dono agaknya merupakan wilayah fantasi yang terus berubah wujud, menjelma dan menyamar, yang memungkinkan setan dan malaikat saling berganti peran. Dunia tempat sinar kejahatan dan kebaikan bisa terus bertukar posisi.
Lahir di Jakarta sebagai anak kota, ia tak punya tradisi kampung. Heri Dono mengaku tak punya ikatan "religius" dengan pakem tradisional. Dengan bekal itu, ia merasa merdeka mengawinkan elemen-elemen tradisional. Hasilnya adalah gamelan dengan keyboard, wayang yang diracik dengan campuran seni pertunjukan modern.
Ia memakai dinamo bekas mainan anak-anak untuk membuat gerak. Dalam pamerannya di Jepang, sayap-sayap malaikat dalam Angles Caught On a Trap malah cuma digetarkan semburan angin penyejuk udara (AC). Heri memang tak punya niat membuat karya dengan bobot teknologi. Ia memanfaatkan tukang reparasi televisi di Yogya untuk membantunya menciptakan hantu-hantu digital yang primitif. Dengan teknologi kampung ini, karya Heri mendapat tempat bersanding dengan karya seni rupa teknologi tinggi di Museum Intercommunication Center di Tokyo.
Sulit dibantah, Heri Dono, 41 tahun, serta-merta menjadi ikon seni rupa kontemporer Indonesia. Bukan cuma di Tokyo, karyanya menjadi koleksi museum terkenal, dari Brisbane, Singapura, hingga Swiss. Prince Claus Foundation di Belanda memberikan penghargaan tiga tahun lalu. Buku Fresh Cream, terbitan Paidhon, menempatkan Heri Dono sebagai salah satu dari 100 seniman kontemporer kondang dunia tahun ini.
Meskipun namanya mulai menjagat, ia tetap tinggal di rumah warisan kakeknya di sebuah gang di Yogya. Berbagai pernik hasil karyanya tergantung begitu saja di dinding. Sehari-hari ia memakai kaus, kain sarung, atau celana kombor. Ke mana-mana ia mencangklong tas kain dan mengayuh sepeda tua. "Kesederhanaan adalah kemewahan. Saya jadi merdeka," katanya.
Pada awalnya, Heri Dono merupakan pelukis di atas kanvas. Tapi, ketika dunia seni lukis sedang digandrungi pasar, sedang dikejar-kejar uang, ia justru melarikan diri. Ia tidak tertarik dengan komersialisasi. Ia melukis sebagai "surat pribadi", bukan untuk kepentingan kolektor.
Seperti ketidakpeduliannya dengan "komersialisasi", Heri Dono tidak merasa risau dengan penjiplakan. Ia mengaku tak punya klaim pada "heridonoism" (yang dengan guyon sering ia pelesetakan menjadi hedonism), yang kini mewabah, sebagai gayanya sendiri. Ia tak bisa melarang orang mengekspresikan gaya serupa. "Ini seperti patung Bali," katanya santai, "milik semua orang." Ia mengaku dipengaruhi beberapa pelukis Eropa, wayang beber, dan lukisan kaca Cirebon….
Kalau sekarang masih melukis, itu karena ia memerlukan ruang pribadi. Selain itu, ia harus hidup agar bisa terus berkreasi. Ia mengaku hanya membuat 20-30 lukisan setahun, yang sebagian besar dikoleksi "kolektor kelas dua" di luar negeri.
Dari pabrik duit ini, Heri Dono bisa membayar tukang becak, penggali kuburan, paranormal, mereka yang bukan berasal komunitas seni, untuk tampil berkesenian. "Uang tak harus dikutuk, sepanjang dipakai untuk sesuatu yang positif," katanya kepada kurator internasional kelahiran Swiss, Hans Ulrich Obrist, di Helsinki, tahun lalu.
Tapi, celakanya, karya-karya instalasinya kini juga sudah mulai laris, mulai digila-gilai uang. "Kalau begitu," katanya, "saya harus mencari tempat lain."
R. Fadjri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini