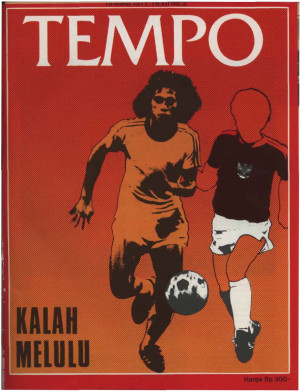CALON Arang versi Bali tidak pernah menyelesaikan soal siapa
yang menang. Cerita yang berkisar antara tokoh Calon Arang dan
Empu Barada ini - di zaman pemerintahan Erlangga - selalu habis
dengan menggantung. Pertunjukan berhenti tatkala peperangan
masih berlangsung. Ini agaknya semacam petuah moral, agar setiap
penonton ikut aktif melanjutkan sisa pertempuran dalam diri
mereka.
Maka tampillah penata tari Wayan Diya, di Teater Arena TIM -
4-5-6 Maret - dengan drama-tari Duta Buta. Para pemain telah
menabuh gamelan sebelum gong resmi dipukul. Di tembok belakang
arena, tampak menara bambu yang tinggi, di puncaknya terdapat
bilik yang tertutup korden (langse). Daun daun hijau yang segar
- seperti pisang -- dipasang di pintu dan di kaki menara,
menimbulkan suasana desa di bawah langit terbuka.
S 1000
Lakon mengisahkan saat tatkala Ki Patih Madri diutus sebagai
duta, untuk membatalkan lamaran Erlangga kepada Ratna Manggali,
puteri ratu Dirah. Calon Arang - ratu Dirah tersebut tetu saja
jadi mot-motan. Madri kemudian dianiaya dalam perjalanan pulang.
Patih jadi buta, sehingga rakyat Erlangga penasaran. Dengan
pimpinan Ki Patih Taskara Maguna, terjadilah pertarungan seru
antara pihak Erlangga dengan Dirah. Yang belakangan ini dipimpin
oleh Ni Rarung, murid utama Dirah. Di tengah-tengah pertempuran,
lampu mendadak padam. Lalu di pojok kanan arena TIM -- dari
balik kaca pengamat di tembok atas -- muncul topeng kepala Dirah
yang biasa dijadikan oleh-oleh turis yang datang ke Bali. Di
bawahnya tertulis: $ 1000.
Dengan tetabuhan yang terdengar klasik, Diya berusaha memberi
banyak unsur tari dalam tontonannya kali ini. Lebih banyak dari
pertunjukan sebelumnya. Ia pun telah mengerahkan isteri dan
adiknya - yang terbilang penari-penari tangguh -- untuk memberi
andil. Juga ayahnya sendiri, seorang penabuh terompong yang tak
asing namanya di studio RRI Denpasar. Ditambah dengan Roda,
Kompyang, Sadra serta bebera mahasiswa/siswi IPKJ. Dengan kata
lain, potensi sebenarnya cukup. Herannya pertunjukan belum
mengulang, setidak-tidaknya, prestasi lakon Cupak dari grup Rasa
Dhavani ini di tahun 1975.
Tidak sedikit ide-ide segar sempat meletup. Tetapi tak mendapat
penyaluran yang tuntas sehingga tinggal menggantung, seakan
bagian-bagian lepas. Misalnya ide untuk membuat set panggung
yang tinggi dan ide untuk menggantung kepala Dirah sebagai benda
oleh-oleh. Apalagi ide memainkan anyaman-anyaman bambu sebagai
level - di atasnya bergulatan pemain-pemain -- dalam adegan
pertempuran. Tontonan ini secara visuil kaya dan dinamis. Pada
bagian-bagian tertentu ada peluang bagi para penari buat
memperlihatkan kebolehan. Sayang sekali perekat elemen-elemen
itu tidak dikerjakan selesai. Lebih menampakkan kebimbangan
Diya: atau dia ingin menggarap secara konvensionil cerita klasik
itu, atau mengeksploitirnya sebagai ekspresi aman sebagaimana
dikerjakan Sardono.
Sebagai penari, dalam memainkan Dirah Wayan tampak unggul. Juga
kita sempat mendengar improvisasi kendang yang unik, kuat dan
mempesona. Sayangnya tidak didukung oleh banyak pemain pria yang
kelihatan bukan penari-penari baik. Meskipun mereka bergerak
dalam barisan yang tidak menuntut kejempolan tarian individuil,
toh mereka sudah merusak bau sederhana yang menjadi temperamen
pokok penampilan Diya. Banyak yang cenderung terlalu dramatis
dan emosionil, pada adegan-adegan yang sebetulnya lebih
memerlukan suasana rituil dan magis.
Barangkali kejadiannya akan lain, seandainya secara merata
pelaku pertunjukan punya dasar tari yang kuat. Juga dasar ikatan
sebagai satu grup tetap, sehingga tidak terjadi keanekaan
takaran dalam gebrakan. Kita masih percaya bahwa Rasa Dhavani
berada di tanan yang baik. Ia punya peluang besar sekali untuk
bisa komunikatif -- karena adanya tari dan gamelan tradisionil
sebagai penopang. Juga banyaknya kemungkinan yang masih bisa
mencuat dari topeng-topeng yang mereka miliki. Tinggal menunggu
dimainkan oleh orang yang tepat.
Masa jedah, yang dilaksanakan dengan memunculkan topeng-topeng
satu persatu (sejak pertunjukan-pertunjukan sebelumnya) bisa
menjadi sesuatu yang khas grup ini. Tahun lalu misalnya, penari
Sardono ikut menyumbang memainkan sebuah topeng dalam adegan ini
dengan kocak. Sedang dalam tontonan Cupak dahulu, ada Made Netra
dan Soegeng yang menghidupkan bagian tersebut. Sekarang babak
tersebut gagal karena lelucon-lelucon yang hendak disuguhkan
dikerjakan ragu-ragu. Padahal bila adegan ini hidup, segala
kekurangan sebelumnya akan bisa terangkat.
Setidak-tidaknya adegan-adegan yang sering disebut bebonresan
atau bebagrigan itu, merupakan inti teater Bali yang mengajak
penonton setiap kali sadar pada lingkungan mereka. Juga pada
hakikat tontonan sebagai tontonan, meskipun merupakan bagian
kehidupan yang dikerjakan dengan tak kurang bersungguh-sungguh
-- dari misalnya bekerja atau sembahyang.
Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini