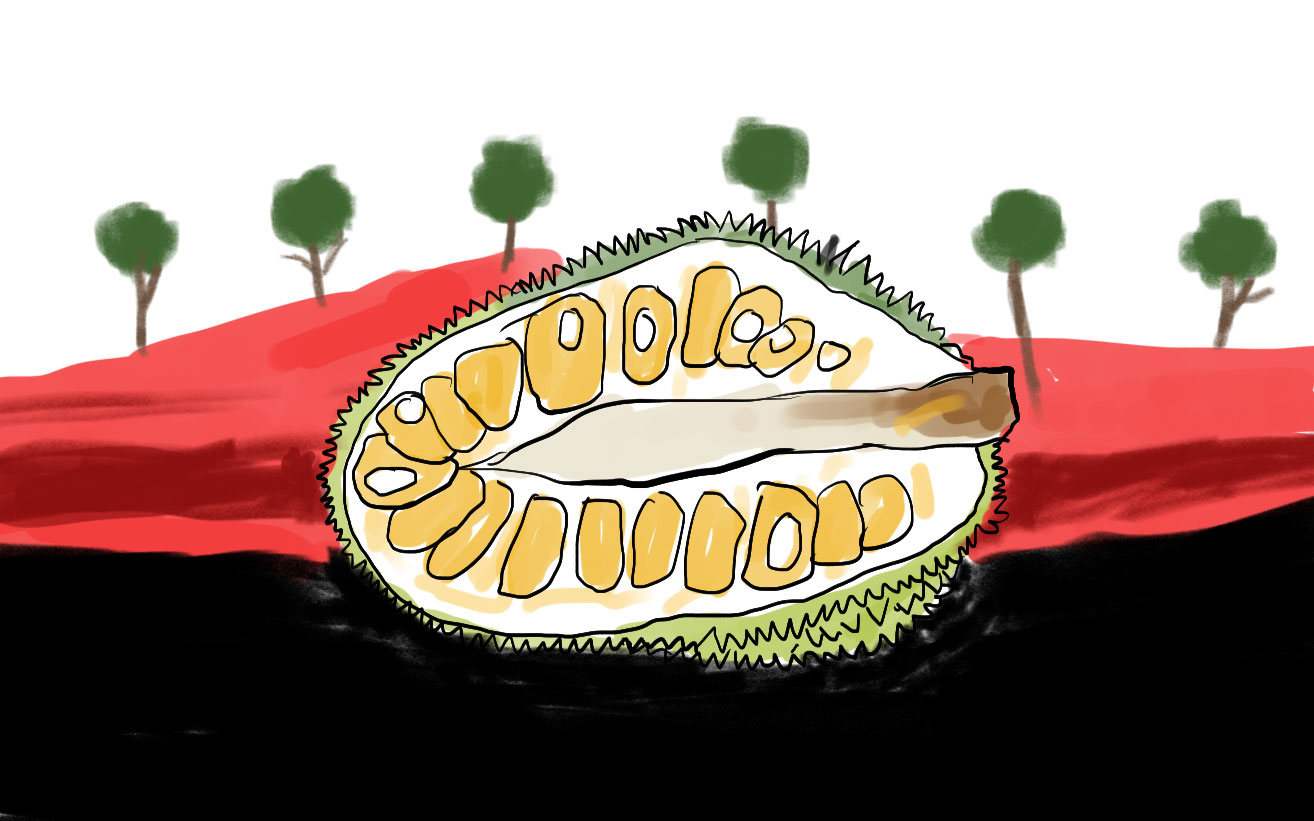Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Novan Leany
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KATA SUKU BALIK
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

bersama Kai Medan
Maka, jangan panggil aku Balik
jikalau semua tak kembali padamu,
Suara Tuhankah itu?
yang kau tetak-tetak di batu Bedak
sebab, ada air mata tumpah
ke bunga kecemasan
dalam kepala kami
yang satu-persatu menetas
persis Kencana Ungu
Apalah lagi yang hendak
kau rampas, tuan?
Entah, itu suara siapa
bahkan langit dengan tujuh bintang
tak juga memberi jawaban
atas semua
Konon, ini sungai Sepaku masih melingkari
pinggang kampung persis akar Bahar
di lingkar lengan pendatang
dari tanah Jawa, dan tidak
dapat ia mengerti sebuah batas;
antara kepala naga dan ekornya
atau kampung dan silsilah
“Kami tak pernah dikutuk jadi rantau,
namun kehidupan tidak berubah
- melulu mengungsi,” seorang melantang
dari pusar tambang dan sawit
yang merentang ke punuk-punuk
Jayakarsa dan Mulung
(o, inikah jerit kuasa dalam tanah,
bukan musim kawin para Payau)
Cuma jalur panjang,
dengan ingatan yang lindap
dan seorang Kai berjalan
memikul Nipah, tertatih
seperti burung ingin menitipkan
letihnya pada rumah
yang sesungguhnya tiada lagi
Pernah, sesekali ia berhenti
menyeru nama seorang bocah
yang tak aku kenali
dan ia perlihatkan sebuah luka
bekas gigitan Buaya di antara dua paha
lalu berkata, ”Nak, moyang kita muak
tunggul-tunggul ladang telah tumbang
makam ibu kita ditambang,
lantas jangan panggil ia Balik
jika semua tak kembali,”
2023
SANGGAR TIWADAK
Vanili yang kerap tumpah ke selendang tenunmu
ialah janji kemenangan atas sumpah moyangku
membekas seperti darah beku di lipatan-lipatan lehermu
ibarat jembatan Lambung Mangkurat memenggal silsilah
kampung halaman kita, tapi wangimu, kerap mengekalkan
manisnya rindu para perantau yang menyembunyikan
perih lambungnya
Acil itu tahu, aku tak hendak jadi nyiur lagi
yang tumbuh sebagai pohon tua di halaman belakang rumah
bukan kepunyaan kita, sebab di atas segala
punggung tanah yang retak kita dikutuk
jadi Cempedak, rasa getah dan manis
buah matang yang kerap gugur,
sebagai kecemasan
Tapi acil,
kami bukan pohon Nangka
yang kerap ditebang dan tumbang
padahal, ini Gambus mulai sumbang
dan ringkik Payau hilang maknanya
Warta tentang kematian
masih berserakan
dan belum sehalus tepung terigu
yang mengadon sanggar
Tiwadak, dan Molen
di Gang Masjid
Hingga kelak, biji-biji yang dikau pisahkan diam-diam
sebelum merendam Mandai adalah butiran rasa malu
kita pada Tuhan, Tuhan yang kita pisahkan
dari rinjing, piring kayu, dan nampan,
“Nah, jangan ikam buang bijinya ngul,
itu kawa dimakan,” ujar seorang dalam Banjar,
ia harap dapat tinggal sejajar
Seperti menuai gara ke ujung lidahmu
yang telah lama lahir dari rasa hambar
kau tercekat, bahwa garis-garis kening
yang menyempit dari renyitmu
akan lebih terkenang sebagai
manis masa lalu yang hanya singgah
dari masam yang bertelagah
bagai Mempelam,
yang kita iris tipis-tipis
di cobek batu untuk
makan siang para Datuk
Maka, tengoklah bahwa aku dan kau
cuma orang-orang kota yang tersenyum perih
dalam parit-parit ingatan yang selalu kita keruk
setiap minggu pagi; bangkai kucing,
setangkup dialog asing, dan lumut-lumut
kerap menumpangkan hijaunya
bagi tembok-tembok di ruas jari Masjid
dengan pamflet Pemilu tahun lalu
Duhai sebuah kota yang setia
menyediakan tempat tinggal
bagi orang-orang yang
sekedar mengadu lapar
dan kita hanyalah Pingai,
tersentak dan berlepasan
tak kembali lagi
pada kusutnya kabel listrik
dan layang-layang
Nah, janganlah engkau buang, sebab,aku mau jadi biji tiwadak
yang kau pisahkan diam-diam menunggu seorang perantau
menawak ke punggung tanah, agar tumbuh ia jadi cabang-cabang muara,
meliang ia ke kutai, ke sepaku, ke makassar ke banjar
dan jika sampai pada simpang dari situ semua bermula tubuhku
akan kembali ke hambar lidah, meski harapan telah mati rasa
persis keram yang kebas tak berasa di lutut kita
karena lelah mengejar malam-malam sunyi serupa hitam matamu,
selubung masa silam yang paling pangkal sebagai silsilah
kampung halaman janji atas sumpah kemenangan
moyangmu,
atau moyang kepunyaanku?
2023
Novan Leany, kelahiran Samarinda, 28 November 1997, sedang berproses untuk persiapan buku antologi puisi keduanya. Dosen filsafat dan hermeunetika di salah satu kampus negeri di Samarinda ini bergiat di komunitas TerAksara dan Naladwipa for Social and Cultural Studies.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo