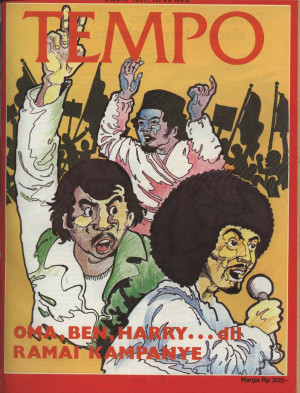SANDIWARA Putu Wijaya, Hum Pim Pah (Teater Tertutup TIM, 22-26
Maret), padat pengunjung. Pihak penjualan karcis bahkan
menunjukkan bahwa jumlah penonton berangsur menaik: makin hari
semakin besar, dan ini biasa ditandai sebagai akibat "kampanye
lisan" sesama mereka. Banyak orang berkata: "Saya suka sandiwara
Putu yang ini. Ceritanya bagus, dan lebih jelas dari yang
dulu-dulu".
Jadi itulah faktor utama kenapa tontonan itu "bagus". Dan bila
itu ukurannya, maka si pengarang sendiri boleh bersedih. Sebab
setelah gebrakan demi gebrakan ia lakukan di pentas, yang
semuanya mengukuhkan kehadiran teater sebagai tontonan yang
tidak pertama kali tergantung pada hadirnya cerita, orang toh
rupanya masih lebih mudah mengukur baik-buruk pementasan dari
soal 'jelas-tak jelas'.
Padahal Hum Pim Pah boleh dinilai sebagai "bukan apa-apanya"
dibanding tontonan-tontonan Putu sebelumnya. Plot yang bagus
saja belum lagi jaminan. Juga naskah yang bagus - yang seperti
halnya naskah-naskah Putu lainnya, telah merebut kejuaraan
sayembara Dewan Kesenian Jakarta. Soalnya: pementasan telah
begitu banyak merugikan naskah.
Banyak kalimat berpanjang-panjang, misalnya, yang dalam naskah
menyiratkan unsur main-main, menjadi begitu "heroik". Sekaligus
terasa bertele lantaran tunggal nada. Dan di samping pertunjukan
dengan demikian didominir omongan -- sesuatu yang dibenci
pengarang ini sendiri - Putu di sini tiba-tiba seperti muncul
sebagai seorang "pejuang".
Moral Pelacur
Perjuangan itu, sangat menarik, menyangkut moral. Ini antara
lain moral seorang pelacur (tokoh kesayangan Putu) yang dengan
keras namun tulus mencintai seorang bajingan (yang bahkan tidak
peduli siapa nama perempuan itu). Para petugas, yang memburu
dedengkot ini, berhadapan dengan sang ayah yang dihormati karena
jasa-jasanya sebagai pemimpin revolusi dahulu. Si ayah, yang
pura-pura yakin anaknya sudah mati (sebab begitulah disebarkan
oleh kawan-kawannya untuk memisahkannya dari anaknya) sekarang
menghadapi tugas untuk mengambil tindakan terhadap sang anak.
Kawan-kawannya semasa revolusi, atasnama keagungan generasi yang
lampau, memaksa dia untuk mengambil tugas itu. Tetapi ia lumpuh.
Dan makin lama makin jelaslah posisi pelacur yang dijatuhi
sumpah serapah segala pihak (ia misalnya dianggap menipu sang
ayah, karena sementara ia menolong orang tua itu dalam
pengobatan dan perawatan, ia mengadakan pertemuan-pertemuan
dengan dedengkot di gudang, sebuah "tempat yang bersejarah").
Tetapi ia juga yang dari semula melindungi dan berusaha agar
cowoknya melarikan diri - meskipun akhirnya terlambat. Dan ia
juga yang "menelanjangi" tokoh-tokoh lain, tentang betapa
palsunya apa yang mereka aku sebagai tanggungjawab atau
semacamnya. (Ayah dedengkot sendiri, setelah tak kuasa menembak
anaknya, dan sebelum dihukum mati atasnama "kebesaran generasi"
mengaku bahwa ia sebenarnya pengecut dan bahwa lingkungan
sekelilingnyalah yang memaksa dia menjadi "lambang").
Memang ada semacam penyampaian pesan dari Putu Wijaya. Kali ini
Putu menjabarkan dalam kalimat-kalimat, hal-hal yang selama ini
sebenarnya mendasari karya-karyanya yang "tanpa ide" itu - yakni
sikap yang cenderung nihilistis, yang sering muncul dalam
perwujudan main-main walau betapapun kasarnya. Hanya, tak pernah
terbayangkan bahwa sebuah pementasan Putu akan berkhotbah
seperti malam itu.
Sentimentalitas
Materi pemain memang sangat menentukan. Yang disebut pemain
mentah ialah, yang bisa bersuara dengan jelas, bisa bergerak
tanpa canggung, namun sesuatu dalam umur dan pengalamannya
menghalangi dia untuk menyentuh hal-hal lebih dalam dari sekedar
jalan kalimat. Hal-hal lebih esensiil seperti ironi misalnya,
termasuk yang sukar diungkapkan kegetiran biasanya akan muncul
tak lebih dari sentimentalitas. Sutradara, Putu Wyaya, berbuat
dosa karena ketidak-mampuannya menangani hal-hal ini, istimewa
pada pemegang peran kunci: si pelacur (Puspita). Demikianlah, di
samping humor dan kekonyolan banyak sekali yang hilang,
kalimat-kalimat panjang tak lebih dari hanya pidato seorang
partisan --yang diungkapkan dengan nada tinggi.
Dan nada tinggi, yang mewarnai seluruh pementasan, menunjukkan
betapa para pemain yang selama ini hanya dipersiapkan memerankan
"tokoh-tokoh" tanpa omong dalam karya-karya Putu terdahulu,
dihadapkan untuk 'bermain' satu per satu - tanpa ditolong oleh
keributan panggung model Putu. Mereka misalnya harus berakting
wajar, dan bersuara wajar. Dan celakanya justru suara wajar ini
dalam akting sungguh-sungguh -- yang selama ini belum merupakan
bagian dari kesibukan teater Putu Wijaya.
Tragis, karena begitu pemain disuruh bersuara, ia kembali ke
"pola" drama drama yang selama ini secara keliru disebut
"realistis": pola yang bergelombang, pola melodrama, pola pidato
- alhasil pola palsu seperti yang bisa dijumpai dalam film-film
Indonesia. Sungguh anak-anak TIM itu memang sudah dirusak oleh
"mazhab akademis" semacam itu. Kekurangan akting dan dialog
itulah yang bisa menguatkan alasan Putu untuk tidak mementaskan
naskalnya ini dengan cara "biasa".
Kok Fanatik Amat
Keributan panggung yang diciptakannya, yang dari-satu segi
menunjukkan bahwa ia "lebih berbobot dari pemainnya", memang
berhasil memunculkan sebuah tontonan yang riuh, total dan utuh
dalam suasana, berwarna coklat kotor, dan tidak menampakkan
dengan jelas pihak-pihak maupun alur-alur. Kecuali kalau orang
lebih dulu membaca semacam sinopsis dalam folder, sesungguhnya
mereka tak tahu benar, misalnya: apa beda 'kawan-kawan' dan
'petugas'. Apakah pelacur itu mati ketika ditembak, kemudian
bicara sebagai roh, atau tidak ditembak - atau ditembak tetapi
tidak mati. Atau mengapa ayah itu harus membunuh anaknya sendiri
-- kok fanatik amat.
Bahkan fokus di situ terasa sengaja digosok-gosok Putu biar
tidak kentara. Tokoh dedengkot misalnya, tidak menonjol
kepribadiannya yang liat, yang ditunjukkan dengan cara tidak
ngomong dari awal sampai akhir. Pertemuannya dengan pelacur yang
bisa mengharukan, tidak diberi perhatian oleh sutradara yang
memang takut sekali jatuh cengeng. Ketulusan yang unik dari
pelacur itu sendiri tak muncul, kecuali sebuah cinta yang banyak
omong dan puber. Sedang dedengkot sendiri, anehnya, hi lang
seluruh kejantanannya: ia malah, bagai anak aleman, main-main
bergantung-gantung dengan nyentrik.
Sekiranya tidak ada pemain seperti Budhiman (kepala petugas),
maka tak ada apa-apa yang tinggal dari awak panggung untuk
dinilai. Kecuali bahwa mereka telah membantu Putu Wijaya untuk
menghadirkan sebuah drama verbal baru, dari jenis yang tidak
konvensionil.
Syu'bah Asa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini