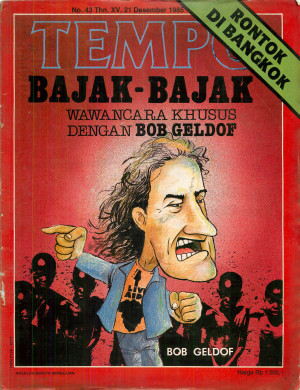RENDRA di pentas kembali. Ia melangkah teratur ke tengah panggung, disoroti lampu besar, dengan tangan kanan terkepal dan teracung ke atas. Kepalanya tegak, parasnya semisenyum. Seperti marionet. Rambutnya rapi tebal menggelombang, tubuhnya tetap ramping (meskipun sedikit lebih gemuk), dalam celana ketat yang dipasangi mikropon kecil di pinggangnya. "Burung merak," seru pembawa acara Taman Ismail Marzuki (TIM) mengantar penampilan penyair yang telah beberapa tahun dikabarkan dilarang muncul itu. Dan sekitar 1.000 penonton yang memadati gedung "Graha Bhakti Budaya" bertepuk riuh. Rendra, dalam usia 50, tapi tampak lebih muda belasan tahun, memang seperti tak lekang. Ia masih memikat selama sekitar dua jam, membaca sajak terus-menerus. Kadang ia tenang, hanya mempermainkan suara aktornya. Kadang - dalam gaya yang teatral - melakukan gerak yang lebih: misalnya menjatuhkan tubuh ke lantai. Puisi memang telah jadi seni pertunjukan. Dan di sini Rendra seorang maestro, sejak ia mengawali penampilannya dengan suara jelas dan kuat, "Assalamualaikum . . .". Di awal itu Rendra juga meminta maaf. Khususnya kepada para peminat yang tak kebagian karcis dan berjubel di luar gedung. Orang memang berduyun - antara lain tentu karena orang selalu ingin tahu tentang segala hal yang pernah, atau sedang, dilarang. Dan di halaman parkir TIM yang penuh mobil itu pun muncul para catut, mengikuti hukum ekonomi bebas. Mereka menawarkan karcis dengan tarif yang dikibarkan sampai Rp 15.000. Rendra sendiri kesal betul dengan pencatutan itu. Ia, seperti dikatakannya, telah minta agar karcis dihargakan Rp 3.000, lebih murah dari biasanya, yakni sampai Rp 5.000. Toh, dengan harga itu, dengan karcis yang dicetak 2.000 lembar untuk dua malam pertunjukan di awal pekan lalu itu, TIM beroleh laba. Menurut Hardi, pelukis yang memimpin Badan Pengelola Pertunjukan Pameran di TIM, hasil yang didapat dari acara Rendra sampai Rp 8 juta. Perincian: Rp 6 juta dari karcis, Rp 2 juta dari sponsor, yakni PT Mitra Adisankha, yang, menurut presiden direkturnya, J. Handojo, bergerak dalam "bidang jasa yang menyangkut komunikasi". Rendra, yang tak percaya bahwa penyair harus hidup melarat, beroleh Rp 3 juta. Dilihat dari jerih payahnya bertahun-tahun menulis puisi dan mengalami perkara sulit sehubungan dengan itu, juga dilihat dari kemasyhurannya, jumlah itu bisa dibilang kecil. Apalagi, seperti dikatakan Rendra, untuk acara baca puisi itu ia perlu "latihan dengan kaset dan video". Tapi ia sudah telanjur minta Rp 3 juta, dan ia rela: "Biarlah uang yang masuk TIM itu untuk menyelenggarakan pertunjukan lainnya," katanya. Ia memang ingin tetap tak beranjak dari pernyataan-pernyataannya yang penuh semangat solidaritas sosial. Sajak-sajak yang dibacakannya - sebanyak 12, termasuk tiga sajak terkenalnya dari kumpulan Blues untuk Bonnie, yang ditulisnya hampir 20 tahun yang lalu - berbicara tajam, atau menggugah, dengan tema itu. Tokoh Maria Zaitun dalam Nyanyian Angsa, pelacur yang yang dekat mati didera sifilis dan diusir dari segala penjuru dan hanya ditolong Yesus, adalah tokoh yang terinjak, sebagaimana suara Orang Kepanasan adalah suara para underdogs. Dilihat dari itu, Rendra tetap Rendra. Juga pendiriannya untuk berani dalam kontroversi. Beberapa belas tahun sebelum ia menggugat perusahaan-perusahaan besar yang selalu disebutnya dengan "mastodon-mastodon", ia menggugat hal-hal lain: pastor yang tak memahami penderitaan, atau massa yang hanya menginginkan sensasi, seperti kita dengar dalam sajak indahnya Khotbah. Bagi Rendra, penyair adalah penggugat, adalah "orang urakan", yang diperlukan bila masyarakat tak hendak beku oleh ketertiban. Sejarah, begitulah kira-kira pandangan Rendra, bergerak justru karena dialektik antara ketertiban dan penjebolan, antara jawab yang selesai dan gugatan pertanyaan. Kesulitan penyair mungkin itulah yang oleh Rendra disebut "neraka" yang mengikuti penyair ialah bila ia terbentur pada hal-hal yang tak terelakkan. Ia bisa terbentur pada kekuatan sosial-politik, sering kali dalam bentuk tangan pemerintah yang tak hendak diganggu dengan usikan lama atau baru. Rendra sendiri pernah mengalami itu, baik ketika menghadapi Lekra maupun ketika ia ditahan oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi lebih sulit, dan lebih subtil, ialah benturan lain: kecenderungan kita untuk tak ingin mengusik konklusi kita sendiri. Dengan kata lain, penyair tak cuma terancam oleh larangan, tapi juga oleh pengulangan. Rendra, dalam kebebasannya kini, justru berada dalam titik yang licin sekali: bagaimana suara protesnya tak repetitif, karena kemarahan yang paling murni pun bila dibaca berkali-kali bisa jadi boyak. Apalagi, di luar, suasana tampaknya bergeser. Setelah Peristiwa Tanjung Priok 1984 - suatu peristiwa yang esktrem - pelbagai posisi tampak berubah, seakan-akan dalam sebuah jejer baru: setelah ledakan kekerasan, terasa bahwa kata-kata dalam sajak yang paling tajam pun terasa cuma angin yang nakal, tapi moderat. Getaran kontroversial puisi Rendra - betapa pun menyegatnya masih ke kuping seorang pejabat - pada akhirnya toh tak sedahsyat pekik perlawanan dengan taruhan hidup atau mati. Puisi protes jadi terasa "aman" - yang bisa berarti tak keras menggigit lagi. Mungkin itulah sebabnya Rendra kini bisa tampil, tanpa tekanan, tanpa sensor. Tapi ini mungkin juga sebuah eksperimen kita dengan kebebasan, yang mudah-mudahan besar manfaatnya. Apa boleh buat, itulah peran dan nasib Rendra, untuk berada tepat di baris depan. Suatu hal yang membuktikan bahwa ia bukan seorang penyair biasa. Ia salah satu tonggak sejarah Indonesia. Goenawan Mohamad, Laporan: Putu Setia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini