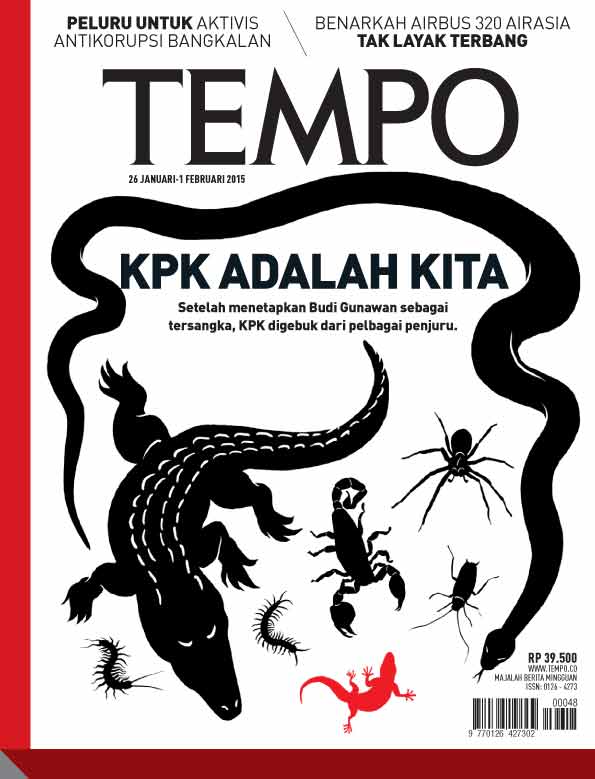Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Blackhat
Sutradara: Michael Mann
Skenario: Morgan Davis Foehl, Michael Mann
Pemain: Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis, Ritchie Coster
Kesalahan utama para penggemar film, mereka (termasuk saya) sering berharap banyak pada nama-nama besar karena jaminan karyanya di masa lalu. Nama Michael Mann sudah telanjur menjadi sutradara yang saya nantikan karyanya, terutama dua film yang mendapat pujian kritikus, yakni Heat (1995, ketika pertama kalinya Al Pacino berhadapan dengan Robert De Niro) dan The Insider (yang kemudian menjadi salah satu tontonan wajib para calon wartawan).
Apalagi sutradara Michael Mann datang ke Jakarta untuk berburu lokasi dan syuting di Lapangan Banteng setahun lalu sekaligus menyempatkan diri bertemu dengan komunitas film Indonesia buat membagi pengalaman. Harapan itu semakin membubung ke langit bukan hanya karena nama besarnya, melainkan juga karena kisah ketelitian dan perfeksionis sang sutradara.
Blackhat, yang disebut sutradaranya sebagai film cybercrime thriller, termasuk proyek ambisius yang menantang. Film ini mencakup lokasi Los Angeles, Beijing, Perak, dan Jakarta. Menurut sang sutradara, ia ingin menggabungkan kisah cybercrime sekaligus laga.
Maka Mann menciptakan sosok Nicholas Hathaway. Nick yang tubuhnya sangat Thor (baca: hanya berisi otot dan batu bata) dan sudah jelas mudah menaklukkan belasan begajulan hanya sekali tekuk itu harus kita percayai sebagai seorang jenius Internet jebolan kampus prestisius MIT, Amerika Serikat. Nick dipenjara karena berhasil menjebol sebuah bank besar. "Saya hanya melakukan hacking terhadap bank besar yang merugikan masyarakat," demikian sang hacker jenius menuturkan logikanya. Ia divonis penjara 15 tahun untuk logika yang miring itu.
Mann membuka adegan filmnya dengan perjalanan kamera yang meliuk-liuk menyorot jaringan sirkuit yang menjadi imaji dunia dalam jaringan komputer. Imaji ini menyajikan bayangan betapa cepat dan sigapnya data bisa terkirim dan terlempar ke dunia lain yang begitu antah-berantah di luar jangkauan kita, manusia awam yang tak fasih dengan bahasa Internet. Dan dunia tak terjangkau inilah yang bisa disentuh oleh orang jenius semacam Nicholas Hathaway.
Ketika sebuah sistem pusat tenaga nuklir di Beijing terganggu dan harga saham kedelai mendadak melejit secara tak wajar, pihak intelijen kedua negara menyadari adanya hacker yang mengganggu sistem, meski mereka tak paham apa keinginan penyelundup itu. Apa boleh buat, setelah mengupayakan semua ahli forensik cyber yang gagal paham, analis keamanan digital Chen Dawai (Wang Leehom) meyakinkan kolega dari biro penyelidik federal Amerika (FBI), Carol Barrett (Viola Davis), untuk meminta bantuan Nick Hathaway mengulik dan memburu hacker tersebut.
Lantas penonton pun berkenalan dengan sang hacker jenius yang angkuh, ganteng, gigantik, dan segalanya. Nick dibantu adik perempuan Chen Dawai yang cantik bernama Chen Lien (Tang Wei). Bersama dua agen FBI, lengkaplah tim pemburu itu mencari tahu si penjahat dunia maya dan apa tujuan akhir dari kegemarannya mengacaukan harga saham dan mengacaukan jaringan nuklir Cina. Lebih gawat lagi, menurut si jenius bertubuh Thor, "Serangan yang sesungguhnya akan terjadi sebentar lagi," sehingga mereka diburu waktu.
Kriminal dalam dunia cyber—bahkan bagi sutradara papan atas pun—memang tak mudah dibuat menarik secara visual. Sejauh ini, semua film yang menyangkut kejahatan cyber, baik di dalam serial televisi maupun layar lebar, selalu saja memperlihatkan tokoh-tokohnya menatap layar, lantas berdialog pingpong tentang yang terjadi pada layar komputer, seraya melontarkan kata "IP address" dan kata-kata teknis lain yang membuat penonton terpaksa percaya saja apa pun yang diucapkan sang tokoh.
Para jagoan teknologi itu akan berbincang yang sebetulnya berisi penjelasan kepada penonton bahwa si penjahat sudah melakukan A, B, dan C dan mereka sebagai superhero cyber harus melakukan X, Y, dan Z. Nah, X, Y, dan Z ini diartikulasikan oleh Michael Mann sebagai gabungan kisah Jason Bourne yang berlari-lari sepanjang film; lantas ada elemen James Bond karena mereka berloncatan ke berbagai negara eksotis (harap maklum, Indonesia dan Malaysia untuk Hollywood terdengar jauh dan eksotis); lantas ada sedikit elemen Julian Assange yang menempuh jalan menabrak hukum demi apa yang dianggap sebagai perbuatan baik untuk masyarakat.
Untuk drama dan emosi, tentu kita perlu mengenal anggota tim itu satu per satu. Carol Barrett, yang diperankan dengan sangat baik—mungkin dia menjadi salah satu alasan untuk bertahan—diberi latar belakang keluarganya; lantas yang sudah bisa ditebak adalah keterlibatan "superhero" kita, Nick Hathaway, dengan si jelita Chen Lien.
Sayang, dengan nama besar sutradara dan setting yang begitu mahal, tetap saja bagi penonton yang sudah dihajar dengan film thriller-laga seperti serial Bourne atau Mission: Impossible, film terbaru Mann menjadi sungguh layu. Gerak perburuan tak sesigap dan secepat film thriller Hollywood lazimnya. Para penjahat juga ternyata tetap klise: wajah begajulan seperti preman, bahkan di Jakarta kita bertemu dengan si bos yang mengenakan kemeja batik. Astaga. Tokoh-tokoh baiknya pun tak sempat tertanam di dalam hati penonton untuk ditangisi kematian atau kesengsaraannya. Semuanya serba tanggung.
Bagi penonton Indonesia, mungkin daya tariknya adalah bagaimana Mann memperlakukan Jakarta sebagai bagian dari dunia rekaannya. Setelah berburu penjahat ke Beijing dan Perak, sejoli Nick Hathaway dan Chen Lien meneruskan pengejaran ke Jakarta dalam situasi buron, karena Nick lagi-lagi melanggar hukum dengan menembus situs National Security Agency untuk menguak software Black Widow yang seharusnya merupakan rahasia negara. Dengan mendapatkan software Black Widow, Nick dan timnya berhasil mengetahui jejak para kriminal yang sudah kabur ke Jakarta.
Jakarta yang dipilih Mann adalah Lapangan Banteng yang dalam film ini dibuat sebagai taman fiktif bernama Papua Square. Sebuah perayaan fiktif yang terdiri atas berbagai tari—salah satunya tari Bali—yang kemudian dicampur dengan berbagai simbol "keindonesiaan" seperti ondel-ondel dan patung wayang, digunakan sebagai efek dekoratif. Adegan besar dan diisi oleh 2.000 orang figuran Indonesia ini adalah sebuah adegan akhir, sebuah adegan konfrontasi antara Nick dan serombongan penjahat yang lebih mirip preman biasa daripada orang-orang yang akrab dengan komputer. Harus diakui, meski adegan ini tak berhasil membangun ketegangan apa pun, warna-warni festival dan energi para penari menarik.
Mann mengaku kepada Tempo bahwa ia memilih Jakarta sebagai lokasi karena, "Ada energi di Jakarta yang menarik hati saya. Ada denyut nadi dan reaksi penduduknya terhadap problem kepadatan jalanan yang sungguh mengagumkan." Dia mengaku tertarik pada "arsitektur Jakarta yang warna-warninya bertabrakan dengan lampu neon berwarna biru, hijau, dengan aksen kuning".
Memang warna-warni itu kontras dengan gelap malam Jakarta. Sayang sekali, adegan kejar-mengejar di tengah festival tak bernama itu tetap saja tak mengirim ketegangan apa pun. Akhir dari tembak-menembak dan baku hantam itu juga tak memberikan penyelesaian apa-apa. Nick dan Chen Lien keluar dari Jakarta seolah-olah mereka keluar dari sebuah kawah yang baru saja membakarnya. Padahal di Jakarta tidak terjadi apa pun, kecuali baku hantam melawan penjahat berbaju batik itu.
Sudah waktunya kita tak lagi berharap terlalu tinggi pada nama besar sutradara.
Leila S. Chudori
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo