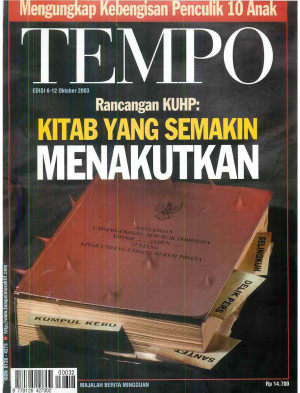Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ANDA senang kembang api? Aku dulu senang merokok. Namaku adam tanpa huruf kapital!" Penggalan kalimat-kalimatnya cerdas, lebih personal dan santai. Kita tahu, kembang api dan rokok adalah paparan problematika yang dihantarkan melalui metafora dan simbol-simbol kehidupan keseharian dalam pengalaman sosial. Inilah bentuk perkembangan pemikiran, dan kesadaran juga makin tumbuh dengan cara yang lebih matang, dewasa, dan diiringi oleh sikap dialogis, dan bukan cuma saling tuding yang berakibat perseteruan yang tak habis-habisnya. Protes atau gugatan dialogis, bukan berbentuk tudingan atau penghakiman dari salah satu pihak.
Simbolisme kembang api dan rokok merupakan tampilan awal setelah beberapa pemain yang memakai topeng berbentuk pipa besar dan panjang membagi-bagikan kembang api dan surat dari adam sebagai pembuka pertunjukan Teater Sanggar Merah Putih dari Makassar. Sanggar yang memanggungkan produksinya yang ke-54 sejak berdirinya 25 tahun yang lampau. Itulah repertoar berjudul namaku adam TANPA HURUF KAPITAL, yang diangkat dari puisi karya Shinta Febriany yang juga menyutradarainya di Teater Arena Taman Budaya Surakarta pada 3-4 Oktober 2003. Repertoar ini, yang juga dipanggungkan di Gedung Kesenian "Societeit" Yogyakarta pada 5 Oktober, dan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 7 Oktober 2003, merupakan rangkaian perjalanan keliling kedua kalinya setelah pada tahun 2000 lalu.
Beberapa tahun terakhir ini isu gender tampak marketable di pelbagai bidang: dari tari, teater, hingga—terutama—seni rupa. Memang, budaya maskulin atau phalic culture yang selama berabad-abad mendominasi kehidupan kebudayaan dan keseharian di lingkungan kita. Tapi kita sering menyaksikan bentuk ekspresi kesenian yang menampilkan isu gender senantiasa menggunakan perspektif dan kerangka pemikiran yang hitam-putih. Yang satu menunjukkan kaum Hawa sebagai makhluk lemah di bawah dominasi kaum Adam yang "konon" sebagai takdir. Yang lain menggunakan tafsir teologis sepihak yang mempertahankan kepentingan posisi dan peran kaum laki-laki.
Pertunjukan Sanggar Merah Putih kali ini berbeda. Bahkan berbeda dari pementasan dengan tajuk Ketika Kita Kaku garapan sutradara Arman Dewarti, tahun 2000. Posisi kaum perempuan ditampilkan dalam bentuk protes mendalam dan frontal: perempuan bukan—dan bahkan—tidak datang dari tulang rusuk kaum laki-laki.
Repertoar namaku adam TANPA HURUF KAPITAL, menurut sutradaranya, menampilkan "rekoleksi-rekoleksi tentang lelaki yang saya dapatkan di sekitar mata dan hati saya." Penderitaan dihadapinya, namun bukan dalam bentuk perlawanan, melainkan sekadar seruan. Dengan kata lain, soal yang dihadapi bukan masalah perseteruan antara jenis kelamin yang berbeda, tapi sebuah rumah yang terbuat dari tepung dan mentega yang meluluri seluruh kehidupan laki-laki dan perempuan. Maka persoalan dibuka dengan paparan bagaikan reportase rumah tangga keseharian yang saling mengenal satu dengan lainnya, dan terasa akrab. Dan dengan itu pula isu gender tidak kita rasakan dipolitisasi, dan tanpa pula berpretensi menjadi pahlawan.
Lebih dari itu, gugatan justru memasuki ruang yang paling dalam pada wilayah kehidupan manusia. Itulah perspektif dan konsep teologis yang dikukuhkan dan sekaligus diambangkan dengan pernyataan: "Kami semua adalah adam malam ini. Tapi sungguh, kami bukanlah adam dalam kisah cinta yang kalian baca di kitab-kitab suci terjemahan". Tentu ada sedikit protes dalam bentuk bentakan "capek?!" atau ungkapan tentang persahabatan sebagai omong kosong atau mi instan akibat penderitaan yang dialami, yang cuma diserukan dan bukan dalam sebuah perlawanan.
Menyaksikan pertunjukan ini kita diantarkan kepada kecenderungan realitas seni panggung dan kehidupan yang sepenuhnya berupa paparan pernyataan yang "non-linear", patah-patah, dan sepenuhnya montase persoalan dan adegan dalam bingkai yang batas antara teater dan performance art demikian tipisnya. Dan sudah pasti tidak berbeda dengan teater yang mendasarkan kepada alur cerita konvensional. Hal itu mengantarkan kita kepada perkembangan teater yang lain di Makassar, seperti juga Teater Kita dengan sutradara Asia Ramli Prapanca sejak tengah tahun 1990-an, yang sangat berbeda dengan pendahulunya. Realitas ini bisa menjadi khazanah dan memperkaya keberagaman peta kehidupan teater di Indonesia.
Halim H.D., networker kebudayaan di Solo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo