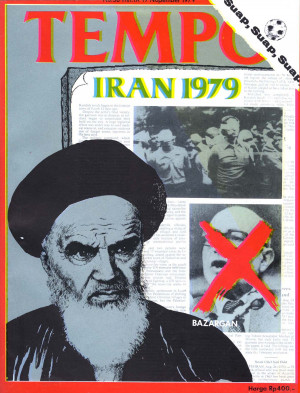KRIDO LANGEN SWORO RONGGOLAWE
Penata tari: S. Kardjono
Penyusun dialog & tembang: Aries Mukadi dan S. Kardjono
Produksi: Jaya Budaya
ARENA menjadi remang-remang. Ronggolawe, Adipati Tuban, berdiri
tegak sambil berpeluk tangan di bawah sorotan lampu. Dia ragu.
Kebo Anabrang, salah seorang senopati Majapahit, menantangnya
berkelahi di dalam air. Dia tahu, ini pantangannya. Ia pun
lantas teringat impian isterinya, kemudian di bagian belakang
arena, di belakang para pemukul gamelan, dilihatnya Dewa
Yamadipati -- dewa kematian.
Ia pun mengerti. Tetapi sebagai prajurit ia pantang mundur,
meski kematian sudah jelas di hadapannya.
Adegan paling bagus dari Krido Langen Sworo Ronggolawe ini, 10-
13 November di Teater Arena TIM, toh kurang mengharukan. S.
Kardjono, 39 tahun, penata tari pementasan Jaya Budaya kali ini
-- sekaligus memerankan Ronggolawe -- agaknya kurang
mempersiapkan adegan-adegan sebelurnnya, sehingga tidak
mendukung adegan yang seharusnya menjadi klimaks.
Konflik tak terasa. Baik ketika Ronggolawe harus memutuskan
melayani tantangan Kebo Anabrang atau tidak. Maupun ketika dia
menghadapi pendapat isteri-isterinya, juga Wirorojo, ayahnya,
yang mencegahnya meneruskan tindakannya. Konsep Kardjono memang
menciptakan Ronggolawe yang berjalan lurus, tanpa pertentangan
batin. Sehabis, pementasan malam pertama, katanya kepada TEMPO:
"Tokoh Ronggolawe bagi saya adalah tokoh yang tak pintar bicara.
Ia polos."
Drama tari ini mencoba memberi tempat pada tembang dan dialog
tanpa menyisihkan tari. Sayangnya, kecuali Kardjono, Kies Slamet
(sebagai Kertarejasa) dan Sal Murgiyanto (sebagai Tosan) pemain
lain tidak memiliki suara bagus. Padahal, "ekspresi lebih kena
kalau ditembangkan oleh penarinya sendiri daripada ditembangkan
oleh waranggana," kata Kardjono, menjelaskan mengapa ia memilih
Langen Sworo (olah suara).
Isyarat Kematian
Yang agak sayang ialah bahwa tembang-tembangnya kurang membentuk
suasana di arena. Dalam adegan pembuka saja, kehadiran
Ronggolawe di Majapahit terasa tiba-tiba. Dan begitu cepat,
kemudian perdebatan berlangsung di hadapan Raja Kertarejasa:
sudah pantaskah Nambi diangkat menjadi Patih Kerajaan. Dan
begitu cepat pula Ronggolawe meninggalkan paseban tanpa pamit.
Semuanya berjalan hampir tanpa sentuhan ke dalam "rasa". Tapi
mungkin karya Kardjono memang tidak dimaksudkan ekspresif
melainkan --seperti lakon tradisional wayang orang - semata-mata
naratif. Dan seperti sikap pementasan tradisional, perpindahan
yang cekatan, tempo yang tinggi serta suspens kurang penting
dibanding dengan tertampungnya sebanyak mungkin unsur bercerita.
Adegan di Keputrian Kadipaten Tuban, bagi sementara penonton
mungkin terasa lepas, seperti tak ada hubungannya dengan adegan
sesudah maupun scl elumnya. Tapi, "adegan itu untuk lebih
menggambarkan watak Ronggoldwe -- bagaimana ia tetap
mementingkan negara daripada isteri-isterinya," kata Kardjono.
Unsur yang memperjelas itu sayang tak begitu tergambarkan dalam
sikap tanggap Ronggolawe. Ketika isterinya menceritakan impian
yang mengisyaratkan kematian, duduk Ronggolawe nampak kurang
"gawat". Tapi mungkin, sekali lagi, di sini yang ekspresif tidak
dibutuhkan.
Kardjono kurang memuaskan bagi mereka yang menghendaki puisi
atau pun drama watak atau konflik psikologis. Dengan kata lain,
bagi yang terbiasa dengan dinamiknya tari dan drama "modern",
tokoh Ronggolawenya agak datar dan tragedinya agak "enteng".
Tapi Kardjono mungkin punya referensi lain, yang lebih dekat
kepada wayang orang seperti yang kita lihat sewaktu anak-anak.
Ini jelas misalnya dalam adegan dua punakawan Ronggolawe. Humor
mereka cukup kita kenal, dan karenanya mungkin tidak segar.
Peran mereka sebagai penasihat juga konvensional. Tanpa
intensitas seperti banyak aktor pemain Ki Lurah Semar yang
unggul, kedua punakawan malam itu jadinya sekedar selingan
beristirahat. Ini pun lazim, bukan?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini