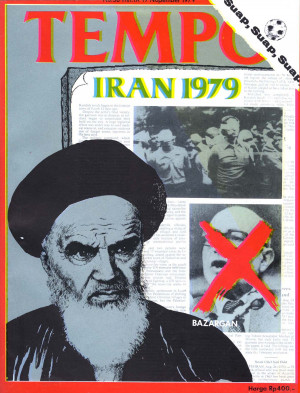JUMLAH penonton masih bisa dihitung dengan jari tangan, walau
jam pertunjukan sudah harus dimulai. Penjual karcis duduk
mengantuk menanti pembeli yang tetap sepi. Penyobek karcis
berwajah suram tanpa tenaga. Sambil mengintip lewat layar, satu
dua orang anak wayang mencoba mengintip ke tempat penonton:
kursi-kursi masih kosong melompong. Gending Kodok Ngorek yang
mencoba memberi warna pada suasana suram itu tidak sepenuhnya
berhasil.
Itu adalah pemandangan pada pertunjukan Wayang Orang Taman
Hiburan Rakyat Sasana Suka Yogya. Sehingga tidak jarang, FX
Kusnadi (44 tahun) yang memegang peran tetap sebagai Gatotkaca
harus "berkelahi" dengan perut keroncongan. "Bayangkan," sahut
isterinya, "satu kali main, dapat uang makan Rp 50 saja." Itu
kalau main. Empat tahun terakhir ini mereka hanya bisa main tiga
kali seminggu. Bahkan tidak jarang, cuma dua kali seminggu.
Harga karcis untuk turis asing Rp 750 dan untuk penonton lokal
cukup bayar Rp 300 di barisan depan dan Rp 100 kelas belakang.
"Penghasilan tiap malam kami bagi rata," kata Kusnadi lagi.
Seluruh personal ada 60 orang, termasuk tukang sapu, yang jadi
Arjuna atau yang jadi Kreshna, niyaga dan pesindennya. Jadi
kalau penghasilan dari jual karcis cuma Rp 3.000, dibagi 60,
tentu saja terus menjawab teka-teki Rp 50 seperti dikatakan
Kusnadi tersebut.
Grup wayang orang di Taman Hiburan Rakyat (THR) ini pecahan dari
grup Cipto Kawedar di Sala. Grup yang tadinya keliling kota ini
pada 1972 menetap di Yogya, setelah Walikota Yogya (waktu itu
Sujono AY ) menjanjikan perumahan, ditambah subsidi keuangan
dan bangku sekolah untuk anak-anak grup yang jumlahnya saat itu
ada 70 orang.
Penonton 40%
Memang mereka mendapatkan hak-hak tersebut. Rumah cukup menempel
di sekitar dinding gedung pertunjukan. Grup yang masih bujangan
boleh tidur di mana saja: di panggung, di bangku penonton,
sejadi-jadinya. Memang ada sumbangan dari Pemda, tetapi
jumlahnya hanya Rp 62.500/bulan - kalau dibagi rata
masing-masing mendapat Rp 1.000. Tidak jelas bagaimana cara
mengatasi sewa gedung Rp 3.000/bulan, pemeliharaan gedung,
kostum dan urusan lainnya.
Masa pahit juga dialami oleh grup Ngesti Pandawa dari Semarang.
Masa puncaknya (1952 - sekitar 1970) telah hilang. Kursi diisi
penonton paling banter sekitar 40% saja, kecuali malam Minggu
atau kalau ada pengunjung dari luar kota yang melancong ke
Semarang. "Walaupun begitu, kami tidak melihat adanya
tanda-tanda bakal tutup," kata Kasido Gitosewoyo yang paham
betul akan manis pahitnya grup wayang orang ini.
Gitosewoyo -- yang pernah jadi dalang kesayangan Bung Karno --
tidak melihat ketidak-setiaan anggota grup. Dia memberi alasan
keterikatan yang berupa fasilitas perumahan dan pembiayaan uang
sekolah untuk anak-anak dari anggota grup. Biaya sekolah ini
hanya sampai tingkat menengah pertama saja, biarpun "Ngesti
Pandawa seperti kebo kabotan sungu," kata Gitosewoyo. Beban
yang berat dengan pemasukan yang tidak seimbang itu
mengakibatkan telah dijualnya sebidang tanah milik Ngesti
Pandawa kepada sebuah toko batik.
Gratisan
Selain itu," sambung Gitosewovo "anggota grup merasa lebih
terpangil oleh jiwa seni mereka." Tapi diakui juga jika uang
masuk lebih banyak para pemain lebih bersemangat, lebih kreatif
dan mutu terus nomor wahid.
"Tetapi dengan teknik yang bagaimanapun" kata Hardjosuman,
sesepuh wayang orang Sri Wanita yang kini jadi lurah di salah
satu desa di Kabupaten Semarang, "wayang orang sulit bersaing
dengan bioskop." Tahun 1950, Kota Semarang hanya mempunyai 9
buah bioskop. Jumlah ini sudah lipat dua sekarang. "Jadi faktor
laku tidaknya, menentukan juga hidup matinya kami," ujar
Gitosewoyo.
Nama Ngesti Pandawa resmi didirikan pada 1937 oleh Almarhum
Sastrosabdo. Semula hanya grup keliling. Tahun 1948, mendapat
tawaran main di Pekan Raya Semarang. Empat tahun berikutnya,
berhasil menetap di gedung GRIS, Jalan Pemuda, hingga sekarang.
Namanya melambung ketika wayang orang ini adalah satu-satunya
tontonan yang dianggap mempunyai teknik tinggi waktu itu.
Sastrosabdo misalnya menemukan "alat malihan" raksasa untuk
merubah wujudnya menjadi kesatria dalam sekejap. Alat ini berupa
permainan lampu sorot yang cepat dan rapi. Juga untuk adegan
rampogan, yaitu iring-iringan suatu perjalanan, Ngesti Pandawa
berhasil menyajikan kereta kencana untuk sang raja,
gajah-gajahan, kuda-kudaan yang cukup mengesankan. Dengan
iringan gending disertai suara seruling, genderang, tentara yang
bersenjatakan tombak, pedang dan tameng, suasana panggung cukup
semarak.
"Kekhasan tersebut kemudian ditiru oleh banyak grup wayang orang
lainnya," ungkap Gitosewoyo. Setelah tahun 1970-an, pengunjung
banyak sekali berkurang. "Karena itu, biar bagaimanapun, kami
tak bisa bersaing dengan bioskop," sambung Gitosewoyo lagi.
Di Semarang kini hanya tinggal 3 grup wayang. Ngesti Pandawa,
Sri Wanita dan Wahyu Budaya. Dua yang terakhir agaknya lebih
parah dibanding Ngesti Pandawa, walaupun Wahyu Budaya telah
disubsidi oleh THR Tegalwareng.
Yang sedang bernasib baik ialah grup wayang orang Sriwedari di
Sala. Bulan lalu telah diumumkan bahwa dengan SK Presiden 9 Mei
1979, telah keluar sumbangan Presiden Soeharto sebanyak Rp 50
juta. Uang ini untuk pemugaran gedung wayang orang tersebut
setelah beberapa waktu lalu mengirim surat meminta sumbangan
kepada Kepala Negara.
Sementara itu ketoprak di THR yang sama (Sriwedari) lama
sudahamblas. Tahun lalu, Teguh dari Yayasan Sri Mulat telah
mendirikan ketoprak di Bale Kambang, bagian lain dari Kota Sala.
Menurut pengakuan Teguh, ia telah melemparkan modal sebanyak Rp
50 juta untuk mengganti wajah Bale Kambang jadi tempat
remang-remang sarang tuna-susila kelas ratusan rupiah seperti
sekarang. Ketoprak Teguh yang memakai nama Tjokrodjijo ini di
bulan-bulan pertama memang cukup padat penonton. Kini paling
banter mereka cuma bisa mengumpulkan pendapatan sekitar Rp
10.000 tiap pertunjukan.
Ketoprak Teguh memang tidak memakai sistim primadona. Padahal
Sriwedari masih mempunyai bintang kesayangan penonton yang
bernama Rusman, Surono dan Darsi.
Yogya, mempunyai beberapa grun wayang orang dan ketoprak. Ada
ketoprak Bagong Kussudiardjo. Di Gedongkiwo ada wayang orang
siang hari. Di Keben, dekat Tamansari selalu terpampang dalam
bahasa Inggeris Ramayana ballet, now showing. Tapi pertunjukan
itu semuanya untuk suguhan turis asing. Kabarnya kini melorot
jumlahnya.
Biarpun Pemda Yogyakarta lebih memfokuskan perhatiannya pada
Ramayana, dan karcis dijual Rp 1.000 untuk pertunjukan sekitar 2
jam saja, toh nasib pemainnya masih menakjubkan. Yaitu hanya Rp
2 00 untuk tiap kali main -- karena sumbangan Pemda dan hasil
penjualan karcis, harus dipotong untuk promosi dan komisi.
Perkumpulan Kampung
Atau penduduk Yogya sudah tidak senang wayang? Alasan ini tidak
benar. Wayang kulit maupun wayang orang, tetap digemari. Bahkan
masih menjadi falsafah hidup mereka. Tetapi rupanya mereka tidak
biasa nonton wayang dengan membayar, dengan tempat duduk yang
rapi dan interior yang terlalu mewah. Dan kenyamanan penonton
menyebabkan pula harga karcis yang lebih mahal. Yang lebih
mengasyikkan mereka adalah pertunjukan wayang di
kampung-kampung, di tempat orang punya haat. Tentu gratis.
"Membantu atau memberi subsidi agak susah, karena itu wewenang
Pemda," tukas Kasim Achmad (44 tahun), Kepala Sub Dit Seni
Teater Film dan Sastra, Direktorat Pembinaan Kesenian,
Departemen P&K. Tambahnya: "Paling banter bantuan secara
insidentil." Sydney Jones dari Ford Foundation memberikan
beberapa saran untuk menggalakkan kembali seni tradisional
semacam wayang orang. Bukan hanya dari beberapa badan swasta
(dan Ford telah membantu AS$ 100.000 untuk hal ini lewat
ayasan Seni Tradisional), tetapi juga dari pribadi-pribadi
dermawan. "Yang kaya cukup banyak di Indonesia," kata Jones,
"tetapi yang dermawan dan berminat dalam bidang ini yang
jarang."
Ucapan Jones ini mengingatkan akan riwayat wayang orang Sri
Wanita di Semarang Grup ini pada mulanya hanya berwujud
perkumpulan kampung saja. Tahun 1935 seorang bernama Tan Liong
Kwie menang lotre. Uang ini oleh Liong Kwie digunakan untuk
mendirikan gedung. Pertunjukan dikomersialkan. Mengalami nasib
duka sepeninggalnya Liong Kwie, grup ini telah berpindah gedung
berkali-kali. Kini dikelola oleh para purnawirawan dengan nama
PT Seni Sanggar Budaya "Sri Wanita". Karena tidak juga menemukan
dermawan lain, napas Sri Wanita tentu saja seperti para
pensiunan itu juga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini