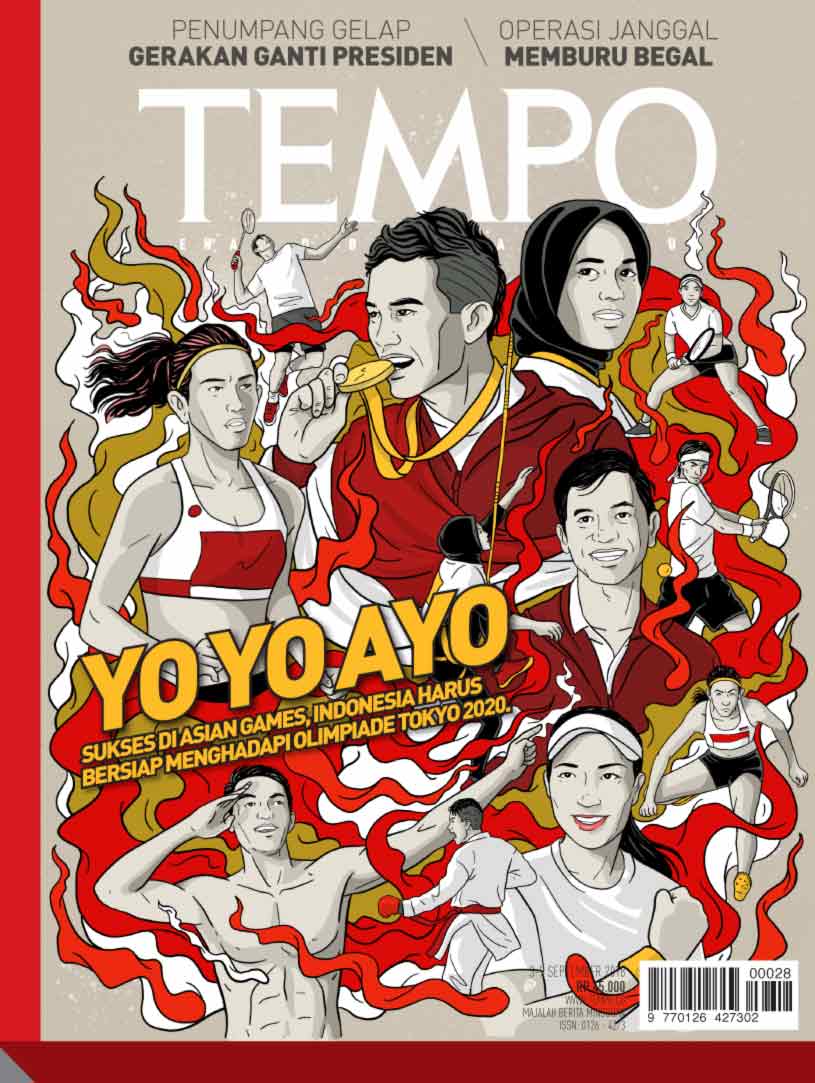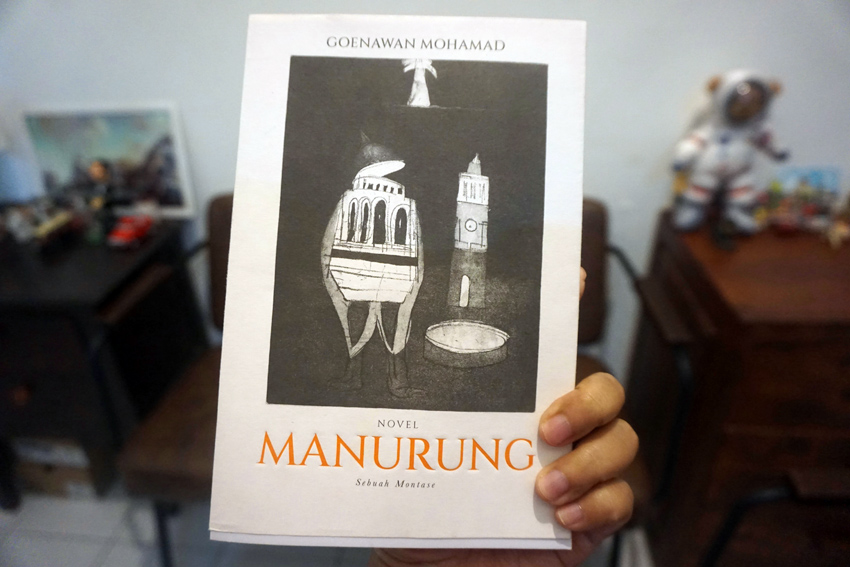Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Iksaka Banu
Mengapa Tuhan menciptakan wabah penyakit? Apakah Ia jemu melihat kedamaian dan ketenteraman umat-Nya? Mengapa Tuhan gemar membuat ironi? Lihatlah Hindia Timur, untaian zamrud molek ini. Kepulauan luas dengan siraman matahari sepanjang tahun, hasil bumi melimpah, serta penduduk yang rajin melempar senyum. Bandingkan dengan Eropa: dingin, miskin, tak bermoral. Tidak seharusnya Tuhan menurunkan kutukan atau wabah penyakit di sini.
Bukan. Bukan wabah kolera atau pes, meski keduanya juga sempat membantai sepertiga populasi manusia di dunia. Aku bicara tentang cacar. Variola. Gelembung kecil bernanah di sekujur tubuh disertai demam tinggi, yang mengantar penderitanya ke gerbang kematian. Wabah yang sejak sepuluh ribu tahun lalu telah memangsa jutaan jiwa, dan sejak abad ke-14 menjangkiti Hindia. Mulai dari Ternate, Ambon, dan kini Bali. Ya, delapan belas ribu orang kehilangan jiwa di Bali karena wabah cacar menjelang akhir 1871 ini.
"Kita bersyukur, penangkal penyakit ini berhasil ditemukan sekitar 75 tahun silam," kata Dr. Jan Veldhart, wakil kepala Geneeskundige Dienst di Weltevreden. Siang itu aku datang memenuhi undangan yang ia beri catatan ‘segera dan darurat’.
"Pengiriman vaksin cacar dari Belanda ke Hindia juga semakin cepat dengan dibukanya Terusan Suez dua tahun lalu," sambung Dr. Jan Veldhart. "Tetapi tidak cukup cepat menghadang laju penyebaran wabah di Bali. Sekali menyentuh Batavia, lumpuhlah semua kegiatan ekonomi."
"Kabar terakhir, karantina sudah diberlakukan. Militer telah memblokir jalan dari dan ke daerah epidemi," sahutku.
"Angkat topi untuk kegesitan pejabat setempat." Dengan tangan kanan, Dr. Jan Veldhart memperagakan kalimat yang ia ucapkan. "Sekarang giliran kita mengambil tindakan. Ini perintah langsung dari Gubernur Jenderal."
"Sejujurnya, kita perlu mendirikan lebih banyak lagi lembaga yang bisa memproduksi vaksin cacar di Hindia." Aku menarik kursi, duduk di hadapannya.
"Tuan Adriaan Geest, sejak 1854, vaksin cacar telah diproduksi di Madiun, Pasuruan, Kedu, serta Kediri," kata Dr. Jan Veldhart. "Namun daerah yang terkena wabah berada di pedalaman. Tak bisa mengandalkan vaksin dengan benang celup dijepit kaca berlapis damar untuk menyelamatkan mereka yang belum terinfeksi. Ada risiko kedaluwarsa. Kita terpaksa memakai cara kuno. Menggunakan tubuh anak-anak sebagai pembawa vaksin aktif. Sepuluh anak kecil berusia sembilan hingga lima belas tahun."
"Sulit membujuk orang tua bumiputra dari keluarga baik-baik melepas anak mereka pergi seorang diri ke luar Jawa." Aku menggeleng. "Kita wajib menanggung biaya anggota keluarga yang ikut menemani anak-anak itu. Bila satu anak dan satu orang tua masing-masing mendapat upah f50, akan diperlukan f1.000 untuk sepuluh peserta. Belum termasuk ongkos kapal dan makan. Kecuali kita mau menggunakan anak-anak gelandangan."
"Tak mungkin." Dr. Jan Veldhart menggosok lensa kacamatanya. "Kita tidak bisa menjamin darah mereka bersih dari bibit penyakit lain. Tentu kita bisa memeriksa mereka satu per satu. Tetapi butuh waktu lama. Padahal kita harus bergerak cepat. Kapal yang berangkat ke Bali tidak banyak."
"Bergerak cepat. Seberapa cepat?"
Dr. Jan Veldhart menatapku lesu. "Dua minggu. Dan sedikitnya sepuluh anak dengan catatan kesehatan bersih, serta tak ada masalah dengan keluarga mereka."
"Dua minggu?" suaraku meninggi.
"Tuan adalah officier van gezondheid yang kerap diperbantukan militer. Piawai di lapangan. Punya pengalaman menakjubkan mengatasi penyebaran kolera di Aceh. Saya percaya kemampuan Tuan dan rekan-rekan."
"Tetapi ini wabah cacar…"
"Aku tahu. Kalau dari bumiputra sulit diperoleh, cobalah anak-anak Eropa. Mereka berani pergi tanpa orang tua."
Anak-anak Eropa. Ya, tentu saja. Mereka lebih mandiri. Teorinya begitu. Ternyata sama saja. Banyak orang tua Eropa tak ingin anak mereka pergi, karena rata-rata mereka sudah kehilangan satu atau dua orang anak akibat wajib militer dalam Perang Aceh. Selama lima hari, kelompok gerak cepat yang kubentuk baru memperoleh satu anak Eropa. Itu pun lantaran orang tuanya terjerat utang, dan berharap memperoleh banyak uang dari pengiriman anaknya.
Untunglah anggota kami yang lain panjang akal. Mereka pergi ke panti asuhan yatim piatu di sekitar Rijswijk dan Kramat. Lima anak berhasil mereka bawa. Kurang empat lagi.
"Ada panti asuhan lain, lokasinya di bekas rumah Gubernur Jenderal Reinier de Klerk. Milik College van Hervormde Gemeente," kata seorang rekan. "Itu panti terbesar di Batavia. Ada gerejanya pula. Bila Tuan Geest sendiri yang datang, mungkin mereka akan lebih cepat membuka diri untuk membantu."
Aku setuju. Maka pergilah aku ke tempat itu setelah mengirim surat dan mendapat izin bicara langsung dengan pengelolanya.
Sebenarnya sudah sering aku lewat di depan rumah megah di Jalan Molenvliet ini, namun baru sekarang berkesempatan masuk. Melihat luasnya bangunan serta serasinya setiap sudut ruangan, aku yakin Gubernur Jenderal Reinier de Klerk adalah seorang jutawan di Batavia abad lalu yang memiliki selera seni tinggi. Itu sebabnya aku berani memastikan tiang-tiang Yunani penyangga ruangan depan yang buruk ini dibangun belakangan, karena tampak sangat berbeda dengan langgam keseluruhan yang lebih banyak mengambil unsur hias Cina.
"Bagian ini memang baru." Terdengar suara serak seseorang, seolah membaca pikiranku. "Di sinilah kebaktian Minggu dilangsungkan. Sementara bagian belakang dan paviliun berfungsi sebagai panti asuhan."
"Luar biasa indah, mijnheer De Domine." Aku menyambut tangan Van Kijkscherp, pendeta yang berdiri di depanku. Ia adalah wakil kepala panti asuhan. Seorang lelaki tua murung yang melengkapi wajahnya dengan alis kelewat curam, serta sepasang mata yang selalu menyipit dan bersarang jauh di bawah dahi. Membuat keseluruhan air mukanya seperti seseorang yang senantiasa memandang sesuatu dengan tingkat kecurigaan tinggi. Dan dugaanku benar belaka.
"Ini Hendriek Plathart. Diaken kami," sambung Van Kijkscherp. Tangannya terayun kepada pria tambun berkacamata tebal di sisinya. "Kami sudah membaca surat Tuan. Mohon maaf, kami tidak mengizinkan anak-anak dibawa ke Bali. Terlebih sebagai donor vaksin. Ada yang ingin Tuan jelaskan lagi berkaitan dengan surat itu? Banyak yang harus kami kerjakan petang ini. Besok para donatur akan datang, melihat anak-anak yang mereka santuni."
"Mengapa mereka tidak diperkenankan pergi, Tuan Pendeta?" tanyaku. "Anak-anak ini akan memperoleh upah f50 per orang. Kami bahkan tidak keberatan bila Tuan menarik dana untuk biaya pemeliharaan panti. Akan kami naikkan upah mereka menjadi f75. Bila mereka diantar seorang pengawas, orang itu pun akan kami bayar f75."
"Bukan soal dana." Alis Van Kijkscherp bertaut. "Kami keberatan karena Tuan akan memasukkan bibit penyakit ke tubuh anak-anak itu."
"Itu disebut inokulasi. Sama sekali tidak berbahaya," sahutku. "Gagasannya diperoleh dari para gadis pemerah susu di Eropa. Telah terbukti bahwa mereka-yang pernah tertular penyakit cacar sapi––ternyata menjadi kebal saat terjadi serangan cacar manusia. Belakangan diketahui, virus cacar sapi memiliki kemiripan dengan cacar manusia namun daya rusaknya lebih lemah, sehingga tubuh kita sempat beradaptasi menjadi lebih kuat, mampu melawan balik bila datang serangan cacar manusia. Proses pengerjaannya pun cepat sekali."
"Mula-mula kami akan mengambil bibit cacar yang sudah dilemahkan, lalu menggoreskannya ke lengan anak-anak sehingga bibit itu masuk, membentuk nanah darah," lanjutku.
"Walau si anak meriang, tubuhnya akan segera bangkit menaklukkan penyakit itu. Anak menjadi kebal cacar. Seluruh proses itu akan kami lakukan di tengah perjalanan ke Bali sehingga setiba di tujuan, vaksin dari tubuh mereka masih segar. Bisa dipanen untuk banyak orang di sana. Baik kalangan Eropa maupun para bumiputra. Dengan demikian, tercipta benteng kekebalan penyakit di tengah warga. Penyebaran wabah akan terhenti."
"Jelas sekali Tuan tidak paham maksud kami!" suara Van Kijkscherp semakin terdengar hambar. "Sadarkah, bahwa di sini Tuan sebenarnya sedang berusaha mencampuri urusan Tuhan?"
"Bagaimana manusia yang sekecil debu ini bisa mencampuri urusan Tuhan?" tanyaku.
"Tuan Geest, ada sekitar 25 ayat tentang takdir di dalam buku itu." Van Kijkscherp menunjuk Alkitab berukuran besar di dalam rak di belakang kami.
"Bacalah. Intinya, kita tak bisa menghalangi rencana Tuhan. Seandainya anak-anak itu terjangkit cacar lalu selamat, itulah ‘karya agung’ Tuhan bagi umat-Nya. Bila mereka mati, itu juga kehendak-Nya. Tak ada yang bisa dilakukan di antara kedua kejadian itu."
"Ribuan orang tewas di Bali. Apakah Tuhan ingin mencabut lebih banyak nyawa lagi dalam waktu dekat? Tuhan macam apa yang bengis seperti itu? Bagaimana bila Ia sesungguhnya justru ingin menyelamatkan mereka melalui tangan kita? Melalui ilmu kedokteran yang diberikan oleh-Nya?"
"Tuan Geest!" bentak Van Kijkscherp. "Apakah Tuan pernah membaca kisah Sodom dan Gommora? Ribuan orang dimusnahkan. Bengis, bukan? Ia sedang menunjukkan kepatuhan terhadap ucapan dan janji-Nya sendiri. Ia tidak pernah ingkar memberi rezeki dan hukuman."
"Ya, dan di bagian lain dikisahkan bahwa Ia mengampuni pendosa," sahutku.
"Jangan mengajariku soal pengampunan dosa, Tuan Geest!" Van Kijkscherp memukul meja. "Mari kukutipkan satu ayat: Sebab di dalam Dia, Tuhan, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Efesus 1:4-5."
"Itu soal apa? Takdir?"
"Ya. Tetapi kalau tak paham bagian takdirnya, pikirkan kalimat berikutnya yang lebih sederhana dalam ayat tadi."
"Boleh Tuan ulang?"
"Jangan menghinaku, Tuan. Mari kita perjelas. Tuan akan mengambil darah anak-anak kulit putih ini untuk dicampurkan, bahkan dimasukkan ke tubuh para bumiputra, dan di kesempatan lain Tuan melakukan sebaliknya. Betul? Apakah Tuan lupa, kita harus menjunjung tinggi kemurnian dan kekudusan tubuh suci ciptaan Tuhan? Tidak mencampurkannya, baik melalui perzinahan dengan wanita jalang, persetubuhan dengan nyai, maupun persatuan darah semacam ini. Mestinya pemerintah menyiapkan tenaga kesehatan bumiputra untuk urusan mereka sendiri."
"Ini keadaan darurat. Saya bisa menunjukkan nama-nama pemuka agama yang mendukung upaya serius mencegah wabah mematikan ini."
"Banyak orang sesat di luar sana. Tuan ingin menambah jumlah mereka?" Mata Van Kijkscherp membesar.
"Darah memang akan bercampur." Kuabaikan amarah Van Kijkscherp. "Karena hanya dengan cara itulah wabah bisa dicegah, sehingga peradaban kita tetap hidup dan menjadi penerang di sini. Kita berdua memiliki tugas besar yang mungkin berbeda dalam cara, tetapi sama dalam tujuan, Tuan Pendeta."
"Lagi pula tidak semua anak di sini lahir dari orang tua teladan, bukan? Beberapa anak memiliki ayah atau ibu yang mungkin lebih bejat akhlaknya dibandingkan bumiputra. Apa bedanya?" tambahku. "Oh, satu lagi. Pemerintah sudah mendirikan sekolah Dokter Jawa. Lulusannya akan menjadi mantri cacar bumiputra."
"Baiklah, Tuan Geest. Tampaknya antara Tuan dan saya akan sulit tercapai suatu kesamaan sudut pandang. Jadi saya pikir pembicaraan bisa kita akhiri sekarang. Selamat petang," Van Kijkscherp bangkit dari duduk.
Aku tak menjawab. Sambil melangkah menuju dokar, kupaksa benakku bekerja. Sia-sia. Di mana memperoleh anak dalam waktu sesingkat ini? Kubenamkan tubuh di bangku dokar. Bergidik membayangkan amukan wabah cacar ke seluruh wilayah Hindia. Kurasa para dokter harus bersatu. Minta agar Gubernur Jenderal mengeluarkan peraturan yang bisa menaklukkan orang-orang seperti Van Kijkscherp.
Mendadak kusir menahan kendali.
"Tuan, di sebelah kiri gerbang. Di bawah lampu jalan," katanya.
Aku mengangkat kepala.
"Tuan Diaken?" seruku kepada tubuh tambun di depan.
"Sebentar saja, Tuan." Hendriek Plathart mendekati dokar. "Besok sore, pergilah ke Kenari Laan. Rumah ketiga setelah perempatan, ke arah Meester Cornelis. Kutunggu di situ bersama lima anak mestizo. Empat lelaki, satu perempuan. Tempat itu cukup jauh dari sini, tetapi semoga bisa membantu menghentikan wabah cacar ganas di Bali."
"Terima kasih banyak, Tuan." Kugenggam tangan Hendriek Plathart. "Kami ambil yang laki-laki saja. Jangan yang perempuan. Tetapi bagaimana dengan orang tua anak-anak itu?"
Hendriek Plathart terbatuk beberapa kali sebelum berkata lirih, "Mereka anak-anakku, Tuan. Sebelum menikah dengan istri Eropa-ku, aku pernah hidup bersama seorang wanita bumiputra. Jangan katakan kepada Tuan Pendeta. Janji?" Ia mencari persetujuan di mataku.
Kutatap wajah bulat bersih di depanku ini, yang dalam kegelapan petang itu seolah berpendar di bawah siraman lampu gas, memancarkan cahaya kesalehan sekaligus bara api neraka. Kujabat tangannya sekali lagi.
Jakarta, awal April 2018
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo