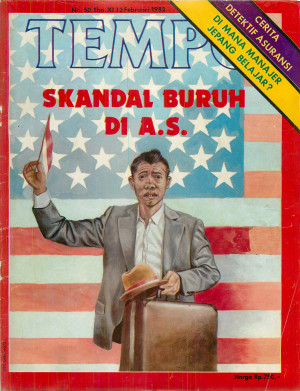O AMUK KAPAK
Sutardji Calzoum Bachri
Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981, 131 halaman
DI dalam colonnes sans fin, Sutardji Calzoum Bachri
mempergunakan tiang tanpa akhir sebagai motif sajaknya. Motif
itu tentunya diambil dari patung pemahat Constantin Brancusi,
yang telah mendirikan sebuah tiang berbuku-buku yang lurus
menjulang ke langit. Gerak ke atas seperti yang dikesankan oleh
patung itu berulang-ulang kita jumpai dalam sajak-sajak
Sutardji. Apakah gerak itu pada "burung/sungai/kelepak/mau
sampai ke langit" (daun), pada para peminum yang mabuk mendaki
gunung "memetik bulan/di puncak" (para peminum) atau pada diri
penyair yang dibawa "ke atas bukit ke atas karang ke atas
gunung/ke bintang bintang" (perjalanan kubur).
Gerak ke atas itu bisa menyaran kepada pencapaian penyair dalam
kerja sastranya, seperti pada sajak nuh: "tanah-tanah-tanah/beri
aku puncak/untuk mulai lagi berpijak!" Kepuasan akan
keberhasilan itu ditunjukkan juga dengan motif tiang tak
berujung Brancusi itu "Tiang tanpa akhir ah betapa kecilnya kau
jauh di bawah kakiku," katanya dengan sombong. Dalam sajak-sajak
lain gerak ke atas itu punya sangkutan dengan salah satu tema
pokok Sutardji, yakni gapaian dan pencariannya kepada Tuhan.
Lingkup perhatian dalam sajak-sajak Sutardji tidaklah luas dan
beserba. Pemikirannya melingkar-lingkar pada tiga masalah hidup
yang asasi, yakni Tuhan yang menjadi teka-teki, maut yang
merundung manusia sejak semula, dan cinta.
Cinta ini ditanggapnya dalam gejalanya yang primitif, sebagai
gairah seks dalam bentuknya yang paling bugil. Misalnya seperti
yang dinyatakannya dalam sajak apakah manusia? yang dimulai
dengan unsur hasrat. Atau dalam bentuk gerak-gerik mekanis,
seperti dalam sajak mesin kawin. Tanggapan yang lahir dari
kejiwaan yang sengaja hendak menanggalkan pakaian peradaban itu
tercermin juga dalam penonjolan judul ketiga kumpulan sajak yang
diterbitkan dalam satu buku ini O Amuk Kapak.
Sudah cukup memperbincangkan orang mengenai Kredo Puisi atau
semacam 'surat kepercayaan' Sutardji mengenai sajak-sajaknya.
"Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban
idea." Pernyataan ini biasanya keliru ditafsirkan seakan-akan
Sutardji dalam menulis sajaknya membebaskan kata dari
pengertian. Sebenarnya pengertian itu masih lekat dengan
tebalnya pada kata-kata Sutardji, bahkan pengertian itu identik
dengan kata. "Kata adalah pengertian itu sendiri," kata penyair
itu dalam Kredo-nya.
Justru karena kata-kata Sutardji masih dihinggai pengertian,
bisa kita tangkap kedalaman pikiran dan kesungguhan
pengalamannya yang tertuang dalam kata-kata penuh asosiasi
seperti ini: "rasa dari segala risau sepi dari segala nabi tanya
dari segala nyata." Bahkan pada kebanyakan baris sajak,
kata-katanya masih tetap merupakan "alat mengantarkan
pengertian" yang justru hendak dihindarkan penyairnya.
Pengertian jelas terungkap oleh kata-kata ini: "aku telah
nemukan jejak/aku telah mencapai jalan/tapi belum sampai tuhan."
Rupanya di antara dalil-dalil Kredonya, yang betul-betul
terlaksana adalah pembebasan kata dari "tradisi lapuk yang
membelenggunya seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain
seperti moral kata." Memang terdapat sejenis keberanian pada
Sutardji, yang mempergunakan kata-kata yang biasa dianggap jorok
dalam pergaulan sopan--seperti menyebut langsung alat kelamin
dan lontaran caci maki.
Paling menyolok adalah tak pedulinya terhadap aturan-aturan umum
tata bahasa. Berbagai fungsi kata telah diputarbalikkan kata
sifat menjadi kata benda ("seribu sibuk"), kata benda menjadi
kata sifat ("yang paling mawar/yang paling duri"), kata
keterangan menjadi kata kerja ("kusangat ingin-Nya"), kata benda
menjadi kata kerja ("kapan kau sayap diamnya batu").
Bentuk jamak tidak lagi diulang sekali melainkan banyak kali,
seperti "dari datuk-datuk-datuk-datukku". Kata ingkar "tak "
dieksploatasi sehabis-habisnya, sehingga lebih ekspresif dengan
meletakkannya pada hubungan kalimat yang tidak biasa: "segala
buntung segala tak tangan", atau "guruh tak ada/kilat tak", juga
"tapi mungkin kalian tak hau masih tak tak". Mengejutkan adalah
kombinasi kata-kata yang tidak pernah terdengar sebelumnya,
seperti "ribubelas babi nyeruduk", "resah-risau resah-balau".
Penyelewengan dari aris umum pemakaian bahasa itu merupakan
unsur kejutan pada estetika sajak Sutardji. Demikian juga gejala
paradoks atau pertentangan pengertian seperti "sepisau nyanyi"
(nyanyi yang setajam pisau?) atau "sebatas allah ' (kekuasaan
Tuhan punya batas?) adalah cara-cara berbahasa Sutardji yang
memukau.
Tetapi bukanlah bentuk-bentuk ucapan itu yang mengangkat
sajak-sajaknya di atas perkembangan sastra dewasa ini.
Unsur-unsur kejutan yang menarik perhatian kepada pemakaian
bahasa sendiri itu hanya menunjukkan adanya suatu gaya yang khas
Sutardji. Yakni salah satu di antara berbagai gaya dalam kerja
kepenyairan modern Indonesia.
Yang sebenarnya menonjolkan Sutardji sebagai penyair penting
dewasa ini adalah usahanya untuk mencapai hakikat kata.
Dikatakannya dalam Kredonya, bahwa ia "mengembalikan kata pada
awalnya". Lebih dari penyair lain, Sutardji sadar akan kekaburan
makna kata. Ia pada dasarnya menaruh curiga kepada kata. Makna
kata selalu berada antara ada-tiada, dan setiap kali luput dari
gapainnya. Tetapi sekali tercapai kata yang benar dan tepat,
kita juga akan mencapai makna yang inti, yang paling mula.
Selama belum tercapai, penyair Sutardji tetap rindu kepada kata
itu. Dan Sutardji bergelut dengan beringasnya untuk merebut
hakikat kata itu.
Hakikat kata identik dengan hakikat Tuhan. Sutardji mengutip
katakata dari Bibel "Pada mulanya malah kata" (Kredo). Rindunya
kepada kata dan perasaan sepinya karena tiadanya kata, pada
Sutardji telah mencapai tingkat dan suasana religi. "sejak kapan
sungai dipanggil sungai", katanya, "sejak kapan tuhan dipanggil
tak/sejak kapan tak dipanggil rindu" (sejak). Dalam sajak lain
ia berkata: "bagaimana penyair bisa sampai tuhan/kalau kata tak
sampai?".
Alif lam Mim.
Hampir putusasa rupanya hendak menggapai kata benar itu,
Sutardji sampai pada bunyi kucing "ngiau" sekedar supaya Tuhan
datang kepadanya. Atau ia memanggil Tuhan dengan kata-kata
kosong tak berarti: "papaliko arukabazako kodega zuzukalibu..."
Kata dan Tuhan tetap merupakan teka-teki. Dan kerahasiaan
itu diungkapkan dengan amat misterius dalam sajak Q, yang berisi
kata-kata Quran alif lam mim di tengah tanda-tanda petik.
Huruf-huruf sampai kini tak bisa diartikan dengan pasti, tetapi
dapat ditafsirkan dengan berbagai macam arti.
Rindunya hendak mempersatukan diri dengan hakikat kata itu telah
menghasilkan pula berbagai sajak tasauf yang mempesona, seperti
sajak sudah waktu, tapi dan dapatkau. Kesadaran mistik itu telah
berkali-kali terucapkan dalam sebutan hampir senapas "aku" dan
"Kau". Juga pada kalimat dalam sebuah sajaknya "aku telah hidup
sebelum musa", kutipan dari ucapan Nabi Isa dalam Bibel.
Pencarian kepada kata dan Tuhan itu menyelusuri juga kumpulan
sajak Kapak, yang menurut kata pengantarnya bertema maut. Tetapi
maut adalah sisi balik dari Tuhan atau hidup. Maka kesepian,
kerinduan, perasaan sia-sia dan pula sinisme karena putusasa
dalam menghadapi hakikat Tuhan, terus meronta-ronta sampai akhir
ketiga kumpulan sajak Sutardji ini.
Perkembangan sajak modern Indonesia, yang pernah dikuasai oleh
sajak naratif sebangsa balada Rendra, oleh Sutardji telah
dikembalikan kepada rel Chairil Anwar yang bertolak dari sikap
dan pandangan filsafat. Sutardji telah membebaskan sajak dari
cerita, dari situasi manusia yang aksidental. Dengan Sutardji
sajak kembali mengungkapkan situasi manusia yang mutlak, yakni
selalu rindunya kepada persatuan dengan asal kejadiannya lewat
penghayatan kata. Bahwa pada dasarnya kerinduan itu terdapat
pada kita semua, dinyatakan oleh Sutardji dalam sajaknya
berjudul Kalian yang berisi satu kata: "pun".
Subagio Sastrowardoyo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini