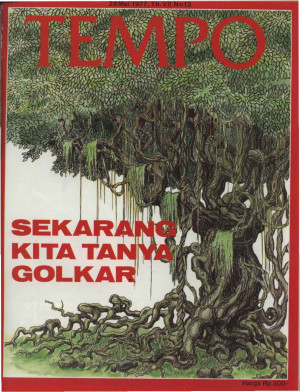10 orang tamu dari Bandung itu bukan orang-orang baru. Mereka
mengisi Galeri Cipta TIM - 9-16 Mei ini - dengan 46 buah karya
patung modern. Tentu saja ruangan yang kecil itu jadi kewalahan
menerima karya-karya yang pada hakekatnya masih memerlukan
ruang. Menikmatinya pun jadi sulit karena kita terseret
membanding-banding. Ada di antaranya yang agresif ada yang
narsis (cinta diri sendiri), sehingga tak bisa dihindari
interaksi dalam ruangan menyebabkan suasana kurang tenang.
Para seniman itu: Edith Ratna, But Muchtar, Bambang Irawan,
Sidharta, Sunaryo, Surya Pernawa, Otong Nurjaman, Rita Widagdo,
Iriantine, Jim Supangkat, memiliki dunia masing-masing. Ada juga
di antara mereka yang mengerjakan motif-motif yang sama,
meskipun dengan watak yang lain. Bambang Irawan (33 tahun) dan
Otong Nurdjan (35 tahun) misalnya sama-sama menggarap mental
dengan kecenderungan sendiri-sendiri. Bambang menangkap gerak
dengan garis-garis ambular dan menimbulkan kesan musikal,
sementara Otong lebih masif dan menangkap momen-momen dramatik.
Tapi keduanya terasa tidak orisinil serta kering karena
formilnya.
Sidharta dan Sunaryo juga sama-sama mengerjakan semacam
totem-totem yang magis. Sidharta cenderung rasionil 2 sementara
Sunaryo menggali intuisinya dengan kiblat totem-totem Irian.
Sidharta (45 tahun) memanfaatkan perenungannya pada kehidupan
dan mencoba memadukan nilai magi pada totem tua dengan kehidupan
praktis yang serba teknik pada masa ini.
Kita teringat ornamen-ornamen AfrDka atau Dayak melDhat
garis-garisnya. Tetapi kita diingatkan pula bahwa kita tidak
hidup di zaman baheula, tapi sekarang, saat ini, di saat sudah
ada satelit - serta pemilu yang penuh tekanan itu. Ini berbeda
dengan Sunaryo (34 tahun) yang tampil dengan bahan-bahan kayu
dan menembus ke pedalaman serta mengangkat suara-suara dalam,
lari sesuatu yang diam.
Sunaryo dari Banyumas berpendidikan Departemen Seni Rupa ITB
serta pelajaran teknik marmar di Carara, Italia. perlu kita
catat karena suasana agrarisnya yang masDh sempat dipertahankan.
Ia berbeda dengan Surya Pernawa (38 tahun) yang juga
mempergunakan kayu (multipleks) tetapi sudah amat rasionil.
Sunaryo sempat menangkap watak diam tetapi berbisa dari
tote-totem pedalaman negeri ini. Patung-patungnya: Inan I, Irian
II, Irian III, Serenada I, Serenada II, seakan-akan melekat ke
bumi. Menyebarkan keintiman, bau lokal, tetapi tidak mengganggu.
Patung-patung itu mewarisi watak monumen tradisional, yakni
memberikan jiwa pada ruang dan menimbulkan keseimbangan yang
mengikat suasana sekitar - tetapi sama sekali tanpa menonjolkan
diri. Hanya kalau kita memberinya perhatian, lantas muncul
detail-detail yang dikerjakan dengan kesederhanaan, keluguan
yang menimbulkan imajinasi yang kaya. Sunaryo berhasil pula
menahan diri untuk tidak membuat duplikat yang bisa
mengakibatkan patung-patung itu menjadi berbau turistis. Di
antara patung-patung lainnya ia tampak paling menampilkan watak
pribumi, dengan ketrampilan teknik yang tidak tercela.
Mempelai Emas Keemasan karya Sidharta barangkali memang sempat
pula menampilkan suasana yang sama dengan patung-patung Sunaryo
-- kendati bobot magisnya sudah berbeda. Sunaryo menggali
kebisuan sementara Sidharta cenderung kenes.
Jim Supangkat. Ia satu-satunya orang yang muncul dengan patung
yang tidak lagi harus dinDai sebagai hiasan. Ia juga tidak
menempatkan karya-karyanya sebagai totem atau monumen yang
memberikan unsur tertentu pada ruangan. Ia menampilkan
kenyataan-kenyataan pahit dan pedih karena orang sudah terlalu
banyak berbicara dengan puisi-puisi gelap, sehingga makna yang
sebenarnya jadi kabur. Ia bicara dengan terus terang - dan
dingin. Maka muncullah patung seperti Si Cantik Lia yang
memperlihatkan sesosok besi di atas roda dengan ujung-ujung
panah di puncaknya. Atau Kursi si Cippi -- sebuah kursi
anak-anak dengan sabuk-sabuk pengikat yang maunya membuat anak
itu keok tidak mampu bergerak lagi.
Memang sangat literer, dan bisa dianggap "kasar" oleh mereka
yang berselera abstrak. Tetapi keterbukaannya dan kemungkinannya
untuk ditunggangi asosiasi penonton merupakan kekuatan utama
patung semacam ini. Jim melemparkan idiom lain -
setidak-tidaknya untuk ukuran pribumi. Di samping itu ia telah
pula mengucapkan kesedihan, kepahitan, penderitaan yang "tidak
indah", yang tak sudi dilakukan oleh senirupa romantik negeri
ini. Karena hidup di tangan Jim begitu kejam, buas tapi toh
harus dihadapi.
Hampir bertolak belakang dengan Jim adalah Rita Widagdo -- yang
kita kenal di Jakarta sebagai pencipta patung (39 tahun) kalau
ditinjau dari dunia Jim jadi terasa seperti pembuat
patung-patung narsis. Karya-karyanya berjudul: Tiga Bentuk,
Empat Bentuk, Marmer Itali, Bentuk Bundar, Dari Dua Dimensi ke
Tiga Dimensi, semuanya monumental dan amat memaksa minta
diperhatikan. Dia tidak menawarkan dialog, tidak menawarkan
suasana - anggun seperti burung merak yang ingin dinikmati
kemulusannya. Rita asyik hidup di tengah alam imajinasinya
sendiri.
Berbeda dengan Edith Ratna Suryosuyarso (31 tahun), yang juga
monumental tetapi lebih sederhana. Edith sangat sensitif, lembut
dan butuh berkomunikasi. Siapa saja yang menonton karyanya
seperti diajak bercakap-cakap. Ia jauh lebih intim dibanding
Rita, lebih human meskipun Rita memang lebih unggul secara
teknis: ia telah mencapai kemantapan dalam jiwa dan kematangan
dalam pengolahan.
Belum Menyentuh
Iriantine (27 tahun), yang paling muda dalam pameran,
mengetengahkan patung-patung "meleleh" yang masih lebih bersifat
studi. Padanya judul-judul patung: Certain Smile, Nuansa, Lotus,
Clown 77, Torso Terkulai, Sudu, masih merupakan
tempelan-tempelan. Ia jelas sedang memantapkan tehniknya serta
asyik dengan kejutan-kejutan yang ia temukan dalam proses. Ia
tidak seperti Jim yang penuh gagasan, juga bukan Rita yang
selesai dalam soal-soal teknis.
Berbeda dengan But Muchtar (47 tahun), orang paling tua dalam
pameran yang berkarya sangat akademis. But menganalisa dengan
cermat sebelum bekerja. Ia melantunkan suasana lukisan-lukisan
kubisme. Kedua patungnya dalam pameran, Ikatan I dan Ikatan II,
lebih terasa sebagai usaha pemindahan keindahan kanvas ketiga
dimensi. Patung-patung ini amat membutuhkan peranan cahaya:
cahaya yang masuk ke rongga-rongganya akan menimbulkan kehidupan
yang berbeda-beda dari detik ke detik.
Teknik dan komposisi merupakan hal yang amat penting. Di samping
itu patung di atas memiliki ruang tersendiri dalam dirinya, yang
membuat kita harus siap membuat analisa bila ingin menikmati.
Ada problim yang selesai dan bersih dalam buah tangannya,
sehingga karya-karyanya lebih menyerupai hiasan ruang dalam gaya
modern.
Keseluruhan pameran belum mampu menyentuh hulu hati. Problem
yang ditawarkan lebih merupakan proble dunia patung. Kadar
kehidupan nyata terasa tipis - pameran ini bersifat akademis.
Sementara dunia senirupa tiga dimensi di negeri ini cukup kuat
dan punya sejarah yang baik. Selain pameran patung jarang,
tantangannya juga beMt. Sehingga untuk sampai pada hasil yang
dapat dipujikan, para pematung di negeri ini tidak seyogyanya
hanya berguru pada teknik dari mancanegara semata-mata. Kalau
bisa tentu saja.
Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini