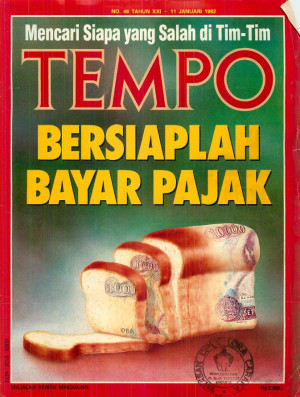KEBOCORAN adalah hal biasa, termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hanya saja, tak banyak yang tahu, berapa besar rembesan dan siapa "tikus-tikus" yang telah merugikan kas negara. Jadi, cukup mengejutkan ketika wakil ketua Komisi APBN DPR RI, Aberson Marle Sihaloho, mengatakan pada akhir Desember lalu, bahwa kebocoran pada APBN 1991-92 mencapai 30 persen. Kalau sinyalemen itu benar, berarti negara digerogoti lebih dari Rp 16 trilyun! Dan, kalau tingkat kebocoran yang sama masih terjadi dalam RAPBN kali ini, jumlahnya naik hingga lebih dari Rp 18 trilyun. Jumlah ini luar biasa, apalagi dalam masa uang ketat seperti sekarang. Ketika TEMPO bertanya, dari mana ia mendapat angka sebesar itu, Aberson mengaku bahwa angka tersebut bukanlah hasil temuannya. Ia mengutip dari sumber yang layak dipercaya, yaitu dari pidato ilmiah pakar ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo. Pidato ini diucapkan dalam acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1990. Angka kebocoran yang dilansir Aberson dibantah oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gandhi. Berdasar perhitungan instansinya, yang berhak memeriksa secara detail laporan keuangan di semua departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen, kebocoran yang terjadi tak sampai 1 persen. Ia mengambil contoh tahun anggaran 1991-92. Sampai semester I, hanya terjadi 68 kasus dengan nilai kerugian di bawah Rp 100 milyar. Berarti, seperseratus enam puluh dibanding perkiraan Aberson. Jumlah ini menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya, yang di atas Rp 100 milyar. Dari kebocoran Rp 100 milyar itu, Departemen Pertambangan dan Energi, misalnya, menyumbang Rp 11,7 milyar, yang menyangkut 42 kasus pelanggaran dan umumnya berasal dari BUMN Pertamina di seluruh Indonesia. Kebocoran di Departemen Keuangan lebih besar sedikit. Sampai dengan 31 Juli 1991, sudah Rp 13,6 milyar bocor. Belum didapat jumlah kebocoran sampai akhir tahun lalu. Sedangkan tahun 1990-91, kebocoran di Keuangan mencapai Rp 24 milyar. Mengenai sumber kebocoran, Gandhi sependapat dengan Sumitro dan Aberson, yakni dari kegiatan dan pembelian barang fiktif serta tender yang direkayasa. Kegiatan fiktif mudah dilakukan melalui pelbagai acara seminar, kunjungan kerja, atau perjalanan dinas yang memakan banyak uang negara. Aberson banyak tahu kejadian ini berdasar temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah, ketika ia mengadakan kunjungan kerja. "Tapi sulit dicek kebenarannya, karena seluruh kuitansi pengeluaran lengkap," ujarnya. Sumber kebocoran terbesar berasal dari pengadaan barang. Bisa terjadi pembelian fiktif atau pengadaan barang dengan mutu rendah. Bukti kebocoran ini baru didapat Aberson ketika ia menemukan sendiri adanya rekayasa tender pada sebuah proyek PLN yang bernilai milyaran rupiah. Kendati ditenderkan -- pura-pura tentu -- tidak diputuskan siapa pemenangnya sampai 9 bulan. Padahal, penawar terendah sudah ada. Agar sumber kebocoran dapat dihambat dan pengawasan lebih ketat, Aberson menyarankan susunan APBN diubah. Sekarang ini penerimaan atau pengeluaran APBN dijabarkan dalam bentuk sektor dan subsektor. Ini menyulitkan DPR dalam melakukan pengawasan, karena tidak jelas proyek yang akan dibangun dan kegiatan yang sedang berjalan. Seharusnya, pos-pos penerimaan dan pengeluaran APBN dijabarkan dalam bentuk program, proyek, sampai satuan kegiatan di departemen maupun lembaga nondepartemen. Karena lembaga-lembaga itu adalah mitra kerja DPR, para wakil rakyat bisa mengoreksi, mana saja kegiatan yang tidak banyak manfaatnya. Anggota DPR yang berkulit gelap ini mengambil contoh sulitnya pengawasan bila anggaran tak dijabarkan dalam proyek. "Mana bisa kita mengoreksi, bila hanya disebutkan anggaran untuk listrik sekian trilyun. Tapi, misalnya, kalau disebut anggaran itu untuk membangun PLTU di Jawa, kita bisa bertanya mengapa harus PLTU dan apakah di Jawa masih kurang pembangkit listrik sehingga harus dibangun lagi. Usul Aberson itu sudah diajukan ke Pemerintah, tapi pihak eksekutif menyatakan, tak sanggup menjabarkan anggaran dengan lebih detail. Padahal, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan sudah melaksanakannya demi memudahkan pengawasan. Sementara itu, Aberson yakin bahwa menyusun anggaran per proyek tidak sulit. Soalnya, anggaran yang sedang disusun pun mendapat data dari departemen dan lembaga nondepartemen, tepatnya dari Daftar Isian Proyek dam Daftar Usulan Kegiatan. Dia akhirnya berkesimpulan, alasan ketidaksanggupan Pemerintah itu hanya trick. Untuk apa? Supaya anggaran bisa diputar-putar dari sektor ke sektor lain, atau subsektor ke subsektor lain. Kalau kondisinya demikian, jelas DPR tidak bisa mengoreksi hal yang salah. Padahal, pengawasan dari DPR diperlukan karena pengawasan fungsional, internal, dan melekat yang sekarang berjalan, dinilainya tidak cukup ampuh untuk mencegah kebocoran. Tentu ada kecenderungan, orang pemerintah akan melindungi kepentingan lembaga pemerintah. BPKP sebagai lembaga pengawas pun, menurut Aberson, kurang berkembang di daerah, padahal obyek pengawasan makin bertambah. Dwi S. Irawanto dan Diah Purnomowati
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini