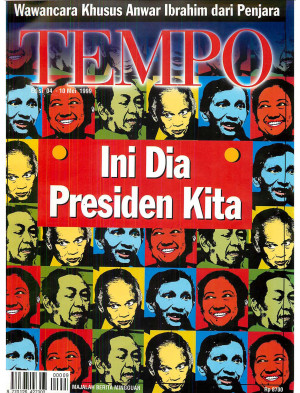--------------------------------------------------------------------------------
Jakarta tiba-tiba seperti magnet besar penyedot dolar. Hanya dalam dua pekan, ratusan juta dolar dari mancanegara mendadak tersedot ke bursa saham Jakarta. Mereka menyerbu dan memburu apa saja yang bisa dibeli.
Saham-saham perusahaan menengah yang sering dinilai sebagai perusahaan kelas dua, seperti Tempo Scan Pacific, Modern Photo, dan Barito Pasifik, mereka borong. Apalagi saham perusahaan jempolan macam Telkom, Astra International, dan Gudang Garam. Pokoknya, semua mereka sikat tanpa sisa.
Belakangan aksi borong ini bahkan menjalar ke saham perusahaan ''kelas tiga" yang kinerjanya masih amburadul. Sejumlah perusahaan properti yang utangnya berjibun, penjualannya seret, dan—tentu saja—prospeknya tak jelas, tiba-tiba harganya melonjak tak ketulungan. Saham Ciputra Development, perusahaan properti yang masih berkutat dengan utang hingga US$ 400 juta, misalnya, naik hampir 200 persen, hanya dalam tempo satu minggu.
Akibatnya, grafik harga saham di bursa Jakarta seperti tokoh kartun yang kena setrum. Jingkrak-jingkrak. Kegilaan investor saham ditandai dengan melejitnya indeks harga saham gabungan. Kamis pekan lalu, indikator yang mengukur pergerakan harga-harga saham di bursa Jakarta itu melejit hingga 592, titik tertinggi dalam 20 bulan terakhir.
Demam bursa bukan cuma menyetrum harga saham tapi juga menyihir nilai perdagangannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perdagangan saham di bursa Jakarta mencapai Rp 1,8 triliun dalam satu hari. Semenjak krisis, nilai transaksi saham rata-rata cuma Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar setiap hari. Pendek kata, di bursa saham hari-hari ini, krisis ekonomi telah dibuang ke laut.
Lalu, pertanyaannya: gelagat apakah ini? Sebuah pertanda awal kepulihan perekonomian Indonesia? Boleh jadi. Bursa saham sering disebut sebagai lead indicator, sebagai gelagat awal dari merah birunya perekonomian masa mendatang. Jika perdagangan saham bursa menghangat dan harga saham menanjak, kita bisa berharap, 6 atau 12 bulan mendatang perekonomian bakal membaik.
Apalagi, bursa saham bukan cuma satu-satunya petunjuk. Gelombang dana asing di bursa itu juga diikuti sejumlah sinyal sedap yang lain. Inflasi, misalnya, cenderung terus merosot. Setelah babak-belur digencet cepatnya pergerakan harga sepanjang tahun lalu, masyarakat mulai bisa mengambil napas.
Empat bulan pertama tahun ini, laju kenaikan harga bahan pangan, papan, sandang, dan transportasi mulai melamban. Dari Januari hingga April, laju inflasi cuma 3,37 persen, jauh di bawah laju inflasi periode yang sama tahun lalu. Dalam dua bulan terakhir, Indonesia bahkan mencatat adanya deflasi alias penurunan harga.
Seiring dengan mengendurnya ancaman inflasi, pelan-pelan suku bunga juga bisa ditekan turun. Dalam lelang terakhir pekan lalu, sertifikat Bank Indonesia (SBI) cuma memberi bunga 31,5 persen, turun dari 35 persen bulan lalu. Sejumlah pejabat moneter yakin, suku bunga SBI bisa ditekan hingga di bawah 30 persen akhir bulan ini.
Turunnya suku bunga SBI akan menekan suku bunga deposito dan akhirnya bunga kredit. Itu berarti, risiko kredit mengendur. Jika tren ini bisa bertahan, ada dua hasil yang bisa dipetik sekaligus: kemampuan perusahaan melunasi utang bakal membaik dan adanya alokasi dana bank untuk kredit baru.
Dari sisi neraca perdagangan, harapan pun setinggi langit. Dalam satu setengah tahun terakhir ini, jumlah dolar hasil ekspor melampaui kebutuhan devisa impor. Selisih yang sering disebut sebagai surplus perdagangan itu, belakangan, terus meningkat, rata-rata di atas US$ 1 miliar per bulan.
Tambahan surplus perdagangan bersama-sama arus modal asing di bursa saham, dan bantuan rutin yang dicairkan dari pelbagai lembaga keuangan internasional, tentu saja menggemukkan cadangan devisa. Ini mempertebal benteng pertahanan bagi rupiah sehingga nilai tukar tak juga goyang kendati diempas pelbagai kerusuhan.
Akhirnya, semua sinyal itu terangkum dalam statistik: produk domestik bruto (PDB) meningkat. Setelah terus menyusut hingga belasan persen, tiga bulan pertama tahun ini, PDB meningkat 1,34 persen. Artinya, aktivitas ekonomi (entah itu konsumsi, belanja pemerintah, investasi, ataupun selisih bersih ekspor impor) tampak menanjak dan menggeliat.
Jadi, kerak terbawah dari krisis ini sudah terlampaui? Begitulah, agaknya, keyakinan para pejabat. Tak mengherankan jika Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, langsung memperbaiki sejumlah target ekonomi makro. PDB yang tadinya diperkirakan akan bergerak dari minus 1 persen sampai plus 1 persen, kini dengan yakin dinaikkan menjadi 0 persen hingga plus 2 persen.
Laju inflasi yang tadinya dipatok 17 persen kini ditekan hingga 10 persen. Bahkan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF), dokter yang mencoba menyehatkan perekonomian Indonesia, Hubert Neiss, yakin bahwa inflasi malah bisa didesak hingga satu digit alias di bawah 10 persen. ''Ini target yang realistis," katanya yakin.
Apa boleh buat, optimisme tampaknya sudah kadung menggelembung. Bahkan Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara Federal Amerika Serikat, Alan Greenspan, juga melihat gelagat yang sama. Dalam sebuah seminar di Chicago, Rabu lalu, untuk pertama kalinya Greenspan mengakui, ''Ada sinyal kuat bahwa Indonesia dan Hong Kong telah melalui situasi terburuk dari krisis."
Mudah-mudahan Greenspan yang omongan dan tingkah polahnya selalu didengar dan jadi patokan pemain uang kelas dunia itu tak meleset. Analis saham SocGen Global Equities, Erwan Teguh, yakin jika gelombang dana asing yang masuk ke bursa Jakarta ini terus bertahan, dalam tempo enam bulan ke depan ekonomi kita bakal menanjak.
Baguslah. Tapi sabar dulu, ada banyak pendapat lain. Tentang serbuan dana asing ke bursa itu, sebagian analis keuangan yakin telah terjadi semacam euforia. Harga saham di bursa New York yang terus menanjak membakar animo investor hingga terjadi demam saham di negeri Amerika Serikat sana. Kegilaan pada surat saham ini mendorong para investor untuk ramai-ramai menyerbu bursa.
Sayangnya, harga saham di bursa AS dan negara maju sudah pada kemahalan. Sudah mateng, kata orang, sehingga tak banyak ruang lagi untuk bergerak naik. Akibatnya, para pemodal mulai melirik (kembali) pasar di negara berkembang, termasuk negara yang baru terhantam krisis.
Betul, harus diakui, kesehatan dan prospek perusahaan di negara-negara itu sudah remuk ringsek. Dibandingkan dengan perusahaan yang terdaftar (listed) di Amerika atau Eropa yang mengkilap seperti Mercy, perusahaan di bursa Jakarta ibaratnya bemo. ''Tapi bemo itu sudah begitu murahnya," kata Direktur SocGen Global Equities, Lin Che Wei. Karena itu, tanpa bisa dibendung lagi, dana-dana investasi dari Amerika dan Eropa berebut menyerbu Asia.
Gelombang ini sebenarnya sudah dimulai sejak Februari lalu, ketika harga saham di pelbagai bursa Asia mulai menggeliat. Makin lama, laju pergerakannya semakin cepat. Sampai awal April grafik indeks harga saham Asia serentak menanjak seperti mendaki gunung terjal. Perdagangan saham di Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul, Manila, dan Bangkok meledak dengan kenaikan harga rata-rata 20 persen, dalam tempo sebulan!
Keuntungan mendadak dari perdagangan saham ini tentu menggemaskan. Bandingkan dengan bunga deposito yang cuma 35 persen setahun, iming-iming 20 persen sebulan tentu lebih dari menggiurkan. Ini mengundang sejumlah pemain baru untuk ikut-ikutan memborong saham.
Akibatnya, gampang ditebak, banjir duit ke bursa telah mendongkrak harga si bemo jadi kemahalan. Fakta bahwa ada sejumlah saham yang terus saja diborong walau kinerjanya amburadul membuktikan bahwa harga saham sudah kebablasan. Ini terjadi di mana saja. Jakarta, Manila, Kuala Lumpur, Seoul, begitu juga Bangkok.
Thai Petrochemical Industry, misalnya. Salah satu penunggak utang terbesar Thailand ini telah menunda pembayaran utang selama satu setengah tahun. Dengan utang US$ 3 miliar yang jatuh tempo tahun ini, Thai punya peluang besar untuk dituntut bangkrut para pemberi kreditnya.
Tapi para investor saham seperti tak peduli. Mereka main embat sehingga harga saham Thai naik tiga kali lipat dalam empat bulan terakhir. ''Ibarat banjir besar," kata Che Wei kepada wartawan TEMPO Agus Hidayat, ''Bukan cuma kapalnya terangkat, sampah-sampah busuk pun ikut naik ke permukaan."
Jakarta? Sama saja. Tiba-tiba saja orang seperti tergila-gila dengan saham perbankan. Benar, sejumlah bank yang ikut rekapitalisasi, untuk sementara, memang akan tertolong dari maut. Tapi tak ada yang menjamin, bank-bank itu bisa tetap bertahan hidup. Saham Bank Bali, yang sedang diuji tuntas oleh Standard Chartered, misalnya, terus diborong hingga harganya naik hampir 300 persen dalam tempo sepekan saja. Investor saling pacu, seperti tak mau ketinggalan kereta.
Kalau mau dihitung rata-rata, harga saham di bursa Jakarta kini dua atau dua setengah kali lipat lebih mahal dari nilai wajarnya. Menurut kalkulasi ekonom dari Lippo Securities, Martin Panggabean, perbandingan antara harga saham dan peluang untungnya di bursa Jakarta kini sudah 20 kali lipat.
Artinya, investor berani membayar proyeksi laba perusahaan yang cuma Rp 100 dengan harga Rp 2.000. Jika laba perusahaan tetap, bisa dibilang baru 20 tahun kemudian sang investor kembali modal. ''Ini gila," kata Martin, ''Masa harga saham di Indonesia sudah mendekati harga saham di bursa New York."
Dengan sifat transaksi yang begitu spekulatif, sebagian besar analis pasar modal yakin, gelombang dana yang mengalir ke Jakarta bukanlah duit jangka panjang yang mau mendekam berlama-lama di bursa. Mereka sangat mobil dan siap terbang jika ada gangguan.
Bahwa sekarang mereka masih bertahan, menurut seorang analis keuangan, itu karena kegilaan akan saham terus ''dipanasi" pemerintah. Caranya, pemerintah ikut rajin memborong sejumlah saham agar perdagangan makin bergairah.
Petunjuk ke arah itu bukan tak ada. Akhir April lalu, analis kita dikabari bahwa sejumlah pengelola dana investasi dari Jepang memborong 10 juta saham Ciputra Development. Tanpa bisa menahan rasa herannya, analis kita ini tertawa meledek, ''Ah, yang benar aja, saham perusahaan loyo begitu diborong."
Sulit dibantah, kinerja Ciputra kurang berkilau. Perusahaan properti besar yang sejak tahun lalu mengaku tak kuat membayar bunga obligasi ini sedang berupaya mengonversi utang US$ 270 juta dengan saham baru. Namanya juga perusahaan properti, pada masa krisis dengan bunga tinggi seperti ini, Ciputra harus puasa panjang. Penjualannya seret.
Namun, tanpa hujan atau angin, pekan lalu harga saham Ciputra tiba-tiba, wus, terbang. Tidak seperti semula, yang tak beranjak dari angka Rp 100 sampai Rp 150, kini mendadak lumpat 200 persen jadi Rp 275. Analis kita merasa aneh bin ajaib. ''Saya heran,'' katanya, ''Tak satu helai rambut pun yang mengubah nasib perusahaan ini." Maksudnya, beban utangnya tetap, prospeknya juga tak beranjak. Sang analis jadi yakin, para fund manager Jepang itu, ''Sudah dapat bocoran bahwa Ciputra bakal digoyang."
Lalu siapa yang menggoyang? Entahlah. Sejumlah analis percaya bahwa pemerintah yang berkuasa punya kepentingan untuk membakar semangat investor di bursa saham. Apalagi menjelang pemilu. ''Jika bursa marak, rupiah tegak, penguasa punya modal besar untuk bertahan di kursinya," kata seorang analis.
Prasangka buruk? Barangkali saja. Tapi campur tangan seperti ini, konon, bukan tak pernah terjadi. November lalu, ketika tragedi Semanggi meletup, publik terkejut: mahasiswa ditembaki, demo tiap hari, tapi bursa bergairah dan rupiah malah menguat.
Belakangan ada selentingan, pemerintah telah ''menyuntik" bursa Jakarta dengan dana siluman melalui beberapa lembaga investasi London. Lembaga ini muncul mendadak dan memborong saham pada pukul 3 sore, satu jam menjelang perdagangan ditutup. Toh, dana yang dibutuhkan tak perlu besar, lantaran tinggal memboceng arus investasi yang memang benar-benar masuk ke Jakarta.
Intervensi semacam ini memang tak pernah diakui. Tapi, kalaupun gosip campur tangan itu tak benar, harga saham yang kebablasan bisa jadi bumerang bagi bursa Jakarta. Euforia bisa menguap sewaktu-waktu jika ada sedikit saja angin keras yang bertiup, entah itu keributan dalam kampanye atau semasa pemilu. Dengan gesit, dana-dana jangka pendek ini akan terbang begitu cepatnya, menclok ke sarang lain yang lebih aman.
Dan ingat, sebelum terbang, uang rupiah hasil penjualan saham itu tentu harus ditukarkan lagi dengan dolar agar laku di luar negeri. Akibatnya, rupiah malah bisa makin tertekan.
Singkat kata, karena amat mobil, dana asing di pasar modal tak begitu bisa diharapkan. Lalu bagaimana dengan indikator yang lain? Hampir sama saja. Inflasi yang terus merosot bahkan deflasi, misalnya, sebenarnya bukan 100 persen kabar gembira. Di balik kendurnya ancaman kenaikan harga, deflasi juga menyimpan hantu lain perekonomian: rendahnya daya beli. Karena kemampuan menyerap barang tak ada, produsen terpaksa menurunkan harga.
Rendahnya daya beli menyulut overkapasitas. Pabrik-pabrik menganggur lantaran barang yang dibuat tak habis terjual. Kalaupun tetap beroperasi, mesin-mesin dipaksa berputar dengan kecepatan minimum agar produksi tak menumpuk di gudang. Akibatnya, jumlah karyawan harus dipangkas atau giliran kerjanya dikurangi.
Ujung-ujungnya, pengangguran meningkat. Menurut data dari Departemen Tenaga Kerja, akhir tahun nanti tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 22 juta orang, naik 10 persen dari tahun lalu. Sulit dihindari, naiknya angka pengangguran dengan mudah makin menurunkan daya beli.
Suku bunga? Suku bunga boleh saja terus turun. Tapi itu tak otomatis mendorong bank untuk mengobral kredit. Di masa krisis seperti sekarang, bank perlu duit untuk dirinya sendiri. Selain itu, risiko kredit macet masih tetap besar. Artinya, sektor perbankan belum mampu menjadi pelumas sektor riil yang membutuhkan uang.
Neraca pembayaran juga boleh terus menguat. Tapi harus dicatat, surplus perdagangan yang terjadi bukan karena aktivitas ekspor yang bergelora. Kelebihan itu lebih disebabkan karena impor begitu loyo. Menurut catatan TEMPO, selama masa krisis ini, nilai ekspor kita menyusut lebih dari 15 persen, sementara nilai impor berkurang lebih dari 20 persen.
Selain indikator-indikator yang tampak ''manis tapi rapuh" itu, perekonomian Indonesia juga tetap dihantui dengan beban utang luar negeri yang tak kecil. Dua tahun lalu, ketika krisis baru mengintip di Thailand, hampir semua ekonom selalu memakai argumen ini: Indonesia tak akan ikut terkena krisis lantaran fundamental perekonomian kita kuat, karena porsi utang luar negeri terhadap PDB tidak besar. Ketika itu, utang luar negeri kita tak sampai 25 persen dari PDB, sedangkan negara-negara yang terkena krisis lebih dari 50 persen.
Tapi, lihatlah sekarang. Porsi utang luar negeri Indonesia sudah mengerikan. Indonesia telah tenggelam dalam lautan utang. Menurut perhitungan Business Week, posisi utang luar negeri kita sudah mencapai 170 persen dari PDB, sementara Thailand tak sampai 100 persen, Malaysia 60 persen, dan Korea Selatan cuma 50 persen. Dengan posisi utang segawat itu, surplus yang diperoleh dari perdagangan mustahil dipakai untuk menutup cicilan utang, kecuali jika para kreditur di luar negeri berbaik hati untuk memberi pengampunan.
Harapan yang terakhir itu pun tampaknya tak akan kunjung datang. Lobi pemerintah yang mengantre di Paris Club (kelompok negara-negara pemberi utang yang mengurusi keringan pembayaran utang) bisa dibilang tak menghasilkan apa-apa. Indonesia cuma mendapatkan perpanjangan masa pelunasan tanpa diskon sama sekali.
Upaya yang dilakukan perusahaan swasta juga setali tiga uang. Sejak dibuka tahun lalu, hingga kini belum ada satu pun perusahaan yang berhasil mengikuti program penyelesaian utang Indra yang didukung pemerintah. Dalam Indra, perusahaan lokal yang berutang dolar bisa mencicil utang dolarnya dalam mata uang rupiah.
Memang betul, ada beberapa per-usahaan yang berhasil melobi krediturnya dan mendapat sejumlah keringanan pembayaran. PT Danareksa Sekuritas, Astra International, dan Bakrie & Brothers kabarnya telah mendekati tahap-tahap akhir dalam perundingan restrukturisasi utang.
Tapi itu juga bukan tanpa masalah. Bakrie & Brothers, yang mengaku proporsalnya sudah mendapatkan persetujuan kreditur, misalnya, kini harus menemui masalah baru. Bank Export Import Amerika Serikat, salah satu kreditur Bakrie Electronics Company, minta agar para kreditur yang lain memeriksa ulang keuangan Bakrie.
Soalnya, menurut perhitungan Exim Bank Amerika, proporsal penyelesaian utang Bakrie agak keterlaluan: masak untuk setiap US$ 1 utang, Bakrie cuma akan membayar US$ 0,06. Itu artinya, kata seorang analis, ''Bakrie minta diskon sampai 94 persen, bagaimana mungkin dikasih?"
Ribut-ribut antara Bakrie dan kreditur agaknya masih makan waktu lama. Soalnya, menurut The Financial Times, para kreditur memang belum menyetujui usulan Bakrie. Yang disetujui para kreditur hanyalah, ''Untuk mendiskusikan usulan itu."
Rentannya dana di pasar modal, rendahnya daya beli, besarnya overkapasitas, tingginya tingkat utang luar negeri dan lambannya program restrukturisasi sektor riil, hanyalah beberapa masalah. Selain itu, masih ada soal-soal nonekonomi, seperti pemilu yang ricuh dan tak jujur, yang siap melemparkan kembali kondisi perekonomian Indonesia ke dalam kegelapan krisis.
Selain itu, masih ada pula ancaman potensial dari luar negeri. Dua raksasa perekonomian Asia, yaitu Jepang dan Cina, hingga saat ini tidak sedang mendukung pemulihan Asia. Cina mendekati resesi, sedangkan Jepang masih juga berkutat dengan sistem perbankan yang tak kunjung bisa dibenahi.
Di luar itu, ada pula Rusia dan Brasil. Kegagalan dua kekuatan ekonomi dunia ini untuk memulihkan kepercayaan investor negara maju seperti tanda start yang akan memicu kaburnya dana-dana investasi dari negera berkembang. Jika ini terjadi, cadangan devisa Indonesia bisa benar-benar mengering.
Singkat kata, ujung terowongan, kendati sudah samar-samar terlihat, masih begitu jauh.
Dwi Setyo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini