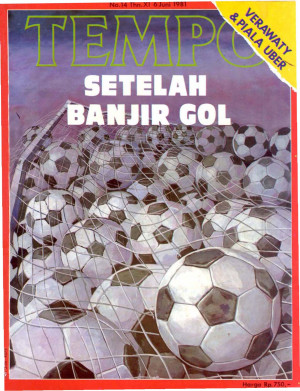PENGIRIM surat ke media ternyata bisa kalap, seperti M. Sudiawidjaja, 31 tahun. Ia jadi mata gelap sesudah berulang kali Bandung Pos menolak sejumlah suratnya. Suatu Selasa pagi ia berusaha membakar kantor koran itu di Jl. Braga, Bandung. Sejumlah arsip surat dan dokumentasi koran sempat terbakar, tapi untung api cepat dikuasai. Tatkala akan ditangkap, Sudiawidjaja, bujangan penganggur dari Cimahi, secara demonstratif membeberkan sejumlah poster, antara lain berbunyi: "Pers beritanya bohong" dan "ASEAN kayak pelawak Ateng." Tak lama kemudian ia roboh di jalan dengan tangan tetap menggenggam golok -- pingsan. Peristiwa pekan lalu itu sempat jadi berita -- berarti penting dan menarik. Tapi apa persoalannya? Menurut Tatos Kesuma, redaktur surat Pos, surat Sudiawidjaja pernah dimuat (Desember 1980) di koran tersebut. Di situ ia menceritakan kesulitannya mencari pekerjaan di Jakarta. Sekalipun sudah punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) -- dibeli Rp 5.000 -- Sudiawidjaja tetap tak memperoleh pekerjaan. Dengan pedas ia mengritik praktek jual-beli KTP di Jakarta. Sejak surat pertamanya dimuat, Sudiawidjaja kemudian sering menulis untuk redaksi Pos. Tapi koran itu tak pernah mau memuatnya lagi. Karena "isinya caci maki melulu, dan bisa-bisa melanggar SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar aliran/golongan)," ujar Tatos. "Mana ada koran maupun majalah yang berani memuat surat seperti itu." Kebijaksanaan redaktur koran itu tentu saja menjengkelkan Sudiawidjaja. "Karena itu lebih baik saya bakar saja kantornya," ujarnya kepada wartawan TEMPO Hasan Syukur. "Saya siap menanggung segala risikonya. " Sudiawidjaja, menurut pemeriksaan medis R.S. Sartika Asih, tidak memiliki kelainan mental. Ia kini berada dalam tahanan pihak berwajib. Persoalan frustrasinya menimbulkan pertanyaan: Patutkah pengirim bersikap demikian terhadap pers, hanya karena suratnya tidak dimuat? Dan haruskah redaktur memuat surat pembaca berisi caci maki yang tak proporsional? Pers biasanya tak mau memuat surat pembaca yang bersifat caci maki kasar, kritik tak proporsional, dan fitnah yang ditujukan kepada pribadi atau instansi tertentu. Jenis surat demikian, kalau toh dimuat, hanya akan menyebabkan pers bersangkutan diseret ke pengadilan. Surat-kabar kampus Salemba, UI, misalnya, pernah berurusan di pengadilan karena memuat surat pembaca (20 Agustus 1979) yang dianggap mencemarkan nama baik seorang pejabat. Di sltu pengirim surat menuduh bahwa sang pejabat menghamili pembantunya hingga melahirkan anak. Untung saja pengadilan Jak.ta Pusat membebaskan Salemba, karena peniuatan surat itu dinilainya "demi kepentingan umum." Untuk melindungi kredibilitas, pers sering meminta kepada pengirim surat melampirkan identitas diri -- berupa fotokopi KTP atau SIM. Dengan cara itu, pers berusaha mencegah masuknya surat yang memakai nama dan alamat palsu. TEMPO, majalah anda ini, pernah juga kebobolan surat yang memakai nama palsu (Singkilaya) dan alamat palsu (di Manado), sekitar delapan tahun lalu. Sekalipun upaya pencegahan sudah dilakukan, pers masih sering jadi korban kiriman surat dari sejumlah pembaca yang tak bertanggung jawab. Mengancam redaksi dengan tindak kekerasan merupakan pengalaman yang sering dijumpii bila surat seseorang tak dimuat. Dan dari peristiwa kekalapan Sudiawidjaja itu, Pos "akan lebih hati-hati lagi menerima surat pembaca," kata Mohammad Siddik, Wakil Pemimpin Redaksinya. "Koran sebagai lembaga masyarakat, memang unik kedudukannya. Tapi tak mustahil, karena kekurangan hati-hati memuat surat, koran bisa jadi sasaran amarah publik."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini