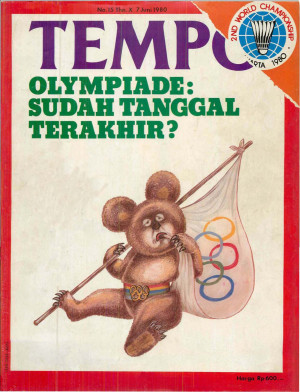INI terjadi 10 tahun yang lalu, atau sekitar itu. Saya bicara
berbisik-bisik dengan P.K. Ojong tentang seorang kenalan kami.
Kenalan ini sehari sebelumnya mengeluarkan suatu pernyataan yang
dikutip pers. Isinya waktu itu memberi kesan yang mengecewakan
bagi mereka yang merasa memperjuangkan, untuk Indonesia, sesuatu
yang layak disebut demokrasi.
Pak Ojong diam mendengarkan. Kenalan itu cukup dekat dengannya.
Karena itu penilaian saya mungkin tak mengenakkan. Tapi kemudian
ia berkata: "Sukar, ya, bagi generasi saudara, ya. Tidak banyak
orang yang bisa dijadikan teladan." Ia seakan tak menjawab apa
yang saya katakan.
Waktu itu ia sudah di atas 45 tahun dan saya belum lagi 30.
Dengan kepongahan anak muda saya sebenarnya tak yakin apakah
generasi saya memang mencari teladan. Tapi beberapa tahun
kemudian saya lebih tahu diri sedikit: kian tinggi jabatan, kian
besar kekuasaan, kian banyak masalah yang pada dasarnya
menyangkut moral diri sendiri. Untuk itu tak ada rumus. Orang
butuh teladan.
P.K. Ojong tak termasuk tokoh yang tampil untuk meneladani. Ia
tidak karismatis, ia tidak flamboyan. Ia tak pandai bicara.
Artikulasinya seperti terganggu oleh aksen Sumatera Barat, dan
saya suka heran bagaimana dia bisa jadi guru. Sejak saya
mengenalnya pertama kali, sekitar 18 tahun yang silam, tak
pernah ia menonjol dalam pertukaran pikiran.
Tapi kenapa ada saat-saat ketika saya memandang ke arahnya
(kendati dari jauh), untuk memperoleh semacam "contoh" bagaimana
suatu masalah harus dihadapi?
Beberpa belas tahun yang lalu tinggal seorang kenalan asing di
sebuah desa di luar Paris. "P.K.", demikian ia menyebut Pak
Ojong yang jadi sahabatnya sumur hidup, "punya sesuatu yang
bis disebut kebangsawanan hati." Saya kemudian tahu apa
maksudnya: seorang yang punya harga diri cukup dan karena itu
tak punya ego yang besar seorang yang terutama hadir untuk
melayani, bukan untuk dilayani.
Siapa pun dapat bicara tentang P.K. Ojong tanpa sekedar upacara
memuji seorang yang baru meninggal: di atas kesuksesannya
sebagai pemimpin perusahaan ia tetap seorang keras untuk tidak
mengistimewakan diri. Seorang rekan yang bekerja dengan dia
sejak masa majalah Star Weekly, bercerita bagaimana pemimpin
redaksi itu tak juga mengganti mesin tik yang dipakainya,
sementara redaksi lain sudah memakai yang baru. Itu hanya satu
contoh.
Sebagai orang-orang yang ikut mengurusi majalah kesusastraan
Horison, kami sering bertemu dalam rapat. Horison adalah majalah
kecil dan dikelola dengan dana kecil. Antar pengurusnya terjalin
semacam pertalian - meskipun kami bisa berbeda pendapat dalam
segala hal. Terutama di tahun-tahun lalu, sering ada pertemuan
di rumah Mochtar Lubis di Tugu, beberapa kilometer yang sejuk di
luar Jakarta.
Di sana biasanya hadir sejumlah sastrawan dan pelukis. Lazimnya
masing-masing bersama keluarga. Acara rapat tentu saja kemudian
tenggelam dalam suasana piknik. Dan di situlah saya mengenal
lebih baik Pak Ojong seorang bapak yang intim bagi keluarganya,
seorang yang setia bagi teman-temannya, seorang pekerja tanpa
pamrih bagi sebuah usaha kebudayaan yang tak spektakuler tapi
sering bikin pusing kepala.
Bayangkan. Dia orang No. 1 dalam organisasi besar yang
menerbitkan Kompas (sekitar 300.000 eksemplar tiap hari) dan
Intisari (di atas 100.000 eksemplar tiap bulan). Tapi dia dengan
bersemangat mengurusi langsung keuangan Horison (tak sampai
6.000 eksemplar sebulan), -- berkala yang tiap kali harus
mengatasi krisis. Singkatnya, ia tetap seperti dulu: di zaman
"Demokrasi Terpimpin" yang penuh tekanan, ia dengan rajin
melayani teman-temannya, mengirimi mereka bahan bacaan yang
tetap bisa dipakai memelihara kemerdekaan berpikir, di tengah
indoktrinisasi yang bertubi-tubi.
Mungkin banyak orang kini hanya melihat P.K. Ojong sebagai
manajer sebuah perusahaan besar di bidang media. Orang mungkin
banyak tak tahu bahwa tokoh yang meninggal mendadak pekan lalu
ini (lihat Pokok & Tokoh) pada dasarnya seorang cendekiawan dari
tradisi yang terbaik: seorang yang mencintai ide-ide, dan karena
itu juga selalu memimpikan demokrasi. Rekan sekerjanya di Star
Weekly mengatakan Ojong di masa itu bahkan sama sekali tak tahu
perkara perusahaan. Dunianya hanya buku dan pemikiran.
Maka Star Weekly yang dipimpinnya, sebelum dibreidel pemerintah
Orde Lama, adalah majalah keluarga yang ternyata juga bicara
tentang teori Arnold Toynbee, atau tentang lukisan mutakhir,
atau pandangan filsuf Islam Muhammad Iqbal (ditulis oleh P.K.
Ojong sendiri).
Rubrik Kompasiana yang dulu ditulisnya di harian Kompas, dengan
populer juga sebenarnya bicara soal-soal pokok -- dan merupakan
inspirasi di hari-hari pertama Orde Baru, ketika kita semua
tengah mencari tata bernegara yang lebih baik. Meskipun seakan
rubrik itu hanya bicara soal pohon di jalan, kembang atau tukang
air di pagi buta.
Barangkali itulah cerminan pribadi Ojong: ia mengurus soal-soal
yang bagi banyak cendekiawan besar dianggap remeh. Ia
memperhatikan kembang dan jembangan, tapi ia yakin ia sedang
menyusun sesuatu yang sangat besar. Atau bukan besar sebenarnya.
"Berharga" adalah kata yang lebih tepat.
Dan berharga, baginya, adalah berharga untuk orang lain. Saya
teringat sebuah buku yang ditulisnya dengan nama samaran setelah
Star Weekly dibunuh. Di sana ia mengecam satu kalimat dalam
drama Jean-Paul Sartre yang termashur, Huis Clos: "Neraka adalah
kehadiran orang lain." Dia memang punya kebangsawanan hati.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini