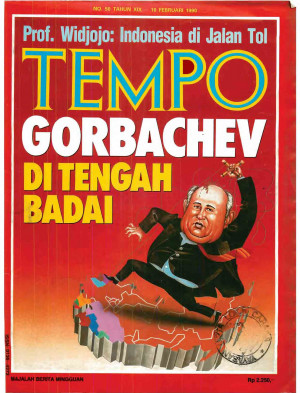Langkah Keseimbangan Lewat Pakjan Misi pemerataan dalam Paket Januari mengharuskan tambahan biaya pada bank-bank tertentu. Pengusaha lemah itu apa? Layakkah pegel beraset Rp 600 juta disebut kecil? DI saat banyak bank mengalam over liquid, dan uang yang diparkir di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) meningkat sampai Rp 3,6 trilyun -- padahal, pada 1988 hanya Rp 800 milyar -- Pemerintah menggelindingkan kebijaksanaan perkreditan baru yang kini dikenal sebagai Paket Januari (Pakjan). Ada pihak menilai, Pakjan adalah koreksi terhadap Pakto, tapi ada juga yang melihatnya sebagai langkah awal ke arah pemerataan ekonomi. Yang pasti, di saat persaingan semakin ketat -- karena banyak bank baru dan lebih banyak lagi cabang-cabang bank yang juga baru -- ada kesan bahwa Pemerintah malah membatasi gerak operasi mereka. Sementara itu, dengan Pakjan, pengusaha kecil tak perlu lagi terlalu merengek-rengek, misalnya untuk sekadar memperoleh kredit beberapa juta rupiah (maksimal Rp 200 juta). Tapi, kenapa? Kini, bank-bank diwajibkan mengalokasikan 20% dari kredit yang disalurkannya kepada pengusaha golongan ekonomi lemah alias pegel. Ini kabar baik untuk pegel, tapi kalangan perbankan dituntut lebih cermat, agar satuan kredit yang bernilai di bawah Rp 200 juta bisa mencapai angka 20% dari total dana yang disalurkan. Dan ketentuan ini tidak mungkin diabaikan, selama para bankir mau agar banknya dinilai sehat. Namun, alokasi itu bukan perkara mudah. "Ini bukan tugas yang ringan," kata Widigdo Sukarman, Direktur Bank BNI. Alasannya, untuk mengejar angka 20%, BNI (dengan 47 kantor cabang) membutuhkan tambahan tenaga yang tidak sedikit -- yang juga berarti tambahan biaya. Soalnya, demi target yang 20% tersebut -- kredit BNI untuk pegel hingga kini baru 13% -- BNI tidak mau mengorbankan kualitas peminjam. Menurut Widigdo, inilah jalan yang terbaik menghindari risiko. Kenapa? Katanya, kredit buat pegel mengandung risiko yang lebih tinggi. Lain halnya pengusaha besar. "Kalau salah satu usaha mereka macet, masih bisa di-cover dengan usaha lainnya," tutur Widigdo. Memang bank-bank besar, seperti BNI, lebih banyak memusatkan usahanya ke corporate banking. Jauh berbeda dari bank-bank yang terbiasa melayani sektor eceran. "Ketentuan itu bukan masalah," kata Hidajat Tjandra Djaja, Direktur Bank Internasional Indonesia (BII). Menurut dia, jumlah KUK (kredit usaha kecil) yang disalurkan BII sudah Rp 200 milyar. Atau sekitar 17% dari total kredit. "Untuk mengejar yang 3% lagi, bukanlah hal yang sulit," ujarnya. Untuk itu, manajemen BII melakukan desentralisasi. Kini, 43 pemimpin cabang BII diberi wewenang untuk memberikan kredit langsung kepada pengusaha kecil, tanpa konsultasi ke kantor pusat. Syaratnya cuma satu: Nilai kredit tak melebihi Rp 200 juta. "Kami pun tidak lagi menjadikan agunan sebagai syarat mutlak, sepanjang usaha nasabah yang bersangkutan dinilai efisien dan menguntungkan," kata Hidajat. Memang, jumlah kantor cabang sangat menentukan dalam memenuhi kriteria 20% ini. Bank Central Asia (BCA), dengan 200 cabangnya, berhasil menyalurkan 30% dari total kredit kepada pengusaha kecil di sektor perdagangan, pertanian, dan industri kecil. Dan, tampaknya sukses. Terbukti, kredit macet di kelas pengusaha bawah ini hanya 1%. "Cabang-cabang kami itulah yang selama ini mengembangkan KUK," kata Abdullah Ali, Presdir BCA. Tentu, tidak semua bank umum bisa berekspansi seperti BCA dan BII. Maka, sebuah jalan keluar ditawarkan oleh Gubernur Bank Indonesia Dr. Adrianus Mooy. Sekarang, bank-bank umum diperbolehkan bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tapi Mooy berpesan, dana yang dipinjamkan kepada BPR jangan sampai digunakan untuk kepentingan BPR sendiri. Juga, jangan sampai BPR memberikan kreditnya kepada nasabah yang sudah beroleh pinjaman dari bank-bank lain, hingga total kreditnya lebih dari Rp 200 juta. Mooy pun menegaskan, jika dalam masa satu tahun masih ada bank yang belum meningkatkan penyaluran KUK-nya menjadi 20%, "Akan kami peringatkan. Dan itu akan kami perhitungkan dalam menilai kesehatan bank yang bersangkutan," ujarnya. Ini sebuah ketegasan, yang disambut hangat oleh kalangan pegel. Hadi Santosa, misalnya, pemilik Daine Shoes yang menjadi bapak angkat 100 perajin sepatu Cibaduyut. Menurut dia, untuk menunjang pemasaran produknya, "Kami memang membutuhkan modal tambahan." Tapi, seperti yang dialami Dadang Suhendar, pimpinan Melati Shopping Centre (juga di Bandung), untuk memperoleh pinjaman dari bank bukanlah soal mudah. "Prosedurnya cukup jelimet," ujarnya. Misalnya, nasabah harus mengagunkan sertifikat tanah, atau rumahnya. Padahal, mayoritas penyewa tokonya rata-rata hanya memiliki tanda bukti pemilikan tanah berupa kikitir. Dan tidak gampang untuk mengubah kikitir menjadi sertifikat. Harus diakui, tidak semua pegel sulit mendapat kredit. Lihatlah koperasi Intako-Sidoarjo, yang beranggotakan 160 perajin tas dan koper. "Selama meminjam atas nama koperasi, tanpa jaminan pun kami bisa memperoleh kredit dari bank," kata Khoiron, Sekertaris Intako. Lain lagi kalau kredit itu atas nama individu. Menurut H. Ghazali, bendahara Intako, prosesnya bisa dua tahun. "Habis, kebanyakan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Banyak bank yang tidak percaya," ujarnya. Terlepas dari berbagai kerumitan itu, bagaimana peluang Pakjan untuk menyukseskan pegel? Mengingat, bahwa kriteria pegel adalah pengusaha yang beraset maksimal Rp 600 juta (di luar tanah dan gedung), layakkah mereka terkategori "kecil"? "Lho, setiap departemen kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri," kata Gubernur Mooy. Di Departemen Perdagangan, misalnya, yang masuk kelas pegel adalah yang beraset Rp 25 juta. Lantas, bagaimana kriteria BI? Tidak jelas benar. Sebelumnya, batasan BI untuk pegel hanya Rp 300 juta. Dan itu, menurut Mooy, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan batasan Bank Dunia yang 500 ribu dolar (Rp 900 juta). Budi Kusumah, Bambang Aji, Budiono Darsono (Jakarta), Ida Farida, Hasan Syukur (Bandung), dan M. Baharun (Surabaya)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini