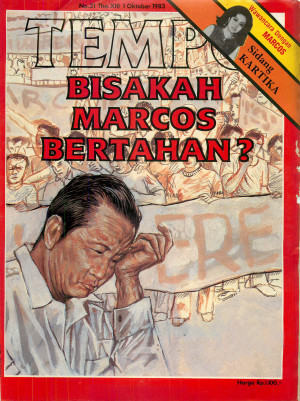HARI-hari ini pihak Direktorat Jenderal Pajak sibuk
mengumpulkan puluhan nama pembayar pajak pendapatan (PPd) pajak
kekayaan (PKk), dan pajah perseroan (PPs) dari Medan,
Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dari
keenam kota itu akan dipiih pembayar terbesar PPd, PKk, dan
PPs, masing-masing 50 nama, untuk dipublikasikan secara luas.
Dengan cara itulah, menurut sebuah sumber, "wajib pajak
dirangsang untuk memenuhi kewajibannya secara tertib dan
teratur." Lewat publikasi itu pula, masyarakat awam bisa
mengetahui siapa yang selama tiga tahun terakhir (1980-1982)
tergolong pembayar pajak besar. "Tidak ada jeleknya cara seperti
itu dilakukan untuk merangsang pengusaha," ujar Sudwikatmono,
direktur kelompok Indocement.
Sudwikatmono menyebut, Indocement yang punya kapasitas terpasan
pabrik semen 1,7 juta ton setahun, belum tentu akan tampil
sebagai pembayar PPs terbesar. Maklum, katanya, sebagian dari
enam unit pabrik itu - yang masing-masing dikelola sebuah
perseroan terbatas sendiri - masih menikmati masa bebas pajak.
Keuntungan yang diperoleh dari ekspansi unit tanur I dan II,
menurut dia, hampir seluruhnya diinvestasikan kembali untuk
membangun tanur ketiga, keempat, kelima, dan keenam sebagai
penyertaan modal (equity ). "Kami bukan mau menhindari pajak,
tapi mau memanfaatkan semua peraturan yang ada," katanya.
Kendati demikian, sebuah sumber berusaha meyakinkan, Indocement
bersama kelompok Astra, Harapan, Gunung Sewu, Samudera
Indonesia, Pardede, dan Berdikari hampir pasti bisa digolongkan
sebagai pembayar PPs cukup besar.
Pihak Departemen Keuangan sendiri hingga pekan ini belum
menjelaskan apakah pembayar pajak terbesar itu kelak akan
menerima kompensasi, misalnya berupa keringanan pajak. Kalau toh
kompensasi semacam itu sulit diberikan, Fuady Mourad, direktur
Panin Bank, mengharapkan agar pemerintah memberikan kemudahan
dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Jadi, jika suatu
perusahaan sudah diaudit akuntan publik yang diakui "laporan
keuangannya tentu tak perlu dikoreksi lagi," katanya.
Sudah menjadi rahasia umum, memang, pihak Direktorat Jenderal
Pajak belakangan ini sering mengadakan koreksi terhadap laporan
perusahaan sekalipun sudah diperiksa oleh akuntan publik.
Perbedaan pendapat biasanya terpusat pada soal pengeluaran dan
cara menghitung penyusutan kekayaan perusahaan yang bisa
mempengaruhi laba bersih akhir. Pengatur suhu ruangan (AC),
misalnya, oleh pihak pajak sering dikategorikan sebagai barang
mewah yang tidak wajib disusutkan. Sedang gedung, kata seorang
akuntan publik, harus disusutkan selama 40 tahun. Padahal, hak
guna bangunan sendiri masa berlakunya hanya 20 tahun. "Jadi,
bagaimana kalau suatu gedung yang belum habis disusutkan sudah
harus digusur karena HGB-nya sudah habis?" tanya akuntan publik
itu.
Perbedaan semacam itu toh masih juga muncul kendati pemerintah,
27 Maret 1979, telah memutuskan akan memberikan keringanan pajak
jika wajib pajak menggunakan akuntan publik untuk memeriksa
keuangan perusahaan. Sadar bahwa keputusan itu belum cukup,
pemerintah kemudian membentuk Tim membina Pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan 27 Maret 1979, yang bertugas mengatasi
munculnya perbedaan pendapat antara akuntan publik dan petugas
pajak. Syukur, sesudah itu jumlah badan usaha milik negara yang
kemudian menggunakan jasa akuntan publik naik dari l.133 sebelum
Maret 1979 menjadi 2.558 perusahaan pada awal 1982.
Dalam kaitan itulah, Fuady Mourad mngusulkan pula agar
pemerintah mau secara terbuka mengumumkan siapa saja akuntan
publik yang dianggapnya sehat. Cara pemerintah menilai dan
menyeleksi lembaga keuangan, katanya, perlu pula diterapkan
disektor ini. Kantor akuntannya perlu pula diterapkan di sektor
ini. Kantor akuntan SGV Utomo dan Budi Utomo, misalnya, sudah
memeriksa laporan keuangan PT Kalimantan Steel Co., tapi
pemerintah toh masih menganggap PMA Jepang itu melakukan
manipulasi pajak. "Umumkan saja, siapa akuntan publik yang
sehat, biar wajib pajak tahu dan tak salah pilih," katanya.
Bukan itu saja yang dituntut wajib pajak. Bagi industri
elektronik menurut Abdul Rahman, direktur PT Sanyo Industries
Indonesia, pengenaan pajak berganda terasa memberatkan perakit
di sini. Berdasarkan peraturan pemerintah, mereka mau tak mau
harus membayar tiga kali PPn - saat mengimpor komponen,
menyerahkan sebagian perakitan pada subkontraktor, dan terakhir
ketika menjual barang jadi ke konsumen. Akibatnya, tentu harga
barang elektronik itu menjadi mahal. Karena itu, "sulit bagi
kami menjualnya murah," kata Abdul Rahman pada TEMPO .
Sebagai PMA Jepang, Sanyo, yang membuka usaha diJakarta sejak
1972, menurut Abdul Rahman kini setiap bulan membayar pajak Rp
300-Rp 500 juta, bagian terbesar merupakan PPn. Seperti juga
kebanyakan pengusaha, dia meminta agar penarikan MPO (menghitung
pajak orang lain), yang merupakan bagian pembayaran PPs, tak
dibayar di muka tapi dibayar sekaligus dalam bentuk setoran PPs.
Maklum dalam keadaan dana serba mahal akibat masih
tingginya suku bunga kredit, "kami banyak membutuhkan uang untuk
modal kerja," kata Abdul. Tapi usul demikian dianggap sulit
dilaksanakan karena mekanisme pembayaran MPO sudah diatur dalam
suatu undang-undang.
Yang juga sulit dilaksanakan, menurut sebuah sumber di
Departemen Keuangan, adalah mengenai usul. Nyoman Moena. Ketua
umum Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta itu mengusulkan agar
penghitungan pajak bank didasarkan atas persentase ari jumlah
kreit yang diberikan, bukan atas laba kotor. Usul Moena rupanya
sulit diterima.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini