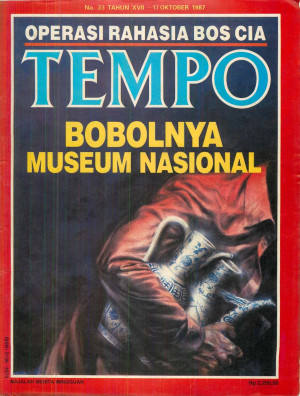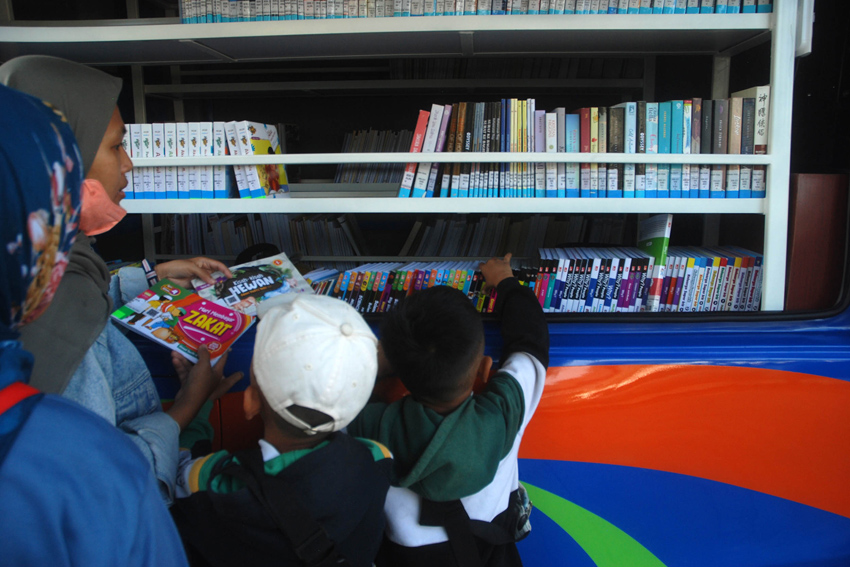ASCARIS lumbricoides namanya, tapi bukanlah Socrates atau Hypokrates, meski ia juga berkulit kuning kemerahan. Ascaris hanya seekor cacing, yang hidup dalam usus manusia sembari menghisap makanan di situ. Berdiameter sekitar 0,5 cm, dengan panjang tubuh 20-40 cm, parasitini menggerogoti tubuh 80% anak-anak Jakarta. Artinya, 8 dari 10 anak di Ibu Kota menyimpan cacing gelang dalam tubuhnya. Selasa pekan lalu Ascaris mendapat kehormatan untuk dibahas dalam sebuah seminar di Jakarta. Diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Proyek Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga, seminar dihadiri pula oleh tiga ahli pemberantasan cacing dari Jepang. Forum itu sendiri -- yang diketuai Soetjipto Wirosardjono, M.Sc., -- terdiri dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kusuma Buana, dan Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia (P4I) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan 8 Pengajaran DKI Jaya. Forum itu juga membuat survei pada 3.354 murid di 35 SD se-Jakarta. Hasilnya: 80% anak sekolah mengidap cacing gelang (Ascaris), lebih dari 50% anak mengidap cacing cambuk (Trichuris trichiura) dan 30% dihinggapi cacing tambang (Necatoramericanus). Setelah tinja anak-anak itu diperiksa satu per satu, ternyata banyak pula anak yang mengidap lebih dari satu cacing terutama gabungan antara cacing gelang dan cambuk. "Memang keduanya sering berjalan sama-sama, kebetulan lingkaran hidup keduanya satu arah," kata dr. Sri S. Margono, dari P4I. Lingkaran hidup cacing gelang, misalnya, dimulai dengan perkawinan cacing jantan dan betina dalam usus halus manusia. Hasilnya tidak kurang dari 200 ribu telur sehari. Untung, telur-telur itu tidak menetas, melainkan ikut terbuang bersama tinja -- dan tampak seperti durian kecil di bawah mikroskop. Waktu tinja (dan telur) jatuh di kebun, halaman, atau tanah, telur jadi matang. Terbawa angin dan debu, telur yang matang ini pada gilirannya masuk kembali ke perut kita -- lewat air dan makanan, termasuk sayuran mentah. Perantaranya bisa serangga, seperti lalat, kecoa, dan, jangan lupa: kuku. Sebuah hasil penelitian di Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung, Agustus 1987, menunjukkan peran kuku ini. "Ternyata, 20% kuku siswa SD yang kami teliti mengandung telur cacing," kata dr. Ridad Agus, dari Lembaga Parasitologi Unpad, Bandung, kepada Hasan Syukur dari TEMPO. Telur-telur yang menetas di usus cepat beraksi. Dalam sehari saja, seekor Ascaris mampu menggerogoti 0,14 gram zat karbohidrat yang diperoleh dari pemecahan nasi, misalnya. Rekannya, cacing cambuk, tidak saja menghisap makanan tapi juga darah. Dan seekor necator bisa lebih nekat: menyedot sampai 0,2 mililiter darah sehari. "Tak heran bila anak yang ditumpangi parasit ini menjadi sering diare, lemah, kurang darah, tak bergairah, dan mundur di sekolah," ujar dr. Sri S. Margono. Lebih-lebih lagi jika ia berada dalam badan anak yang bertubuh relatif kecil -- bahkan di banyak daerah dalam kondisi sangat kurang gizi. "Anak yang bergizi baik pun terpengaruh, apalagi jika gizinya jelek," kata Sri lagi. Seorang peneliti di Surabaya, dr. Koesdianto Tantular, pernah menghubungkan gejala kelesuan itu sebagai apa yang dulu disebut Belanda dengan "kemalasan orang Jawa". Bahkan Koesdianto menyimpulkan bahwa prevalensi (jumlah penderita) cacing tambang di desa dekat Jember dan Lamongan, Jawa Timur, mencapai 60% sampai 90%. (TEMPO, 1 September 1984). Masuk akal, memang, jika di daerah pedesaan dengan tanah yang luas, cacing tambang lebih mudah berkembang -- melalui rute larva yang menerobos kulit kaki petani. Beda dengan perjalanan cacing gelang dan cacing cambuk yang melalui mulut, dan dipermudah oleh kepadatan penduduk serta lingkungan yang buruk. Kesemuanya jelas berkait dengan kebiasaan tidak sehat dan higiene yang kurang baik. Itulah sebabnya para ahli yang berseminar di wisma PKBI itu berpendapat bahwa penanggulangan penyakit cacing di Indonesia mesti dimulai dengan mengubah kebiasaan tak sehat dalam masyarakat. Lebih dari itu, dr. Adi Sasongko, M.A, ketua Tim Pelaksana Proyek, menegaskan, "Usaha pemberantasan penyakit cacing ini merupakan titik awal untuk usaha yang lebih jauh, berupa peningkatan kebersihan lingkungan dan kebersihan diri." Maka, karena yang hendak diperbaiki adalah sikap buruk masyarakat, menurut Adi, tim sering sekali melakukan penyuluhan di banyak tempat, termasuk sekolah-sekolah. "Misalnya dengan pemasangan poster-poster, penyebaran pamflet, ataupun pemutaran film video tentang siklus hidup cacing, yang disumbang oleh ahli Jepang," kata Adi lebih lanjut. Dengan metode begini, ahli dari Jepang pun optimistis bahwa pasien penyakit cacing bisa segera dikurangi. "Kami yakin Indonesia akan lebih berhasil ketimbang Jepang dulu," kata Suzuki, ahli dari Tokyo Health Serice Association. Jepang -- yang mulai dengan masalah berat ini pada akhir Perang Dunia II (1945) -- perlu waktu sekitar 10 tahun untuk menurunkan prevalensi dari 80% menjadi 10%, sedangkan Indonesia mungkin hanya butuh waktu setengahnya. Soalnya, menurut Ny. IIjima, rekan Suzuki, Jepang memulai dengan kondisi yang sangat buruk. Sehabis PD II itu, Jepang memang porakporanda. Tanah gersang di mana-mana, dan dana yang sedikit, memaksa mereka menggunakan pupuk alami, termasuk pupuk dari kotoran manusia, untuk menyuburkan tanah. Tentu saja pupuk tinja itu jadi sumber penularan beberapa penyakit yang sangat potensial. Apa boleh buat. Keberhasilan Jepang, menurut dr. Sri dan dr. Adi, agaknya berkait erat dengan cakupan penyuluhan yang luas -- misalnya meliputi ratusan sekolah sekaligus. Maka, menurut mereka, jika Indonesia ingin sukses pula, hendaknya kuantitas liputan penyuluhan juga diperluas. "Sehingga, diharapkan prevalensi bisa diturunkan sepuluh persen setahun," kata Adi. Akan halnya pengobatan, menurut dr. Sri, hendaknya masyarakat sendiri mau berswadaya -- mengingat murahnya harga obat cacing yang hanya perlu diminum enam bulan sekali itu. Maksudnya supaya beban pemerintah berkurang -- dan bisa dialihkan untuk penanaman masalah kesehatan lain yang mendesak. "Supaya kita tidak jadi parasit seperti cacing-cacing itu," kata dr. Sri setengah bergurau. Syafiq Basri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini