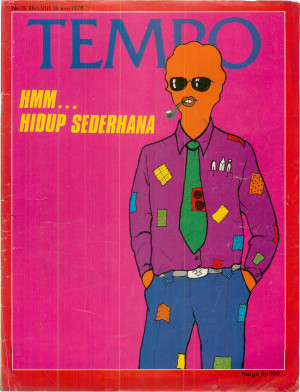PARA petani Banjarmasin sempoyongan pada musim tebas. Mereka
jadi penganggur. Untuk sementara sawah tidak memerlukan tenaga
mereka. Kebutuhan sehari-hari dapat disumpal dengan hasil panen,
meski secara pas-pasan. Sebagai akibatnya, penawaran tenaga
manusia berlimpah, harganya merosot keras.
Pada masa seperti itu, tenaga kerja sehari penuh hanya berharga
Rp 300 sampai Rp 400. Toh asal ada kesempatan orang berbondong
datang -- daripada tidur dan menghitung rusuk rumah. Lalu kalau
pekerjaan tidak ada? Inilah yang mendorong mereka memberondong
kota, berusaha merebut kesempatan apa saja. Belakangan ini,
koresponden TEMPO di Banjarmasin, Rahmat Marlim, menyaksikan
sendiri kedatangan orang-orang desa itu. Ramai.
Disrempet Truk
Dengan memakai sepeda, mereka tampak berkeliling Martapura dan
Bayanbaru menjual atap rumbia. Kalau diperhatikan, mereka
berasal dari Desa-Desa Astambul, Sungai Alat, Pasar Jati --
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Inilah pemandangan yang
tak mungkin dijumpai sekitar 5 tahun di belakang. Petani-petani
ini rata-rata membonceng 100 bidang atap yang disusun
berjepitan. Panjang atap sekitar satu depa. Diikat baik-baik
dengan tali, karena seringkali perjalanan menempuh puluhan
kilometer.
Sejak dahulu memang ada tradisi untuk menjual atap rumbia.
Tetapi para penjual cukup menunggu pembeli di pinggir sungai, di
sampan atau rakit mereka. "Sekarang kami antar sampai ke rumah
langsung," kata Settar, salah seorang penjual atap dari Kampung
Astambul. Lelaki usia 40 tahun ini terang-terangan melaporkan
perebutan rezeki sudah semakin keras, sehingga servis perlu
ditingkatkan.
Abdusyukur, berusia 51 tahun, dari Sungai Alat, sering mengayuh
sepeda sampai tembus ke Banjarmasin -- jarak yang kalau ditotal
tak kurang dari 47 kilometer. Bayangkan bagaimana alot dan tekun
orang tua ini, toh harapan laku tidak selamanya terjamin. Ia
memboyong rata-rata 125 bidang atap. Kalau sudah penasaran ia,
tak ragu-ragu menisik lorong-lorong Banjarmasin. Ini pun bukan
jaminan.
Sering ia terpaksa bermalam. Tidur di sembarang tempat. Yang
paling disukainya di surau, sebab kalau di losmen atau
penginapan lain pasti labanya yang tidak seberapa bisa ludes.
Modal 100 atap rumbia sekitar Rp 1700 sampai Rp 1800. Biasanya
ia berusaha menjual dengan harga Rp 2000. Keuntungan yang tipis.
Toh "kalau pembelinya kurang, kurang dari itu dilego juga,
daripada pulang menggenjot lagi," kata orang tua itu dengan
tenang.
Dengan baju kuyup peluh, muka dinaungi topi, Kakek Syukur
membelah kesibukan jalan raya. Ia selalu mengutamakan sikap
hati-hati, karena anak-anak dan isterinya selalu menunggu dia
dengan was-was. Maklum salah seorang rekannya bernama Suman (30
tahun) sempat diserempet truk sehingga cacat seumur hidup.
Syukur tidak ingin menjadi beban keluarga. Ia justru andalan
keluarganya. Semua tukang atap itu juga andalan keluarga
masing-masing. Mungkin ini yang menyebabkan mereka saling
tolong-menolong. Sering di antara mereka ada jual beli atap,
sehingga membantu terutama yang usia gaek, supaya laku.
Settar, yang punya tanggungan setengah lusin anak, menambahkan:
"Kalau tidak demikian, kami tak dapat menyambung hidup. Maklum
hasil bersawah tak menentu, kadangkala berhasil kadangkala hanya
kembali modal bibit." Menurut pengalamannya, berjualan atap
rumbia sekali boyong belum tentu berhasil satu hari. "Adakalanya
baru laku esoknya, atau bahkan tidak jarang dua tiga hari
kemudian." Karena itu ia sempat menyusun filsafat rezeki "Pasal
rezeki, kalau belum waktunya tiba pada kita," ujarnya dengan
yakin, "tak akan bisa dikejar-kejar. Yang sudah ada dalam mulut
dan perut sekali pun kalau belum rezeki kita, tapi rezeki ayam,
termuntahkan dan dicotok ayam akhirnya."
Terpaksa
Sebelum dijual, menyusun sekian atap di sepeda juga punya aturan
sendiri. Barang itu dionggokkan di ancak belakang sepeda. Nyaris
setinggi orang dewasa -- setelah dipres dengan ikatan tali
plastik yang ditarik kencang-kencang. Di tengahnya dipancangkan
sepotong kayu ulin untuk membagi keseimbangan dan kemantapan.
Untuk ukuran priyayi, berat sepeda itu bukan main. Apalagi kalau
usia sudah gaek. Kalau tak biasa menangani, sekali genjot bisa
tersungkur. Apalagi kalau dipapas kendaraan berat yang kencang
larinya. Jadi kalau tidak hati-hati memang mudah tertimpa nasib
seperti Suman.
Pagi hari konvoi sepeda tukang atap itu merupakan santapan mata
yang seronok. Mereka beriring, berat tetapi lancar, memasuki
Banjarmasin. Kecuali dengus nafas petani yang ngobyek itu, tidak
ada seruan-seruan menjajakan dagangan. Para pembeli yang
berminat harus memperhatikan arus mereka. Kalau petang tiba,
iring-iringan kembali ke asalnya. Beberapa orang yang tak
berhasil menjual hari itu menitipkan atap mereka di
kenalan-kenalan mereka, untuk esok harinya dijajakan kembali.
"Tapi tiga kali pernah atap yang saya titipkan habis disikat
maling," kata Jarkasi, usia 39 tahun. "Terlalu juga. Mengapa
kami yang seperti ini yang dicuri." Terpaksa Jarkasi
memperhitungkan kehilangan itu sebagai hutang. Cara menebusnya,
dengan cicilan. "Untungnya langganan saya mau. Juragan saya pun
percaya. Hutang itu kemudian lunas juga," katanya.
Jarkasi ini memang termasuk orang kuat. Ia sanggup menggenjot
sepeda yang ditongkrongi 150 buah atap. Bahkan sanggup dua kali
dalam sehari bolak-balik dari kampung ke kota. Nafasnya juga
tidak ngos-ngosan. Biasa saja. Ditanya apa rahasianya, ia
langsung menunjukkan falsafah yang dia anut. "Niat saya menjual
atap, agar rumah orang ternaung dari hujan dan panas, yang punya
rumah merasa teduh, hati saya juga teduh," ujarnya dengan kalem.
Tukang-tukang atap Banjar ini rupa-rupanya berbakat jadi
tehnosof.
"Sebenarnya kami ini bukan jual atap. Tetapi jual tenaga saja,"
kata Bakeri dari Desa Pasar Jati. Orang tua berumur 56 tahun ini
bermata rabun. Pendengarannya juga sudah tidak bisa dipercaya
lagi. Toh dia ikut juga mengadu nasib. "Terpaksa. Cari makan,"
katanya. "Anak bukan tidak ada. Ada ya ada, tapi hanya cukup
buat dia anak-beranak juga."
Karena tubuhnya sudah ringkih, ia Sering berhenti di tengah
jalan. Misalnya sambil istirahat di bawah pohon beringin di
Alun-alun Martapura. Tapi ia tidak menyesali nasib.
Kadang-kadang hanya bergurau: "Yah kalau saya pegawai negeri
seperti Guru Simuh, saya sudah pensiun. Tapi saya cuma petani.
Pensiun saya cuma mati." Kalimat terakhir itu katanya hadis
Nabi.
Bakeri juga tidak ingin mengalami nasib seperti Suman. Ia sadar
pada usianya yang tua dan keringkihannya, karena itu selalu
memegang stang sepedanya kuatkuat kalau sudah berada di dalam
kota. "Kalau mendengar deru truk di belakang, wah hati saya
dag-dig-dug. Tangan saya saya tegapkan pegang stang sepeda, hati
terus berdoa agar diselamatkan Tuhan dari musibah diseruduk
truk," ujarnya dengan serius. Dari balik topi purunnya yang
butut kemudian ia berpesan kepada pembaca TEMPO: "Tolong doa
bapak: hari ini atap ini laku cepat."
Pungli
Untuk menghemat, banyak di antara penjual atap membawa ransum
dari rumah. Biasanya dimasukkan ke dalam bakul yang bergelayut
di stang sepeda. Tapi lihatlah, betapa nilai keluarga sangat
tebal. "Kalau laku pagi, kami segera pulang lagi ke kampung.
Makan di rumah saja," kata Settar.
Settar dan kawan-kawan akan lenyap dari jalan manakala kesibukan
sawah sudah memanggil mereka kembali. Jadi pada hakekatnya
mereka benar-benar petani. Atap-atap itu bagaimanapun tetap
hanya sambilan. "Kalau bersandar ke hasil menjaja atap saja,
terang tak cukup. Untung kami punya tanah sawah warisan
orangtua," kata Settar.
Apalagi bagi mereka, selain merupakan sumber tambahan, berjaja
atap memberi variasi. Menurut Settar pemandangan di sepanjang
jalan bisa banyak berbicara. Apalagi pengalaman-pengalaman yang
diperoleh. Lelaki yang menanggung 10 perut di rumahnya ini
sempat mengemukakan perbandingan seperti ini: "Sekarang saya
bisa merasakan bau tengik peluh saya berbarengan debau wangi
pakaian pembeli atap saya." Ya, ini terjadi kalau ada nyonya
yang wangi berkenan beli atap Settar untuk bikin kandang ayam.
Settar sudah menembus jalan sampai Tambela, Aranio, menanjak dan
tiba di Bukit Mandiangin di Riam Kanan. Ia sudah bertemu
berbagai macam pembeli. Ada yang kasihan padanya, lalu
mengeluarkan teh panas dan biskuit. Bahkan sekali ada yang royal
dan menjamu makan. "Tapi tak jarang tak apa-apa. Apa boleh buat,
terpaksa saya minta air putih." Terhadap keadaan pada masa kini,
ia mengatakan cukup puas. "Dulu kami bawa atap ke luar kampung
dicegat, kena pajak. Sekarang, kata orang itu pungli, dilarang
Sudomo. Benar sebutannya begitu, Pak, saya cuma dengar-dengar."
Memang benar, sejak kisah "pungli" ramai digunjingkan, penjaja
atap di Astambul lega dan aman. Dulu pernah ada pungutan
"restribusi" kalau melewati pos Hansip di Kecamatan. "Masak atap
rumbia yang ditanam di bencah dimasukkan hasil hutan. Yang
dicukai justru kami, penjajanya. Bukan yang punya atap," protes
Settar. Syukurlah semuanya sudah berlalu. Tapi kenang-kenangan
itu masih berbekas. "Padahal hansipnya kawan sekampung. Galaknya
masya Allah!"
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini