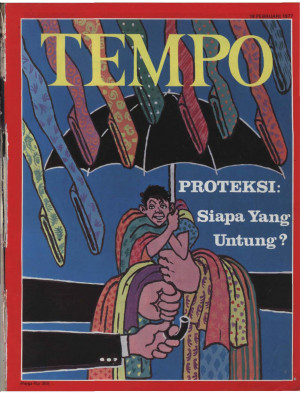SEORANG pasien di sebuah rumah sakit swasta kelas utama di
Jakarta, pertengahan tahun 1976, meninggal dunia setelah dirawat
9 bulan. Selama dalam perawatan boleh dikatakan dia tak sadarkan
diri Sanak-keluarga sekuat-kuatnya menanggung ongkos perawatan
yang tidak sedikit. Rupanya mereka percaya bahwa ikhtiar para
dokter tentu akan berhasil. Meskipun kemudian para dokter
ternyata tak bisa menolong, dan penyakitnya tak berhasil
ditemukan sampai si pasien menghembuskan nafas penghabisan.
Belum seorang pun di antara dokter-dokter kita nampaknya yang
berminat untuk membicarakan apakah penderitaan berkepanjangan
serupa itu perlu diakhiri atau tidak.
Tapi untuk mati sekarang ini jadi bahan pembicaraan yang hangat
di antara para dokter luar negeri. Di bawah ini sebuah bahan
dari International Herald Tribune, 26 Januari, tentang masalah
tersebut:
� Seorang dokter Afrika Selatan dengan keyakinan penuh telah
mengakhiri penderitaan ayahnya yang terserang kanker dengan
injeksi obat bius.
� Di Denmark seorang dokter menolak untuk memadamkan mesin alat
penolong bagi seorang pasien yang otaknya sudah tak bekerja,
karena dia tidak menyetujui sikap mengakhiri hidup seseorang
karena alasan kemanusiaan.
� Seorang kepala rumahsakit di Zurich membiarkan 9 orang pasien
yang sudah sekarat, mati perlahan-lahan dengan mengurangi kalori
dalam makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya lewat slang ke
pembuluh darah.
Ketiga peristiwa tadi menunjukkan perbedaan pandangan para
dokter dalam menghadapi persoalan hak untuk mati bagi pasien
yang gawat. Seorang ahli dari Irlandia menggambarkan pengobatan
terhadap pasien-pasien sekarat sebagai satu daerah yang
samar-samar dalam kode etik kedokteran.
Masyarakat di negara-negara maju di Eropa menyokong hak untuk
mati tadi. Negara seperti Denmark dan Swedia misalnya sedang
didesak masyarakat untuk mensahkan hak untuk mati.
Tekanan-tekanan itu datang dari organisasi yang menyebutkan
dirinya "Wasiat Hidupku" di Denmark. Di Swedia organisasi serupa
menyebutkan diri "Hak Akan Kematian Kami".
Orang Kementerian Kehakiman Swedia mengatakan: Orang-orang sudah
memikirkan masalah hak untuk mati ini. Mereka takut kalau satu
ketika mereka akan mati dengan menyedihkan di rumahsakit".
Ribuan orang di negara itu telah menyampaikan permintaan untuk
mati tanpa penderitaan kalau mereka suatu ketika sakit kronis
dan tak mampu berbicara lagi. Sementara itu di Kopenhagen
sekitar 2000 orang yang bergabung dalam organisasi "Wasiat
Hidupku" telah membubuhkan tandatangan yang meminta hak untuk
mati kepada Kementerian Kehakiman. Dan dari hari ke sehari
jumlah itu terus bertambah.
Dalam sebuah pemilihan pendapat yang dilaksanakan baru-baru ini
di negeri Belanda ternyata 61%, dari suara yang masuk
menyetujui disahkannya euthanasia (mengakhiri hidup seseorang
dengan alasan kemanusiaan) Di Australia 71% dan di Perancis
92%.
Jederal Franco
Di antara mereka yang menyetujui masih juga tersisa persoalan.
Misalnya: Apakah euthanasia yang hisa digunakan? Yang aktif
(seperti injeksi mematikan) atau yang pasif seperti
menghentikan sistim-sistim pertolongan? Kapan hidup berakhir
dan siapa yang menentukan.
Prof Karl Hoermann dosen untuk moral agama Katolik di
Universitas Wina mengemukakan pendapatnya: "Kami menolak
euthanasia aktif dalam menghabisi riwayat seseorang dengan
injeksi membunuh yang dilakukan oleh seorang dokter". Dalam
kenyataannya euthanasia aktif sangat sedikit yang dilaporkan.
Yang umum adalah cara mengakhiri hidup seseorang dengan
menghentikan mesin-mesin penolong.
Tuntutan terhadap hak untuk mati mungkin sudah setua sejarah
pengobatan ketika orang menemukan penderita yang tak
tersembuhkan. Tetapi peristiwa Karen Ann Quinlan di New Jersy,
Amerika Serikat, agaknya merupakan permulaan penting. 15 April
1975 gadis berusia 21 itu tergeletak tak sadarkan diri di
rumahsakit. Dia menderita kerusakan otak yang kemungkinan
sebagai akibat dari minum pil penenang yang tercampur dengan
alkohol. Tujuh bulan dia sekarat. Tak bisa buka mulut untuk
bicara. Bernafas tak bisa, karena itu dia mendapat alat
pernafasan buatan. Tak tahan melihat penderitaan anak pungutnya,
Joseph Quinland, meminta supaya para dokter mematikan alat
pernafasan dan mesin-mesin pembantu lamnya. "Saya ingin dia
hidup kembali secara alami, seperti kemauan Tuhan", kata bapak
anak itu. Tetapi para dokter tak sampai hati melakukannya.
Mereka menolak. Lantas Joseph Quinland berangkat ke pengadilan.
Ia minta hakim supaya meluluskan permintaannya. Hakim akhirnya
memberikan hak itu kepadanya sesudah melalui persidangan yang
hangat dan ramai.
Alat pernafasan dan mesin-mesin pembantu hidup Karen lantas
dihentikan. Keajaiban kedua terjadi lagi pada dirinya. Begitu
semua alat-alat itu dimatikan dia bukannya menemukan ajal. Dia
kini malahan bisa bernafas tanpa bantuan apa pun.
Langkah-langkah dokter di Inggeris tampaknya lebih "maju". "Di
sini para dokter akan segera menghentikan bantuan pernafasan
begitu ada persetujuan dari keluarga pasien. Tak perlu
memperpanjang umur orang melewati batas", kata seorang dokter
yang juga bekerja di bidang pertahanan. "Anda tidak membunuh
seseorang. Anda hanya menghentikan hubungan antara alat-alat
pembantu dengan sang pasien", kata yang lain pula.
Jenderal Besar Fransisco Franco ari Spanyol barangkali adalah
contoh paling bagus dari euthanasia di Eropa, Penderitaan Franco
selama 5 minggu pada tahun 1975 akhirnya menggoncangkan tuntutan
masyarakat ketika ke-30 lebih dokternya memutuskan untuk
mematikan mesin yang memperpanjang hidupnya. Mereka mencabut
mesin itu katanya, karena dengan alat itu Franco bukannya
tertolong, malahan menambah berat penderitaannya. Franco
meninggal keesokan harinya.
Tapi siapakah yang menentukan keputusan tindakan itu? Boerje
Langton, Kepala Dewan Hukum Nasional di Swedia, mengatakan:
"Dokter akan meneruskan pengobatan sejauh masih ada harapan.
Kalau segalanya sudah dikerjakan dan pengobatan berikut ternyata
tak berguna, dialah yang akan menentukan apakah pengobatan tetap
diteruskan atau dihentikan. Dokterlah yang menentukan, bukan
siapa-siapa". Lain lagi pandangan Francis Zacharias, Ketua
Ikatan Dokter Denmark. "Ikatan dokter percaya bahwa manusia
haruslah diizinkan untuk menentukan nasibnya sendiri tentang
berapa lama dia terus menanggungkan bantuan pengobatan",
katanya.
Dicampur Madu
Sementara itu di Belgia para dokter dituntun oleh kode etik yang
ketat. Di situ disebutkan, kalau seorang pasien sudah tak
sadarkan diri, dan pengobatan tak memberikan harapan lagi,
dengan persetujuan sanak-famili mereka boleh menghentikan
mesin-mesin penolong. Tetapi secara pribadi dokter-dokter di
Belgia mengaku bahwa mereka melanggar kode etik tersebut. Kata
seorang: "Keputusan tersebut sangat teknis. Saya memang sudah
dilatih untuk masalah itu". Ia mengaku bahwa dia tidak meminta
nasihat dari famili si pasien. Katanya: "Sanak famili punya
problem rupa-rupa yang harus dipecahkan. Dan tidaklah baik untuk
membebani mereka dengan persoalan tekhnis lagi di mana mereka
tidak pernah dilatih untuk menjawabnya".
Tentang soal kapankah tindakan euthanasia itu dikerjakan, Dr
Anntti Isatalo, Kepala Dewan Kesehatan Nasional Finlandia,
beranggapan bahwa "pengobatan harus dihentikan kalau seseorang
sudah berada dalam keadaan di mana aktifitas otak sudah
berhenti". Di Inggeris pun "mati otak" itu jadi patokan untuk
menjalankan euthanasia.
Malangnya, para dokter di Eropa yang memberikan hak mati kepada
para pasiennya tak luput juga dari tuntutan salah obat dan
pembunuhan. Masih mujur bahwa di negara-negara tadi peristiwa
salah obat amat sedikit kalau dibandingkan dengan Amerika
Serikat. Dan dalam tuntutan membunuh, meja hijau nampaknya
memberikan simpati kepada para dokter. Seperti peristiwa di
Zurich yang diceritakan terdahulu: kepala rumahsakit tersebut
tak sempat diadili. Dia hanya dipecat dan tak lama kemudian
direhabilitir.
Begitu juga dengan kejadian di Liege, Belgia, tahun 1962.
Seorang ibu berusia 25 tahun membunuh anak cacadnya dengan
memberikan obat bius yang dikocok dengan madu. Anak itu cacad,
karena ketika dia dikandung ibunya meminum Thalidomide. Dokter
yang menuliskan resep Thalidomide, suaminya, ibunya dan kakaknya
yang juga terlibat dalam tuduhan pembunuhan ternyata dibebaskan
oleh 12 hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Kemudian di tahun 1973 di Leeuwarden, Belanda, seorang dokter
wanita Geertruida van Boven dituduh telah membunuh karena
memberikan morpin dosis tinggi atas permintaan ibunya sendiri.
Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman satu bulan penjara dalam
masa percobaan 1 tahun. Juga dokter di Afrika Selatan yang
memberikan injeksi obat bius dosis tinggi kepada ayahnya yang
menderita kanker yang dituntut karena membunuh, atas permintaan
Mahkamah Agung dibebaskan selama padilan masih berlangsung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini