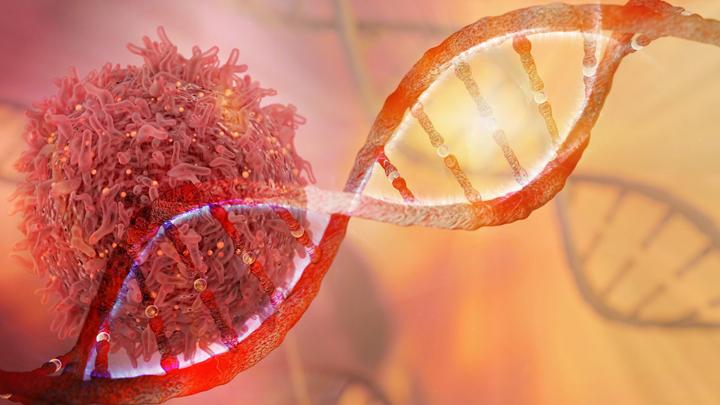PENONTON selalu menjadi wasit terbaik. Atau seperti pepatah
Belanda: nakoda terbaik berdiri di daratan. Tapi dalam setiap
pertandingan sepakbola, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan
hijau tak selalu terlihat oleh penonton. Untung jika reaksi
penonton hanya berupa teriakan-teriakan. Kalau sampai mereka
menyerbu ke tengah lapangan dan menjadikan wasit sebagai bola,
cerita pun jadi lain.
Itu misalnya dialami wasit Soetedjo SH dalam kompetisi Galatama
Minggu 20 Januari lalu di Bandung antara Saribumiraya (Bandung)
lawan Jayakarta (Jakarta). Karena menganggap beberapa keputusan
Soetedjo berat sebelah, pada menir ke-70 puluhan penonton
menyerbu ke tengah lapangan dan mengeroyok wasit itu. Kepala dan
dahinya luka. "Untung tidak sampai parah," kata Soetedjo kepada
TEMPO.
Tentang keputusan-keputusannya yang dianggap tak seimbang dalam
pertandingan itu, dibantah keras oleh Soetedjo. "Mana mungkin
saya memihak Jayakarta," tuturnya, "karena sebelum pertandingan
saya sudah berdoa kepada Tuhan agar diberiNya petunjuk yang
benar." Kapokkah dia? Soetedjo menggeleng. "Kalau orang-orang
tidak mau menjadi wasit lagi, lalu bagaimana persebakbolaan
kita?" katanya. Menurut Soetedjo tak ada kebahagiaan seorang
wasit selain pertandingan yang dipimpinnya berjalan lancar,
tanpa keributan.
Mang Dudung
Oetje Soetedjo (47 tahun) sarjana hukum keluaran Universitas 17
Agustus (Jakarta) adalah juga staf Danjen Koserse MABAK dengan
pangkat mayor. Pria bertubuh kekar dengan 5 orang anak ini
berkenalan dengan bola sejak usia muda melalui klub sepakbola
POP di Persija. Pada 1964 ia mengantongi Certifikat 3 (C3)
untuk menjadi wasit klub dan 1973 memperoleh C1. Kini ia sedang
dicalonkan PSSI untuk menjadi wasit FIFA (organisasi sepakbola
dunia).
Ada 3 tingkat wasit, yaitu C3 untuk pertandingan antar klub, C2,
untuk pertandingan tingkat bond (provinsi) dan C1 untuk
pertandingan tingkat nasional. Bila dipandang telah cukup
berpengalaman, seorang wasit pemegang C1 dapat diusulkan PSSI
untuk menjadi wasit FIFA. Hingga sekarang Indonesia sudah
memiliki 6 orang wasit FIFA.
Semestinya Soetedjo memimpin pertandingan Pardedetex melawan
Grasshopper (Swis) di Senayan 26 Januari lalu. Tapi kebetulan
dalam waktu bersamaan, tetangganya di Kompleks POLRI Pengadegan
(Jakarta) mengadakan pengajian untuk Almarhum Dudung. Ia memang
bertetangga dengan tokoh Reog BKAK yang baru-baru ini meninggal
dunia. "Agaknya Mang Dudung ingin membawa saya juga," katanya
dengan suara rendah mengenang kejadian di Bandung itu. Ia tak
banyak bicara ketika ditanyai lebih banyak tentang pengalamannya
sebagai wasit. "Selama hidup, baru di Bandung itulah saya
merasakan pengalaman pahit" -- itu saja katanya.
Wasit Achmad Karim memang belum pernah mengalami nasib buruk
seperfi Soetedjo. "Sebagai wasit, saya sangat berbahagia kalau
pertandingan berjalan lancar tanpa kericuhan," kata Karim.
Dengan status wasit FIFA, Karim berpengalaman memimpin
pertandingan-pertandingan internasional di Bangkok, Kualalumpur,
Seoul dan Tokyo. Ia mengaku kedudukannya sebagai wasit hanya
hobi. "Di seluruh dunia tidak pernah ada wasit profesional,"
tuturnya. Memang, katanya, wasit menerima uang tugas. Tetapi
kalau uang itu dipandang sebagai upah, "tak seorang pun yang
akan mau menjadi wasit di Indonesia dalam iklim seperti
sekarang."
Bertubuh ramping dengan kumis melintang, Karim (55 tahun)
berstatus tetap sebagai kepala SPG Negeri Bantaeng (Sul-Sel),
kampung kelahirannya. Ia tak mau menyebut berapa honornya
sebagai wasit pada tiap pertandingan. "Sepuluh kali memimpin
perrandingan, belum cukup untuk membeli perlengkapan wasit,"
kata Karim. Sedangkan, tambahnya semua perlengkapan seragam
hitam, sepatu dan kaus kaki -- ia beli sendiri. Yang
menyenangkannya adalah kalau ada kesempatan memimpin
pertandingan di luar negeri. Sebaliknya, yang dia khawatirkan
adalah jika pertandingan yang dipimpinnya kacau. Karena itu,
katanya sebelum memimpin suatu pertandingan, seorang wasit
selalu berdoa lebih dulu, agar mendapat petunjuk yang benar dari
Tuhan.
Wasit yang juga sering menulis artikel tentang perwasitan di
beberapa koran ini, berpendapat, "untuk menjadi wasit secara
teoritis gampang, cukup kursus 3 minggu." Tapi yang penting,
menurutnya, adalah pengalaman praktek. Di lapangan, seorang
wasit dituntut agar berpikir cepat, ingat semua peraturan
pertandingan, punya reaksi yang cepat untuk memberi keputusan
dan dalam detik itu juga harus menerapkan keputusannya. Tapi
lebih penting lagi adalah kepribadian. "Seorang wasit akan
hilang wibawa tanpa punya kepribadian yang kuat," tambah Karim.
Karim tak setuju jika ada pendapat bahwa pemain tak perlu
menguasai peraturan pertandingan. "Justru para pemain yang harus
mengetahui peraturan," ucapnya, "karena mereka yang main, sedang
wasit hanya pengawas." Tentang pemain yang memukul wasit,
menurut Karim, "jelas itu kesalahan ofisial."
Wasit Sanusi dari Cirebon misalnya pernah juga dipukul pemain.
Suatu ketika ia memimpin pertandingan PSIS (Semarang) melawan
Persis (Sala). Seorang bek Persis memprotes ketika
ksebelasannya dihukum dengan tendangan penalti. Tapi Sanusi
tetap pada keputusannya. Dan setelah pertandingan usai, bek tadi
langsung memukul Sanusi. Ketika itu juga ia memberi kartu merah
dan si pemain diskors Komda PSSI Sala. "Bila pemain melakukan
pelanggaran yang membahayakan lawannya atau bermain tidak sopan,
dapat langsung diberi kartu merah, tanpa lewat kartu kuning
dulu," ungkap Sanusi.
Wasit golongan C1 ini sehari-hari adalah karyawan Departemen P &
K Cirebon. Semula ia adalah pemain PSIT Cirebon. Sejak 1964 ia
lulus wasit C3. Ia juga mengaku menjadi wasit hanya sebagai
hobi. Dan ia tak ingin seorang pun dari ke-5 putranya menjadi
pemain bola. Ketika belakangan ini sering terjadi keributan di
lapangan hijau, menurut Sanusi (45) istrinya selalu berdoa
setiap kali suaminya hendak memimpin suatu pertandingan.
Pernahkah ia didekati tukang-tukang suap? Ia menggeleng.
"Kalaupun ada pasti tak saya layani," katanya, "sebab yang
menentukan pertandingan para pemain, bukan wasit."
Pengalaman duka di lapangan hijau juga pernah dialami R. Hatta,
seorang di antara wasit FIFA di Indonesia. Dalam pertandingan
antara Indonesia Muda lawan Angkasa di Surabaya Maret tahun
lalu, tiba-tiba saja ia telah dikerumuni dan langsung dikroyok
pemain-pemain Indonesia Muda. Gigi palsunya mental dan mukanya
babak belur. Keputusannya dinilai tidak adil. "Memang sulit
untuk memuaskan semua pihak," ucapnya kepada TEMPO, "kejadian
itu paling buruk dalam pengalaman saya."
Menurut Hatta berada di lapangan jauh berbeda dibanding jadi
penonton. Ia mengambil contoh seorang pemain meludahi atau
mengejek wasit. Pemain lain di dekatnya mungkin tidak mengetahui
kejadian itu, apalagi penonton. Lalu jika kemudian wasit memberi
kartu kuning atau merah, penonton atau pemain lain yang tak tahu
itu marah-marah -- padahal apa yang dilakukan sesuai dengan
peraturan.
Namun Hatta (45 tahun) tak merasa perlu mengundurkan diri karena
pengalaman pahit itu. Apalagi karena ia tetap memandang wasit
sebagai pengabdian. Soal honor tak begitu ia hiraukan. Sebab
memang ternyata tidak besar. Ia menyebut pendapatannya Rp 1.000
sekali main di kompetisi Persebaya, Rp 1.250 jika pertandingan
antar instansi dan Rp 7.500 untuk kompetisi PSSI/Galatama. Tak
ada gaji tetap. Sehari-hari ia adalah karyawan PT Karya Adiguna
dan istrinya, Sutrialin, bekerja di PTP XX Surabaya. Dari
sumber-sumber itulah rumah tangganya berjalan.
Pengalamannya yang lain adalah ketika 1976 memimpin pertandingan
Persebaya melawan Ayax (Belanda) di Surabaya. Penonton berjubel
di Stadion 10 Nopember, diperkirakan sekitar 100.000 orang.
Tentu saja hasil pertandingan dapat mencapai puluhan juta
rupiah. Tapi Hatta hanya mendapat honor Rp 1.500.
Laki-laki yang sehari-harinya adalah salah seorang staf di
perkebunan kelapa sawit PTP VI Pebatu, Tebing Tinggi (Sum-Ut)
itu bernama R. Hamler. Sudah haji. Mungkin karena itu ia tampak
tetap berlapang dada sehabis mengalami kericuhan di Stadion
Teladan (Medan) pada pertandingan antara Indonesia Muda lawan
Pardedetex akhir Desember 1979 lalu. "Malahan istri dan
anak-anak saya terus mendorong agar saya tetap menjadi wasit,"
tuturnya.
Tentu saja kejadian itu tak mungkin ia lupakan. Disertai
ejekan-ejekan penonron Medan, ia telah menjadi bulan-bulanan
beberap main Pardedetex, termasuk para ofisial klub ini. Dia
babak belur. Untung petugas-petugas keamanan segera
menyelamatkannya ke luar lapangan. "Itu risiko wasit," tuturnya
kemudian kepada TEMPO. Keributan berpangkal pada beberapa
keputusannya yang dinilai penonton maupun pemain Pardedetex
tidak adil. Tapi Hamlet sendiri tak menyalahkan siapa-siapa.
"Habis tingkat kita baru sebegitu," ucapnya, "kita belum
mengerti bagaimana sebenarnya permainan yang baik dan sportif."
Bermain Bersih
Untuk menjadi pemain maupun penonton yang sportif, menurut
Hamlet, harus dikaitkan dengan sikap moral. Sikap ini
dipengaruhi berbagai faktor, katanya, antara lain lingkungan dan
motifasi. "Untuk menyaksikan suatu pertandingan bola yang
sportif, baik pemain maupun penonton kita, masih butuh waktu,"
ungkap Hamlet, "dan itulah kira."
Hamlet (42 tahun) telah menyandang gelar wasit FIFA sejak 1975.
Semula ia pemain Bunut Sporting Club Kisaran, sebuah perkumpulan
bola dari pabrik karet di Bunut (Kisaran) tempat ayahnya
bekerja. Sang ayah juga pernah bermain untuk klub itu. Antara
1957-1959 Hamlet pindah ke klub Dinamo Medan sekaligus sebagai
kanan luar PSMS. Ia berhenti sebagai pemain sejak bekerja di
perkebunan kelapa sawit. Tapi tak lama setelah ia menggantungkan
sepatu bolanya, 1965 ia mulai tampil sebagai wasit.
Beberapa pertandingan internasional pernah dipimpinnya. Paling
berkesan menurutnya adalah ketika ia harus mewasiti Malaysia
melawan Korea Selatan pada Merdeka Games beberapa tahun lampau
di Kualalumpur. Ia tahu waktu itu Malaysia ingin sekali menang.
"Mereka bermain bagus, tapi lawan lebih bagus lagi," ungkapnya.
Tapi kedua pihak bermain bersih. Begitu pula penonton tuan rumah
tertib, malahan mereka mengejek pemain Malaysia ketika harus
menyerah 4-0 pada lawan. "Masing-masing pihak sportif,"
tambahnya. Dan ia puas -- satu-satunya harapan setiap wasit
telah tercapai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini