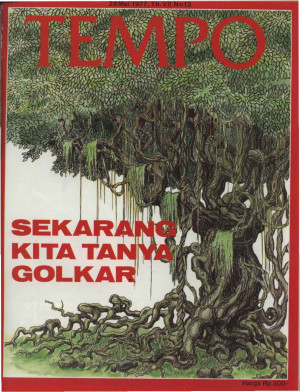BAGI banyak orang mengumpulkan lukisan mungkin kerja orang
gendeng. Di samping biayanya meliputi deretan 0 yang panjang,
juga menyimpannya merupakan soal yang memusingkan. Kolektor
seperti Adam Malik yang punya ratusan lukisan, sampai merelakan
koleksinya untuk pajangan museum. Sementara lihatlah rumah orang
seperti Alex Papadimitrou, kolektor terkemuka di Jakarta, yang
tumpat padat oleh lukisan bagaikan gudang. Apa lukisan itu tidak
lebih rewel dari anak-anak misalnya?
Tapi kemudian bayangkanlah sebuah lukisan Amri Yahya yang kini
telah sanggup mencapai harga Rp 3 juta. Bukan main. Ini memang
semacam kubangan yang boros tetapi juga sekaligus investasi masa
depan yang amat menguntungkan seperti yang dibayangkan oleh
Alex. Tergantung dari kepintaran memilih barangnya. Artinya,
pada akhirnya, di samping memang benar-benar mengandung moral
mencintai seni -- juga ada segi dagang di baliknya.
Dalam suatu kesempatan wawancara dengan Adam Malik di rumahnya
perihal lukisan-lukisan yang ia canangkan untuk isi Museum
Senirupa, ternyata ia juga tidak benar-benar hafal piaraannya
itu. Misalnya tatkala ditanyakan siapa pelukis lukisan yang
tergantung di dinding depan ia mengelak dengan bijak. Ini boleh
jadi karena tidak semua lukisan di dinding seorang pejabat
dibeli.
Bisa hadiah. Ia harus dipajang meskipun tidak perlu diketahui
siapa pelukisnya. Sementara di sebuah rumah di bilangan Ancol,
Eben, seorang pedagang lukisan dengan pasih bisa menerangkan
lukisan-lukisan yang ada di dinding rumahnya. Ia pun punya
pengamatan yang ahli dari segi artistik maupun komersiil.
Di Surabaya masih ada kolektor 400 buah lukisan. Rumahnya di
jalan Diponegoro dengan teras gelondong kayu. Namanya: Soenarjo
Oemar Sidik. Ia tidak hanya memiliki tapi juga mencintai.
"Semuanya terbentuk dengan tidak sengaja", kata orang tua yang
bercambang dan berambut putih itu. Dalam bahasa Jawa ini disebut
dengan istilah "dadi karepe dewe". Tidak didahului dengan
perencanaan. Pada tahun 1950 Soenaryo mulai membeli sebuah
lukisan untuk menghiasi rumahnya. "Dari satu yang saya anggap
sebagai kebanggaan ini, lalu saya ingin beli lagi yang kedua,
dan seterusnya", ujarnya pada TEMPO.
Pabrik Es
Sementara deretan piaraannya bertambah, diam-diam makin merasuk
pula rasa cintanya. Dengan kata-kata yang berlebihan dia
simpulkan: "Bahwa seni adalah kehidupan, tanpa seni tak ada
kehidupan". Yang jelas seluruh dinding rumahnya penuh
bergelantungan segala macam lukisan dari berbagai format dan
aliran. Ada Affandi, Sudjojono, Rusli Barli, Kartika, Abas,
Tedja serta pelukis-pelukis Surabaya seperti Daryono, Amang
Rachman, Isbandi dan tidak terlupakan Karjono JS -- pelukis yang
paling dikaguminya sampai saat ini.
Deretan nama ini memang segera membayangkan berapa nol nilai
seluruhnya. "Lukisan itu mahal harganya, malahan sebenarnya
sulit untuk dinilai dengan uang", kata Soenaryo yang pengusaha
pabrik es. Dengan terus terang ia mengaku, berkat persobatannya
dengan para pelukis, lukisan itu bisa dibeli cicil seenaknya.
Tapi ulahnya ini malah membuat para pelukis itu merasa berhutang
budi lalu pingin menyebutnya sebagai "bapaknya seniman".
Ia menolak untuk disebut kolektor. Karena ukuran utama profesi
itu baginya dalah duit banyak dan mutu ]ukisan yang hebat.
Kendati ia mencintai seluruh isi dindingnya ia masih sangsi
adakah orang lain bisa menerima baik kwalitas koleksinya. "Buruk
baiknya lukisan tidak terpancang karena "dug" atau semata-mata
kwalitas cat", ujar Soenaryo dari balik asap tembakau Mars Brand
yang selalu dicangkingnya kian ke mari. Ia memperlihatkan betapa
hampir tak pernah ia merawat lukisannya secara khusus. Ini boleh
saja berakibat ada kemunduran dari segi warna serta ketahanan
kanvas.
Lukisan-lukisan itu seperti terpatok di dinding dan menjadi
sebagian isi rumah yang membisu di tempatnya. "Paling-paling
kalau dinding rumah akan dikapur, ya sekalian debu yang melekat
dibersihkan, baru mau tak mau lukisan itu diturunkan", tutur
orang tua ini. Ini sedikit berbeda dengan apa yang kita jumpai
di rumah kolektor Alex Papadimitrou, Jakarta. Di sini lukisan
seringkali harus pasang bongkar, karena kebutuhan pameran.
Dipinjam atau bisa jadi ditukar oleh lukisan lain oleh sesama
kulektor.
Meski dengan rendah hati tak sudi disebut kolektor, orang tua
ini ternyata, juga diam-diam telah mencintai lukisan dengan cara
memberikannya pada orang lain. Sejak tahun 1951
sekurang-kurangnya sudah 300 (tiga ratus) buah lukisan ia oper
kepada 215 orang kenalannya. Ia memiliki daftar lengkap dan bisa
jadi merupakan sebagian dari kebahagiaan masa tuanya. Di sana
tercatat nama-nama seperti: Jenderal Polisi Soekarno
Djojonegoro, Prof. Mr. Toha, Samadikun, Kolonel Soekotjo, Mayjen
Moh. Wijono, Prof. Eri Sudewo, Jenderal Sunitro dan lain
sebagainya. Dalam usia 56 tahun kini (memakai setelan putih), di
antara koleksanya ia seakan-akan seorang bapak yang amat
berbahagia dan bangga. Ia mengutip sabda yang berbunyi: "Memberi
habis-habisan, tapi makin kaya". Pekerjaannya yang banyak
menghamburkan duit itu disertai pula penghargaannya yang nyaris
kultus pada pribadi seniman. "Mereka adalah manusia biasa plus
X", katanya menerangkan lalu disertai oleh pendapat bahwa "seni
itu tak pernah mandeg apalagi nundur". Maka wajar bila ia
mengatakan bahwa pelukis-pelukis kini sudah bnyak kemajuan bila
dibandingkan denan pelukis di zaman PERSAGI.
Bagi Soenaryo yang mampu membelanjai "cintanya" itu, jelas
mengumpulkan lukisan tak ada dukanya. Ia punya uang, punya
hubungan baik dan punya nafsu untuk memberi pada orang lain. Ini
berbeda dengan apa yang dialami leh sama-sama kolektor yang
bermukim di Surabaya, Oei Bun Po. Tokoh ini berusia 70 tahun
pemilik apotik Madya di jalan Simolawang Baru. Ia mengumpulkan
lukisan sejak berusia 12 tahun. Dengan rajin ia menyisihkan uang
sekolahnya lalu bergegas ke toko beli lukisan sekitar harga 10
sen. Hingga ia memiliki ratusan buah lukisan. Tetapi malang tak
dapat ditolak. Pada tahun 1945 rumahnya terbakar, lalu lenyap
pulalah "tambang masa depanya" itu. Sekarang ia memiliki nasehat
begini untuk dirinya sendiri: "Saya tidak perlu mengoleksi
lukisan banyak-banyak, biar sedikit, pokok yang pilihan sekali".
Kini ia memiliki sekitar 40 buah lukisan pilihan. Di antaranya
ada nama Affandi, Hendra Goenawan dan Srihadi 3 nama yang
menjadi pujaannya. Lukisan Srihadi pernah digebraknya di tahun
1965, 12 buah sekaligus seharga a Rp 5000. Waktu itu orang masih
belum tahu anak muda itu bakal begitu menanjaknya, sehingga kini
lukisannya berharga sampai Rp 1 juta per buah. "Terhadap
lukisan-lukisan ketiga pelukis itu, saya nggak akan menjualnya
kepada orang", kata Oei. Pernah sekali ada yang datang mau bujuk
beli karya Affandi yang bernama "Orang Jual Nasi Gudeg Di Masa
Revolusi" seharga Rp 5 juta. "Saya tolak", tukas Oei tandas.
Sebagaimana juga beberapa kolektor di Jakarta, Oei mengaku
pernah menjual lukisan di samping membeli. "Itu saya lakukan
bila keadaan saya krisis", katanya. Uang yang diterimanya
rata-rata sekitar Rp 1 juta. Krisis itu tatkala ia harus menutup
toko alat-alat listriknya di jalan Kembang Jepun. Demikianlah
lukisan itu telah sanggup membalas cintanya dengan menyelamatkan
sang tuan, dengan harga yang tidak kecil. Seperti kata orang,
lukisan itu tidak ada yang turun harganya. Makin disimpan makin
mahal. Tak heran kalau Affandi menyindir melihat banyak orang
suka memborong lukisannya sambil mengharapkan bisa menelorkan
duit bila ia telah tiada.
Oei merawat piaraannya secara khusus. Tiga minggu sekali ia
membersihkan debu-debu yang menempel. "Lukisan-lukisan itu harus
digantung di dinding, jangan ditaruh di bawah", katanya memberi
nasehat. Berbeda dengan Soenarjo, ia menilai senilukis Indonesia
zaman PERSAGI unggul timbang hasil-hasil masa kini. "Saya lebih
mengagumi zaman PERSAGI, sebab yang sekarang ini lebih berbau
komersiil sehingga bobotnya kurang".
Kecintaan Oei pada lukisan, serta hubungannya yang erat dengan
Affandi, membuatnya berada di lereng Gunung Agung pada tahun
1963. Sedang sibuknya kawah mengamuk, mereka berdua berusaha
untuk memotret peristiwa itu. Di sana menyaksikan lewat mata
sendiri batu-batu sebesar rumah serta kaki dan tangan manusia
yang sudah terputus dari tubuhnya. Lewat jepretan itu kemudian
Affandi mendasari beberapa buah karyanya.
Di lain saat, bersama orang yang sama dia sudah berada di pantai
Kesombe - di kawasan Bali juga. Dengan kedua belah tangannya ia
menahan kanvas Affandi, (lupa membawa dug tempat melukis). Ini
berlangsung tidak kurang dari satu jam -- waktu rata-rata yang
dibutuhkan Affandi untuk sebuah lukisan. Ia ikut menahan terik
matahari sembari terpesona oleh kegairahan melukis si pelukis
kawakan yang seperti orang edan itu. Apalagi sedang getol
memplotot-plotot tiba-tiba saja sang pelukis kemudian tersungkur
ke atas pasir panas - tak sadarkan diri. Dasar seniman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini