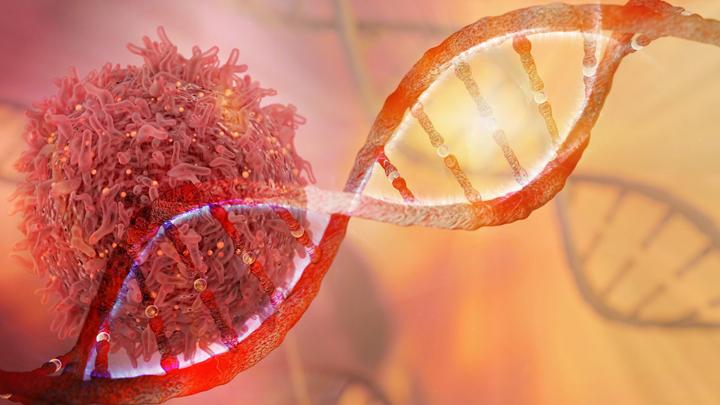DAHLAN membawa murid-muridnya ke stasiun. Setelah sampai
anak-anak itu disuruhnya jongkok dan meraba rel kereta api.
"Sudah tahu, rel itu seperti apa? Nah, begitulah," kata Dahlan
AS, 36 tahun, setelah kembali di kelas 4 SD/Sekolah Luar Biasa
(SLB) di Jalan E.S. Fatmawati Jakarta untuk melanjutkan pelajaran
IPA.
Dan sejak itu para muridnya yang tunanetra itu pun paham benda
apa yang bernama rel kereta api itu. "Habis, mereka tak mungkin
dapat membayangkan seperti apa itu rel. Ada yang bilang loncong,
bulat, rata, lebar dan lain-lain," tambah Dahlan.
Rupanya peragaan untuk menerangkan suatu pelajaran agar
diketahui anak-anak yang tak dapat melihat, bukan hanya soal
rel. Dahlan juga sulit menerang kan bentuk sapi Australia yang
biasa diperah. Setelah memutar akal, ia panggil salah seorang
murid laki-laki. Anak itu disuruh merangkak di depan kelas. Si
murid pun tahu, sapi berkaki empat. "Nah, coba. Di mana letak
susu yang di perah itu?" kata Dalian, tamatan SPG yang mengajar
anak tunanetra di Cilandak sejak 1977. Kontan muridnya menunjuk
teteknya sendiri. Sang guru buru-buru menunjukkan tempat yang
benar.
Dahlan, ayah seorang anak itu semula tidak membayangkan bakal
mengajar anak buta. Ia tidak pernah masuk bangku Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa (SGPLB). Tapi dari pada lontang-lantung di
Jakarta, pemuda asal Aceh itu menerima tawaran kepala SD/SLB di
Cilandak. Tahap pertama, ia mempelajari huruf braile dari
temannya yang memang mendapat pendidikan khusus. Ia baru tahu,
orang buta pun bisa diajar. "Sebab di Aceh, orang buta hanya
ongkang-ongkang saja. Kerjanya cuma minta-minta," katanya.
Kini, ia tahu dan ikut membantu orang buu mengurus diri sendiri.
"Yang buta cuma maunya. Yang lain bisa didimanfaatkan untuk
bekera," katanya.
Karena itu, Dahlan selalu mengarahkan muridnya agar bisa
mengurus diri sendiri. "Mula-mula memang berat, terutama murid
yang biasa manja dan serba dilayani," katanya.
Sejak SD anak-anak yang tidak bisa melihat itu sudah diajar
mencuci pakaian sendiri, mengikat sepatu, membersihkan kelas
sampai harus bisa menandai seragam yang perlu dipakainya setiap
hari. "Hubungan kasih sayang saya bukan lantaran mereka buta,
tapi terutama karena mereka murid saya," katanya.
Tapi Nyonya Ning (Ny. Arnasih Nahraeni Suwardjo), 48 tahun dari
Yayasan Pendidikan Anak-anak Cacat (YPAC) Hang Lekir III Jakarta
Selatan, pernah jengkel berurusan dengan orang tua muridnya yang
menderita cacat mental. Berupa tidak, orang tua murid itu
kebanyakan tak peduli lagi terhadap anaknya yang dititipkan di
asrama karena merasa telah membayar biaya yang ditentukan.
Malahan ada yang malu mengunjungi anaknya yang cacat. "Sikap
orang tua semacam ini justru tidak membantu perkembangan jiwa
anak," katanya. Karena itu pula, sejak 2 tahun lalu sistem
asrama dihapuskan di YPAC itu.
"Dan yang paling susah bila latihan penyesuaian di sekolah tidak
ditunjang dengan latihan di rumah," kata kepala sekolah yang
bertugas di YPAC itu sejak 1962. Kecuali guru di sekolah, orang
tua juga diminu ikut serta mendidik. Yang membuatnya jengkel
antara lain tingkah muridnya dari keluarga kaya. "Kalau ada
latihan penyesuaian seperti pramuka, pergaulan dan lain-lain,
ada saja alasan sakit ini atau itu agar tidak ikut," kata Ning.
Orang tua sering beranggapan, anaknya harus bisa apa saja
setelah keluar dari YPAC. "Pada dasarnya, kami hanya ingin
mengubah apa yang bisa diubah," kata ibu 4 orang anak itu.
Misalnya penderita muscle distrophy -- kemunduran otot -- tidak
bisa diapa-apakan lagi. "Hanya pasrah nasib pada Tuhan,"
katanya.
Pengalaman guru musik di YPAC itu,Andik Sumarno, memang agak
berbeda dengan Ny. Ning. Musik yang diajarkari adalah Orff
Gamelan Therapy Music yang dimaksudkn untuk menunjang
penyembuhan. Musik ini dibawa ke sana oleh Ruth Bardacb, staf
kedubes AS di Jakarta yang sukarela membantu melatih musik
sekiur 1967. Lagu-lagu yang dimainkan dipilihnya dari lagu
rakyat. Suatu ketika, musik pun mengalun dengan manis. Tiba-tiba
menjadi sumbang. Ada apa? "Ee, ternyata ada yang terkena muscle
distrophy, penurunan tenaga drastis sekali," katanya. Ada pula
yang salah tabuh nada karena pemainnya menderita saraf. "Secara
tak sadar, ia menabuh A, padahal seharusnya G," kata Andik.
Untuk mengajar anak cacat, guru tak segan-segan meluangkan waktu
khusus untuk seorang murid. "Karenanya, untuk mengajarkan satu
mata pelajaran saja, bisa makan waktu berbulan-bulan. Tergantung
jenis cacatnya,'! kata Salmiah Pohan, 40 tahun, guru kelas cacat
fisik YYPAC Medan. Hal semacam ini sering membuat orang tua
murid kesal, bahkan menuduh sekolah di YPAC tidak ada gunanya
karena anaknya tidak maju-maju.
Menelan Pil
Cara mendidik anak tunamental (terbelakang) sangat berbeda
dengan yang cacat badan. "Mereka bisa diajar secara bersama,"
kata Anita Silitonga, teman mengajar Ny. Salmiah. Di tengah
murid yang tingkat kecerdasannya sangat rendah, sering timbul
hal-hal aneh. Suatu kali, guru lulusan SGPLB bergaji Rp 51 ribu
itu harus mengajar anak didiknya menelan pil. Ia rentangkan
tangan kanannya sambil memegang pil, dan pelan-pelan menekuknya
ke mulut. Beberapa kali dilakukan sampai muridnya bisa
menirukan.
Setelah semua berhasil memasukkan ke mulut, Ny. Anita bertanya,
"Setelah itu langsung di ...." Semua muridnya bengong. Tiba-tiba
murid bernana Hasudungan (bukan nama sebenarnya), 14 tahun,
dengan suara serak berteriak "Dibondut," artinya ditelan.
Jawaban itu benar, tapi teman sekelasnya tetap ribut karena
tidak juga mengerti diapakan pil yang telah ada dalam mulutnya.
Pengalaman Hadi Sudarso, 44 tahun, guru kawakan sejak 19S6 di
YPAC Sala, memang tidak banyak kesulitan dengan orang tua
muridnya. Yang rewel justru muridnya sendiri. "Anak yang baru
masuk, sering gampang tersinggung atau marah kalau diajari-
sesuatu," katanya. Ia tentu harus sabar membimbing anak semacam
itu. Akalnya? "Dalam peragaan saya buat diri saya ini juga
seperti cacat," katanya. Misalnya pelajaran menulis. Kalau yang
diajar kebetulan tidakpunya tangan kanan, ia berusaha menulis
dengan tangan kiri. "Dengan tangankiri itu, saya ajari bagaimana
memegang pensil, menggerakkan tangan dan menulis," katanya.
Yang paling menyenangkan Hadi adalah karena "sekolah anak cacat
bukan SMP auu SMA yang jadi rebutan. Dlls tidak ada yang
menyogok." "Kalau mau cari citra guru yang buk, penuh pengabdian
dan belum dilanda komersialisasi jabatan, ya di lingkungan
sekolah untuk anak cacat," tambah sarjana muda IKIP bergaji Rp
105 ribu itu sambil tertawa.
Menjadi guru anak cacat kecuali penuh pengabdian, juga harus
kreatif dan pintar mencari metode sendiri. "Sebab tidak mesti
cocok metode dalam buku dengan kasus yang dihadapi," kata Ny.
Sri Slamet, guru YPAC Surabaya. Pengalamannya, ada muridnya
selama 2 tahun tidak bisa menulis walau lancar membaca tulisan
termasuk koran dan majalah. Ia aduk buku catatan sewaktu kuliah
di PGSLB (Pendidikan Guru Sekolah Luar Biasa) dan perpusukaan
sekolah. Ia juga mengadakan konsultasi dengan berbagai ahli di
lingkungannya. Hasilnya nol. Lantas ia iseng-iseng mengajarinya
dengan menuliskan huruf besar-besar."Nah, anak itu pelan-pelan
bisa menirukan," kata Sri senang.
Kesimpulan Sri: "Menjadi guru anak cacat 5 orang, jauh lebih
berat ketimbang menghadapi anak normal 50 orang." Anak cacat
harus dilayani sendiri-sendiri. "Artinya, guru anak cacat harus
mempersiapkan metoda dan bahan lebih banyak," ujarnya.
Prsiapan SD
Sugiantinah, 26 tahun, guru kelas 2 SLB -- yang menjadi tempat
latihan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGP LB) --
Yogyakarta, suatu saat mengajar bilangan 1 sampai 10 untuk
muridnya yang cacat mental. Tiba-tiba seorang murid yang sudah
berusia 14 tahun berdiri dan berteriak: "pipis". Dengan cepat ia
seret muridnya ke kamar mandi diajari cara membuang air dan
membersihkannya.
Untuk sekolah anak cacat mental, ada jenjang kelas trynable lA
sampai 5 B, setingkat persiapan SD. Lulusan 5 tingkat itu dapat
melanjutkan ke P1 (persiapan 1) dan P2. Bila lulus, dapat masuk
sekolah setingkat SD, khusus untuk cacat menul. "Urltuk umur,
tidak ada batasannya. Ada yang sudah 24 tahun masih di tingkat
trynable," kata guru yang sudah 5 tahun mengajar di sana.
Tiap kelas hanya ada 5 orang murid. "Untuk sekolah luar biasa
tiap kelas paling banyak murid," kata Sugiantinah karena "guru
SLB tugasnya banyak dan macam-macam."
Sebagian pelajaran diberikan dengan peragaan: cara melepas dan
memakai baju, menggosok gigi, mandi, makan bersama, buang a* dan
makan. "Tak beda seperti mengasuh anak sendiri," kata
Sugiantinah yang belum punya anak mesti telah 4 uhun berumah
tangga.
Mendidik anak cacat mental bagi Sugiantinah kadang-kadang
menjadi hiburan. Dengan senang hati ia menggendong muridnya yang
berusia 6 tahun ke lapangan untuk berolahraga. Kemudian ia
copoti baju muridnya dan diganti dengan kaus. Dalam kelasnya,
Sugiantinah lebih menekankan pelajaran sensomotons, melatih
ketrampilan anak.
Pelajaran tidak lancar karena daya ingat anak cacat menul sangat
lemah. "Selain kemampuan anak itu lemah sekali, perkembangan
juga lambat," katanya. Namun sangat jelas berbeda, anura yang
mengenyam sekolah dan sama sekali tidak pernah menjamahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini