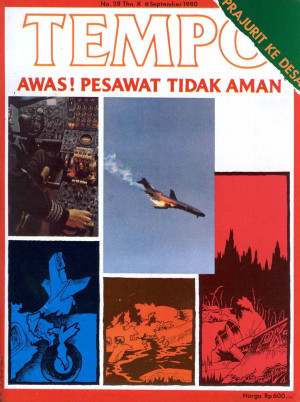DARI jarak ratusan meter, suara melengking-lengking itu sudah
terdengar. Besi ditempa besi beralas besi pula. Dan di tengah
menggebunya industri modern belakangan ini, suara-suara itu tak
pernah mengganggu anak telinga Nyoman Lugra, seorang pandai besi
di Banjar Dajan Tanggluk, Desa Kesiman, Denpasar.
Kedua tangan Nyoman, sepanjang hari, setiap hari, masih terus
memompakan angin ke tungku. Suara pompa itu mendengus-dengus
seperti kambing kasmaran, menghembuskan angin: bara-bara yang
menyala dan besi pun melunak siap ditempa menurut kehendak
Lugra.
Nyoman sudah berada di tempat kerjanya sejak fajar mulai
menyingsing. Mengenakan celana kolor dan berkacamata putih, ia
langsung menyiapkan arang pembakar. Sendirian. Begitu besi yang
akan dibentuk siap ditempa, ia pun berlari-lari ke tempat
penempaan. Lalu mengikir -- dan seterusnya.
Nyoman Lugra, 60 tahun, sudah 25 tahun menjadi pandai besi. Ia
mewarisi kerja itu dari ayahnya. "Seingat saya, sejak anak-anak
saya bermain-main dengan api dan besi," katanya mengenang.
Mula-mula ia membuat sabit bergerigi. Ternyata para petani dan
gembala ternak menyukai buatannya. Setiap hari ada saja pesanan
datang, sampai Lugra kewalahan. Bahan baku yang diambil dari
drum bensin sulit didapat. Akhirnya ia membuat pengumuman,
"setiap pemesan harap membawa bahan baku sendiri-sendiri."
Lugra juga membuat pacul berbentuk garpu, pisau, belakas, golok,
kapak dan sebagainya. "Tapi sekarang saya lebih suka menerima
pasuh (reparasi) saja," ujarnya, "karena selain sulit bahan
baku, hasilnya lebih lumayan" Misalnya saja sebuah golok yang
dijual dengan harga Rp 600 bahan bakunya, yang terdiri dari per
mobil, sudah mencapai Rp 300 Biaya pembakarannya kira-kira Rp
100. "Jadi saya hanya dapat Rp 200 saja. Padahal kalau terima
pasuh, hanya ngetok-ngetok, hasilnya sudah lumayan." katanya
sambil tersenyum.
Sampai Tua
Rata-rata setiap hari Lugra mereparasi 20 buah golok.
Anak-anaknya sering ikut dikerahkan kalau banyak pasuhan. Tak
jelas berapa hasilnya, namun orang tua ini sanggup membiayai
seorang istri dengan 3 orang anak. Rumahnya yang mula-mula
berdinding gedek perlahan-lahan jadi tembok bata dan termasuk
rumah kelas II di banjarnya, apalagi kini juga sudah
ditongkrongi lambang status di desa: sebuah pesawat teve.
Tapi kecelakaan adalah risiko yang sudah dipahami tiap pandai
besi. Suatu kali tangannya cidera kena palu. Selama setengah
bulan ia tak bisa kerja. Sementara pasuhan golok mengalir terus
disertai omelan dari pemiliknya yang tak sabar. Syukur
anak-anaknya dapat mengambil alih tugas, sehingga pekerjaannya
yang kemudian sudah menjadi andalan orang kampung masih tetap
bisa dilanjutkan. "Saya ingin bekerja sebagai pandai besi dengan
semangat membaja sampai tua," kata Lugra dengan bersemangat.
Di Desa Kajar, Kelurahan Karang Tengah, Wonosari, Yogyakarta
sepanjang hari juga terdengar suara benturan besi para tukang
besi tradisional. Di situ bermukim sekitar 50 buah industri
alat-alat pertanian yang tergabung dalam sebuah koperasi yang
bernama "Besi Kajar" -- yang terdiri dari beberapa perusahaan.
Benda-benda yang dihasilkan antara lain kapak, petel, gatul,
pacul, tatah, arit dan sebagainya. Mereka bekerja tidak atas
pesanan. "Ada tidaknya pesanan kami kerja terus," kata Sodinomo,
70 tahun, salah seorang pandai besi di situ.
Di setiap unit koperasi biasa terlihat seorang wanita duduk pada
tempat ketinggian dengan tangan naik turun memegangi tangkai,
memompa angin menyalakan api. Sementara api mengamuk di tungku,
tiga orang empu siap dengan martilnya, yang disebut panjak,
memukul bahan baku yang panas itu untuk dibentuk menurut
kehendak. Besi yang membara itu diletakkan di atas paron (ganjal
besi) lantas secara bergiliran mereka menggebuknya.
Tok-tok-tok-tok ...
Sodinomo jadi tukang besi sejak 1960. Bukan keahlian warisan
nenek moyangnya. Lima tahun sebelumnya ia menjadi tukang pukul
pada salah satu unit pandai besi. Setelah mahir ia baru jadi
empu sendiri. Kemudian ia membuka usaha sendiri dan jadi
juragan. Kini ia membawahi 6 orang buruh. Salah seorang di
antaranya bernama Suhadi, anaknya sendiri, yang juga sudah jadi
empu. Dan nama anak lelaki itulah yang jadi merk usahanya.
Lengkapnya "Suhadi Kajar".
Umumnya setiap buruh bergaji Rp 1.000 sehari. Panjak dapat Rp
500, tukang pompa api alias ububan dapat Rp 300, tukang kikir Rp
500. Jadi setiap hari kapitalis kecil Sodinomo ini harus
mengeluarkan Rp 3.000 untuk karyawannya plus biaya makan Rp
1.000. Dari biaya tersebut setiap hari dapat dihasilkan: 30 buah
wadung, 35 petel, 40 gatul, 20 pacul, 70 tatah dan 40 buah arit.
Masing-masing dijual dengan harga Rp 400, Rp 200, Rp 300, Rp 900
dan Rp 3.000 buat tatah per kodi, sedang arit Rp 200. Empat hari
sekali, setiap Legi, hasil tempaan tersebut dibawa ke seluruh
pedagang pengumpul (agen) di Pracimantoro dan Jatisrono, di
wilayah Kabupaten Wonogiri (Ja-Teng). "Yang jelas waktu
barang-barang tersebut disetor uang langsung diterima," kata
Sodinomo. Keuntungan bersihnya kalau dihitung-hitung hanya Rp
250 per hari. "Cukup untuk makan, tapi tidak bisa beli radio,"
ujar empu itu. Keluarganya memang tidak tampak sebagai kapitalis
kecil yang makmur. Rumahnya pun masih berlantai tanah, gelap,
tak ada jendela serta hanya punya beberapa buah kursi bambu
untuk tamu.
Loterei Buntut
Karena itu untuk mengganjal kebutuhan-kebutuhan lain, Sodinomo
juga merangkap jadi petani di atas satu hektar tanah tegalan.
Sementara itu ketujuh anaknya sudah menancapkan hidup mereka
masing-masing pada profesi tetap. Dua bergaul dengan besi,
sisanya jadi petani.
Besi yang diolah di Desa Kajar berasal dari rel kereta api.
Dibeli lewat koperasi dengan harga Rp 200 per kg. Bahan bakar
yang digunakan adalah arang yang harganya Rp 2o0 per pikul.
Dengan semua itu Sodinomo yang tah pernah makan sekolah berjuang
melawan produk dari industri besi modern, termasuk produk dari
luar negeri dengan nyali yang besar. Hasil-hasilnya secara
kualitas berani ia adu.
Masrun, 19 tahun, pemuda lulusan SD adalah seorang buruh pemukul
di Desa Pinatan, tetangga Desa Kajar. Ia bekerja dari pukul 7
pagi sampai pukul 4 sore. Gaji yang diterimanya sehari Rp 500
untuk ukuran pemuda Gunung Kidul yang belum punya tanggungan
termasuk lumayan. "Tapi habis juga uang itu, soalnva saya suka
membeli loterei buntut," ujarnya. Setiap penarikan ia masang Rp
500. "Kalau kena lumayan, saya bisa beli sepeda," ujarnya.
Masrun bercita-cita kelak jadi empu. Tapi melihat keadaan desa
tetangganya, Kajar, ia merasa cita-cita itu sulit dicapai.
Kenapa? "Di desa saya kebanyakan empu itu sendiri atau
keluarganya yang punya perusahaan. Keluarga saya tak punya
perusahaan, hingga saya sulit maju," katanya mengadu.
Keluarganya adalah pedagang, kecil-kecilan. Paling banter
kadangkala salah seorang keluarganya menemukan besi bekas rel,
lalu dijual kepada majikan Masrun. "Saya tak tahu dari mana besi
itu didapat, entah rel mana yang dicopot," katanya sambil
senyum.
Dokter Atau Kiai
Di dekat Surabaya nasib pandai besi lebih baik. "Di sini
sekarang tidak hanya bisa membuat alat-alat pertanian, tapi
sudah bisa memenuhi pesanan peralatan sepeda dan sepeda motor,"
kata Mohamad Moein 45 tahun, di Desa Pandaian, selatan Surabaya.
Kawasan tersebut sejak zaman Belanda sudah tersohor sebagai
sarang pandai besi yang dulu mempoduksi pacul dan sepatu kuda.
Bahkan sempat dipaksa Belanda membuat topi baja. "Di zaman
Jepang lebih kejam lagi, kami disuruh membuat samurai. Saya
kira sebagian besar samurai yang digunakan Jepang berasal dari
sini," kata Moein.
Moein sekarang lebih banyak membuat sadel sepeda motor atas
pesanan. Pemesan itu kemudian memasang merknya. Buruhnya 25
orang yang menghasilkan 150 buah sadel sehari. Para pandai besi
di Pandaian ini memang telah mengikuti segala gerak-gerik
kebutuhan kota. "Dulu sebelum juragan-juragan Cina mempergunakan
alat-alat modern untuk membuat bodi kolt dan mobil lainnya,
banyak pesanan yang mengalir kemari," kata Moein. Waktu itulah
banyak pandai besi yang jadi juragan dan membangun rumah. Tapi
sejak 5 tahun terakhir ini, pesanan menyusut, karena kebangkitan
alat-alat pres modern oleh pengusaha bermodal besar.
Namun demikian, pesanan masih tetap ada. "Bahkan masih banyak
yang belum terlayani," kata Satta, pengusaha besi yang sudah 3
turunan bergaul dengan besi. "Alhamdulillah jadi pandai besi
dulu dan sekarang memang jauh lebih baik sekarang," sambut
Moein. Tapi ia sendiri tak menghendaki anak cucunya meneruskan
pergaulan dengan besi. "Saya ingin anak cucu saya jadi insinyur,
dokter atau kiai," kata Moein terang-terangan. Kalau liburan
datang dan anak-anaknya bermain di dapur lempat besi itu
ditempa, ia selalu berteriak, "hee sana kamu, nanti kamu
ketularan jadi pandai besi!"
Sebagai Hadiah
Desa Bait, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar, juga penuh dengan
pandai besi. Di pondok-pondok yang beratap daun rumbia dan
berlantai tanah tanpa dinding, tampak penduduk
berkelompok-kelompok memanggang besi, mengikir parang atau
membuat hulu pisau. Desa yang dihuni oleh 3.000 nyawa itu
separuhnya adalah pandai besi.
Utoh Sulaiman, 50 tahun, sejak zaman Jepang sudah bergumul
dengan besi. Penghasilannya sekarang Rp 1.000 sehari. Itu tak
dapat menopang hidupnya secara penuh. Untuk menutup
lubang-lubang dapurnya ia mengerjakan sepetak sawah, kadangkala
jadi buruh di ladang orang lain. Praktis ayah dari 7 orang anak
ini bekerja sampai tengah hari saja di pemanggangan besi. Yang
menolongnya adalah kemajuan industri modern tak sempat membunuh
sumbernya yang utama. "Karena mana sanggup industri modern bikin
parang macam kami buat," katanya dengan yakin dan bangga.
Rekannya, Mohamad Ali, 50 tahun, dikenal sebagai pembuat
rencong. Ia sudah mendapat gelar utoh, artinya sudah ahli dalam
profesinya. Ia membuat rencong atas pesanan dengan harga tinggi.
Sebuah rencong pernah dibuatnya dengan harga Rp 200 ribu, dalam
waktu 34 hari. Tapi pesanan semacam itu jarang. "Biasanya orang
yang memesan menggunakannya sebagai hadiah kepada pejabat," kata
Ali. Di samping itu sulit mendapat bahan baku, karena rencong
terbuat dari besi putih dan kuningan.
Di Jakarta pandai besi sudah sulit dicari sekarang. "Di Jakarta
jarang yang berani capek dan tekun jadi pandai besi," kata
Saleh, pandai besi yang sudah berpengalaman 20 tahun, di Warung
Buncit Jakarta selatan. Disambut oleh Tohir alias Tjien Bi, Cina
Islam yang sudah bekerja sejak tahun 1962 di bengkel dokar:
"Boro-boro pesanan, dandan delman saja jarang sekarang. Boleh
dikata sebulan sekali belum tentu datang."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini