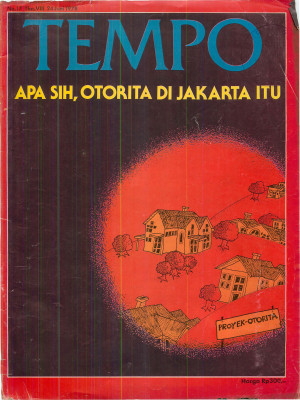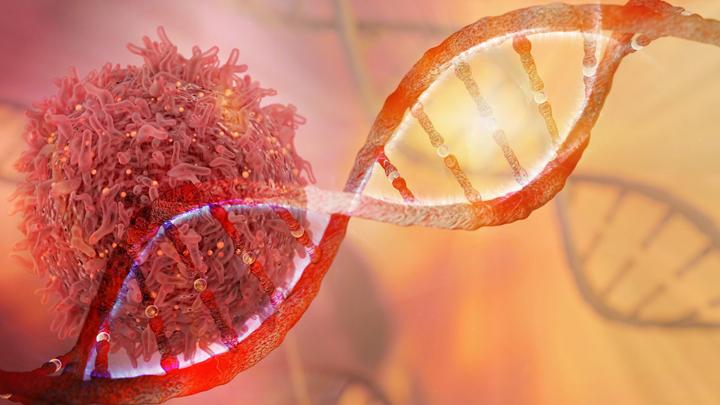DARI keluarga petani yang tidak punya sawah, lahirlah seorang
lelaki bernama Endang Sutara. Di desa Ujung Gubang, Indramayu.
Dunia dari sudut mata orang miskin ini, adalah pasar penjualan
tenaga. Itulah sebabnya ia menerima baik nasibnya, waktu ia
keluar dari bangku sekolah padahal baru kelas 4 SD. Bersama
kedua adiknya yang kemudian meramaikan teratak orang tuanya, ia
ikut menjual tenaga.
Waktu usianya bertambah, Sutara jadi "pedagang". Ia dagang telur
kecil-kecilan. Mula-mula hanya ngubek di sekitar kampung,
kemudian berkembang, tembus sampai ke Pekalongan dan daerah
sekitarnya. Hidupnya jadi senang. Iapun merasa bahwa ia telah
sampai pada masa kejayaan sebagai manusia pedagang telor. Maka
Sutarapun berpacaran.
Kuli Bangunan
Tariah nama pacarnya. Wanita yatim piatu asal Tegal yang satu
profesi. Karena cinta di pelosok tanah Jawa ini tidaklah seruwet
cerita cinta yang dibikin-bikin, singkat dan langsung saja,
kawinlah keduanya. Sutara memboyong Tariah ke Indramayu serta
menjadikannya kongsi dalam bisnis telur. Menurut teori,
kesibukan telur tentunya bertambah bengkak karena dikelola
suami-isteri yang sama-sama ahli. Sayang sekali, kok tidak.
Situasi yang entah bagaimana rupanya lebih kuasa. Bila
perekonomian makin buruk maka tak adalah yang bisa dikerjakan
Sutara dan Tariah kecuali mengamati dengan cemas kemunduran
telur mereka.
Pada suatu ketika, mereka tiba-tiba menjumpai tak ada lagi yang
bisa dikerjakan dengan telur. Dan karena mereka bukan teknosof
yang dikaruniai akal aneh-aneh, mereka tak dapat berbuat lain
kecuali kembali pada pekerjaan nenek moyang. Jadi petani. Lebih
baik dikatakan, buruh tani hidup dengan cara pas-pasan dan
menjemukan. Tapi Sutara pun merasa ada pemberontakan lagi dalam
dirinya, seperti dulu waktu ia jadi kuli. Maka dibukanyalah mata
melihat jauh. Ke Jakarta.
Masa itu Jakarta sedang meledak. Kota ini sedang berada di
pelukan awal jabatan kedua Gubernur Ali Sadikin. Ia bagai kota
yang penuh janji, menghirup harapan orang-orang miskin di
pelosok yang tak tahu ke mana lagi harus menggantungkan nasib.
Sutara mendengar. Sutara terbujuk. Sutara bermimpi: kota yang
bising itu akan menyuapinya, lebih baik daripada membandel
sebagai buruh tani di Ujung Gubang. Dengan meninggalkan anak
bini, ia pun lepaskan cangkul, lumpur dan baju tambalan yang
menjadi seragam resminya di sawah. Ia masuk Ibukota dengan
semangat tempur dan berhasil menyulap dirinya menjadi seorang
kuli bangunan.
Tetapi hidup di Jakarta sama pas-pasannya dengan hidup di udik.
Barangkali variasinya lebih banyak -- tapi meskipun Sutara
berjuang mati-matian, toh tak berhasil mengirimkan apa-apa untuk
keluarganya yang menunggu. Dalam hal ini mungkin ia harus
bersabar. Tetapi matanya telah lebih dahulu bergerak. Melihat
lebih jauh. Sekarang ke luar Pulau Jawa -- ke daerah
trasmigrasi di Sulawesi Tengah. Tawaran yang muncul dari ide
pemindahan penduduk, dari Pemerintah, dianggapnya mengandung
harapan. Hatinya gembira kembali.
Diambilnya keluarganya -- anak dan isterinya -- di Indramayu.
Langsung mereka masuk tempat penampungan calon transmigran di
Jakarta. KTP-nya segera dirubah jadi KTP Jakarta. Maka resmilah
Sutara menjadi transmigran yang tergabung dalam kelompok 100 KK
lainnya. Sebuah kapal, yang ia lupa namanya, pada tanggal 2
September 1974 meninggalkan Tanjung Priok, membawa keluarga
Sutara ke Palu. Dari Palu, sebuah truk membawanya memasuki
Tomini, dan kemudian menghantarkannya ke daerah transmigrasi
Mapanga. Perjalanan yang cukup berat, karena mereka harus berada
di dalam truk selama dua hari satu malam. Antara Palu dan Tomini
terbentang jalan yang rusak berat.
Mapanga merubah nasib Sutara dan keluarganya. Ia tak sia-sia
berharap. Hidup mereka lebih baik, tidak hanya permainan mimpi.
Sesuai dengan janji, Pemerintah memberinya sebuah rumah bedeng
terbuat dari kayu. Dan lebih dari itu, ia tidak perlu lagi
menyebut dirinya buruh, karena ia serta-merta mendapat 2 Ha
tanah. Belum banyak yang tahu, daerah Mapanga termasuk bagian
dari ibu pertiwi yang subur -- meski kesuburan itu harus dibuka
dengan cucur keringat yang deras. Bagi Sutara bekerja berat
sudah biasa. Meski banyak hal yang harus dilakukannya -- banyak
kekurangan fasilitas yang membuatnya harus tabah dan gigih --
Sutara tidak mundur.
Menutup Mata
Cerita tentang daerah transmigran biasanya rawan. Karena daerah
yang harus dibuka itu anti kemalasan, banyak transmigran
seangkatan Sutara putus asa. "Sekitar 40 KK meninggalkan Mapanga
kembali ke Jawa," ujar Sutara menceritakan kenangan itu kepada
Dahlan Iskan dari TEMPO. "Habis mereka malas," katanya mengulas.
Tapi Sutara tidak termasuk di antara pemalas. Didorong oleh
kepedihan masa kecil yang miskin, ia memberontak segala yang
menjepit dan mengujinya. Akhir perjuangan yang ulet itu ia
berhasil. Berhasil jadi transmigran yang baik, termasuk menambah
jumlah anaknya jadi tiga.
Setelah lewat 3 tahun, hidup Sutara makin enak. Kebunnya
menghadiahinya sayur-mayur dan gaplek yang bisa membuahkan duit.
"Hasil kebun itu dibeli oleh koperasi. Harganya tidak bisa
merosot meskipun selagi panen," kata Sutara. Sementara makannya
tiap hari muncul dari padi gunung yang tumbuh dengan baik.
Kehidupan lumayan ini menyebabkan ia mampu bernafas lega. Lalu
isterinya mulai diserang sakit rindu pada keluarga.
Ia minta libur untuk kembali ke kampung asal, menjenguk
keluarga. Lagipula memang saat untuk "unjuk gigi" sudah tiba.
Kalau dulu ia bagai pelarian kumal dari desa, sekarang rumah
tangga mereka tegak dan memiliki harga diri yang pantas. Seperti
kita ketahui, banyak transmigran pengin kembali pulang menJenguk
asal, hanya untuk memamerkan radio, kaset dan uang lebih yang
dimilikinya setelah pindah tanah berpijak.
Sutara mengerti kemauan isterinya. Tetapi ia bertangguh satu
tahun. Janji ini tidak begitu memuaskan Tariah. Wanita itu
mendesak-desak terus. Entah apa yang menyebabkan ia ngebet
seperti itu. Akhir tahun 1976, wanita itu hamil muda. Ini alasan
baik buat Sutara untuk membuat isterinya bersabar. Pertengahan
1977, lahirlah anak ketiga mereka itu, yang dinamakan Sumarni.
Sutara masih ingin menunda 4 bulan lagi sebelum benar-benar
memenuhi permintaan isterinya.
Nasib yang malang mulai. Pada saat persiapan pulang sedang
dirintis, isterinya sakit. Sakit keras. Sutara tidak tahu persis
sakit apa. Ia hanya mengatakan batuk-batuk, tetapi gawat. Obat
tradisionil dan dokter tidak berhasil menyembuhkan. Sutara sedih
sekali, apalagi harus mengurus bayi. Tapi sedih tidak
menyelesaikan apa-apa. Bahkan Tariah menutup mata -- tanggal 17
Desember 1977 ....
Kembali Ke Indramayu
Yah, apa daya. Nasi sudah menjadi bubur. Setelah bersedih, dan
menyesal, akal Sutara bekerja lagi. Sebulan kemudian ia
benar-benar ingin pulang -- untuk menitipkan sebagian anaknya
kepada adiknya yang masih ada di Indramayu. Lalu dipinjamnya
uang Mohammad Yakub, tetangganya, sebanyak Rp 200 ribu. Dengan
uang itu ia naik pesawat terbang ke Surabaya. Sulit menerangkan
bagaimana ia menikmati rasanya terbang. Semuanya akan lain,
seandainya Tariah masih hidup .... Toh ia sibuk menyusun
rencana, di atas harapan bahwa orangtuanya akan menolongnya
menjaga anaknya. Harapan itu makin menyala tatkala ia meneruskan
perjalanan dari Surabaya ke Indramayu.
Di Ujung Gubang, di tanah asalnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba
lemas. Harapannya kempes, seperti balon yang pecah. Ternyata
keluarganya sudah berserakan. Bapaknya baru saja meninggal
diterkam banjir yang ngamuk bulan Desember 1977 itu. Ibunya
sudah lebih dahulu meninggal diterkam sakit. Sementara
adik-adiknya sudah lari ke Bengkulu mencari hidup baru. Tuhan,
Tuhan. Jadi itu rupanya mengapa dulu Tariah ngebet ingin pulang.
Tapi sekarang tak ada tempat buat Sutara untuk mengadu. Yang ada
hanya Lurah Ujung Gubang, dengan cerita yang panjang, serta
Kasiah -- tetangganya -- yang masih berbaik hati untuk
menampungnya selama tinggal di Ujung Gubang.
Di kantong Sutara masih ada Rp 100 ribu. Ia segera mengadakan
selamatan untuk orangtuanya yang hanyut -- serta almarhumah
isterinya sendiri. Selama tidak kurang dari 3 bulan kemudian ia
menghabiskan rindunya pada desa di mana ia bermain-main sejak
kecil. Tapi hidup tentu tidak untuk melepas rindu saja --apalagi
Sutara petani biasa. Rencana dibulatkan lagi. Sutara memastikan,
bahwa ia harus balik ke Mapanga lagi -- dengan seluruh anaknya.
Kalau tidak, ongkos untuk ke Sulawesi akan habis dimakan
rindu-merindu itu.
Dengan harta kurang dari Rp 100 ribu, tanggal 30 Maret yang lalu
Sutara bertolak dari Indramayu ke Jakarta. Ia mengambil nafas di
terminal bus Pulo Gadung, gerbang timur Ibukota. Rencananya hari
itu juga hendak melesat ke Sulawesi dari Kemayoran. Tapi karena
hari masih malam, ia beristirahat di dekat sebuah warung kopi.
Entah kenapa, anaknya yang paling kecil menangis-nangls terus.
Sutara jadi capek sekali. Akhirnya ia pun tertidur. Inilah
kesalahan yang terbesar yang dibuatnya. Seorang yang tertidur di
terminal bus selalu harus menghadapi berbagai macam risiko,
setelah terjaga. Dan ia lupa pada dalil ini.
Kolong Jembatan
Ketika fajar menyingsing, Sutara terbangun. Anak-anaknya bangun.
Terminal itu sendiri sudah terlebih dahulu bangun. Sementara
kopor, pakaian dan uang yang ada di dalamnya -- untuk pembeli
tiket -- ternyata tak ada lagi. Gaib. Hilang. Sutara jadi
pusing. Kepalanya berat. Tapi kopor dan uang itu tak kembali.
Sutara menangis. Anak-anaknya pun membantunya menangis.
Orang-orang hanya bisa memandang. Dan akhirnya ia pun sadar, ia
tak bisa menangis terus. Ia harus bertahan. Maka dengan sisa
uangnya (sedikit), ia mulai menjadi sebagian dari Jakarta lagi.
Waktu malam tiba, ia tak tahu di mana harus berteduh. Setelah
susah payah berpikir, akhirnya ia menyerah di bawah jembatan
kereta api dekat bioskop Jaya, Jatinegara. Dibelinya sepotong
plastik untuk alas. Dan hari itu ia berhenti jadi petani, dan
memasuki hidup kelompok gelandangan.
Toh para gelandangan itu tak heran pada kedatangannya. Setelah
mendengarkan kisahnya, salah seorang di antara mereka memberi
modal: sebuah tongkat jepitan puntung, dan sebuah kaleng. Lalu
menyanggupi membeli puntung-puntung yang akan dikumpulkan Sutara
dan anak-anaknya.
Pagi esoknya, anaknya yang masih 11 bulan digendong. Yang dua
lagi, digandeng. Dari bawah jembatan, mereka anak beranak
bergerak ke timur, berputar sampai ke Jalan Raden Saleh jauh di
barat. Malam hari mereka baru pulang -- artinya kembali ke
jembatan itu. Itulah yang kemudian dilakukan setiap hari. Jam 10
malam ia biasanya baru tiba kembali, bersama ketiga anaknya yang
lebih banyak menangis. Pendapatannya sehari, satu kaleng
puntung, berharga Rp 100. Kurang sekali memang. Untung ia
seringkali menjumpai pegawai kantor yang mengulurkan Rp 100 --
meskipun ia sungguh tidak mengemis.
Tetapi hebat. Sutara termasuk hebat. Dalam tempo setengah bulan,
ia berhasil menabung Rp 6 ribu. Uang itu disimpannya dalam
kaleng yang selalu berada di dekat kepalanya. Ia merencanakan
nanti toh akan tiba masanya naik kapal laut ke Mapanga. Untuk
itulah ia berhemat setengah modar. Makannya diirit, sementara
bayinya hanya diberi air putih.
Tapi nasibnya memang sial. Seorang yang tak kenal kasihan,
menyerobot hasil penghematan itu, sehingga kedudukan Sutara
menjadi "nol" kembali.
Tak berapa lama kemudian, ketika lewat di salah satu gereja di
Jatinegara, ia mendapat hadiah selimut. Berkat hadiah ini,
anaknya bisa tidur lebih nyenyak. Tapi, belum seminggu, selimut
itu sudah disikat orang lagi.
Tapi Sutara hanya menyalahkan diri sendiri. Ia, kalau tidur,
memang benar-benar pulas dan terlena. Bagaimana tidak. Sambil
ngincer puntung, ia harus menggendong dan menggamit anaknya di
tengah kesibukan jalan yang seringkali edan. Capek kan?
Nasib Sutara mungkin masih akan panjang sebagai penghuni kolong
jembatan, kalau suatu kali anaknya tidak menangis panjang lebar
di tepi jalan. Tuhan rupanya menyuruh anak-anaknya menangis di
situ. Ketiga-tiganya menangis seperti koor. Akibatnya, seorang
wartawan tertarik membidikkan lensa. Lantas mulai usil
bertanya-tanya. Nah, tak lama kemudian di Harian Angkatan
Bersenjata terpampang potret keluarga petani yang merosot jadi
pengumpul puntung ini. Potret rupa-rupanya berbicara lebih
banyak dari kenyataan. Beberapa hari saja, setelah potret
dipasang, Sutara dicari orang (termasuk kawan-kawan kita dari
majalah ini). Ia tidak akan dibiarkan lagi tinggal di kolong
jembatan. Nasibnya harus mendapat perhatian. Untuk sementara,
sejak 7 Juni yang lalu, ia ditampung di Jalan Jaksa. Direktorat
Transmigrasi akan mengembalikannya ke Mapanga, tempat
anak-anaknya dibesarkan dan tempat di mana ditanam jenazah ibu
mereka, Tariah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini