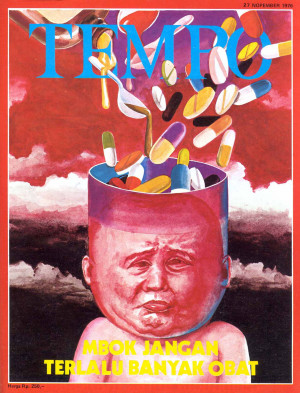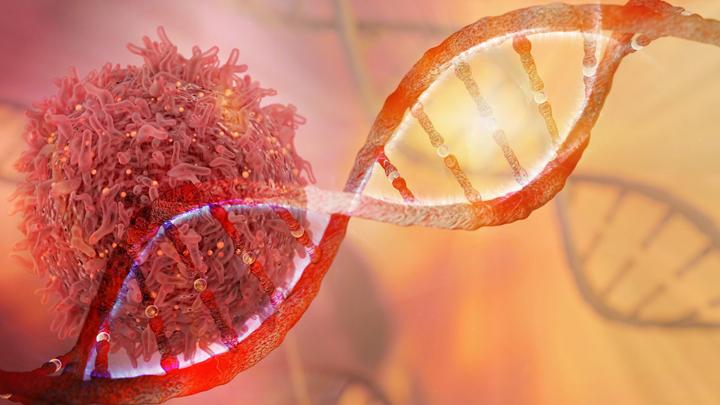SUKAR dipercaya, tapi nyata: sudah ada 7000 lebih merek dagang
obat-obatan yang terdaftar di sini. Maka agak membingungkan
untuk memilihnya. Dan sekarang satu kebiasaan baru mulai
berjangkit di sebagian dokter kita. Mereka tidak lagi menuliskan
generic (nama dasar obat) tetapi sudah mencantumkan
merek-dagang.
Proses pemilihan ini dilakukan di bawah pengaruh kampanye
besar-besaran yang dilancarkan produsen. Mereka misalnya
menghadiahi para dokter dengan alat tulis-menulis, asbak atau
almanak di mana merekdagang mereka tercantum. Sampai pun
mensponsori pertemuan-pertemuan dokter. Dengan bendabenda itu
seorang dokter yang akan menuliskan resep tetracycline misalnya,
tak perlu lagi mengerutkan jidat untuk mengingat-ingat satu di
antara sekian banyak merek obat antibiotika. Sebab di depan
mereka sudah ada benda-benda pengingat, seperti
tabung-penyimpan-klip-kertas bertuliskan Dumocycline.
Seorang dokter yang baik tentunya tidak akan terpengaruh dengan
teknik-teknik promosi. Mereka memilih obat karena mereka tahu
betul mutunya. Hanya mereka yang suka mengkomersiilkan gelar
yang suka ambil untung dari persaingan keras antar produsen.
Pasar begitu sempit untuk jumlah merek dagang yang begitu
melimpah, tapi para ahli pemasaran tidak habis akal. Satu di
antara kepandaian berdagang itu terlukis dalam sebuah laporan
yang ditulis seorang detailman kepada induk perusahaannya di
Jakarta, belum lama ini: "Dalam kunjungan saya ke Padang,
Palembang dan Medan telah diketahui bahwa beberapa perusahaan
melakukan kompetisi kotor terhadap perusahaan farmasi lain,
dengan mengkontrak dokter-dokter tertentu dan memberikan mereka
sejumlah uang imbalan. Jumlahnya biasanya 10% dari harga-resep,
atau sekitar Rp 20.000 (tak disebut perhari atau perbulan- Red).
Akibatnya beberapa dokter terkenal di sana yang biasanya
menuliskan obat kita, sekarang tak melakukannya lagi dan
menggantinya dengan obat buatan perusahaan tersebut".
Persaingan dan dunia usaha memang satu. Detailman di atas kalah
karena tak sanggup mengeluarkan ongkos tambahan untuk memegang
dokter langganan-lamanya. Meskipun mutu obatnya lebih baik,
barangkali.
Dari persaingan perusahaan farmasi ini terlihat kemungkinan
bahwa pemenangnya akan menambahkan ongkos promosi tadi ke dalam
biaya produksi. Atau kalau bukan demikian mereka akan menurunkan
mutu. Dalam keadaan di mana ada-main antara pabrik, dokter serta
apotik, sukar untuk mengetahui apakah harga yang telah dinaikkan
ataukah mutu yang sengaja diturunkan. Sementara pengawasan mutu
menjadi pekerjaan yang hampir musykil karena begitu banyaknya
merek-dagang.
Itulah sebabnya ada pihak yang beranggapan sekarang ini sudah
tiba saatnya untuk meng-KB atau menciutkan jumlah obat-obatan.
Belum pernahnya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan,
Departemen Kesehatan melaporkan tentang ditemukannya mutu obat
yang di bawah standar oleh laboratorium milik pemerintah,
memberikan alasan yang lebih kuat lagi bagi pikiran tadi. Salah
pasang etiket pada sebuah obat-suntik atau vitamin C yang hampa,
yang hanya berisi asam citrat yang disiarkan pers tempo hari,
adalah berdasarkan laporan pabrik sendiri. Atau oleh pabrik
lain, yang untuk kepentingan perusahaan telah melakukan
"kegiatan mata-mata" terhadap pabrik saingannya.
"Bagi kami para dokter timbul pertanyaan apakah kwalitas dari
obat-obat yang jumlahnya membingungkan ini bisa dipertahankan.
Quality control apakah dilaksanakan?", tanya Ketua Umum Ikatan
Dokter Indonesia yang baru, Utoyo Sukaton. "Apakah pabrik-pabrik
farmasi punya peralatan yang cukup, atau hanya nebeng? Saya cuma
mencemaskan hari-hari mendatang, sebab sampai saat ini kwalitas
mereka masih cukup baik", sambungnya pula.
Peralatan pabrik-pabrik obat itu mungkin ada yang tak perlu
dicemaskan dr Utoyo, sebab di antara mereka misalnya ada yang
sampai-sampai mampu menyumbang alat pengawas spectrophoto
meter kepada Departemen Kesehatan.Tapi dari 243 buah pabrik yang
bertebaran di sini -- terutama di Pulau Jawa -- ada juga yang
memang mengandalkan pengawasan mutu pada pihak luar, seperti
pada Bagian Farmakologi Universitas Indonesia, Jakarta.
Soal pengawasan mutu ini, menurut Direktur Jenderal Pengawasan
Obat dan Makanan, drs Sunarto Prawirosuyanto "diawasi sejak
pabrik akan didirikan. Persyaratan bangunan harus sesuai dengan
peraturan yang dikeluarkan dari sini. Dan untuk menjaga supaya
produsen benar-benar mau menjaga mutunya, mereka diharuskan
memiliki spectro photometer dan mesin untuk mentest tablet. Jika
mereka punya niat baik, dengan alat-alat itu obat-obatan yang
mereka buat bisa diperiksa secara benar", katanya. Pemerintah
sendiri, katanya, melakukan pengawasan melalui laboratorium yang
di pusat dan di tujuh kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya,
Semarang, Medan, Palembang, Ujungpandang) dengan dibantu oleh
laboratorium ukuran kecil di sepuluh daerah. Pemeriksaan
dilaksanakan dengan mengumpulkan contoh-contoh obat yang diambil
dari pasar atau dari pabrik.
Untuk pengawasan mutu obat-obatan yang berjumlah ribuan itu,
orang minta pengayoman dari pemerintah. Tetapi bagi mereka yang
yakin dengan teori "yang membuat barang buruk akan mati
sendiri", harapan khalayak itu dianggap terlalu memberatkan
tugas pemerintah. "Saya kira pengawasan yang paling penting
terletak pada produsen sendiri. Mereka haruslah mengawasi
produksinya mulai dari bahan baku, fasilitas penyimpanan sampai
pemasaran. Sedangkan pemeriksaan taraf berikut dikerjakan oleh
Departemen Kesehatan. Sebab saya yakin tak semua macam obat bisa
diperiksa. Sehingga pemeriksaan pada taraf ini cukup insidentil
dan atas dasar laporan-laporan pemakai", ulas dr Iwan
Darmansjah, Kepala Bagian Farmakologi Universitas Indonesia.
TUGAS pengawasan mutu yang menjadi pelik ini bermula dari
kebijaksanaan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
(dulu bernama Direktorat Jenderal Farmasi) yang dalam tahun 1972
membuka pintu selebar-lebarnya bagi penanaman modal dalam negeri
maupun asing. Seperti yang dikatakan Sunarto Prawirosuyanto,
"sejak tahun 1974 Indonesia akan tertutup untuk impor
obat-obatan. Waktu itu para pengusaha masih bersikap menunggu
terhadap kebijaksanaan tersebut. Tapi mereka yang percaya kepada
saya menyambutnya dengan antusias. Dan dengan adanya pula
Instruksi Presiden untuk obat-obatan bagi daerah, orang tambah
ramai lagi". Sunarto berkisah.
Dan berbarengan dengan memuncaknya penanaman di bidang
obat-obatan itu pulalah, pada awal tahun 1975 direktorat yang
dipimpinnya mengambil kesempatan merapikan pencatatan
merek-dagang, sekaligus mengeduk tagihan Rp 10.000 untuk tiap
jenis obat produksi dalam negeri dan Rp 100.000 untuk obat
asing. "Ketika itu yang dilakukan baru dalam taraf registrasi
merek saja, sedangkan penilaian mutu dilaksanakan kemudian",
kata Dirjen.
Ketika itu terdaftarlah sekitar 7000 merek-dagang yang
menggunakan lebihkurang 1700 generic. Dengan jumlah sebanyak itu
Indonesia toh belum juga bisa menutup pintu terhadap impor
obat-obatan. Sebab sekitar 2 1/2% dari oliat yang beredar di
sini masih juga diimpor dari luar, terutama obat obatan yang
mahal dan khasiatnya terutama tertuju untuk penyakit yang
diderita sebagian kecil dari masyarakat. Seperti obat jantung
dan kanker.
Yang benar-benar tertutup waktu itu adalah pulau Jawa. Kata
Sunarto: "Sejak tahun 1975 Jawa tertutup untuk pabrik baru,
mereka yang masih mau tanam modal silakan ke luar Jawa. Tapi
kebijaksanaan ini tidak mendapat sambutan. Mungkin karena
komunikasi yang sulit. Sedang pasar di luar Jawa kecil sekali".
Dasar-dasar untuk menjaga mutu memang sudah dipancangkan oleh
Direktorat Jenderal POM. Seperti yang dikatakan Sunarto, itu
tampak dalam bentuk pengawasan yang dimulai dari rencana
bangunan pabrik dan persyaratan berupa mesin-mesin penguji.
Itulah makanya batasan jumlah merek-dagang unluk satu jenis
generic tidak dibatasi.
Antibiotika untuk penyakit-penyakit infeksi dalam masyarakat
seperti Indonesia tentu saja mendapat pasaran yang paling ramai.
Dan obat ini boleh dikatakan sebagai sumber penghasilan utama
para produsen. Hampir tiap pabrik yang berjumlah lebih dari 200
itu mengeluarkan obat ini dengan merek dagangnya masing-masing.
"Malahan ada sebuah pabrik obat yang membuat 2 merek untuk
tetracycline", kata seorang dokter Puskesmas di Jakarta.
Saingan yang banyak, dokter dan pasien yang terbatas menjadi
gelanggang para detailman untuk adu kepintaran membujuk,
meyakinkan atau menyogok. Di rumah-sakit rumah-sakit kota besar
simpang-siurlah anak-anak-muda tampan-berdasi dengan tas mereka
yang khas itu, berbaur dengan para pasien. Tak lupa
tempat-tempat praktek pribadi diketuk pula pintunya. "Mereka
terasa mengganggu. Itulah makanya saya hanya memberi waktu
mereka hari Senin-Kamis saja dan jam jam tertentu", keluh Utoyo
Sukaton.
Dokter sendiri bisa bingung menghadapi jumlah obat-obatan yang
sekarang. Apalagi seorang awam yang barangkali untuk obat
kepalanya terpaksa memilih di antara puluhan obat pusing.
"Apakah perlu begitu banyak merek", tanya Utoyo Sukaton,
spesialis penyakit kencing-manis. "Obat campuran Bl, B6 dan B12
ada enam atau tujuh merek. Padahal tiga saja saya kira sudah
cukup", jawabnya sendiri.
Sementara itu kata dr. Iwan Darmansyah: "Kompetisi yang bebas
menimbulkan kelemahan, berupa sikap pabrik yang hanya mau
membuat obat laris. Ini tentu mempersulit pengawasan". Usulnya:
"Sebaiknya obat seperti tetracycline dibuat oleh beberapa pabrik
saja dengan omset yang besar. Dengan demikian pabrik tidak
mengurusi soal-soal tetek-bengek lagi. Ekonomi negara untung dan
pengawasan menjadi lebih mudah", begitu tanggapan dr Iwan
Darmansyah dari UI.
Kalau pun penciutan jumlah sudah masanya, bagaimana cara
melaksanakannya? POM sendiri tidak akan mengeluarkan sesuatu
keputusan mengenai hal ini. "Saya menolak monopoli-monopolian",
kata Sunarto satu ketika, "biarlah mereka yang kalah dalam
persaingan mundur sendiri".
Dan pimpinan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, drs Edy Lembong
pendapatnya selaras benar dengan pikiran drs Sunarto. "Sulit
sekali untuk membatasi jumlah merek obat-obatan. Lagi pula tidak
perlu dan tidak baik. Apalagi kalau dilaksanakan dengan
peraturan pemerintah", kata Lembong. Menurut Lembong, pembatasan
obat obatan itu akan berlangsung dengan sendirinya.
Ada beberapa mekanisme yang bagi Lembong akan menyederhanakan
jumlah merek. Antara lain kesadaran masyarakat akan mutu obat,
tahu tentang bio-availability atau adanya khasiat yang
berbeda-beda dari jenis obat yang sama karena diolah dengan
keahlian dan kemampuan yang berbeda yang diserahkan kepada
masyarakat". Dia juga menyebutkan tentang persaingan pasar, daya
beli masyarakat yang semakin meningkat, mutu yang distandarkan
pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah yang selalu membuka
kesempatan bagi masyarakat untuk memakai obat-obat baru.
Tentunya dari pihak pemerintah sendiri masyarakat mengharapkan
obat yang sama mempunyai efek terapetik yang sama --
bioequivalence.
Di kalangan dokter sendiri pendapat tentang perlunya
penyederhanaan jumlah merek ini memang agak keras, seperti yang
tercermin dalam pikiran Iwan Darmansyah, orang yang juga
mengepalai satu usaha monitoring efek-samping obat yang
dilaporkan dokter. "Sampai tahun 1975 jumlah merek sudah
melebihi 7000, padahal Swedia dan Jerman cuma 2000 merek",
katanya.
Menurut keterangannya untuk sebuah rumahsakit sebenarnya 150
sampai 200 generic sudah cukup. Sementara itu kepada masyarakat
perlu ditekankan bahwa obat tak perlu terlalu banyak. Saya kira
90% dari pasien yang datang kepada praktek seorang dokter hanya
membutuhkan 20 macam obat". Sedangkan pengalaman Utoyo Sukaton
menunjukkan "paling banyak 15 merek dagang".
Menyederhanakan jumlah merek-dagang obat-obatan sebenarnya bukan
hanya menjadi impian dokter di sini. Pihak badan kesehatan dunia
sendiri -- WHO dalam sebuah pernyataannya yang dikeluarkan
tanggal 21 Oktober yang baru lalu menganggap penciutan merek ini
sudah waktunya.
Sebab persaingan bebas di pasar belum tentu tidak akan
berpengaruh terhadap mutu obat-obatan. "Satu proses pemilihan
yang dinamis terhadap obat-obatan esensil jika dikombinasikan
(dengan sistim informasi yang intensif di tambah pendidikan
kesehatan masyarakat akan dapat memperbaiki mutu, manajemen dan
penggunaan obat untuk kesehatan", begitu hasil rapat para
konsultan WHO baru-baru ini di Jenewa.
Pertemuan itu diadakan untuk memilihkan obat-obatan terpenting
dalam rangka membantu negara-negara berkembang. Satu daftar yang
terdiri dari 150 zat-zat aktif obat telah dipersiapkan oleh para
peserta sebagai salah satu contoh obat-obatan yang diperlukan
masyarakat. Dan badan kesehatan dunia itu diminta untuk membantu
pemerintah-pemerintah yang jadi anggota, dalam memilihkan
obat-obat tersebut.
Sunarto sendiri, terhadap hal ini hanya mengatakan: "Sulit. Itu
sulit dilaksanakan. Bayangkan, pemerintah India saja beranggapan
untuk mengobati penyakit yang ada di sana sebenarnya cukup
diatasi dengan 116 obat, tapi nyatanya sekarang mereka punya
lebih besar dari kita. Mereka punya 15.000 macam. Janganlah
berorientasi kepada Swedia, sebab penduduk negara itu kurang
dari penduduk Kebayoran", jawabnya.
Jika Dirjen POM teguh dengan pendiriannya mengenai "kompetisi
bebas" dan penciutan itu akan datang melalui persaingan, untuk
melindungi konsumen agaknya dia sudah waktunya bertindak
terhadap obat-obatan yang diragukan efek pengobatannya. Seperti
kata dr Iwan Darmansyah banyak obat yang menunggangi kemauan
yang bukan-bukan dari masyarakat. "Ada obat yang katanya bisa
membuat orang lebih pintar . Dan orang memang banyak mencarinya.
Sementara pabrik mengatakan bahwa efek obat tersebut akan
memakan waktu lama. Obat semacam ini, yang diragukan efek
terapetiknya, harus segera dibuang. Malahan vitaminpun tidak
perlu terlalu banyak. Jika orang sudah makan cukup tak perlu
vitamin lagi. Jangan membuang-buang uang", katanya.
Kesehatan masyarakat yang lebih terjamin, inilah yang menjadi
latarbelakang pendirian para dokter yang menganggap jumlah merek
sekarang sudah terlalu banyak. Sikap pemerintah sendiri telah
digambarkan dalam pendapat-pendapat drs Sunarto: ingin melihat
pertumbuhan industri obat yang maju mengikuti pertumbuhan
produksi di lapangan lain.
Tapi dialog langsung dari kedua fihak ini belum pernah terjadi
secara terbuka. Badan-badan yang tampaknya bisa memainkan
peranan perantara, seperti Panitia Penilai Obat Jadi, kurang
efektif. Tetapi pendapat-pendapat yang terus berkembang
bagaimana pun akan membantu semua fihak dalam menentukan arah.
Siapa tahu dalam Kongres ke Vl Federasi Perkumpulan Ahli-Ahli
Farmasi Asia (FAPA) yang dimulai dari tanggal 22 Nopember ini,
selama lima hari, akan menelorkan jalan tengah buat Indonesia.
Sebab tema kongres ini sendiri memang dekat sekali dengan
persoalan yang sedang kita hadapi: Kesehatan Masyarakat Yang
Lebih Baik Melalui Obat-Obatan Bermutu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini