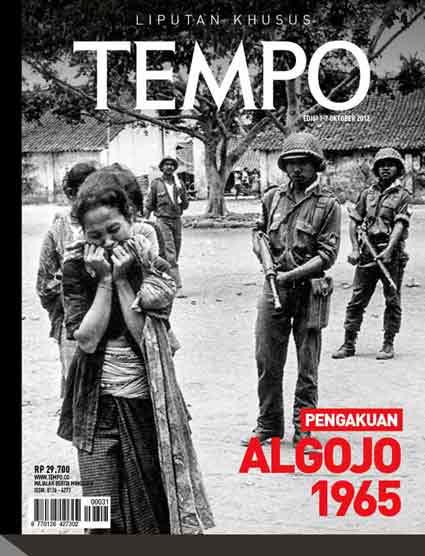Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Johanes Sarwono kini tak lagi banyak bicara perihal bisnis. Meringkuk di ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, dia mengaku sekarang lebih tertarik berdiskusi masalah agama. Lawan diskusinya bukan sembarang orang, yakni Abu Bakar Ba’asyir, pemimpin Pondok Pesantren Ngruki, yang menjadi tetangga selnya. "Saya sering bantah-bantahan ilmu dengan dia," ujar Sarwono saat ditemui Tempo pekan lalu. Di ruang tahanan, ia kini kerap memakai baju koko dan berkopiah.
Sarwono, 62 tahun, ditangkap dengan tuduhan terlibat kasus pencucian uang dana Bank Century. Dia dibekuk Senin, 3 September, dinihari oleh sejumlah reserse di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. "Ada aliran dana Bank Century sebesar Rp 25 miliar untuk membayar lahan di Fatmawati," kata Direktur Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyo kepada Tempo pekan lalu.
Uang itu diduga digunakan untuk cicilan pembayaran peralihan hak atas tanah milik Yayasan Fatmawati seluas 22 hektare. Lahan tersebut berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, berbatasan langsung dengan Rumah Sakit Fatmawati. Pembayaran terjadi pada rentang waktu November 2003 hingga Mei 2005. Sarwono mengakui terlibat jual-beli tanah tersebut. "Saya memang broker tanah milik Yayasan," ujarnya.
Sengketa tanah yang ditaksir nilainya tak kurang dari Rp 400 miliar itu kini memang sudah masuk Mabes Polri, dengan "korban" Sarwono itu. Menurut sumber Tempo, sejumlah pengusaha properti papan atas Ibu Kota juga, diam-diam, mengikuti dengan saksama perkembangan kasus ini. Terletak di wilayah strategis, tanah itu jika dikembangkan—katakanlah dijadikan pusat belanja atau apartemen—akan mendatangkan keuntungan berlipat.
Yayasan Fatmawatilah—awalnya yayasan ini bernama Yayasan Ibu Soekarno—yang menguasai tanah dengan total luas 35 hektare itu sejak 1950-an, dengan status hak pakai. Sekitar 13 hektare di antaranya kemudian dipakai yayasan yang sebagian pengurusnya dokter itu untuk membangun rumah sakit, yakni RS Fatmawati, yang kemudian dikelola pemerintah. Belakangan, kerja sama pemerintah dan yayasan ini menimbulkan masalah dan berbuntut ke meja hijau (lihat "Kemesraan Tak Berumur Panjang").
Masuk ke pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung, sengketa itu—yang jika dihitung-hitung sudah "berumur" seperempat abad—dimenangi Yayasan Fatmawati. Pengadilan memerintahkan pemerintah membayar Rp 75 miliar atas 35 hektare tanah yang dikuasai rumah sakit—perintah yang tak kunjung dilaksanakan.
Nah, pada 2002, Sarwono, yang sehari-hari berprofesi notaris, terlibat urusan ini. Yayasan meminta dia menjadi juru runding menghadapi pemerintah. Hasilnya, disepakati, lahan itu "dibelah" dua: 13 hektare untuk rumah sakit, sisanya dikembalikan ke Yayasan.
Masalah muncul saat pengurus Yayasan mulai kelimpungan mengurus lahan yang luas tersebut. Uang di kantong Yayasan tak cukup untuk mengelola dan memelihara lahan yang dulunya diisi penggarap liar itu. Sarwono lagi-lagi diminta Yayasan mencari mitra alias investor untuk mengelola lahan. "Pengurus Yayasan kala itu tidak terbiasa berbisnis," kata Pembina Yayasan Fatmawati, Dwi Librianto, kepada Tempo.
Sarwono mengajukan proposal ke sana-sini. Proposal itu nyangkut di PT Graha Nusa Utama (GNU). Ini perusahaan milik Robert Tantular, terdakwa kasus penyelewengan dana Bank Century. Toto Kuntjoro, Direktur PT GNU, rupanya tertarik menanamkan investasinya di lahan yang secara tata kota berada di kawasan hijau tersebut. Dengan status seperti ini, tidak boleh ada bangunan berdiri di lahan itu kecuali membeli lahan pengganti sebagai daerah resapan air.
Nilai transaksi kemudian disepakati, yaitu Rp 1,2 juta per meter persegi. Total biaya pengalihan hak pengelolaan lahan Rp 264 miliar. Perinciannya, Yayasan menerima Rp 65 miliar dan Sarwono Rp 199 miliar. Jumlah untuk Sarwono lebih besar karena itu termasuk honornya sebagai makelar.
Dari jumlah uang itu, Sarwono menanggung kewajiban membayar pajak, memindahkan penggarap, membangun perumahan karyawan rumah sakit, dan membangun kembali berbagai fasilitas rumah sakit yang digusur karena berada di luar area rumah sakit. "Biayanya sangat besar. Honor kami jadi menyusut," ujar Sarwono.
Pada 2003, Yayasan dan PT GNU menandatangani kesepakatan bisnis itu. Belakangan masuk pula PT Nusa Utama Sentosa, perusahaan yang satu grup dengan PT GNU. "Robert hadir di tiap acara penandatanganan kesepakatan," kata Dwi. Menurut Sarwono, PT GNU sejak awal tidak menyebutkan secara persis penggunaan lahan tersebut. "Misi pengurus saat itu hanya ingin lahan dimanfaatkan," ujarnya. Kini lahan itu digunakan sebagai lapangan golf.
Pengurus Yayasan mulai gerah saat Sarwono tak kunjung membayar sisa uang pembayaran sebesar Rp 40 miliar. Menurut Dwi, saat itu Sarwono mengeluarkan berbagai dalih, dari kehabisan modal sampai mengaku rugi karena keuntungan lapangan golf tak menutup ongkos mengelola lahan.
Bosan menunggu, pada Juli 2010, pengurus mencari alternatif dengan menggandeng investor lain, yaitu PT Mekaelsa. Salah satu proyeknya adalah kawasan Sentul City di Bogor. Yayasan perlu duit untuk Rumah Sakit R.P. Soeroso miliknya. Kesepakatan pun terjadi. PT Mekaelsa setuju membayar Rp 400 miliar untuk lahan 22 hektare milik Yayasan. "Perusahaan berkomitmen membantu Yayasan membangun rumah sakit," kata Andreas Dony, pengacara PT Mekaelsa.
Di sinilah muncul gesekan keras antara Yayasan dan Sarwono. Dia menuduh Yayasan wanprestasi. Berbagai pertemuan kedua pihak digelar untuk membahas hal ini. Yayasan bertahan dengan keputusannya: memecat Sarwono sebagai utusan dan menggandeng PT Mekaelsa. "Saya punya dokumen lengkap bahwa kami masih menguasai lahan itu," ujar Sarwono.
Kedua pihak mulai melempar cerita miring. Sarwono mengatakan kelompok Dwi mata duitan karena menerima harga dari PT Mekaelsa yang berlipat ganda. Dari sini, cerita perihal lahan ini pun menyeret nama pengusaha Tomy Winata. PT Mekaelsa, yang dimiliki Cahyadi Kumala alias Sui Teng, disebut-sebut di-backup Tomy Winata. Kepada Tempo, pengacara PT GNU, Mohammad Nashihan, mengaku pernah menemui Tomy membicarakan lahan ini.
Pertemuan itu, kata Nashihan, terjadi bulan lalu di salah satu ruangan khusus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Selain Tomy dan Nashihan, hadir Wakil Presiden Komisaris Sentul City Basir A. Barmawi. Pertemuan tertutup itu, menurut Nashihan, digagas Sui Teng, yang justru tak hadir. Dalam pertemuan yang tak menghasilkan kata sepakat tersebut, Tomy tak banyak bicara. "Dia bilang tak akan ikut campur dalam masalah itu," kata Nashihan.
Pekan lalu, Tempo menghubungi Tomy Winata untuk meminta konfirmasi soal pertemuan itu. Dia menyatakan tak ada pertemuan yang dimaksud Nashihan itu. "Saya enggak mengerti apa-apa," katanya. Dia juga menyatakan tak memiliki kaitan bisnis dengan Mekaelsa. "Saya tidak berbisnis di lahan itu," ujarnya.
Basir mengakui ada pertemuan itu. Hanya, ia menyatakan tak ada Tomy Winata di sana. Menurut Basir, dia tak kenal siapa saja yang hadir. "Saya hanya membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan Yayasan Fatmawati," kata mantan Kepala Divisi Humas dan Direktur Sumber Daya Manusia Mabes Polri ini kepada Tempo.
Nashihan menyatakan alasan penangkapan Sarwono itu jelas dibuat-buat. "Penangkapannya juga tak prosedural karena tidak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujarnya. Sebagai penjual, kata dia, Sarwono tak ada urusan dengan asal-muasal uang si pembeli. "Ada campur tangan orang kuat dalam kasus ini," katanya.
Menurut sumber Tempo, kelompok Sarwono ini juga sebenarnya bukan "orang biasa". Saham PT GNU dan PT Nusa Utama Sentosa, kata sumber ini, sudah dikuasai Grup Ancora, yang juga berhasrat berbisnis di lahan Yayasan Fatmawati itu. Grup ini milik Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, yang dulu dikenal sebagai pengusaha. "Memang milik Pak Gita," ujar Nashihan, yang mengaku ditunjuk Ancora mendampingi Sarwono.
Gita disebut-sebut tak tinggal diam. Sumber Tempo mengatakan Gita pernah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi kepolisian untuk mencari tahu "duduk persoalan" lahan Fatmawati "miliknya" itu. Ditanyai soal ini, Nashihan enggan menjawab. Tapi sumber Tempo di Markas Besar Polri menyatakan lahan bernilai kakap di Fatmawati itu memang menjadi rebutan dua kelompok yang masing-masing memiliki pengaruh dan kaki tangan di kepolisian.
Jika kelak Sarwono bisa "ditekuk"—dengan tuduhan adanya duit Century itu—dan ujung-ujungnya jual-beli yang ia lakukan tak sah, bukan mustahil lahan ini bakal pindah ke Mekaelsa. "Dua nama besar itu kini adu kuat di Mabes Polri," kata sumber Tempo.
Mustafa Silalahi
Sengkarut Sengketa
Maret 1999
Mahkamah Agung memutuskan Departemen Kesehatan mengganti uang lahan 35 hektare yang selama ini digunakan Rumah Sakit Fatmawati sebesar Rp 75 miliar ke Yayasan Fatmawati.
2002
Pemerintah, lewat Departemen Kesehatan, secara resmi mengakui lahan milik Yayasan Fatmawati 22 hektare. Sedangkan lahan Rumah Sakit Fatmawati 13 hektare.
2002
Yayasan Fatmawati memberikan kuasa kepada Sarwono, Stefanus, dan Umar untuk mengelola sisa lahan 22 hektare untuk dijual dan/atau dikelola pihak ketiga.
2004
Sarwono membangun lapangan golf untuk mengisi kekosongan di lahan milik Yayasan Fatmawati.
November 2008
Kasus Bank Century meledak. Bank milik Robert Tantular ini dinyatakan gagal bayar.
November 2008
Robert Tantular ditangkap. Ia diduga telah mengakibatkan Bank Century gagal kliring.
Juli 2010
Yayasan Fatmawati menggandeng PT Mekaelsa bekerja sama mengolah tanah 22 hektare milik Yayasan.
Agustus 2010
Sarwono dkk mengadukan Pembina Yayasan Fatmawati, Dwi Librianto, ke polisi karena wanprestasi dan dugaan penipuan karena telah menggandeng pihak lain.
Mei 2011
Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan dua sertifikat masing-masing seluas 13 dan 22 hektare atas nama Kementerian Kesehatan di atas lahan yang dulunya milik Yayasan Fatmawati. Dengan perjanjian, sertifikat untuk 22 hektare akan dibalik nama menjadi atas nama Yayasan Fatmawati.
Mei 2000
Yayasan Fatmawati menggandeng notaris R.M. Johanes Sarwono untuk menyelesaikan sengketa antara Yayasan dan pemerintah.
Desember 2000
Pemerintah dan Yayasan berdamai. Pemerintah sepakat membayar Rp 25 miliar untuk lahan 13 hektare. Sisa Rp 50 miliar dibayar dengan menyerahkan 22 hektare sisa lahan ke Yayasan. Dengan syarat: Yayasan membangun fasilitas pengganti.
2003
Sarwono menggandeng PT Graha Nusa Utama dan PT Nusa Utama Sentosa yang dimiliki Robert Tantular untuk membeli tanah Yayasan. Total harga tanah Rp 264 miliar.
Kesepakatan:
2003-2005
Graha Nusa dan Nusa Utama membayar tiga kali cicilan uang jual-beli lahan, total Rp 25 miliar. Sarwono menerima upah Rp 5 miliar dari total uang itu.
2009-2010
Yayasan Fatmawati berkali-kali melaporkan Sarwono dkk ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, dan pengingkaran kesepakatan.
2010
Markas Besar Kepolisian, yang sebelumnya menangani kasus aliran dana Robert Tantular, membuka kembali kasus ini. Seluruh dokumen dan saksi kembali dipanggil.
5 Desember 2011
Yayasan Fatmawati menyerahkan Rp 20 miliar yang dulu mereka terima dari Graha Nusa dan Nusa Utama ke Mabes Polri karena menduga uang tersebut berasal dari pencucian uang yang melibatkan Robert Tantular.
3 September 2012
Mabes Polri menangkap Sarwono atas dugaan keterlibatan dalam kasus pencucian uang Bank Century.
Mustafa Silalahi
Sumber: Riset dan wawancara
Kemesraan Tak Berumur Panjang
Rumah Sakit Fatmawati dan Yayasan Fatmawati kini bisa disebut tak lagi saling terkait. Rumah Sakit merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Kesehatan, sedangkan Yayasan dikelola sisa-sisa pengurusnya yang murni orang swasta. "Sudah lama putus hubungan," kata Pembina Yayasan Fatmawati, Dwi Librianto.
Rumah sakit di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, itu bermula dari gagasan Ibu Negara Fatmawati Sukarno membangun rumah sakit khusus tuberkulosis anak-anak. Untuk mewujudkan gagasan itu, pada 30 Oktober 1953, Fatmawati menggelar malam amal di Istana Negara.
Dana yang terkumpul malam itu menjadi modal pertama pendirian Yayasan Ibu Soekarno, yang resmi berdiri pada 24 Desember 1953. Dalam kepengurusan yayasan itu, Fatmawati menjadi pelindung. Adapun pendiri dan pengurusnya sejumlah pejabat di kabinet Sukarno, antara lain Menteri Sosial Raden Pandji Soeroso.
Dengan modal awal sekitar Rp 350 ribu, Yayasan Ibu Soekarno membeli tanah seluas 40-an hektare di Kecamatan Cilandak—waktu itu masih Kecamatan Kebayoran Lama. Lahan tersebut merupakan tanah garapan rakyat tanpa izin pemerintah. Setahun kemudian, pada 2 Oktober 1954, Fatmawati meletakkan batu pertama bangunan Rumah Sakit Ibu Soekarno.
Pada 12 Desember 1958, Yayasan Ibu Soekarno menyerahkan gedung rumah sakit separuh jadi kepada Departemen Kesehatan untuk dikelola. Perjanjiannya, antara lain, hak milik atas bangunan dan hak pakai atas tanah tetap melekat pada Yayasan. Adapun penyelesaian gedung dan pemeliharaan bangunan menjadi tanggungan Departemen Kesehatan.
Pada 1966, Direktur Rumah Sakit R. Soehasim mengusulkan nama rumah sakit diganti menjadi Rumah Sakit Fatmawati. Alasannya: nama Ibu Soekarno tidak tepat karena bisa merujuk pada Fatmawati dan Hartini—keduanya istri Bung Karno. Padahal yang mempunyai gagasan mendirikan rumah sakit itu Fatmawati.
Fatmawati setuju. Pada 20 Mei 1967, rumah sakit berganti nama menjadi Rumah Sakit Fatmawati. Dua bulan kemudian, Yayasan pun berganti nama menjadi Yayasan Fatmawati.
Tapi kemesraan Yayasan dan Departemen Kesehatan ternyata tak panjang umurnya. Pada 1967, Yayasan meminta kembali rumah sakit dan gedung yang dibangun pemerintah. Namun pemerintah tak mengabulkan permintaan itu. Jalan tengahnya, pada 25 Juli 1967, dibuat kontrak pengelolaan bersama rumah sakit.
Pada 1987, pengurus baru Yayasan, dengan ketuanya R.P. Harisoehardjo Tjondronegoro, mengajukan perpanjangan hak pakai atas tanah rumah sakit. Tapi Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam menolak permintaan itu. Hak pakai atas tanah malah sepenuhnya beralih ke Departemen Kesehatan.
Tak puas, Yayasan Fatmawati menggugat Departemen Kesehatan. Singkat cerita, pada 19 Maret 1999, Mahkamah Agung memenangkan Yayasan. Mahkamah memerintahkan Departemen Kesehatan membayar kompensasi sebesar Rp 75 miliar kepada Yayasan Fatmawati.
Putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa dieksekusi lantaran pemerintah tak sanggup membayar. Akhir tahun 2000, kedua pihak membuat kesepakatan baru. Pemerintah akan membayar Rp 25 miliar dan menyerahkan lahan 22 hektare. Adapun Yayasan wajib membangun aset pengganti, seperti asrama perawat dan rumah dinas karyawan. Tapi kesepakatan itu hingga kini belum terlaksana.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita mengatakan pemerintah tak keberatan melepas lahan 22 hektare kepada Yayasan, tapi Yayasan harus menuntaskan sejumlah kewajibannya. "Antara lain balik nama lima sertifikat lahan aset pengganti," ujar Ratna pekan lalu.
Jajang Jamaludin dan Gadi Makitan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo