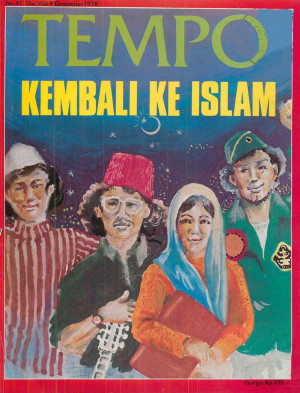KEADAAN Sunar telah betul-betul payah. Menaiki tangga dan
memasuki gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah turun
dari mobil tahanan bersama 44 pesakitan lainnya, 23 Nopember
lalu ia dipapah petugas. Tulang belakangnya pun tampak sudah tak
mampu menyangga tubuhnya yang kurus kering.
Dia terguling rubuh ke lantai ketika berusaha duduk berderet
dengan tahanan lain di bangku panjang. Akhirnya Sunar
ditelentangkan di bangku menunggu panggilan menghadap hakim.
Tapi hari itu ia tak jadi dihadapkan kepada hakim -- dengan
alasan kesehatan.
Apa salahnya? "Saya dikeroyok karena dicemburui ada main dengan
isteri orang," kata Sunar lemah. Waktu itu, ceritanya, ia memang
sempat mencabut golok dan membacok salah seorang pengeroyoknya.
Tapi akhirnya dia berhasil diringkus dan dianiaya. Di tahanan
polisi, Juli lalu, ia memang sudah dalam keadaan runyam. "Di
tahanan hanya sekali diperiksa dokter dan diberi pel." Tapi ia
sudah terlanjur merasakan kelumpuhan pada kedua kakinya.
Pernahkah Sunar minta bantuan hukum? Dia menggeleng sambil
bertanya kembali: "Bantuan hukum itu apa?" Nama LBH (Lembaga
Bantuan Hukum) belum pernah lewat di telinganya.
Bambang Riyanto. Jabatannya tukang parkir dan terakhir mangkal
di Kebon Sirih Jakarta. Pemuda (21 tahun) jebolan sekolah teknik
ini, dituduh tersangkut peristiwa penodongan. Seminggu lebih,
katanya, polisi tak berhasil memeras pengakuan dari mulutnya.
Tapi hari-hari berikutnya lancar. Bambang mengaku juga. "Habis
saya dipukuli dengan kayu dan tangan saya digigit," kata
Bambang.
Di muka hakim, minggu lalu, Bambang mencabut pengakuannya.
Alasannya, seperti yang umum dikemukakan pesakitan sekelas
dengan dia, pengakuan dibuat karena paksaan. Hakim tak mampu
membujuk Bambang untuk kembali pada pengakuan yang dibuat di
muka polisi. Maka sidang diundur untuk memanggil polisi yang
pernah memeriksanya.
Kali ini hakimpun mafhum, cara pemeriksaan terhadap tertuduhnya,
oleh polisi, memang dapat menghasilkan pemungkiran kembali di
muka hakim. Bagi pesakitan yang buta hukum seperti dua kasus di
atas, memang mudah dikerjai oleh pemeriksa untuk mengakui
tuduhan. Sebab diingatkan tentang hakhak hukumnya pun, (seperti
hak mengingkari tuduhan) mereka tak akan mengerti. Apalagi hak
memperoleh bantuan hukum atau menghubungi penasehat hukum. Belum
lagi soal kemampuan mereka membayarnya.
Bagi yang melek hukumpun, masalah bantuan hukum bukan barang
yang mudah diperoleh. Dengan kata lain, soal bantuan hukum bagi
tersangka sejak ia ditangkap, ditahan dan diperiksa, adalah
persoalan hukum yang macet. Sebab bersamaan dengan itu ada
persoalan rehabilitasi dan ganti rugi serta peradilan tata usaha
negara yang belum dirasakan prakteknya. Walaupun, sebagai hak
kemanusiaan, hal itu telah dijanjikan undang-undang (UU Pokok
Kekuasaan Kehakiman). Lebih-lebih pula peraturan pelaksanaan UU
itu belum juga lahir.
Konsensus para pejabat puncak penegak hukum, yaitu Ketua
Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Menteri
Kehakiman di Cibogo Pebruari 1973 -- sebagai ikhtiar pemberian
hak bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum -- gemanya
hampir-hampir tak terasa dalam praktek. Waktu itu para penegak
hukum berpendapat, selama pemeriksaan berlangsung, tersangka
tidak dapat didampingi penasehat hukumnya. Tapi walaupun tetap
diawasi, tersangka boleh berhubungan dengan pembelanya sebelum
dan sesudah pemeriksaan.
Namun, dengan berbagai alasan, dalam praktek polisi atau jaksa
hanya mengizinkan tersangka menghubungi pembela bila pemeriksaan
telah selesai. Artinya setelah pemeriksa merasa puas memeras
pengakuan tersangka.
Namanya juga hanya konsensus. "Kalau saya membandel juga tidak
ada sanksi apa-apa, paling ditegur karena bandel saja," komentar
seorang pejabat reserse berpangkat perwira menengah Polri di
Jakarta.
Belakangan muncul Menteri Hankam Jenderal M. Jusuf yang
mempersoalkan kembali hal itu. Tanggal 11 Nopember lalu dengan
sponsor Kopkamtib, para pejabat tertinggi penegak hukum
mempersoalkan bantuan hukum itu lagi. Kali ini lahir pernyataan
bersama. Antara lain disebutkan: seorang tersangka, pada tingkat
pemeriksaan pendahuluan, "terutama sejak saat dilakukan
penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum."
Bersama dengan itu, demi memperlakukan tersangka "sesuai dengan
martabatnya sebagai manusia", seperti yang diminta Jenderal
Jusuf, tersangka harus boleh berhubungan dengan keluarga atau
penasehat hukum.
Pernyataan bersama, yang dianggap sebagai janji untuk kesekian
kalinya dari para penegak hukum, masih disambut sehangat
konsensus Cibogo. Cuma, seperti yang diharapkan Tasrif, "Peradin
mengharapkan pernyataan bersama itu akan dilaksanakan dengan
konsekwen, konsisten, agar tidak menjadi harapan kosong seperti
konsensus sebelumnya."
LBH Jakarta dan LKBH (Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum)
Fakultas Hukum UI, menyambut pernyataan tersebut dengan sebuah
lokakarya bantuan hukum, 17 s/d 19 Nopember. Idenya menurut
Direktur LBH, Adnan Buyung Nasution SH, sebenarnya sudah
dipendam sejak lama. Namun baru hari-hari inilah dianggap tepat
dilambungkan. "Yah, sekarang baru ada angin baik," kata Buyung.
Untuk Pegangan
Sebenarnya yang diharapkan lebih dari sekedar pernyataan
bersama. Sebab seperti ditanyakan sementara ahli hukum, mengapa
tidak melaksanakan konsensus Cibogo saja? "Pernyataan bersama
itu penting untuk menggaris bawahi konsensus yang telah ada,"
jawab Ali Said, Jaksa Agung, salah seorang penandatangan
pernyataan, "hal itu perlu untuk pegangan bagi aparat bawahan."
Atau, apakah tidak lebih tepat bila penegak hukum melahirkan
saja Peraturan Pelaksanaan UU Pokok Kehakiman yang lebih berarti
dari konsensus atau pernyataan? Sebab menurut Wakil Direktur
LBH, Tatang Suganda, ternyata "mutu" perumusan pernyataan
bersama pun masih berada di bawah kemauan undang-undang.
Pernyataan bersama menyebutkan antara lain, seorang tersangka
"dapat memperoleh bantuan hukum . . . ". Sedangkan undang-undany
menyatakan, soal bantuan hukum itu merupakan hak. Artinya,
menurut Tatang, "undang-undang mewajibkan pemerintah
mengingatkan hak-hak hukum tersangka untuk memperoleh bantuan
hukum. " Tidak hanya sekedar mengizinkan tersangka. Bahkan,
katanya, "undang-undang juga mewajibkan pemerintah menyediakan
penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu tapi ingin
menggunakan haknya ketika mereka ditangkap, ditahan dan
diperiksa. "
Kesempatan bagi seorang pembela berdiri di samping kliennya,
akan merupakan proses penerapan hukum yang sehat. Setidaknya,
"positif bagi hakim," seperti kata J.Z. Loudoe SH, hakim anggota
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Begitu pula diharapkan
berita-acara pemeriksaan akan lebih baik dari sekarang ini. Dan
pemeriksaan di pengadilan akan lebih lancar.
Dan bagi tersangka, betapapun kejahatannya, akan merasa aman di
bawah atap kantor polisi. Tinggal sekarang di pihak kepolisian.
Instansi ini tentu menyatakan setuju terhadap pernyataan bersama
yang ikut ditandatangani Mayjen Pol. T. Ibrahim, Inspektur
Jenderal Kepolisian RI. Tapi bagi beberapa pejabat kepolisian
daerah, seperti terungkap setelah rapat para Kadapol, Laksusda
dan Pangkowilhan, 20 Nopember kemarin, dalam beberapa hal
sebenarnya masih lebih suka menutup mata terhadap
praktek-praktek lama bawahannya. Mereka belum begitu suka
tersangka berhubungan dengan pembela sebelum selesai
pemeriksaan. Juga masih tidak begitu saja menyalahkan pemeriksa
yang main pukul terhadap tersangka.
Rasa Jengkel
Seorang Kadapol dari kota besar masih berkata seperti ini: "Saya
masih bisa mentolerir anak buah yang memukuli penjahat
residivis." Sebagai manusia, katanya, polisi juga punya rasa
jengkel. Bukti dan saksi cukup. "Tapi penjahat tetap saja
penjahat dia masih mungkir." Menghadapi tersangka yang demikian,
Kadapol ini menantang, "coba saya serahkan kepada yang anti
kekerasan. Tapi kalau dua jam tidak keluar pengakuan, saya
kencingi!"
Apakah tersangka sudah boleh menghubungi pembela sejak ia
ditangkap? "Polisi belum siap," kata Kadapol ini. Menghadapi
para pembela yang bertitel sarana hukum, apalagi yang kawakan,
"anggota saya yang berpangkat sersan dan hanya lulusan sekolah
dasar akan dimakan!"
Seorang Inspektur Kodak dari daerah terpencil mengakui pernah
menggunakan kekerasan ketika memeriksa suatu perkara. Pengakuan
diperoleh dari tersangka maupun saksi setelah menggunakan teknik
pemeriksaan keras. Hasilnya Terdakwa dibebaskan oleh hakim.
Sebab baik tersangka maupun saksi memungkiri keterangan yang
pernah diberikan di meja pemeriksaan. Tapi, "kalau ditanya:
apakah cara pemeriksaan dengan pemukulan itu boleh? Saya akan
tegas menjawab: tidak boleh, itu salah!" kata Inspektur Kodak
ini. "Tapi, bagaimanapun, saya masih bisa menerima apabila cara
begitu tidak untuk kepentingan pribadi." Misalnya dengan cara:
bila suasana pemeriksaan sudah panas tersangka berkelit terus,
"saya lebih baik keluar ruangan, agar pemukulan tidak
berlangsung di depan mata saya."
Dari sikap sebagian pejabat kepolisian di atas, agaknya jelas:
target pemeriksaan terhadap tersangka adalah memeras pengakuan.
Seolah-olah hanya dari pengakuan tersangkalah titik tolak proses
pembuktian sebagai modal polisi atau jaksa membawa tersangka ke
pengadilan.
Jadi tersangka harus mengaku? "Hak tersangka untuk ingkar atau
tidak, harus memberikan keterangan yang benar," menurut Tatang
Suganda. Itulah sebabnya, kata Tatang, polisi tidak harus
mengejar-ngejar pengakuan dengan cara-cara yang tidak wajar dan
melampaui batas. Sebagai alat bukti, menurut undang-undang,
kedudukan pengakuan tersangka sendiri masih di bawah keterangan
saksi dan bukti berupa surat. Tanpa pengakuan tersangka, bila
teknik pemeriksaan berhasil mengumpulkan alat-alat bukti lain,
tentulah hakim sudah mempunyai pertimbangan untuk memvonis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini