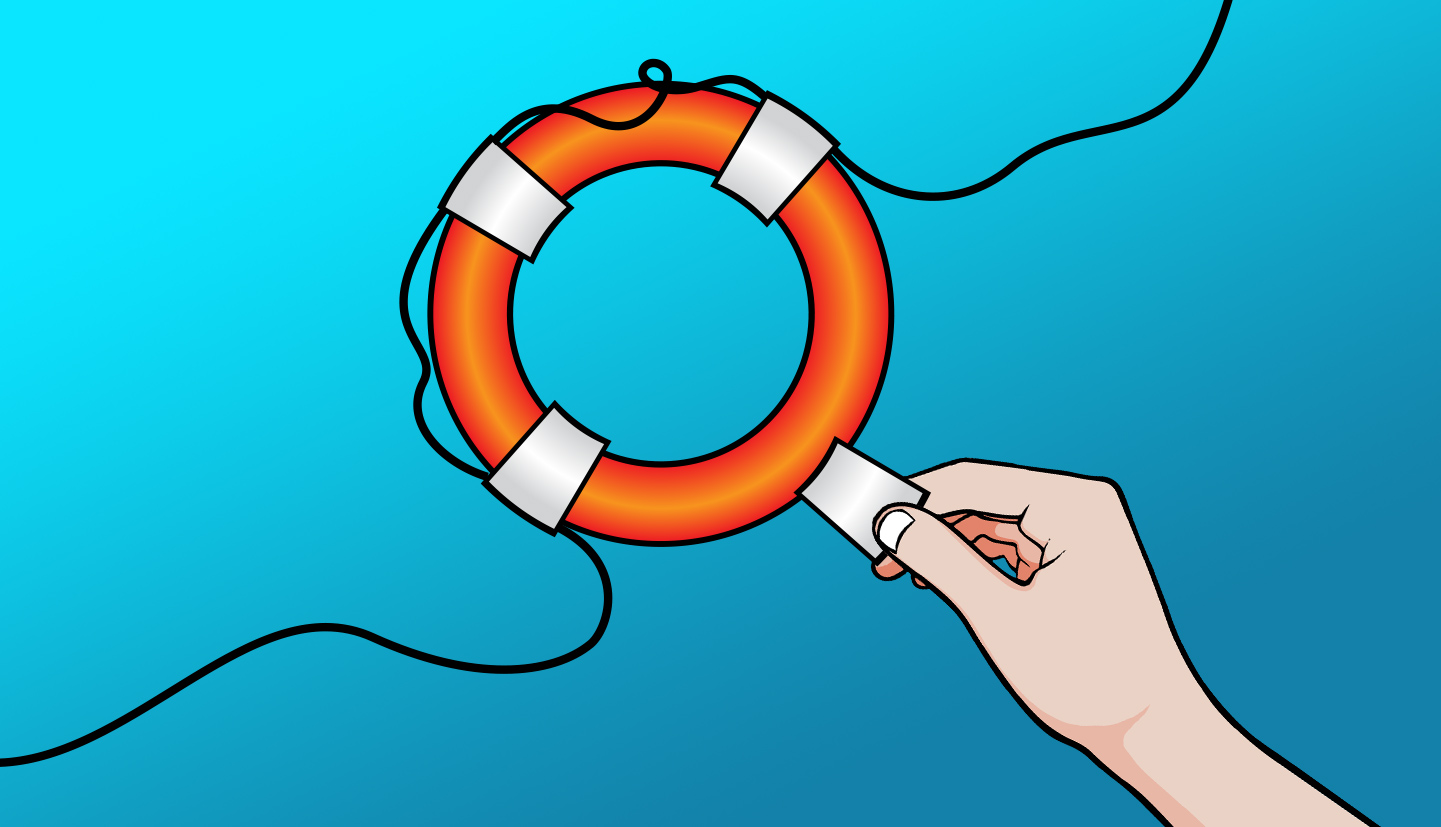Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JIKA benar Presiden Joko Widodo akan mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, inilah kisah ajaib tentang pembentukan kabinet di Indonesia selama 50 tahun terakhir. Pada 1966, Presiden Sukarno pernah mengangkat Letkol Imam Syafii, yang dikenal sebagai ”raja copet Senen”, menjadi Menteri Negara Urusan Keamanan Khusus. Untungnya, ”Kabinet 100 hari” itu lebih pandak usianya ketimbang umur jagung.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo