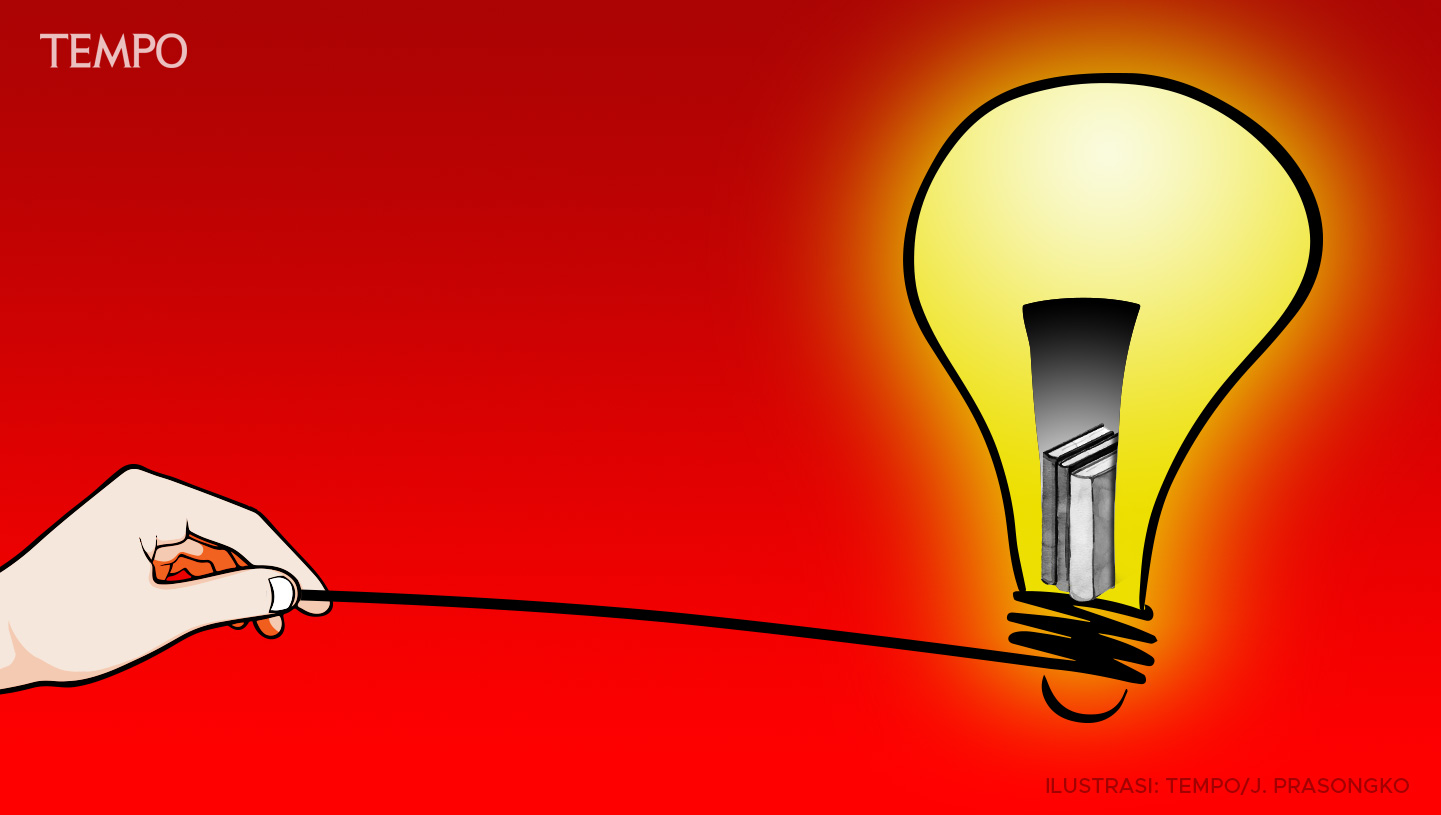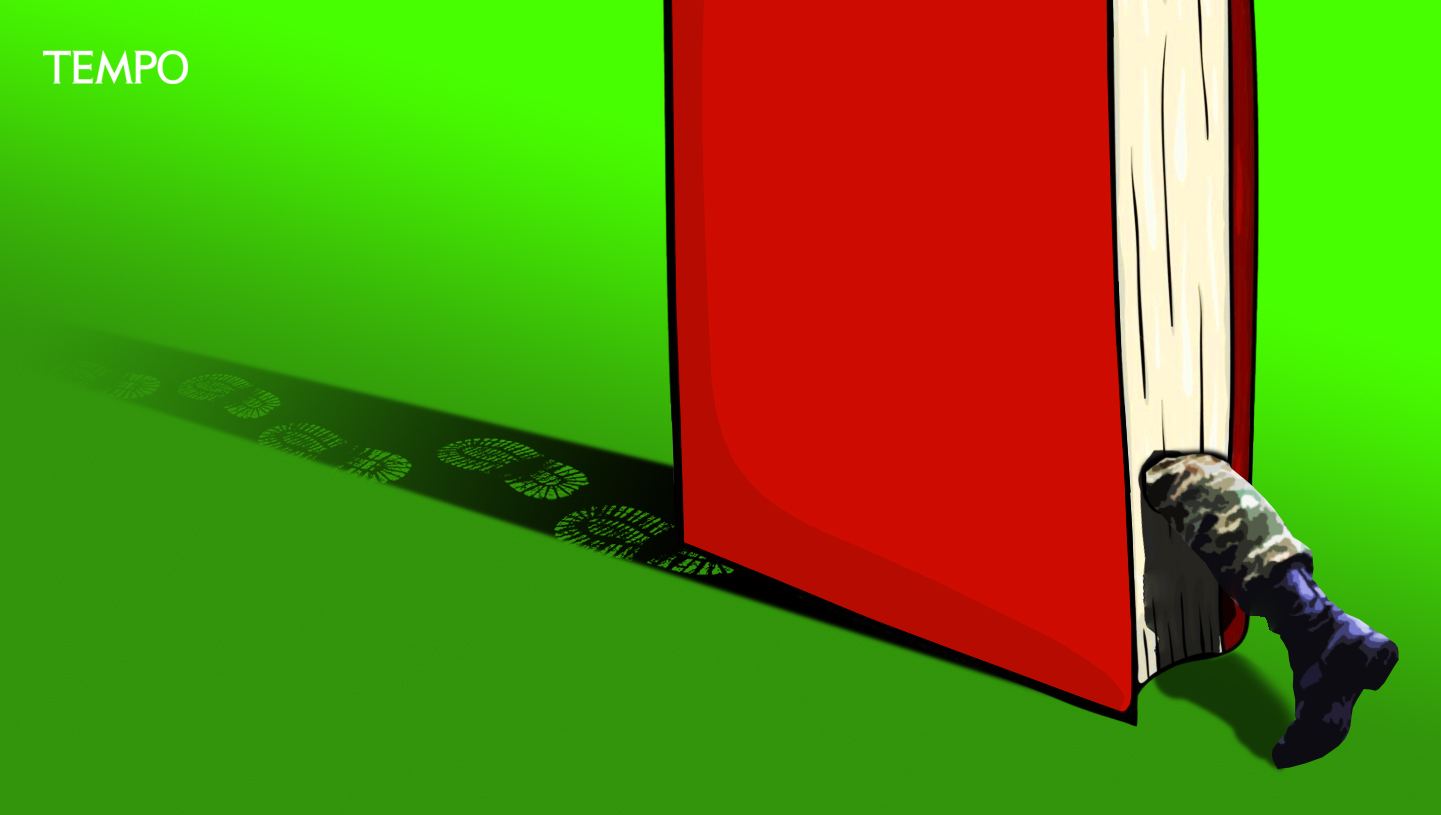Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic and Educational Business Institute, Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Polemik cukai rokok belakangan ini kembali menghangat menyusul keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 23 persen per 1 Januari 2020. Dengan kenaikan ini, harga jual eceran rokok akan naik rata-rata 35 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kenaikan cukai ini seakan-akan menjadi klimaks. Belum pernah ada kenaikan cukai melebihi 20 persen selama 10 tahun terakhir. Pada 2018 saja, misalnya, pemerintah menetapkan cukai rokok naik 10,04 persen dan tetap dipertahankan hingga 2019, sehingga kenaikan cukai 23 persen masih wajar sejalan dengan inflasi.
Kenaikan cukai rokok juga dijustifikasi oleh tren yang berlaku di banyak negara. Peningkatan cukai dan harga jual rokok bahkan lebih pesat di semua negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Beban cukai rokok di negara anggota OECD mencapai 50 persen dari harga jualnya.
Menekan konsumsi rokok menjadi argumen utama atas kenaikan tarif cukai rokok. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi perokok pada usia anak dan remaja usia 18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen, sementara jumlah perokok perempuan melejit dari 1,3 persen menjadi 4,8 persen.
Kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi juga dijalankan untuk membasmi peredaran rokok ilegal tanpa cukai sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Beban target cukai rokok dalam draf awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang sebesar Rp 179,2 triliun (naik 10 persen dari outlook 2019) tampaknya mengamini.
Apa pun alibinya, penargetan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyetor sejumlah tertentu ke kas negara perlu digarisbawahi. Cukai adalah pungutan negara atas barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Cukai rokok dikenal sebagai "pajak dosa" lantaran pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
Namun target setoran itu menunjukkan penerimaan cukai justru sebagai tujuan primer, alih-alih pengendalian konsumsi. Jika Direktorat memang memandang cukai merupakan sumber penerimaan negara, itu harus diikuti oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi obyek terkena cukai.
Dengan asumsi tarif cukai tetap sama, ekstensifikasi harus ditempuh dengan memperbanyak obyeknya. Sejauh ini, hanya ada tiga barang yang terkena cukai, yakni tembakau, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Porsi perolehan cukai tembakau mencapai 95 persen di antara ketiganya.
Opsi lain adalah intensifikasi. Dengan sifat rokok yang adiktif dan inelastis terhadap harga, cara paling mudah untuk menggenjot penerimaan cukai adalah lewat tarif cukai. Jalur ini yang sepertinya dipilih Direktorat. Menurut ketentuan, cukai tembakau dipungut maksimal 57 persen dari harga jual. Maka, selama tarif cukai belum sampai batas maksimum, tarif akan selalu naik demi mengejar target penerimaan.
Pengenaan cukai rokok yang lebih tinggi niscaya melejitkan harga rokok. Jika harga rokok dianggap sudah memberatkan, konsumen akan mencari substitusinya, seperti rokok ilegal. Dengan demikian, kenaikan cukai rokok seolah-olah menjadi "prakondisi" bagi peredaran rokok ilegal.
Kemungkinan substitusi yang dipandang lebih "bergengsi" adalah rokok elektrik. Probabilitas terjadinya migrasi dari rokok konvensional ke rokok elektrik semakin terbuka. Pasalnya, perlakuan pemerintah terhadap cukai dan harga rokok elektrik tidak sama dengan rokok konvensional. Konsekuensinya, ada kemungkinan penerimaan negara menyusut. Kenaikan perolehan cukai dari rokok elektrik tidak sepadan dengan penurunan penerimaan cukai dari rokok konvensional. Lagi-lagi, kepentingan fiskal kurang sinkron dengan eksistensi industri tembakau sebagai "basis" penerimaan cukai.
Kekeliruan dalam mempersepsikan cukai berlanjut pada pemanfaatannya. Faktanya, penerimaan cukai dimasukkan ke postur APBN menjadi satu pos besar, yaitu penerimaan negara. Akibatnya, perolehan cukai, layaknya pajak, dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah.
Padahal cukai pada prinsipnya adalah retribusi yang alokasi belanjanya harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan barang terkena cukai. Karena itu, pelaku ekonomi yang terpapar dampak negatif rokok bisa mengklaim penerimaan cukai yang terhimpun.
Sebagian penerimaan cukai dalam dua tahun terakhir sudah disalurkan untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kecenderungan ini, lagi-lagi, bisa salah kaprah. Penikmat rokok dan peminum alkohol bisa "pede" mengklaim sudah ikut berkontribusi membiayai jaminan kesehatan nasional.
Maka, pungutan cukai rokok harus dikembalikan ke fungsi utamanya. Konsekuensinya, target Direktorat diukur dari berapa capaian konsumen yang terlindungi dari risiko rokok, alih-alih setoran cukainya.
Selama cukai rokok masih salah kaprah dipandang sebagai sumber penerimaan negara, sistem cukai di Indonesia senantiasa gagal dalam menunaikan tugas sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Alhasil, rokok seolah-olah menjadi makhluk dilematis yang dibenci (efeknya) sekaligus dirindu (setoran cukainya).