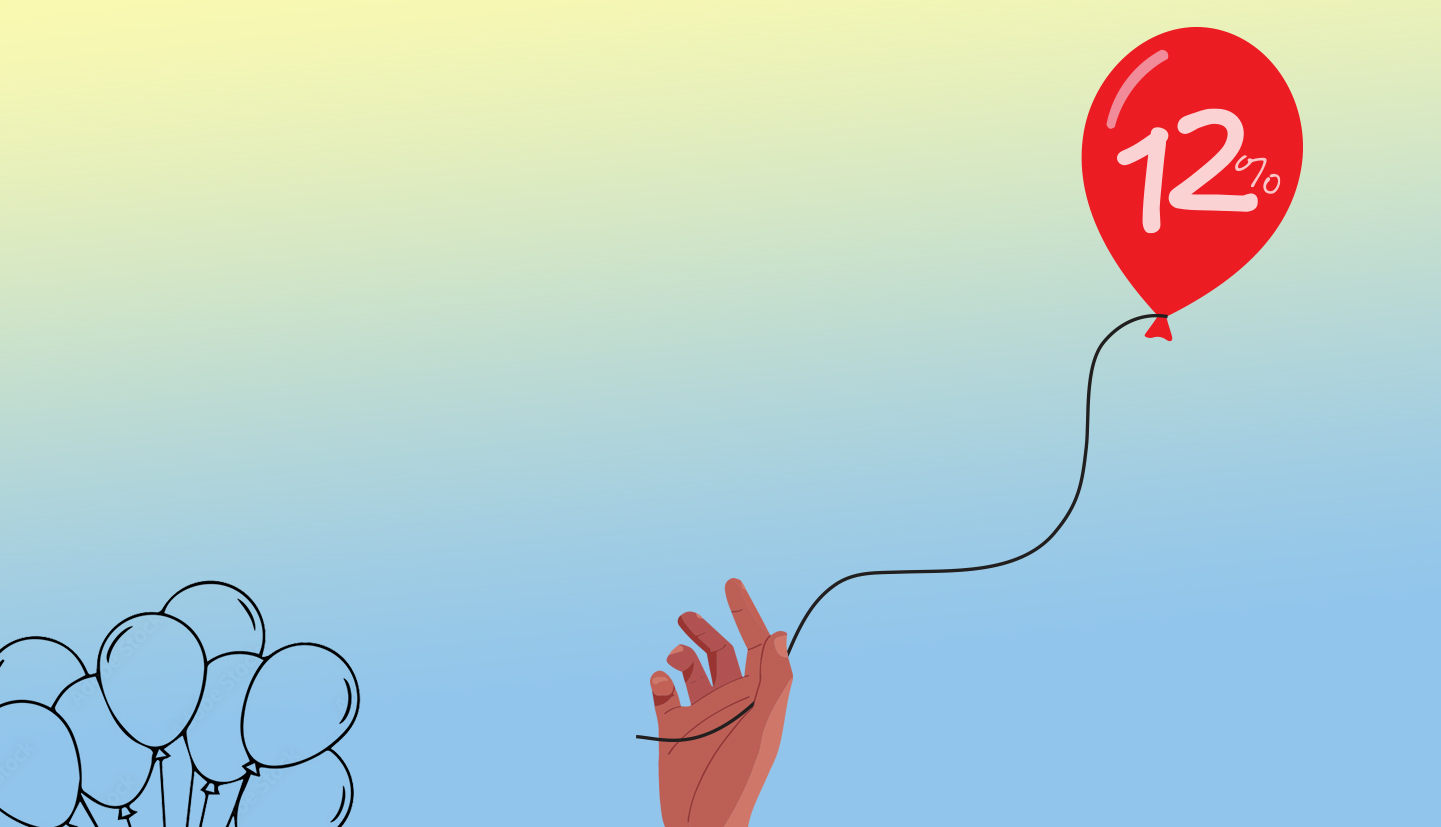Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah harus mengubah doktrin jiwa korsa agar tak dipahami secara sempit oleh prajurit.
Kesetiakawanan menjadi dalih melakukan kekerasan tatkala ada personel TNI terlibat perselisihan dengan warga sipil.
Kekerasan di Deli Serdang semestinya masuk ranah pidana umum karena kejadiannya di luar tugas militer.
SERANGAN puluhan prajurit Tentara Nasional Indonesia Batalyon Artileri Medan 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara, tak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk jiwa korsa. Selain menghukum para pelaku dengan sanksi setimpal, pemerintah harus mengubah doktrin jiwa korsa agar tak dipahami secara sempit oleh prajurit supaya kekerasan serupa tak terulang.
Penyerangan terhadap warga Desa Selamat terjadi pada Jumat malam, 8 November 2024. Bermula dari perselisihan seorang warga dengan anggota TNI, puluhan prajurit mengobrak-abrik perkampungan. Mereka menghajar warga yang bersirobok sembari berteriak-teriak akan membakar rumah penduduk. Kekerasan tersebut menewaskan Raden Barus, 61 tahun, dan menyebabkan banyak penduduk terluka.
Penyerangan tentara terhadap warga sipil di Deli Serdang menambah panjang daftar kasus kekerasan oleh anggota TNI. Imparsial—lembaga pegiat hak asasi manusia—mencatat terjadi 25 kasus kekerasan tentara terhadap warga sipil sejak Januari hingga November 2024. Adapun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendata ada 64 kasus kekerasan tentara terhadap warga sipil sejak Oktober 2023 hingga September 2024, dengan 18 orang tewas dan 75 korban terluka.
Kekerasan tentara terhadap warga sipil acap terjadi karena prajurit salah kaprah memahami jiwa korsa. Semangat kebersamaan tersebut semestinya diterapkan dalam upaya pertahanan negara. Kebanggaan sebagai bagian dari korps seharusnya tidak membabi buta, apalagi sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Di Indonesia, makna jiwa korsa menjadi sempit dan sentimental. Kesetiakawanan menjadi dalih prajurit melakukan kekerasan tatkala ada personel TNI terlibat perselisihan dengan warga sipil. Alih-alih menyelesaikannya dengan berdialog atau membawa masalah ke proses hukum, tentara memilih main hakim sendiri, seolah-olah “jiwa korsa” berada di atas hukum.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat turut bertanggung jawab atas terus berulangnya kekerasan tersebut. Kedua pihak tak punya niat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekerasan seperti yang terjadi di Deli Serdang semestinya masuk ranah pidana umum karena kejadiannya di luar tugas militer.
Undang-Undang TNI sebenarnya telah membuka jalan terhadap revisi tersebut. Pasal 65 undang-undang itu menyatakan tentara tunduk pada kekuasaan peradilan mana pun, bergantung pada pelanggaran hukumnya: peradilan militer dalam pelanggaran pidana militer dan, sebaliknya, peradilan umum jika pidana umum. Pengganjalnya cuma satu: pasal tersebut baru bisa diterapkan apabila ada ketentuan baru dalam Undang-Undang Peradilan Militer.
Sejak Undang-Undang TNI diberlakukan 20 tahun lalu, Undang-Undang Peradilan Militer tak pernah disentuh. Pemerintah dan DPR cuma bisa tutup mata. Ini menyebabkan reformasi TNI tak pernah tuntas. Padahal revisi Undang-Undang Peradilan Militer sangat penting untuk menghilangkan impunitas tentara yang melakukan kejahatan di luar tugas militer.
Karena sistem peradilannya tertutup, peradilan militer seolah-olah menjadi bunker dan tak ampuh membuat jera. Akibatnya, mata rantai kekerasan dan kesewenang-wenangan tentara terhadap warga sipil pun tak pernah putus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo