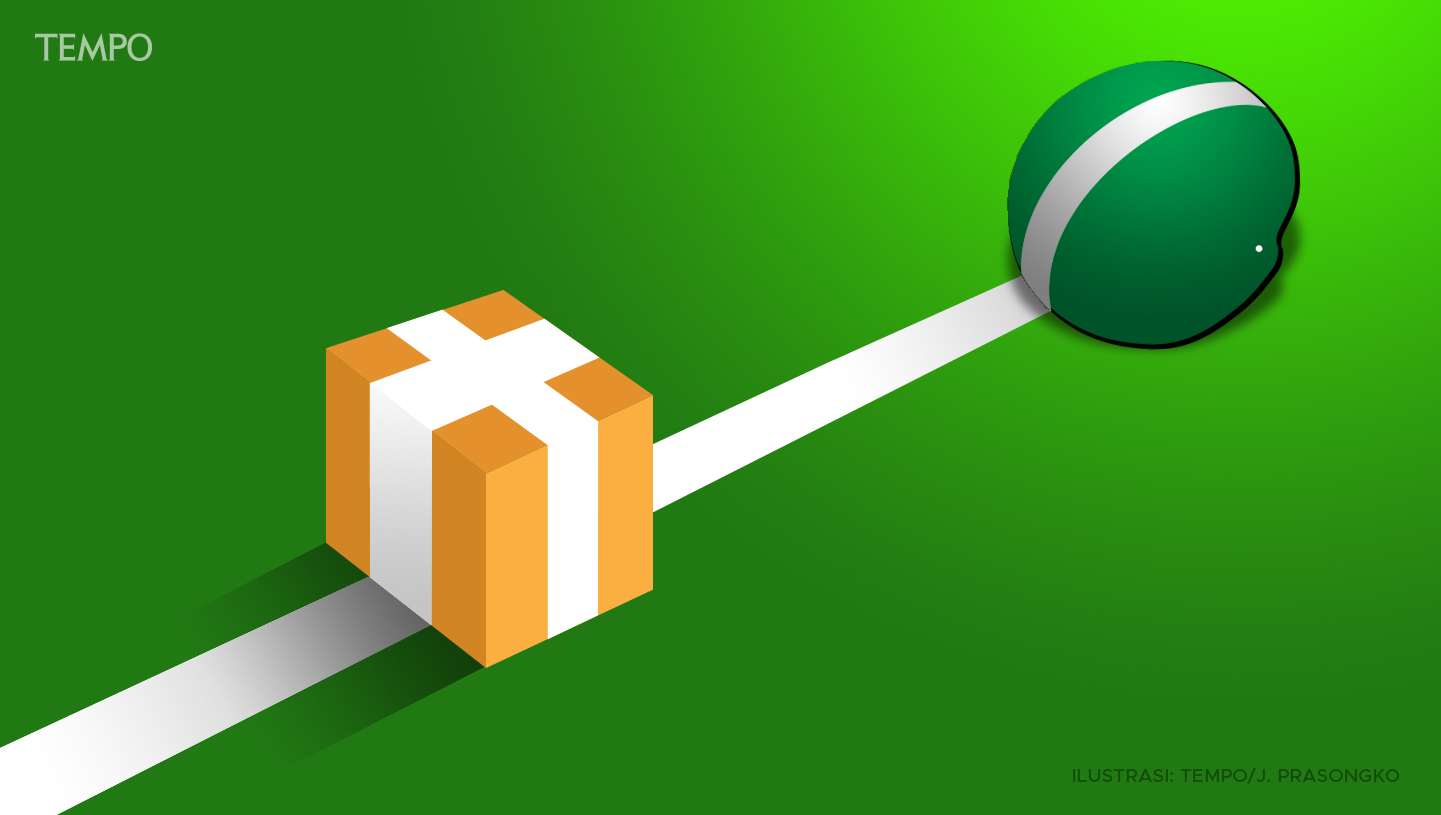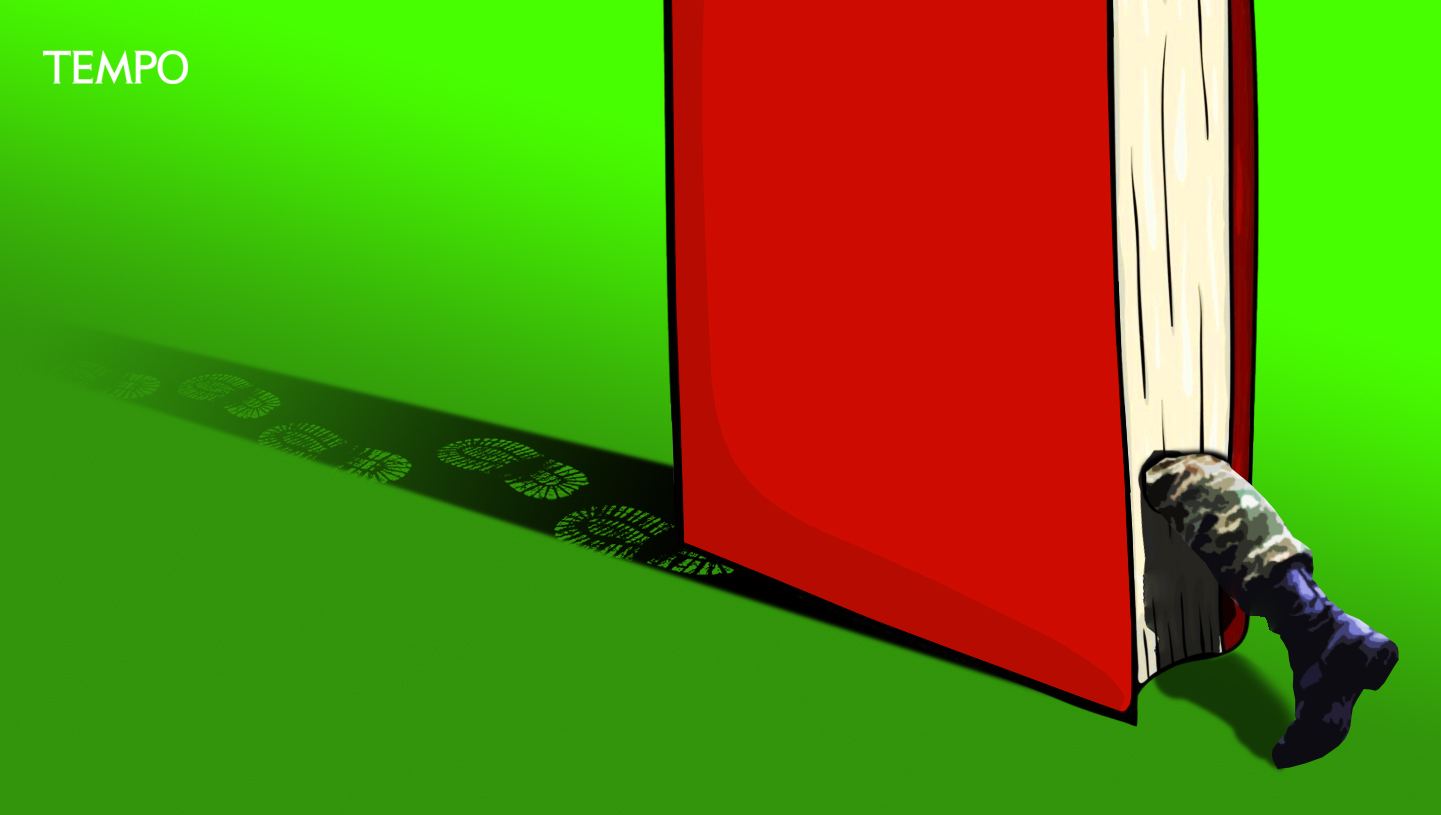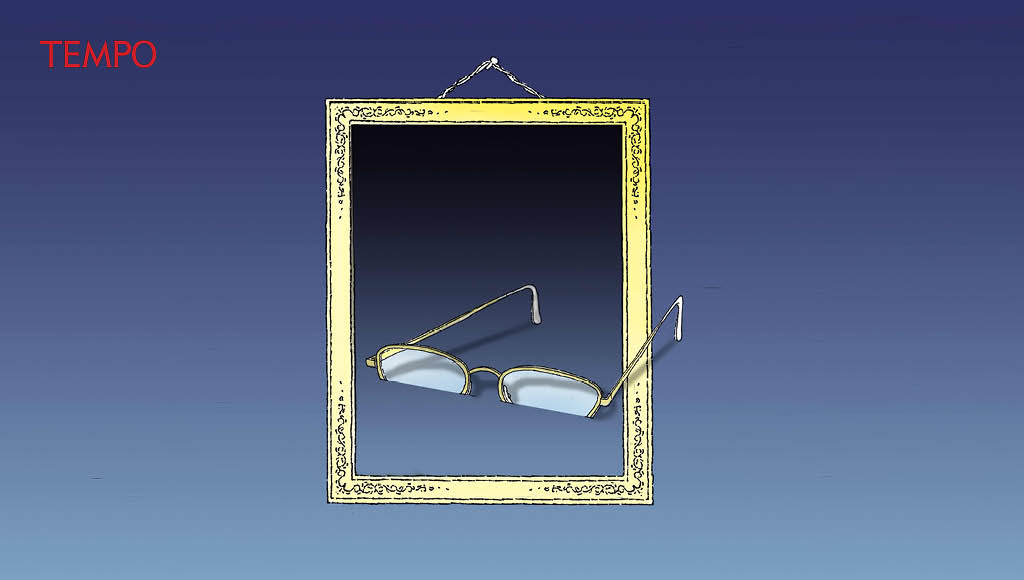Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Dalam lakon Der gute Mensch von Sezuan, Bertolt Brecht memaparkan apa yang belum terjawab: apakah kebaikan perlu?
Kini orang berbohong, berkhianat, dan berbalik gagang tanpa mempertimbangkan kehadiran sesama.
Dalam cerita Brecht, orang baik sangat penting bagi keselamatan hidupa--palagi bagi mereka yang ditipu, dikalahkan, dan disakiti
DI sebuah kota miskin di Sichuan, penjual air itu berdiri di pintu gerbang, menantikan dewa-dewa datang. Namanya Wang. Ia berjualan sesuatu yang tak selalu bisa diperjualbelikan dan, dalam ketidakstabilan hidupnya, ia mencoba berharap.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo