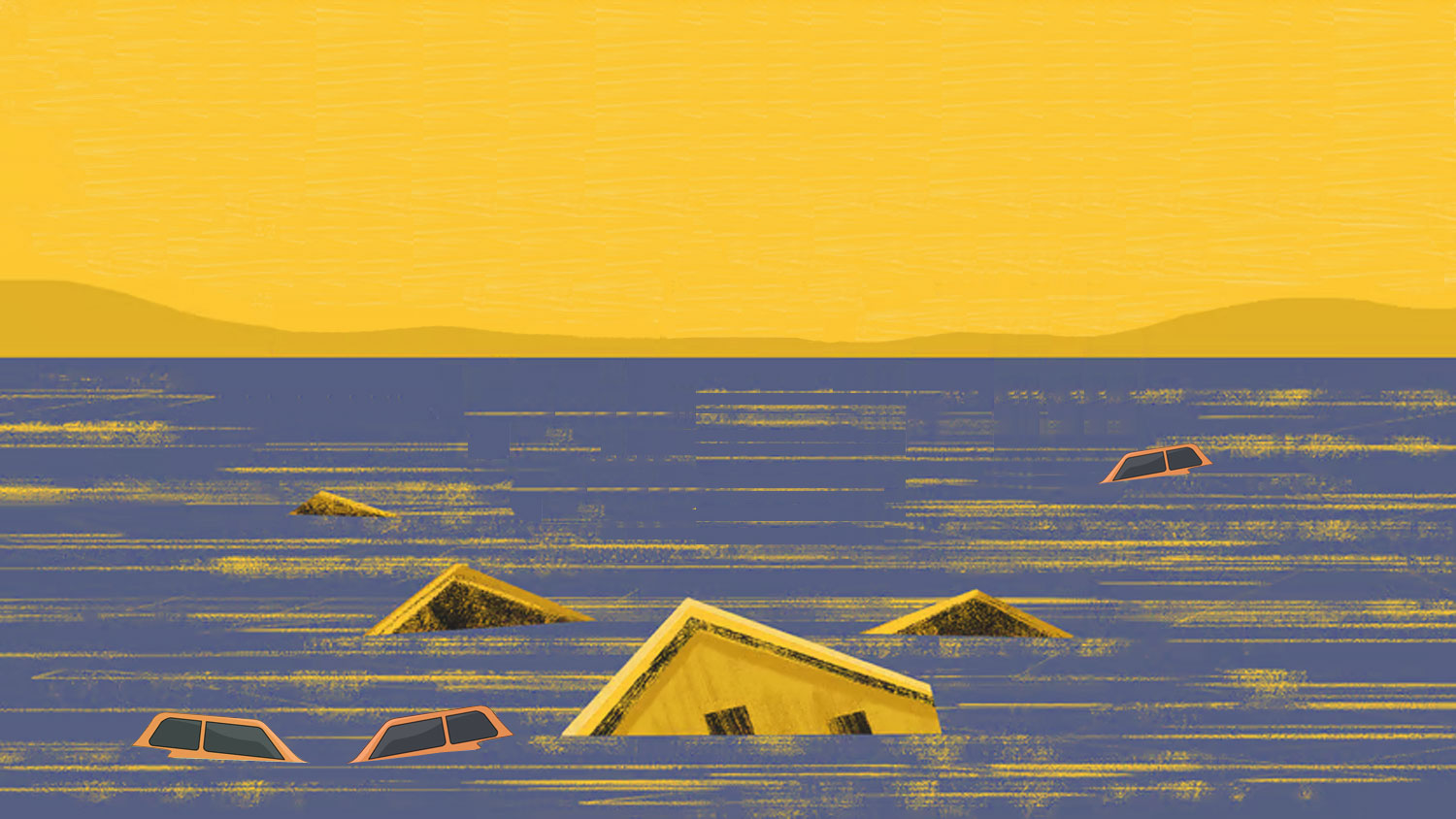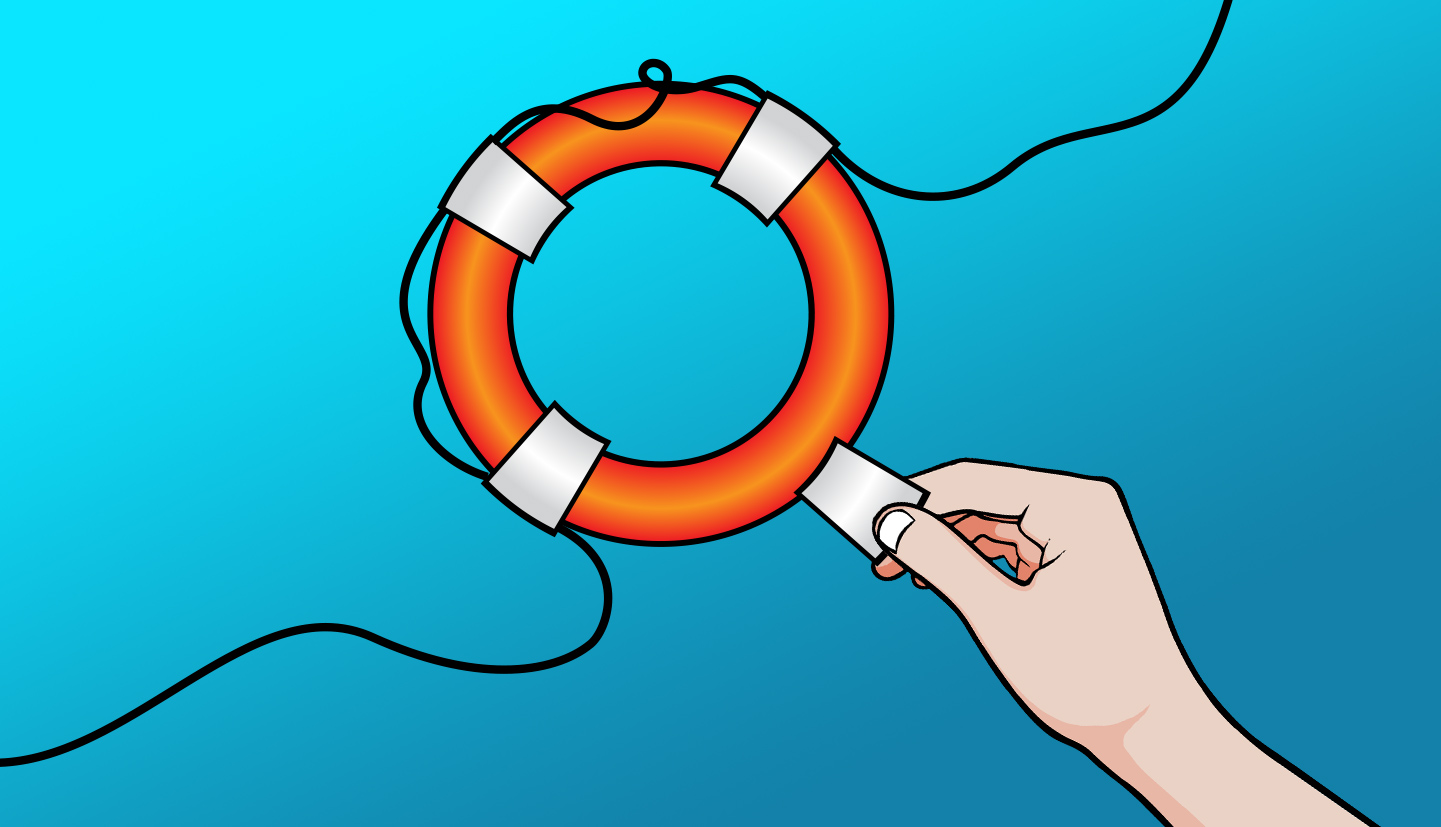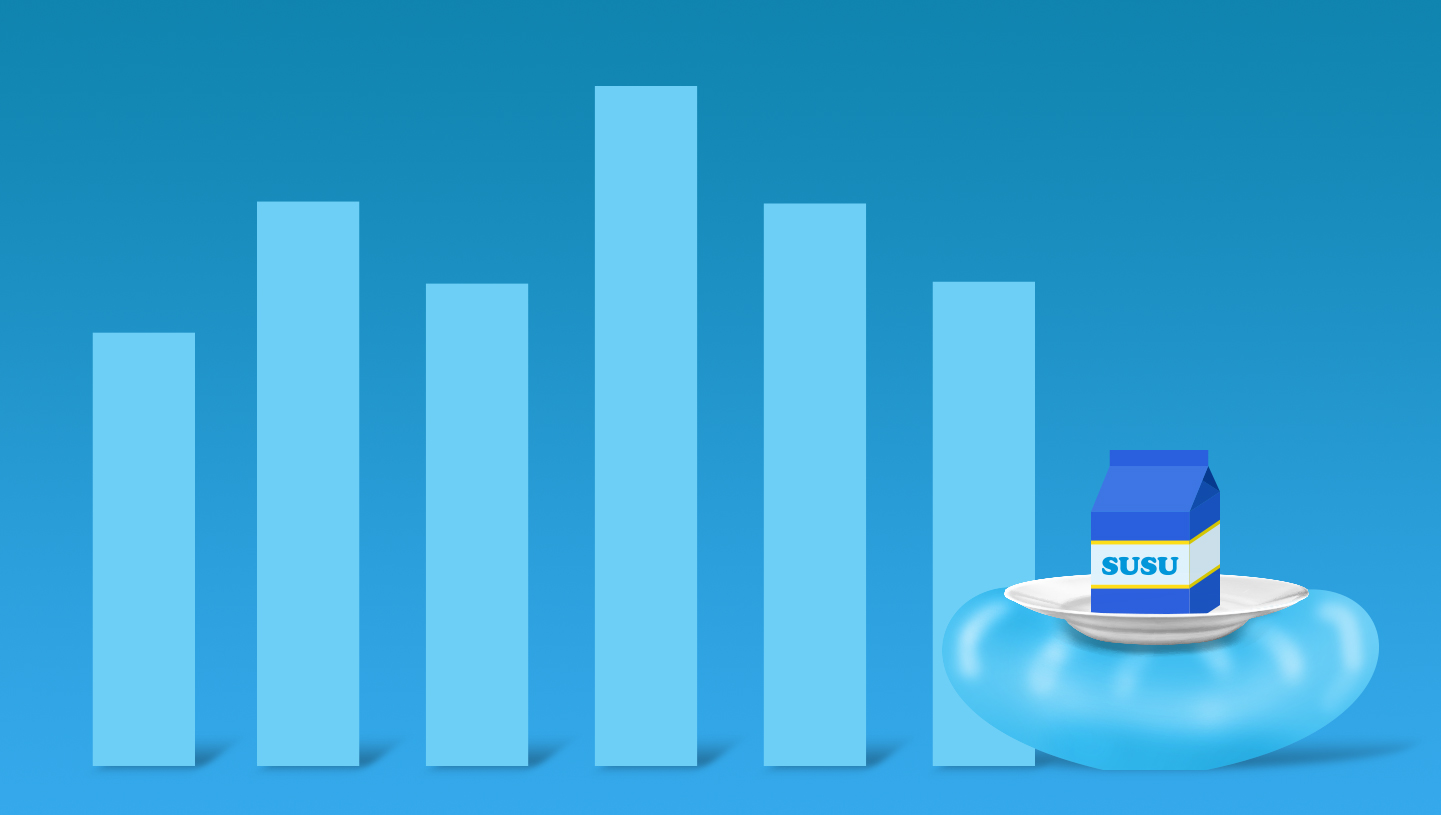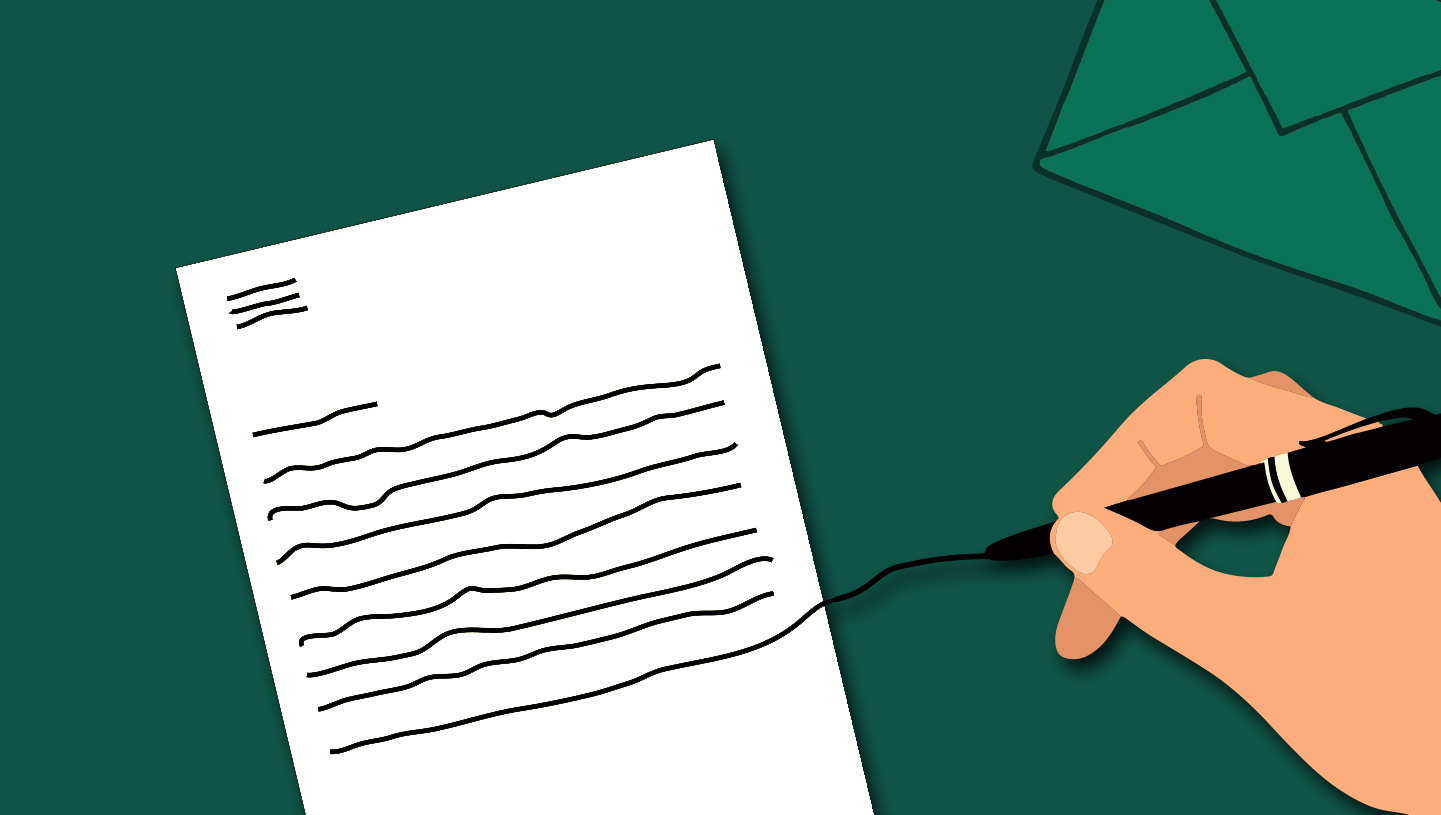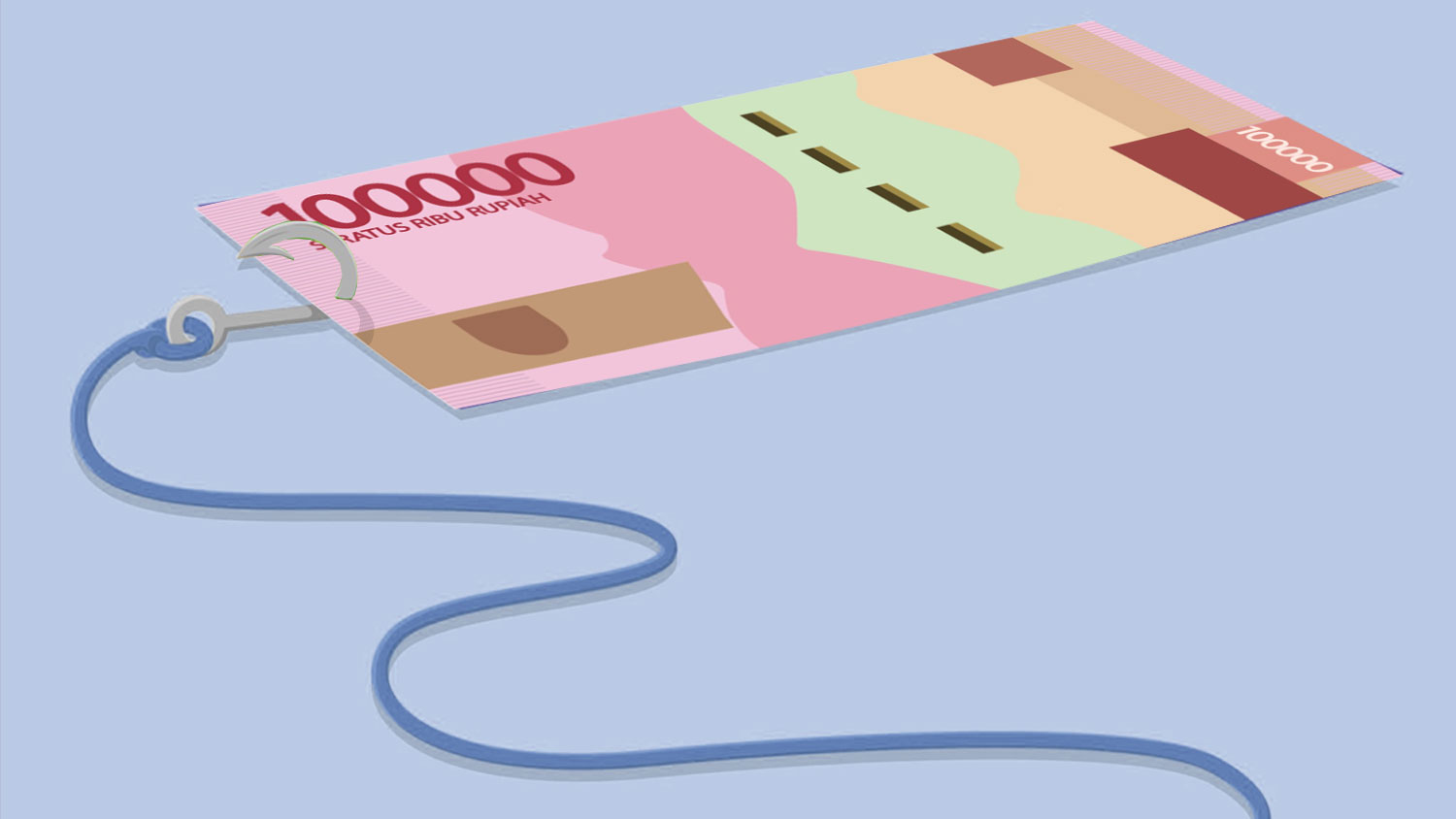Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() R. William Liddle *)
R. William Liddle *)
*) Profesor ilmu politik The Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo