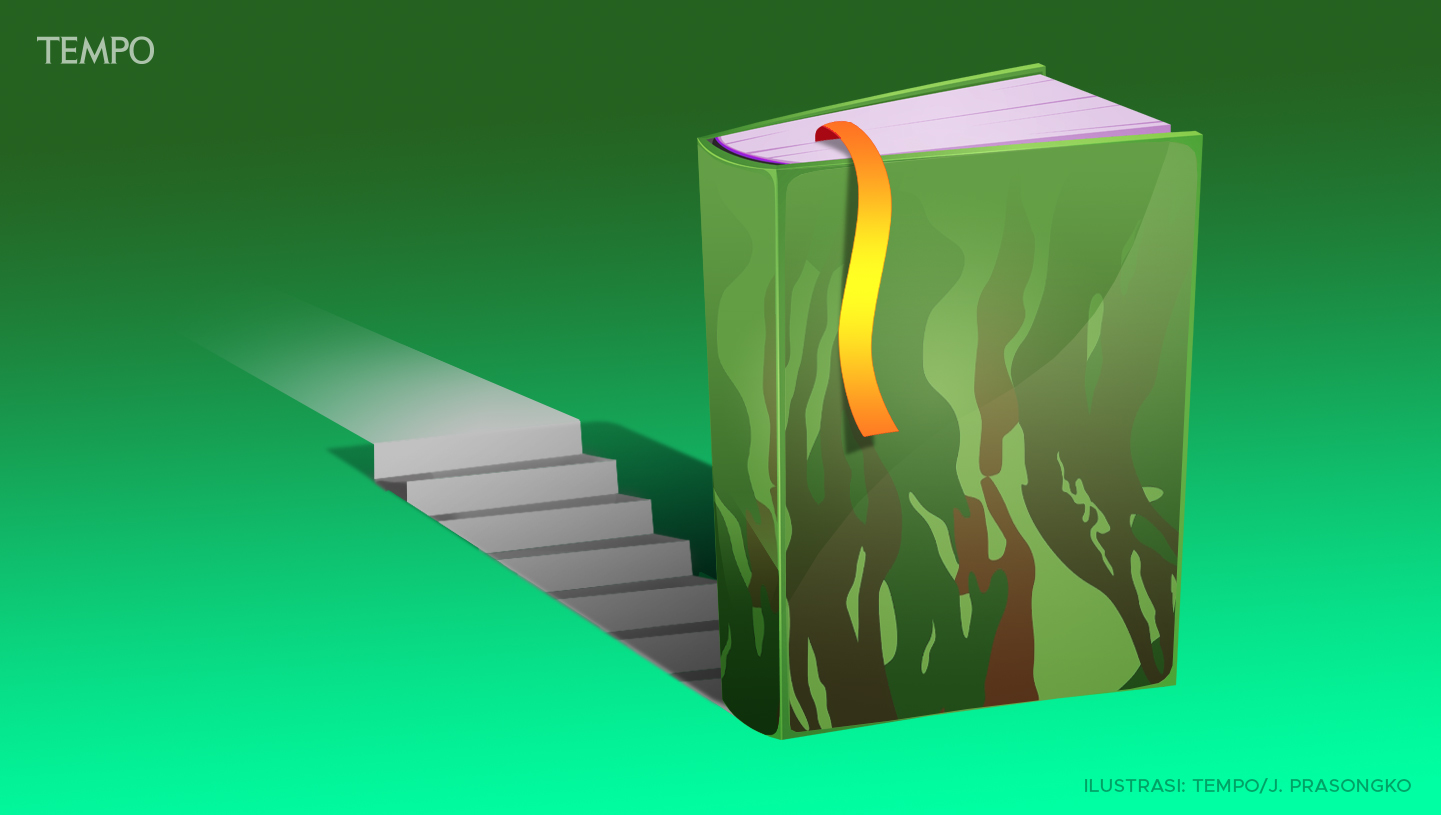Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PADA hari-hari ketika identitas dipersoalkan, ada baiknya kita menengok ke belakang. Syahdan, tersebutlah Djiauw Kie Siong, juragan peti mati yang tinggal di pinggir Kali Citarum, Karawang, Jawa Barat. Pada 16 Agustus 1945 malam, ruang depan rumah pedagang Tionghoa itu dipenuhi kertas berserakan. Sejumlah tamu yang kurang dari 24 jam singgah di rumahnya telah berlalu. Mereka baru saja membahas nasib Indonesia: antara merdeka sekarang atau tidak sama sekali. Keluarga Djiauw tak berani menyimpan kertas-kertas bersejarah itu. Takut disita Jepang, mereka membakarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rumah Djiauw yang berlantai terakota itu baru saja menjadi saksi sejarah. Sejumlah pemuda radikal bersama tentara Pembela Tanah Air menyekap Sukarno-Hatta di sana. Sukarno membawa Fatmawati dan Guntur, anak mereka yang ketika itu baru delapan setengah bulan. Fatmawati mengenang kediaman itu sebagai rumah dengan halaman jembar yang dipenuhi tahi babi. Djiauw memang memelihara babi selain sapi, kambing, ayam, dan itik di pekarangan. Sebelum menempati rumah Djiauw, Sukarno-Hatta disekap di dalam rumah lain dengan ventilasi buruk. Rumah Djiauw dianggap lebih layak, terutama buat Guntur yang masih balita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Djiauw bukan siapa-siapa. Nenek moyangnya keturunan Tionghoa Hakka, dari Provinsi Guangdong, Cina. Pada usia delapan tahun, Djiauw mengikuti orang tuanya menyeberangi Citarum, sungai yang waktu itu kerap meluap airnya. Orang tua Djiauw memilih lembah bekas kali yang sudah mati untuk tempat tinggal. Selain berdagang peti jenazah, keluarga itu menambang pasir dan menjadi pengepul batang bambu. Oleh tetangga, Djiauw dikenal sebagai orang yang suka menolong.
Bersedia memenuhi permintaan para pemuda, cerita hidup Djiauw adalah sejarah kecil dengan dampak besar. Kita tahu: sehari setelah penyekapan di Rengasdengklok, Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Sejak hari itu, perjuangan rakyat Indonesia berubah dari merebut kemerdekaan menjadi mempertahankannya.
Djiauw tidak sendiri. Sejarah berdirinya Republik ditandai dengan peran banyak orang besar dan kecil dari banyak etnis, suku, dan agama. Di kalangan Tionghoa, ada Liem Koen Hian (anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan Yap Tjwan Bing (anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Peran mereka tak kecil, kadang juga penuh ironi. Liem, misalnya, berkeras agar konstitusi menjamin orang Tionghoa yang lahir di Indonesia otomatis diakui sebagai warga negara asli. Gagasannya ditolak. Ia, yang belakangan dekat dengan kalangan komunis, ditangkap untuk kemudian berpindah menjadi warga negara Tiongkok hingga hari tuanya.
Sejarah tak selalu legawa terhadap peran kaum Tionghoa. Di era Orde Baru, peran politik mereka dibatasi, bahkan disetip dari buku pelajaran. Patut disayangkan, peran aktivis dan politikus Tionghoa dihapus dari literatur sejarah resmi. Dalam buku terbitan 1975, disebutkan bahwa struktur badan persiapan kemerdekaan terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil, dan 60 anggota, termasuk empat wakil keturunan Tionghoa, Arab, dan peranakan Belanda. Namun frasa keturunan Tionghoa raib dalam buku cetakan 1993.
Kisah Tionghoa di gerbang kemerdekaan juga Arab atau blaster Indo-Belanda menunjukkan Indonesia tidak didirikan oleh satu etnis, satu suku, atau satu agama saja. Indonesia adalah hasil kesepakatan banyak orang dengan pelbagai latar belakang. Sejak awal, Indonesia adalah negara majemuk sesuatu yang membuktikan betapa tak relevannya politik identitas yang muncul kembali beberapa tahun belakangan ini.
Pemerintah dan pemangku kepentingan hendaknya menyadari sejarah kemajemukan ini. Apalagi sikap curiga masyarakat terhadap Tionghoa berangsur-angsur berkurang. Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 2016 menunjukkan sentimen anti-Cina dalam masyarakat berada di kisaran 0,8 persen jauh lebih kecil ketimbang terhadap terorisme atau kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
Munculnya kembali politik identitas belakangan harus dihadapi dengan cermat. Ditandai dengan demonstrasi besar pada 2017 untuk memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituding menistakan Al-Quran, sentimen anti-Cina kembali muncul. Patut disayangkan, pemerintah menyerah kepada mobokrasi: menghukum Basuki agar demo tidak membesar dan berlarut-larut. Di satu pihak, strategi itu jitu dalam meredam amuk. Tapi, di sisi lain, cara itu justru menjadikan politik identitas membuktikan efektivitasnya.
Upaya mengubur pluralisme harus bersama-sama dicegah. Selain menengok sejarah, kampanye terhadap kebinekaan mesti terus dilakukan. Kemajemukan perlu dipraktikkan di segala segi kehidupan tanpa kecuali.