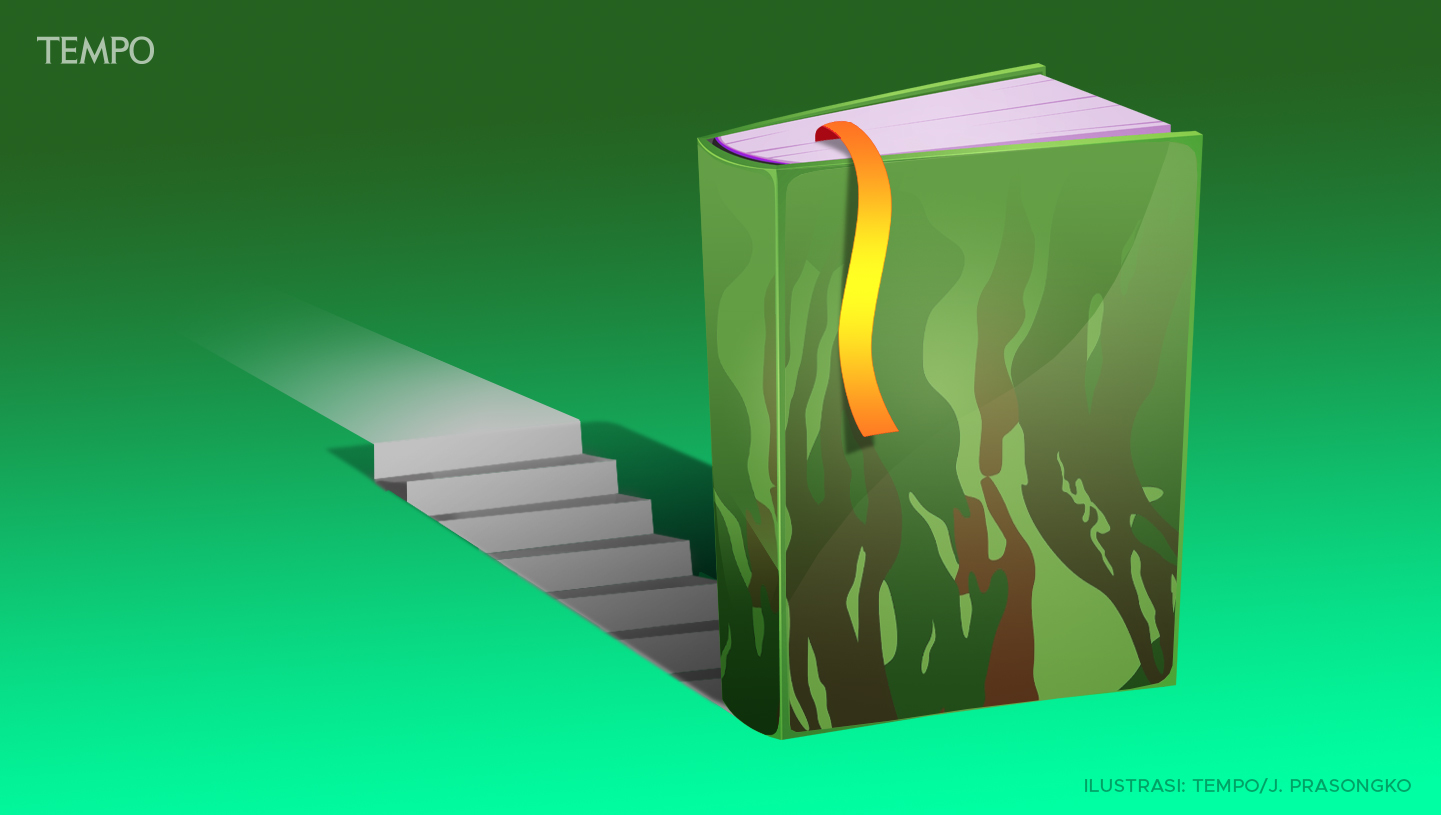Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2019 lalu, dirilis sebuah film dokumenter berjudul “Sexy Killer” yang berkisah tentang kerusakan lingkungan dan polusi oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh jejaring elit ekonomi politik nasional di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menariknya, jejaring elit ekonomi politik yang layak disebut sebagai oligarki tersebut terkait satu sama lain, meskipun mereka berada di belakang pasangan calon (paslon) yang berbeda di pemilihan 2019. Mulai dari keterikatan Jokowi dan keluarga dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kaitan antara LBP dan Prabowo Subianto, antara LBP dan Sandiaga Uno, dan beberapa nama Jenderal dan elit ekonomi politik lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah pemilihan usai, jejaring elit ekonomi politik tersebut termanifestasi secara jelas di dalam pembentukan kabinet pemerintahan baru. Prabowo, sekalipun melalui pemilihan dengan cukup keras dan frontal, memasuki kabinet tanpa tedeng aling-aling. Lalu setahunan kemudian, Sandiaga juga mengikutinya menjadi anggota kabinet Presiden Jokowi.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono yang juga seorang Jurnalis tersebut mendapat jutaan penonton di media sosial Youtube. Tapi pesannya sangat jelas bahwa kontestasi yang dilangsungkan di tahun 2019 tersebut sebenarnya dilatari oleh para pihak yang sangat tipis perbedaannya, karena terdapat tali temali ekonomi politik yang merekat kebersamaan mereka.
Jadi dengan kacamata jejaring oligarki tersebut, akhirnya sebagian besar publik bisa memahami dengan mudah mengapa kubu Prabowo dan kubu Jokowi dengan mudah bisa bersatu setelah menjalani kontestasi yang sengit. Pasalnya, ada celah besar yang bisa menghubungkan kedua pihak dengan sangat mudah, tanpa banyak halangan dan pertimbangan.
Dan setahun menjelang pemilihan umum 2024, kelindan kedua pihak semakin lengket. Kedua kubu semakin tak terpisahkan di satu sisi, tapi di sisi lain Jokowi dan keluarga semakin tercerabut dari akar politik awalnya. Kedekatan dua pihak itu pun menghasilkan koalisi yang cukup besar dan secara asimetris harus berhadapan dengan kubu politik yang telah membesarkan nama Jokowi sedari Solo di masa lampau.
Kini, menjelang pemilihan umum 2024, Dandhy Laksano pun tidak berniat untuk diam. Film baru dirilis sebagai sekuel lanjutan dari Sexy Killer. Setelah perkawinan tak etis dari jejaring elit tersebut, untuk mewujudkan ambisinya dalam melanggengkan kekuasaan, berbagai aturan main ditabrak, yang menghasilkan tidak sedikit kecurangan-kecurangan elektoral.
Film baru tersebut berjudul “Dirty Vote” yang mengisahkan perspektif dan sudut pandang beberapa orang intelektual kritis negeri ini khususnya berlatar ilmu hukum tata negara dalam memandang dinamika politik elektoral beberapa waktu belakangan. Dari sisi narasi dan teknis perfilman dokumenter, Dandhy nampaknya sangat berhasil mengeksplorasi persoalan.
Layaknya “Sexy Killer”, “Dirty Vote” layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita. Dengan kata lain, kedua film tersebut bukan saja hasil kerja seni yang ciamik, tapi juga hasil upaya intelektual yang berharga dan sangat layak mendapatkan ruang yang lebih luas ke depannya.
Kemunculan film “Dirty Vote” ini seketika menuai reaksi negatif dari salah satu paslon dan partai-partai politik yang mendukungnya. Tentu tidak perlu heran. Reaksi politik boleh berbentuk apa saja, selama tidak menghilangkan hak dan peredaran film tersebut, tentu tak ada masalah. Di Amerika Serikat, bahkan film dokumenter semacam ini dibiayai oleh negara.
Stasiun televisi Public Broadcasting Service (PBS), yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat, selalu memproduksi film dokumenter yang menguak kebobrokan kekuasaan pemerintah Amerika Serikat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk setiap menjelang pemilihan umum, PBS selalu memproduksi film dokumenter yang membahas tentang segala sisi para kandidat, mulai dari prestasi sampai pada noda-noda politik mereka.
Jadi di sisi saya ingin mengatakan bahwa penguasa atau pun elit-elit yang menopangnya tak perlu gusar. Jika memang ingin tetap mempertahankan demokrasi, maka film serupa justru harus didukung peredarannya. Jika ingin membantah, tentu sebaiknya dengan data dan argumentasi yang tepat. Atau dengan produksi film sejenis, yang tentunya harus dengan data dan narasumber yang juga kredibel.
Pun lebih dari itu, dari sisi realitas ekonomi politik nasional, film ini memberi lampu kuning kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia bahwa pemilihan umum kali ini adalah titik krusial dalam perpolitikan nasional yang bisa membawa negeri ini kembali ke era minus demokrasi, jika pilihan jatuh ke pihak yang salah.
Kedua film di atas membuka mata kita bahwa ada jejaring kekuasaan ekonomi politik yang sudah memulai “persekongkolan busuk” sejak beberapa tahun setelah reformasi bermula, yang sengaja atau tidak, justru telah melemahkan spirit negeri ini dalam mempertahankan dan memperjuangkan reformasi bahkan nilai-nilai demokrasi.
Selama masa pemerintahan Jokowi, kita menyaksikan kemunduran demokrasi dan ekonomi yang cukup parah. Mulai dari penggerogotan kekuasaan antikoruptif lembaga antirasuah KPK, pemaksaan UU Omnibus Law yang ditentang oleh publik, dan berakhir dengan permainan tidak etis dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diikuti oleh aksi-aksi tak terpuji kekuasaan dalam menunjukkan keseriusannya mendukung salah satu paslon.
Boleh jadi inilah tanda-tanda yang disebutkan oleh Larry Diamond sebagai tanda-tanda “democratic recession”. Ambisi untuk mengekang keterlibatan pubik dalam menentukan kebijakan semakin menguat, permainan kekuasaan semakin kentara, pertunjukan telanjang “pork barell politics”, mengentalnya peran oligarki ekonomi dalam menentukan arah kekuasaan, dan penyerobotan etika-etika demokrasi tanpa banyak pertimbangan demi kepentingan elektoral.
Dengan kata lain, film “Dirty Vote” adalah suara tambahan nan sangat signifikan yang melanjutkan suara-suara kritis dari pihak kampus beberapa waktu lalu di satu sisi dan mengafirmasi kondisi demokrasi nasional yang tidak baik-baik saja di sisi lain. Edukasi politik semacam ini sangat diperlukan oleh pemilih kita, terutama segmen pemilih yang sudah tercerabut dari narasi-narasi sejarah kita.
Pasalnya, mayoritas pemilih milenial dan generasi Z, yang jumlahnya saat ini sudah lebih dari 50 persen, sangat rentan terhadap narasi dangkal penguasa tentang demokrasi dan pemilihan umum. Sehingga film dokumenter semacam ini adalah sumber pengetahuan kritis yang sangat krusial bagi generasi muda dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum nanti.
Demokrasi kita memang sedang tak baik-baik saja. Elit-elit kekuasaan dengan sangat kentara mempertontonkan permainan yang sangat berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi kita dan membawa agenda reformasi ke tepi jurang yang sangat dalam. Sekali saja agenda reformasi Indonesia terjatuh ke dalamnya, maka boleh jadi dibutuhkan waktu lebih dari 32 tahun lagi untuk keluar dari lubang tersebut, karena kali ini, jejaring elit yang bersekongkol jauh lebih besar dan mapan secara ekonomi dibanding jejaring elit yang menopang awal kelahiran Orde Baru.
Oleh karena itulah film ini sejatinya harus menjadi konsumsi mayoritas pemilih kita agar membuka tabir yang menutupi berbagai pelanggaran elektoral selama ini. Bahkan akan jauh lebih baik ditonton secara sekuensial dengan karya Dandhy Dwi Laksono sebelumnya, Sexy Killer, untuk mendapatkan metanarasi yang lebih jelas tentang struktur terselubung yang menopang kekuasaan hari ini.
Kedua film dokumenter ini adalah “counternarrative” yang sangat kuat untuk membantah narasi-narasi standar kekuasaan selama ini. Sebagaimana diteorikan oleh Antonio Gramsci, dibutuhkan kontranarasi yang setara dan sama besarnya dengan narasi milik kekuasaan, untuk melawan hegemoni terstruktur dan sistematis yang disodorkan oleh kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.
Artinya, paradigma yang ditawarkan oleh kekuasaan sudah tidak lagi mewakili fakta dan tujuan negeri ini. Kekuasaan dan jejaring ekonomi politik yang menopangnya sudah mulai memunculkan anomali-anomali yang aneh.
Sebagaimana dikatakan Thomas Kuhn, Filosof kenamaan yang menelurkan teori tentang paradigma, anomali adalah pertanda awal pergeseran paradigma. Artinya, pemerintah sudah mulai menggunakan paradigma non demokratis dalam menjalankan kekuasaan.
Dan anomali-anomali tersebut ditampilkan dengan apik, baik di dalam film “Dirty Vote” maupun “Sexy Killer”. Karena itu, kedua film ini bisa dijadikan sebagai kontranarasi bagi para pihak yang sedang memperjuangkan keberlanjutan demokrasi dan reformasi nasional.
Pun karena itu pula, sebarannya semestinya bisa lebih luas lagi. Dengan kata lain, bermodal niat baik dan spirit penyelamatan demokrasi nasional, semestinya jejaring intelektual kritis, mulai dari kampus sampai masyarakat sipil, menurut hemat saya, harus saling dukung dalam memperluas sebarannya.
Hal ini perlu dilakukan mengingat dunia digital dan media sosial saat ini sudah bukanlah seperti dulu. Media sosial berperan sangat penting pada peristiwa Arab's Spring 2011 lalu. Tapi beberapa tahun kemudian, ISIS juga menggunakan media sosial untuk mendapatkan “traction” dari seluruh dunia, yang langsung menebar ketakutan ke seantero dunia secara cepat.
Lalu tak lama setelah itu, pemerintah dibanyak negara pun mulai memasuki ranah digital dan media sosial, terutama untuk membendung narasi antipenguasa atau narasi perlawanan. Rusia bahkan menggunakan digital campaign dan media sosial untuk mengganggu pemilihan di Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Dan kini, karena penguasaan yang ketat atas dunia digital dan media sosial, pemerintah China malah dikategorikan sebagai pemerintah “techno-authoritarian” dan “techno-tirany”.
Indonesia pun nampaknya sudah mulai mengarah ke sana di mana pemerintah mulai cawe-cawe lebih dalam ke dunia maya dan media sosial. Karena itu dibutuhkan usaha ekstra dari kalangan kritis, kampus, mahasiswa, dan aktifis lainnya untuk menyebarluaskan film-film semacam ini ke ruang publik digital kita atau ke berbagai lini media sosial, agar lebih banyak menyentuh generasi milenial dan generasi Z yang masih ahistoris dalam memandang perpolitikan hari ini.