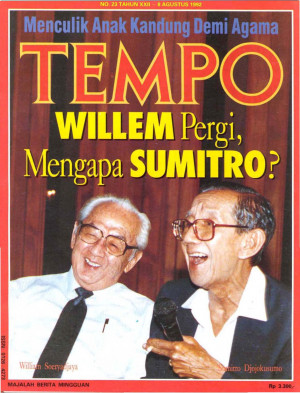GEDUNG Diklat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Bogor, pekan lalu tiba-tiba meriah. Selain para petinggi pendidikan, hadir pula para kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dari seluruh provinsi Indonesia. Mereka, ada sebanyak 600 orang, mengadakan rapat kerja untuk menyongsong penerapan Kurikulum 1994. Hasil rapat kerja itu adalah 27 rumusan sebagai landasan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Rumusan itu menyebutkan pentingnya pengikut sertaan keluarga dan masyarakat, pemantapan kurikulum nasional, keterpaduan pendidikan sekolah dan luar sekolah, pemberantasan buta huruf, dan sebagainya. Wajib belajar 9 tahun bukanlah barang baru. Soal ini sudah dilempar sejak lima tahun silam. Tapi gagasan itu kali ini agaknya sudah matang, tinggal menunggu pelaksanaannya. Program itu merupakan perpanjangan dari wajib belajar 6 tahun. Dengan demikian kelak tak ada lagi Sekolah Menengah Pertama. Soalnya, SMP akan dilebur sebagai pendidikan dasar. Maka SMP pun akan diubah menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Program ini tentu saja dijalankan dengan tempo bertahap. Data 1991/1992 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memang belum merata. Untuk jenjang setingkat SD ada sekitar 170 ribu sekolah dengan jumlah murid 23,5 juta atau 99,6% dari jumlah usia wajib belajar (712 tahun). Sementara itu, jumlah gedung setingkat SLTP masih kurang dari 28 ribu buah, yang menampung murid 2,1 juta siswa atau 65% dari jumlah siswa usia SLTP. Artinya, masih akan banyak siswa yang tak tamat menempuh pendidikan dasarnya. Selain itu, soal kurikulum baru 1994 yang digodok sejak Oktober 1991 belum dibahas tuntas di rapat kerja itu. Menurut Fuad, pihaknya masih menunggu masukan dari lapangan, sehingga dalam rapat itu baru disusun dalam garis besarnya saja. "Kami tak ingin kurikulum itu disusun dari atas saja, sehingga terbentur-bentur dalam pelaksanaannya di lapangan," tutur Fuad. Perubahan jangka waktu pendidikan dasar sudah tentu melibatkan penyesuaian di sanasini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan P & K Harsja W. Bachtiar menyebutkan, kurikulum akan disederhanakan. "Materi pelajaran diharapkan bisa merangsang anak mencari informasi lebih jauh," kata Harsja. Dalam segi jumlah, contohnya, dari 13 mata pelajaran SD sekarang ini dirampingkan menjadi 9 buah saja. Sedangkan penyederhanaan tingkat abstraksinya bisa dicontohkan: Pancasila disampaikan melalui hal-hal yang praktis dan bisa digunakan. Misalnya, butir-butir P4 bukan sekadar dihafal, tapi lebih dijabarkan dalam contoh kehidupan sehari-sehari. Yang melegakan, ada upaya menghapuskan mata pelajaran yang isinya tumpang tindih dalam Kurikulum 1984. Sebut saja antara lain IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), Sejarah, dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Bukan rahasia lagi, dalam keempat mata pelajaran itu ada materi yang sama: soal pahlawan nasional, misalnya. Dalam kurikulum 1994, PSPB yang diajarkan sejak zaman Menteri Nugroho Notosutanto itu tak muncul lagi. Sebagian materi PSPB lebur ke mata pelajaran Pancasila diajarkan sejak kelas 1 SD yang meliputi P4, PSPB, dan Kewarganegaraan. Sebagian lainnya masuk ke IPS dan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, Bahasa Inggris, yang dalam kurikulum lama diajarkan di SMP, dua tahun lagi mulai diajarkan sejak kelas 4 SD. Kurikulum baru, menurut Harsja, tak akan sesentralistik kurikulum sebelumnya. Penyusunan kurikulum dari atas, diakui Harsja, ternyata tak cocok dengan lingkungan murid. "Akibatnya, NEM (Nilai Ebtanas Murni) mereka rendah-rendah, 3,1 sampai 3,7 untuk tiap mata pelajaran," kata Harsja. Padahal standar NEM adalah 6 untuk tiap mata pelajaran. Maka pusat hanya membuat pokok-pokok bahasan saja. Materi pelajaran dibuat oleh wilayah, sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri. Misalnya, di Irian Jaya dipakai contoh babi sebagai binatang menyusui, sedangkan di Jawa dipakai contoh sapi. Begitu halnya gambar dan nama-nama orang. "Kurikulum akan berwarna lokal, agar siswa mengetahui daerahnya," Harsja menjelaskan. Bisa terjadi, pelajaran satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Tapi hal ini tak menjadi masalah rupanya. Soalnya, Ebtanas alias ujian akhir SD dihapus, diganti dengan ujian kenaikan tingkat sekolah. Untuk melanjutkan ke SLTP, buku raporlah yang pegang peranan. Masalah yang diduga muncul adalah kesiapan pelaksanaan di daerah. Misalnya saja, pembangunan gedung sekolah dan pengadaan buku-buku baru. Adapun masalah terbesar datang dari barisan guru. Soal ini sejak dulu memang sudah jadi pembicaraan umum, dan diakui pula dalam rapat kerja itu. Kendalanya, di berbagai daerah masih ada tenaga guru lulusan SD. Padahal, kurikulum baru menyiratkan semua guru SD dan SLP harus dari tamatan perguruan tinggi, minimal program diploma. Untuk menyiapkan guru saja sudah perlu kerja keras dan biaya besar. Ardian Taufik Gesuri dan Indrawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini