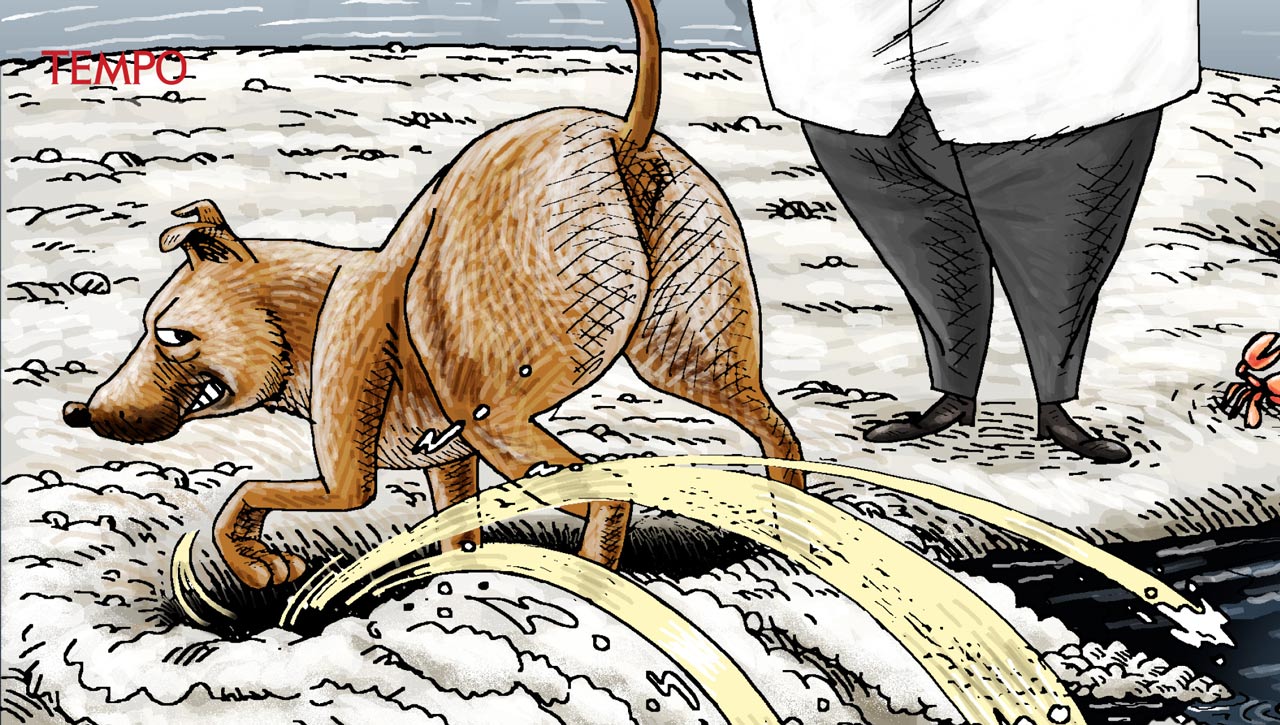KITA bukan bangsa tempe, kata Bung Karno dulu. Kita memang bukan
bangsa yang lemah, tentunya-toh kita bergaul akrab dengan tempe.
Di Jakarta saja tiap hari dibutuhkan sekitar 250 ton jenis lauk
yang "lemah" ini. Tambah tahu (ta-hu), lauk yang bahkan lebih
lemah, 120 ton--yang toh hanya bisa dicukupi 52 ton saja oleh
produksi setempat. Sisanya didatangkan dari tempat lain: Bogor,
Bandung, Sumedang, misalnya. Dibagi secara pukul rata saja
dengan jumlah penduduk tiap hari orang Jakarta menelan 50 gram
tempe --atau tahu. Kira-kira sepotong tempe per kepala.
Kita memang bangsa tempe--dan tahu. Dan kebudayaan yang daif
ini, mungkin sudah bisa diduga, datang dari Jawa. Tempe memang
lebih khas Jawa -- Indonesia -- dibanding tahu yang dikatakan
berasal dari Cina, Korea, Jepang dan sebangsa- nya. Di Jakarta,
dari hampir 4.000 produsen tempe-tahu, sebagian besar tetap
orang Jawa--terutama, ternyata, orang Pekalongan. Yang bukan
Jawa, yakni Cina, Sunda, maupun Betawi, kebanyakan berjuang di
seksi tahu.
Berumur Sehari
Nah, itulah, para pejuang, yang tahu benar penciptaan makanan
berkepribadian yang prosesnya sebenarnya tidak selalu sedap itu.
Sebab air buangan dari bekas kedelai saja, bahan utama
pembuatan tahu atau tempe, bisa menimbulkan problem dengan
penduduk sekitar karena baunya. Terutama bila terletak di
lingkungan orang kaya atau pejabat. Untung kebanyakan tidak.
Karena itulah, mereka yang "pabrik"nya berlokasi di pinggir kali
lebih beruntung: air buangan langsung hanyut bersama kotoran
lain. Lebih unik lagi: yang di pinggir kali mengambil airnya
dari kali itu pula, tentu saja. Ini bisa dilihat misalnya di
sela-sela puluhan tong berwarna hitam yang berderet sepanjang
Kanal Terusan Banjir di Jembatan Besi, Jakarta Utara.
Di situ beberapa laki-laki sibuk menimba air dari kanal ke
dalam tong-buat membilas kedelai yang telah direbus dan
melepaskan kulit arinya. Untuk keperluan terakhir itu seseorang
masuk ke dalam tong. Kedelai diinjak-injak. Diguyur air lagi.
Bila ada kotoran bangsa manusia terikut dalam ember, gampang.
Singkirkan dengan tangan. Sebab memang, sekitar 25 m dari tempat
tong-tong itu, ada jamban umum.
Tapi jangan kuatir Tjarmudi, si pemilik kedelai sebanyak 50
kg tersebut, akan membilas lagi dengan air bersih. Lima pikul
air leding, a Rp 100, cukuplah kiranya untuk memandikan 50 kg
kedelai. Dari situ, kedelai diberi zat pewarna. Warna kuning
pucat lantas beruhah menjadi kuning gadis--kuning indah. Satu
malam direndam lagi, baru keesokan harinya kedelai diberi laru
(biang ragi, agar keluar jamur) dan beberapa kilo onggok (ampas
singkong). Adonan ini kemudlan dibungkus dengan plastik dan
diinapkan semalam lagi. Proses pembuatan tempe--yang sudah tidak
menggunakan daun pisang ini -makan tempo 3 hari lamanya.
Terletak sporadis di beberapa tempat di Jakarta (Sunter,
Kayumanis, Kemayoran, Tebet, misalnya), mereka tidak selamanya
mengolah produksinya dengan air kali, sudah dibilang. Tapi
hampir selalu berkelompok -- lebih-lebih dengan sesama orang
seasal.
Sardani misalnya, berusia lebih setengah abad dan termasuk
tempewan senior--berpraktek sejak 1952--kini pemilik tempat
kerja plus pemondokan di tanah yang juga miliknya seluas 600 m2.
ebanyak 15 keluarga bekerja dan hidup di situ, sambil membayar
Rp 250 per hari untuk ruang 2,5 x 3 m. Serupa sebuah kamp.
"Jadi tukang tempe itu berat sekali," ujar Sardani. Karena
produksi harus berjalan terus, sedang "umur tempe itu cuma
sehari. Lagi pula saingan banyak." Di zaman kedelai mahal dan
susah seperti sekarang (Rp 327 per kilo), membuat tempe juga
masih perlu bahan campuran kulit singkong yang diiris
lembut, ampas kelapa, onggok, nasi atau bahkan nangka muda. Tapi
untunglah, "campuran seperti itu hanya dibuat di Jawa." Tempe
yang diproduksi di Jakarta sih paling banter dicampur onggok
saja--5% dari kedelai.
Rata-rata setiap hari seorang pembuat tempe menghabiskan
sekitar 20 kg kedelai. Sarwono, 31 tahun, yang memproduksi dan
memasarkan sendiri tempe buatannya di pasar Tanjungpriok,
mengaku berhasil mengantungi uang Rp 1.000/ hari--setelah
dipotong sewa kamar. Ayah 4 anak ini, yang sejak usia 6 tahun
diwajibkan ayahnya membantu membuat tempe, hingga kini radio
baterai pun tak punya. Padahal dia bekerja mulai jam 06.00
pagi--mengayuh sepeda ke pasar, membeli kedelai--dan langsung
merebus, merendam atau menyelesaikan pekerjaan kemarin dulu.
Semua kerepotan ini baru rampung jam 22.00.
Bagaimana kalau mengadakan "modernisasi"? Sarwono tidak
bersemangat. Menurut dia, lewat mesin giling penyusutan bisa
mencapai 5%. Sedang dengan cara biasa, paling susut 1%.
Tapi rupanya "modernisasi" dilakukan juga. Mardjuki (48
tahun), juga asal Pekalongan, dan datang di Jakarta 1975,
pertama kali menjadi buruh pabrik tahu milik Cina. Tahun
berikutnya ia membeli mesin penggilingan dengan engkol-alat
penggilingan kedelai dari batu yang biasa dipakai produsen tahu
Jakarta asli. Tenaga yang berjumlah 8 orang secara bergilir
kemudian menggiling mulai jam 03.00 sampai jam 22.0a. Dalam
jangka itu 150 kg kedelai bisa dilumatkan. Tahun berikutnya,
gilingan engkol diganti mesin dengan bahan bakar solar.
Tenaga--nah--dikurangi menjadi 6 orang. Tahun 1978 Mardjuki
membeli mesin yang lebih besar, yang.bisa menggiling kedelai 500
kg.
Tapi, anehnya, dia cuma menggiling 150 kg. Lho? "Lha
penjualannya susah," jawabnya. "Juga yang mengangkut kebetulan
ndak ada."
Pabrik Mardjuki di Cengkareng. Untuk pemasaran, ia
menggunakan armada.sepeda. Tapi jalanan yang ramai rupanya
membuat pengendara sepeda kapok. Misalnya suplai untuk Perumnas
Cengkareng saja, untuk sementara dihentikan. Maklum, sungguh tak
sedap melihat sepeda tahu disenggol Hardtop menaburkan muatannya
sepanjang jalan. Bayangkan: 7 blek tahu yang pribumi itu
terpenyet-penyet di aspal metropolitan yang mulia.
"Teman saya sekampung sudah 4 orang mati ketabrak mobil,"
kata Kasbullah yang juga asal pekalongan. Karena itu produsen
tahu di sekitar Kuningan atau Mampang Prapatan rupanya punya
akal: armada sepeda diputuskan bergerak malam hari, bayangkan.
Maka ada Kopti-Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia-yang di
Jakarta beranggota 2.234 orang. Berdiri Maret tahun lalu, ini
perkumpulan terutama ingin menekan harga kedelai agar tetap rendah.
Disamping itu, "kami bukan saja mencoba meningkatkan produksi,"
kata A.R. Noor, Ketua Pusat. Tapi tidak meningkatkan
Mutu atau setidak-tidaknya kebersihan, sistem pengepakan dan
pemasaran. Untuk itu koperasi ini melihat sebuah mesin kecil
bikinan jepang yang perbuahnya. Berharga sekitar Rp 15 juta,
ini mesin "hanya dilayani 5-6 orang," dan setiap jamnya
memproduksi 60 kg tahu.
Lembek
Lewat kalkulasi, Noor memperhitungkan dalam waktu 6 bulan
harga mesin sudah bisa tertutup. Dan untuk "modernisasi" itu
pula, empat orang dari mereka baru-baru ini berangkat ke
Jepang- bersama dua orang dari Ditjen Industri kecil dan
Ditjen Koperasi. Entah atas sponsor perusahaan mesin tahu atau
tidak, mereka belajar mekanisasi produksi tahu, menurut Noor pula.
Adakah pengangguran bakal lahir oleh upaya mekanisasi semacam
ini? Gubernur Tjokropranolo sendiri, ketika menerima delegasi
mereka 10 November kemarin, ada juga mempersoalkan masa depan
para tahuwan. "Saya melihat, di pabrik tahu tradisional hubungan
majikan dan buruhnya demikian akrab," Kata Gubernur. "Apakah
suasana begitu akan bisa dipertahankan, bila pabrik berdiri?
Dan apakah peningkatan produksi memang menaikan penghasilan
mereka?" Kopti akhirnya hanya diperbolehkan beroperasi dengan
mesin kecil.
Mekanisasi rupanya memang tidak (atau belum?) sepenuhnya
diterima para tahu tempewan. Bahkan Suahadi,(38 tahun), pengurus
Kopti Jakarta Utara, menuturkan pendapat orang-orang, bahwa
mesin itu malah bisa membawa rugi. Sebab alat modern pengupas
kedelai itu ternyata tak mampu memisahkan kulit ari, kacang
dan tunasnya-jadi masih diperlukan lagi tukang tampi. Karena
itu para produsen menganggap cara lama lebih praktis. Dan di
Kopti Jakarta Utara sendiri mesin pemecah kedelai ada
tergolek-tapi rupanyanbelum ada yang berminat.
Gubernur DKI sendiri berpendapat, tidk seharusnya"ilmu jepang
diterapkan serta-merta di sini. Perlu diselidiki dulu." "Tahu
Jepang itu" katanya, "lembek seperti ubur-ubur. Dan sulit
digoreng, tidak seperti tahu kita. Sedang Orang jakarta senang
tahu goreng".......
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini