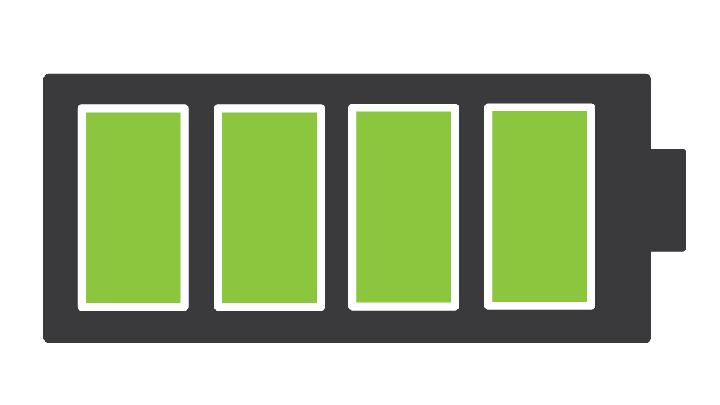PEKERJAAN pugar-memugar candi tak cuma bermanfaat untuk
mengawetkan sisa dari masa lalu. Bahwa itu juga berguna untuk
bangunan masa kini, ir. H. Maclaine-Pont telah membuktikannya
ketika bertugas membangun Museum Majapahit di desa Trowulan,
dekat Mojokerto, Jawa Timur.
Orang asing ini sebelumnya cukup lama mempelajari arsitektur dan
teknik konstruksi bangunan kuno, khususnya candi-candi corak
Jawa Timur. Hasil riset lapangannya itu kemudian dituangkannya
dalam bangunan masa kini di kompleks Museum Majapahit tersebut.
Ada satu keistimewaan pada candi Jawa Timur ini. Seperti
dikemukakan P. Boonekamp C.M. dalam Busos (Juli/Agustus 1978),
suatu penerbitan gereja di Surabaya, batu bangunan kuno itu di
susun tanpa semen. Ini berlaku baik bagi tembok batu padas
maupun batu bata. Lalu, apa yang digunakan sebagai perekat?
"Setelah digosok sampai halus dengan campuran air, gula, dan
gampin (kapur), batu-batu itu dapat menggigit satu sama lain
dengan baik," tulis Boonekamp. Begitulah teknik bangunan batu
tanpa semen yang diterapkan Maclaine-Pont dalam proyek museum
Trowulan.
Selain temboknya dibuat secara tradisional, juga atap Museum
Majapahit itu dibikin mengikuti corak asli, yang joglo Jawa
Timur. Namun membangui museum saja, belum membuat arsitektur dan
teknik konstruksi tradisional itu merakyat kembali. Padahal
cita- cita arsitek asing itu adalah: menghidupkan kembali
tradisi bangunan lama tanpa mengabaikan tuntutan zaman masa
kini.
Maka ketika datang tawaran dari seorang pastor desa di
Pohsarang, tak jauh dari Kediri untuk membangun gereja dengan
teknik yang sama dengan museum Trowulan, Maclaine-Pont tak
menunggu lama. Rakyat setempat umat Pastor J. Wolters C.M. itu,
diajaknya serta. Selama setahun arsitek itu tinggal di desa
Pohsarang, membangun gereja dan bangunan pelengkapnya. Ia
sebagian besar menggunakan bahan baku lokal, seperti batu padas,
batu bata, keramik, dan kayu. Tanpa semen Cibinong, tentunya.
Gereja Pohsarang tersebut dibangun dengan model pendopo, dengan
empat soko guru (tiang utama) dan atap melengkung yang ditutupi
genteng.
Kini, walaupun pemimpin yang antusias seperti ir H. Maclain-Pont
dan pastor Wolters itu tak berdiam lagi di sana (keduanya sudah
pulang ke negeri asalnya di Eropa), rakyat desa Pohsarang sudah
'menemukan kembali' keahlian nenek moyang mereka dalam hal
bangun-membangun gedung.
Teknik yang sama, kemungkinan besar telah diterapkan pada Menara
Kudus, sebuah peninggalan Islam warisan para wali di Jawa
Tengah. Menara bedug inlpun dibuat dari batu bata merah, tanpa
semen pabrik.
Cuma ada satu masalah: dapatkah 'semen asli' yang terdiri dari
gula + gamping yang dicampur dengan air, dapat menggantikan
semen pabrik yang juga harus dicampur dengan air, pasir, dan
kapur? Tak dijelaskan dalam majalah Busos itu, berapa kwintal
gula terpaksa dikorbankan untuk gereja itu.
Sebagai bandingan dapat juga dikemukakan teknik membangun
tembok bata tanpa semen nun jauh di Aceh.
Di tengah kota Banda Aceh, ada kompleks pemandian puteri dan
permaisuri dari masa Iskandar Muda (abad ke 17). Bentuknya
menyerupai candi, berlabur kapur putih. Batu batanya direkatkan
satu sama lain, menurut cerita orang tua-tua, dengan abu dapur
yang dicampur telur dan kapur.
Entah sudah berapa orang wanita berdarah biru yang mandi di
Gunongan itu -- begitu orang Aceh menyebut bangunan tersebut.
Dan entah sudah berapa liter air mencoba merembes di selasela
batu bata yang hanya ditempelkan dengan campuran abu, telur dan
kapur itu. Namun sampai sekarang, bangunan yang sudah berumur
tiga abad itu masih berdiri utuh.
Mungkin peninggalan sejarah terakhir yang masih menggunakan
semen telur hanyalah Mesjid Penyengat, 2 km di luar kota
Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini