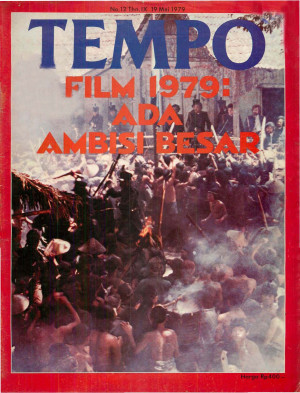FILM November 1828 bisa dibuat terutama berkat kerja sama dua
orang, Nyohansiang dan Teguh Karya. Yang pertama memiliki modal
dan ingin membuat film "lain dari pada yang lain," sedang yang
satunya sutradara yang selalu tampil dengan film-film terkenal.
Karya terbaru Teguh Karya itu nampaknya harus dicatat sebagai
film Indonesia terlama dalam pembuatan dan termahal dalam
pembiayaan. Terhadap film yang dibuat dengan ambisi besar itu,
berikut ini petikan komentar Nyohansiang dan Teguh Karya yang
dipetik dari percakapan mereka dengan wartawan TEMPO, Salim
Said.
Nyohansiang
Saya mula-mula tertarik membuat November 1828 terutama sebagai
orang bisnis. Saya dari dulu ingin membuat film yang lain dari
yang lain. Bukan ranjang dan bukan sadis. Ini mungkin pengalaman
saya membuat film Chicha. Ini betul-betul pengalaman seorang
bisnis. Kalau di satu jalan semua orang jual kembang gula, kalau
saya mau buka toko di sana mestinya jangan jual kembang gula.
Jual roti atau makanan lainnya.
Ide cerita dari Teguh Karya. Dia lebih berat pada aspek seninya,
saya segi bisnis. Pembicaraan lama. Beberapa bulan. Akhirnya
akur. Saya mau karena yakin bisa untung. Pengalaman film Chicha
guru yang baik. Dari modal 80 juta rupiah, bisa kembali jadi 150
juta.
Tadi sudah saya katakan film ini temanya lain dari yang lain.
Tapi yang lebih penting lagi, menurut saya rakyat Indonesia
sekarang ini bimbang. Mau ke mana? Ekonomi maju, pembangunan
jalan. Tapi segi mental? Dalam film ini dicoba kemukakan unsur
patriotisme yang agak realis di tengah-tengah ramainya soal
ranjang dan kekerasan.
Dalam film ini unsur agama juga penting. Saya ini kadang-kadang
bingung. Dulu itu agama Islam selalu berada di depan, seperti di
Aceh, dalam melawan penjajah. Sebagai orang Jawa Tengah, saya
ini mengamati dan berkesimpulan Islam itu bisa membawakan
aspirasi orang-orang tertindas. Tapi sekarang ini kok agama ini
banyak kali hanya diomongkan, tidak diamalkan. Saya ingin
menggugah orang Islam lewat film ini.
Teguh Karya
Suatu kali saya menengok adik saya yang sekolah pendeta di
Malang. Anak itu tadinya penjudi besar. Hanya dengan pengorbanan
besarlah akhirnya yang menjadikan ia pendeta. Pengorbanan adik,
pengorbanan ibu. Ini sama saja dengan pengorbanan keluarga
Kromoludiro dalam November 1828. Saya tertarik membuat film
tentang pengorbanan.
Saya suka sejarah dan selalu berfikir kalau orang dulu bisa
bikin Borobudur, saya tidak percaya sekarang kita tidak bisa
bikin sesuatu yang besar. Kebetulan saya mendapat buku-buku
mengenai Diponegoro. Saya kagum, ternyata pasukan kita hebat.
Saya ingin kisahkan ini, tapi tidak tentang Diponegoro, karena
saya tidak punya ide epis tentang pahlawan ini.
Persamaan dengan lakon Monserrat? Saya tidak cuma dipengaruhi
Emmanuel Robles itu, tapi juga Gandhi, Rizal, kepahlawanan Cut
Nyak Din dll. Kalau secara fisik film saya dikatakan mirip
ceritera Monserrat, itu tidak terlalu penting. Fisik tidak
penting. Lagi pula mungkin hal itu dari bawah sadar saya. Tak
bisa saya elakkan.
Film ini memang diselesaikan sedikit tergesa-gesa. Mengejar FFI
Palembang. Tapi kelambanan yang kau katakan itu bukan tanpa
konsep. Kita tidak mau berkiblat pada nilai dramatik Barat.
Dramaturgi itu ada macam-macam. Ada dramaturgi wayang, randai,
ketoprak. Dramaturgi yang cocok bagi film Indonesia hingga kini
masih terus dicari.
Dalam film ini konflik Van Aken (El Manik) dan de Borst (Slamet
Rahardjo) itu cuma cerita sampingan. Dan sebenarnya cuma untuk
membangun nilai dramatis film ini. Film ini memang multi plot
(mengandung banyak alur cerita), tapi tujuan utama menceritakan
tentang keluarga yang mendapat malapetaka. Kalau konflik Van
Aken dan de Borst diterang-jelaskan, jadinya sebuah cerita baru
lahir. Itu tidak saya kehendaki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini