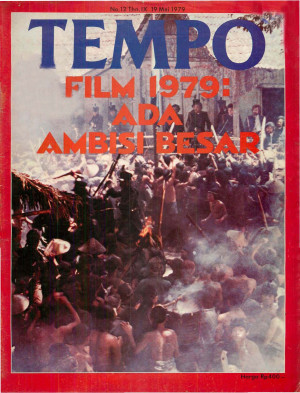TEGUH Karya berkata: "Kalau orang dulu bisa bikin Borobudur,
saya tidak percaya sekarang kita tidak bisa bikin sesuatu yang
besar." Sutradara ini necis, bermuka runcing, berkacamata tipis.
Ia terkenal sebagai orang yang menyukai benda-benda apik yang
kecil. Tapi kali ini rupanya ia pingin berbicara tentang
kebesaran. Dan "besar" memang satu ajektif yang bisa dipasang
untuk filmnya yang pekan lalu menang di Festival Film VII,
November 12.
Setidaknya dalam ambisi dan dalam budget. Film ini digarap
selama hampir setengah tahun. Biaya yang dilahapnya Rp 240 juta.
Penelitian yang mendahuluinya mencapai pelbagai museum di tujuh
kota -- dua di antaranya di Negeri Belanda. Lokasinya dipilih di
sebuah desa di Yogyakarta, desa Sawahan, dan hampir seluruh
penduduk terlibat. Desa itu sendiri tiba-tiba tertolong dari
kemacetan ekonomi, meskipun cuma sementara. Tak heran bila di
mulut jalan yang membelahnya terpasang gagah gapura bambu
bertuliskan "Lokasi November 1828" berwarna merah atas dasar
putih.
Sementara itu, publisitas melancar dengan gesitnya. Jauh sebelum
film ini mencapai setengah, pelbagai koran sudah memuat aba-aba
bahwa satu episode Perang Diponegoro di Jawa Tengah 1825-1830
akan difilmkan. Gambar bintang Slamet Rahardjo memakai uniform
perwira Belanda -- yang cukup meyakinkan -- pun dipasang. Di
sampingnya Yenni Rahman (kali ini tumben tak merangsang) yang
tampil bagaikan gendhuk Jawa tulen. Tak lama kemudian
diberitakan juga bahwa Menteri P&K Daoed Joesoef dan Menteri
Dalam Negeri Malaysia Ghazali Syafei (keduanya tokoh yang suka
kesenian serius) berkunjung ke tempat lokasi.
Ditambah dengan reputasi Teguh Karya di belakangnya, semua itu
menyebabkan orang yakin: November 1828 tak akan mengulangi
kegagalan film Pahlawan Gua Selarong dulu, ketika Ratno Timur
didapuk sebagai Pangeran Diponegoro (seolah-olah pahlawan harus
berwajah ganteng).
Dan syukurlah, November 1828 memang film yang nilainya jauh
lebih di atas. Tapi meskipun hampir sama-sama panjang, film ini
tentunya tak usah dibandingkan dengan Perang dan Damai karya
sutradara Rusia Sergei Bordanchuk yang ingin membuat monumen
tiga jam dari novel Tolstoi yang sudah monumental itu. Kalau
sejauh itu harapan kita, bisa sangat kecewa nanti.
FILM Teguh ini berhasil memperlihatkan pada kita modal banyak
serta kerja penelitian yang lama dan mendalam. Detail film ini
tergarap dengan baik dan begitu teliti.
Sutradara film Indonesia yang lain hampir tak pernah menampilkan
apa yang dicapai Teguh: adat-istiadat zaman yang lampau di Jawa
Tengah, kostum serta properti, semuanya merupakan hidup
kembalinya sebuah dokumentasi yang meyakinkan akuratnya.
Memang ada "bahaya"nya keasyikan dengan benda-benda ini. Teguh
juga nyaris tak lepas dari "bahaya" itu: pada beberapa bagian ia
terasa menonjol-nonjolkan properti yang dihasilkannya, misalnya
alat timba kuno dan payung-payung.
Sebagai akibatnya alur besarnya jadi terhambat. Kisah jadi
terlalu berliku. Teguh Karya mengatakan bahwa filmnya punya
multi-plot atau mengandung banyak alur cerita. Tapi adakah
karena itu ketegangan pokok film ini tak mengalir dengan lancar?
Film ini terasa lebih panjang dari film-film umumnya -- tapi
bukan karena kebesaran masalah yang hendak digarapnya. Di sini
terasa bahwa Teguh, walau ia mampu di bidang lain, belum cukup
kuat untuk menulis skenario. Ia di situ perlu orang lain.
SEBAB faktor yang memikat dari karya Teguh kali ini sama sekali
bukan ceritanya. Tidak sebagaimana lakon Monserrat karya
Emannuel Robles yang termashur itu (yang pernah disadur grup
Teater Populer pimpinan Teguh dengan latar Perang Diponegoro
juga, dan kata orang merupakan jantung November 1828), film ini
tak didukung oleh kejutan atau permasalahan yang memukau. Juga
dialognya tak menampilkan kedalaman. Ia terutama menarik karena
berwarna "rakyat Jawa".
Itu tak berarti film ini hatus ditinggalkan setengah main. Anda
akan kehilangan misalnya adegan yang terbagus dalam film ini
ketika terjadi penembakan di dalam kamar tahanan terhadap tokoh
Kromoludiro (Maruli Sitompul). Tembakan terdengar, kemudian
muncul gambar-gambar di luar rumah yang semuanya terpaku tanpa
bunyi. Anak dioper turun dari kereta. Semua muka memandang ke
dalam rumah dengan penuh anda tanya. Senyap itu menggigit.
Cara ini menjadi konsep pula dalam dramatisasi adegan
selanjutnya. Tapi momentnya tak sebesar saat kemudian
Kromoludiro, sehingga terasa tak sampai. Teguh melakukan ini
barangkali untuk mengatasi kemiskinan variasi adegan, yang hanya
berputar dari ruangan ke ruangan -- paling banter ke halaman dan
sekejap ke luar desa, lalu balik ke halaman. Meskipun ini
cerita kepahlawanan dari sebuah perang besar, wilayh yang
dijangkaunya tidak berhektar-hektar. Di sana kita bergerak
dengan jarak pendek dan dekat -- dari CU ke CU, atau MCU ke MCU.
Kurang sekali long shot. Film jadinya terasa sumpek.
Barangkali memang sulit untuk mengambil gambar jarak jauh di
sebuah lokasi yang sesak oleh penonton di sebuah desa Jawa yang
padat, yang sudah bukan lagi cermin abad ke-19. Atau set yang
disiapkan memang terbatas di markas Kapten De Borst itu saja.
Entahlah. Dengan biaya yang sudah begitu siap besar tentunya
soal teknis itu bisa diatasi. Tapi mungkin sekali struktur
skenarionya sudah begitu rupa terbatas, tak didukung oleh
semangat yang lazim untuk membikin film epis. Karena itu salah
bila dikatakan November 1828 dibikin dengan ambisi spektakuler
Cecil B. de Mille. Film ini belum jauh dari
kepersegi-panjangan sebuah pentas.
TEGUH tampak menyadari hal itu. Ia berusaha memecahkannya dalam
bloking dan akting. Dan sebagaimana dalam filmnya yang lain,
semua pemain berhasil digarapnya. Yenni Rahman sebagai Laras,
puteri Kromoludiro, meskipun tak menunjukkan permainan gemilang,
toh jadi terasa mampu sebagai pemain baik di tangan Teguh --
jadi bukan hanya sebagai penghuni ranjang. Maruli Sitompul, yang
dapat penghargaan sebagai pemeran utama terbaik 11 pekan lalu
untuk perannya dalam film ini, kelihatan bakatnya yang besar.
Tapi sudah waktunya ia dapat porsi karakter yang lebih besar
lagi.
Slamet Rahardjo sebagai Kapten De Borst rasanya sudah bermain
dengan sebaik mungkin. Ia aktor di atas rata-rata dalam dunia
film kita, dan di sini nampak usahanya yang teliti untuk
menjiwai. Namun tokoh yang diwakili Slamet dari awal sudah
terasa sebagai tokoh yang kalah. Hingga ia yang seharusnya bisa
jadi sumber konflik film ini jadi datar saja.
Dalam lakon Montserrat peran seperti dia sungguh dominan. Ia
tokoh penjajah yang kejam, yang bisa membunuh orang tak bersalah
untuk memperoleh pengakuan tentang rahasia musuh. Lawannya
adalah rekannya yang berkhianat kepada korps untuk membela
rakyat yang tertindas. Konflik dalam Montserrat sungguh kuat.
Sayang dalam November 1828 konflik antara Kapten De Borst yang
ambisius dengan Letnan Van Aken (El Manik) yang berpihak kepada
rakyat tak menjadi sesuatu yang sentral. Mungkin sebab itu peran
Slamet kurang "tajam".
Tapi seperti kata Teguh, filmnya tak cuma mau menyoroti perkara
dua perwira Belanda-Indo itu. Ia ingin bicara soal kepahlawanan
lain, Kromoludiro.
Melalui Maruli, Teguh juga ingin menampilkan suasana puitis
lalam kepahlawanan tokoh ini. Pada suatu kali ia tampak terikat
di tiang di dalam rumah, setelah tertangkap pasukan kumpeni
Belanda. Anaknya, Laras, bersimpuh di depannya. Laras telah
ditekan Kapten De Borst supaya Kromoludiro membocorkan tempat
Sentot, panglima pasukan Diponegoro yang mashur itu. Adegan
dimulai dengan tokoh Kromoludiro menembang, kemudian ia
berkhotbah kepada anaknya tentang bagaimana menjadi manusia yang
baik. Suasana puitis ini kita hargai sebagai keberanian
bereksperimen.
Sayang, entah kenapa untuk adegan ini kita terasa kurang
persiapan untuk menerimanya -- mungkin karena tak cukup
dipersiapkan oleh jalan cerita dan suasana sebelumnya. Hingga
kehendak puitis itu tidak luluh ke dalam cerita. Juga tak
membantu menajamkan konflik. Meskipun adegan menembang itu
beberapa kali diulang pada beberapa tokoh, hanya pada tokoh
Bambang Sumpeno (Sardono W. Kusumo) sebagai penari -- tembang
itu bisa terasa "masuk".
Tapi di luar tembang-tembang itu film ini kuat dalam hal musik.
Ilustrasi musik yang dikerjakan Franky Raden (Ini karya pertama
mahasiswa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu) merupakan
contoh penggarapan musik yang berani. Pada adegan-adegan
tertentu, gambar dibiarkannya bicara sendiri. Sedang pada bagian
ketegangan yang memuncak, Franky memasukkan bunyi-bunyi
sederhana dengan ritme yang monoton tapi jadi sangat kuat.
Ilustrasinya mampu menarik gamhar-gambar yang kadang terlalu
"apik" -- jadi lebih berdarah.
DARAH" itu agaknya perlu. Teguh memang tidak membuat sebuah film
perang, meskipun ada adegan perang di akhir cerita. Ia berbicara
tentang kemanusiaan. Namun kemanusiaan itu, yang segera jadi
masalah begitu film mulai, tidak terasa sedang gawat oleh
suasana perang pemberontakan yang melanda desa-desa Jawa selama
tiga tahun. Kita tak dipersiapkan untuk menyaksikan episode yang
brutal dalam sejarah. Bahkan perang sengit yang secara visual
ditunjukkannya di akhir film, lebih terasa molek, tidak
mengiris.
Tapi toh di akhir film ini ada bagian kecil yang menarik sekali.
Waktu itu Kopral Dirun (Mang Udel) dan kawannya -- bekas-bekas
serdadu Belanda yang kalah -- tidak diapa-apakan rakyat. Di
samping kaki Kaptennya yang tewas, mereka bercakap-cakap.
Seorang dari mereka berkata: "Kita ini memang tak berharga.
Hidup boleh, matipun boleh sama-sama tidak dihiraukan."
Selesai menonton film ini, kita tak akan bilang bahwa November
1828 bukanlah film yang dibuat boleh, tidak pun boleh. Ia layak
dihiraukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini