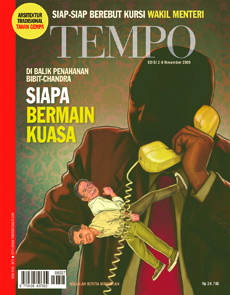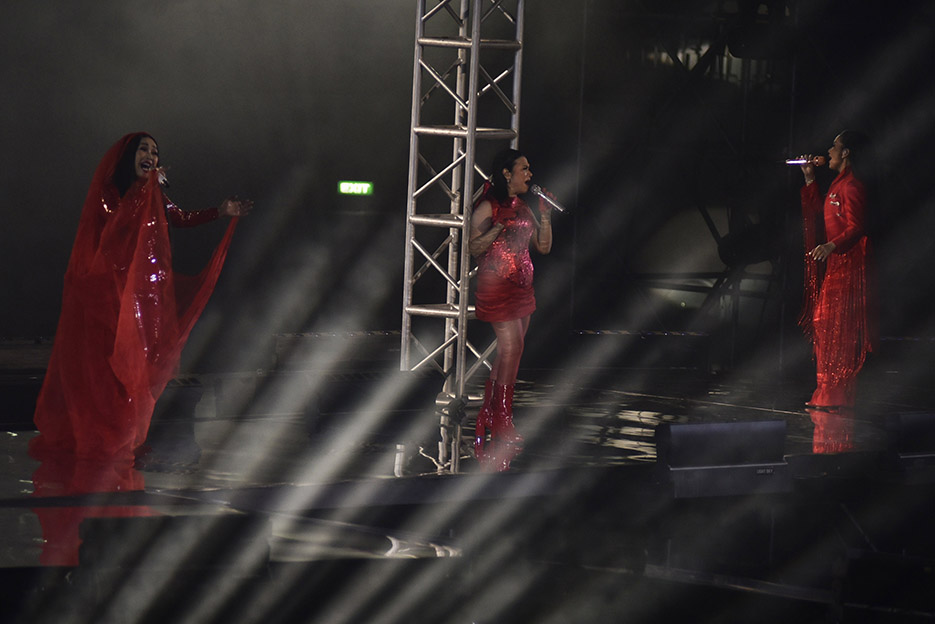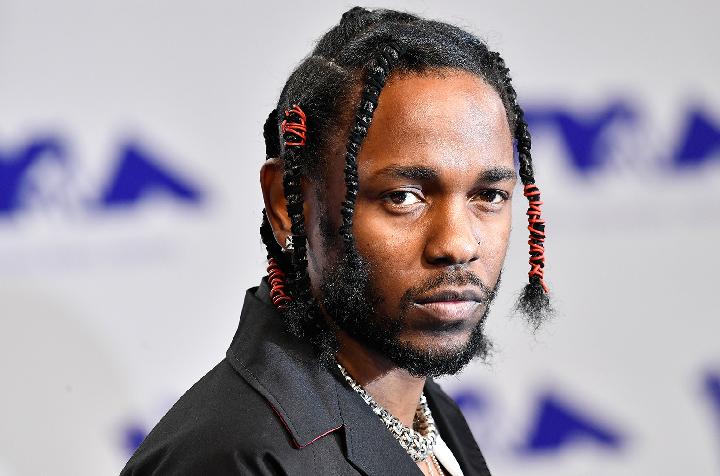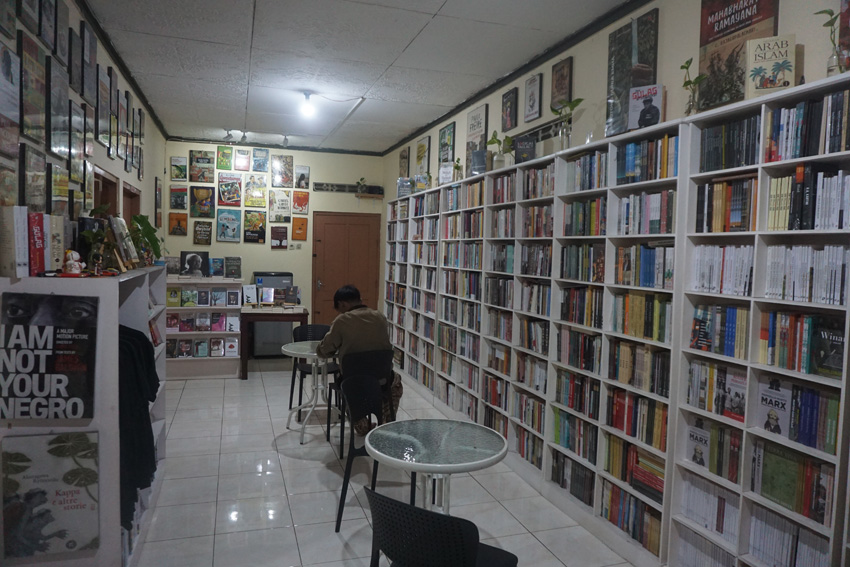Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JARIMIS tenang-tenang saja menatap rumah gadang keluarganya berderak-derak diayun gempa, akhir September lalu. Laki-laki 55 tahun warga Pisang, Kecamatan Pauh, Padang, itu tidak khawatir rumahnya ambruk meski dihajar gempa 7,9 skala Richter. Jarimis pun tak takut tetap berada di dalam rumah ketika gempa, seperti yang pernah dia alami beberapa kali. ”Rasanya seperti naik kapal laut yang terkena ombak saja,” katanya.
Gempa reda. Rumah gadang yang dibangun kakek Jarimis pada 1935 itu tetap tegak. Bahkan di dalam rumah, perabot, seperti lemari dan televisi, tidak bergeser. Hanya beberapa gelas dalam lemari yang posisinya rebah.
Pemandangan kontras terjadi di sebelah rumah gadang itu. Dinding bata sebuah rumah baru runtuh tak kuat menahan getaran gempa. Padahal rumah itu sedang dalam tahap pelapisan dinding bata.
Bukan hanya rumah gadang milik Jarimis yang terbukti kukuh. Rumah tradisional Padang lainnya, seperti yang terletak di Seberang Padang, Kuranji, dan Pauh, tidak mengalami kerusakan fatal. Sedikit kerusakan hanya terjadi pada bangunan tambahan yang berbahan batu bata dan semen, seperti dapur atau tangga. Bangunan tambahan itu rata-rata retak.
Rumah gadang milik Jarimis berupa rumah panggung dengan tinggi dua meter dari tanah, dengan 16 tiang penyangga. Ada empat tiang utama menopang bagian beranda hingga belakang rumah. Dua tiang paling tinggi langsung menopang atap rumah. Ke-16 tiang rumah tidak langsung ditanam di tanah, tapi berada di atas fondasi batu yang datar dengan posisi tiang vertikal. Kayu tidak ditanam agar tidak lapuk.
Bahan dasar rumah hampir keseluruhannya kayu, kecuali atap yang menggunakan seng. Bahan kayu yang digunakan adalah kayu banio yang keras, yang digunakan untuk dinding dan tiang. Seperti halnya rumah-rumah tradisional daerah lain di Indonesia, rumah gadang tidak menggunakan paku atau baut sebagai sambungan sendi-sendi rumah, melainkan pasak kayu yang diselipkan pada bagian pertemuan struktur kerangka utama.
Rumah gadang Jarimis itu merupakan ciri khas tempat tinggal keluarga di pesisir, seperti di Kota Padang, Pariaman, dan Pesisir Selatan. Bangunan yang biasa disebut rumah gadang Padang itu tidak menggunakan atap bagonjong menyerupai tanduk—khas Minangkabau. Atap bagonjong hanya ada di darek atau daerah darat atau pedalaman Minangkabau, seperti Bukittinggi, Payakumbuh, dan Tanah Datar. Namun prinsip utama desain rumah pesisir dan pedalaman sama.
Itulah kearifan lama. Rumah menyesuaikan diri dengan tabiat alam. Materialnya bahan kayu yang relatif ringan dan lentur sehingga tidak akan retak atau runtuh akibat guncangan. Sambungan antarbagian kayu yang fleksibel pun bisa membuat sisi-sisi rumah mengikuti ayunan beban gempa, tidak melawan gaya yang justru memicu kerusakan. Fondasi di atas umpak—tatakan batu berpermukaan rata—juga berperan menghindari potensi patah karena gempa.
Pemeliharaan rumah gadang ini tidak terlalu merepotkan. Rumah milik Jarimis, misalnya, hanya perlu dihuni dan dibersihkan dari debu setiap hari untuk mencegah kerusakan kayu. ”Rumah ini sudah bertahan tiga generasi,” Jarimis membanggakan rumahnya.
Cerita kekukuhan rumah gadang saat gempa di Padang itu menambah daftar bukti kelebihan rumah-rumah adat dibanding yang modern. Fakta serupa dijumpai di Nias ketika dilanda gempa yang disusul tsunami, Maret 2005. Saat itu rumah-rumah roboh. Tapi masih ada kompleks bangunan rumah adat kecil Nias atau omohada yang tetap utuh. Sekitar 600 omohada di Desa Bawomataluo, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, tetap gagah.
Memang, akibat gempa 8,7 skala Richter saat itu, ada juga omohada yang rusak. Seperti yang terjadi pada beberapa omohada di Desa Sihare Sihabili di Gunung Sitoli, yang rata-rata tiangnya patah, dinding kayunya lepas, dan atap rumbia terjatuh. Tapi strukturnya tetap tak goyah. Tak ada bagian rumah yang runtuh menimpa penghuni.
Secara prinsip, desain omohada sama dengan rumah gadang, yakni berupa rumah panggung dengan tiang-tiang kayu sebagai penyangga dengan tumpuan umpak batu. Bahan dasarnya juga kayu dan sendi sambungan dengan teknik pasak. Hubungan antartiang pun tidak dipatok kaku dengan paku, melainkan dengan tali atau dikaitkan saja dengan cara salah satu kayu dikerat untuk pengikat kayu lainnya. Teknik seperti ini biasa disebut knock down atau bongkar-pasang. ”Jadi semacam ada engsel, sambungan kayu tidak kaku,” ujar Yori Antar, arsitek yang gigih menjadi pelestari rumah adat.
Material kayu juga tidak asal-asalan. Untuk tiang, kayu yang biasa digunakan adalah dari pohon laban, yang keras dan besar. ”Biasa diambil menunggu bulan purnama lewat,” kata Pastor Johannes Hammerle, rohaniwan dari Jerman yang sudah tinggal di Nias selama 38 tahun. Dari kacamata ilmu kayu, waktu pengambilan di tengah bulan itu untuk menunggu kadar air dalam pohon rendah.
Dari konstruksi tiangnya, rumah Nias yang besar disokong 35 tiang vertikal dan 12 tiang menyilang. Pada sudut persilangan antara tiang vertikal dan menyilang, dipasang batu sebagai pemberat. Ini dilakukan untuk memperkuat fondasi. Strukturnya tampak rumit, tapi silang-menyilang kayu itulah yang membuat omohada kukuh.
Adapun rumah bagian atas disangga satu tiang utama—yang terpasang dari bawah bersama tiang-tiang penyangga—yang berlanjut ke atas menjadi tiang rumah, seperti dijumpai juga di rumah gadang. Dalam ilmu konstruksi modern, tiang ini berfungsi sebagai inner core, yakni tiang utama bangunan tinggi yang menjadi pegangan struktur bangunan keseluruhan untuk menahan beban guncangan horizontal.
Pulau Sumatera memang berada di atas patahan Sumatera yang melintang dari ujung Aceh hingga ke selatan Jawa. Di sisi barat, terbentang garis pertemuan lempeng Asia dengan Samudera Hindia. Pergeseran kerak bumi sepanjang tahun dapat menimbulkan patahan dan menimbulkan gempa dengan kekuatan sangat besar. Dan itu sudah niscaya.
Rumah-rumah adat, baik di Padang, Nias, maupun daerah lain di Sumatera, sudah menjadi rumah tahan gempa sebelum ada ilmu arsitektur modern. Lihat saja arsitektur rumah adat di enam kabupaten dan kota di sepanjang pesisir barat Sumatera yang rawan bencana gempa tektonik, seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, dan Kota Padang. Mereka lentur dan siap bergoyang bersama lindu.
Sayang, desain rumah adat itu pelan-pelan ditinggalkan orang. Bangunan modern lebih jadi pilihan. Maklum, rumah adat dengan bahan dan teknik asli memang mahal. Pembangunan omohada yang membutuhkan banyak kayu, misalnya, jelas menuntut biaya mahal. Kayu pun tak melimpah seperti dulu.
Dalam hal ini, Yori Antar berpendapat, kearifan lama memang tidak berdiri sepotong-sepotong. Dalam pembangunan rumah berbahan kayu contohnya. ”Dulu begitu anak lahir, orang tuanya langsung tanam pohon, untuk rumah anak setelah besar.” Tapi, semakin modern, orang tidak lagi menanam pohon sebagai investasi atau pengganti pohon yang ditebang, ketika membangun rumah.
Harun Mahbub, Febrianti (Padang)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo