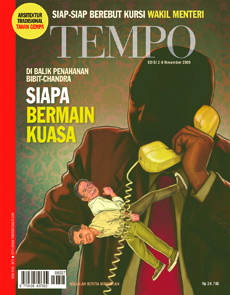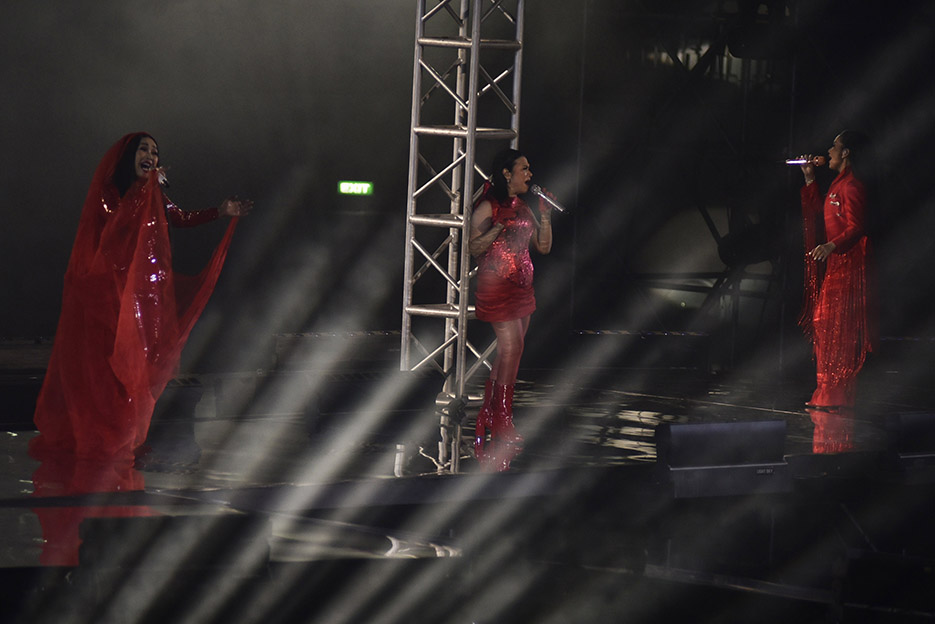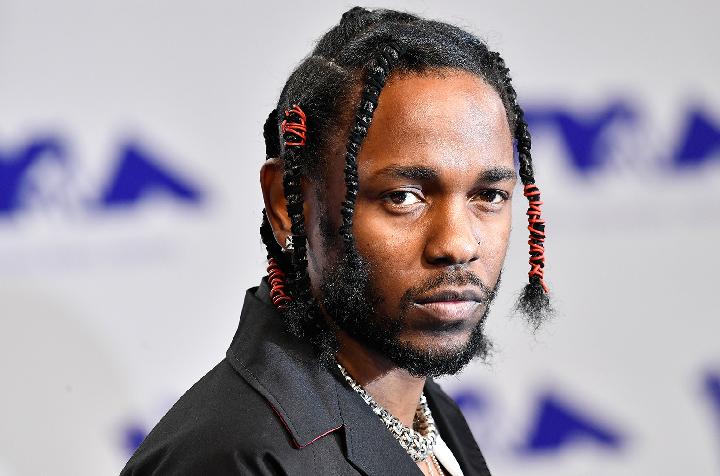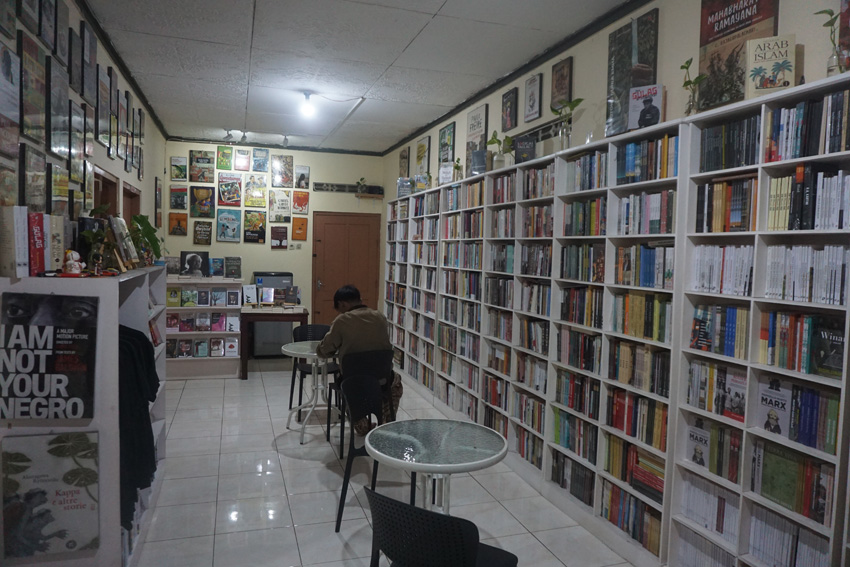Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
RUMAH adat Cikondang itu tetap tegak. Padahal puluhan rumah lain di kampung yang terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, retak dan rusak akibat gempa 7,3 skala Richter pada 2 September lalu. Rumah sepanjang 12 meter, lebar 8 meter, berdinding serat bambu dan atap ijuk itu tetap berdiri, meski rumah tersebut sudah dibangun sejak 1940. ”Bumi (Sunda: rumah) adat kukuh tak rusak sedikit pun, padahal rumah beton di sekitarnya rusak,” kata Ilih Dahsyah, 72 tahun, sesepuh adat Kampung Cikondang.
Rumah adat Sunda itu terletak di kaki Gunung Tilu, di hulu Sungai Cisangkuy yang bermuara ke Sungai Citarum. Bumi yang berdiri di atas lahan tiga hektare itu berbahan kayu, bambu dan ijuk, ada daun kelapa, sirap, dan batu. Rumah yang hanya dimanfaatkan setiap Senin dan Kamis untuk ritual adat dan agama itu berbentuk panggung, mirip rumah adat di Kampung Naga, Baduy di Lebak, Banten, atau Ciptagelar di Sukabumi. Tiang tonggak dibuat dari kayu puspa, kalices, dan albasia, walaupun sebagian pasak kayu dan penguat sendi dari tali ijuk dan bambu sudah berganti paku. Tak ada listrik dan alat elektronik lain di rumah itu.
Ilih mengenang, bumi itu juga kuat digoyang gempa akibat letusan Gunung Galunggung pada 1984. ”Bumi adat bergoyang, tapi goyangannya mengikuti goyangan gempa. Tidak roboh, padahal beberapa tiang penyangga sudah dimakan rayap,” kata Ilih.
Rumah adat itu adalah salah satu yang diteliti arsitek Institut Teknologi Bandung, Sugeng Triyadi dan Andi Harapan. Mereka juga meneliti rumah adat Kampung Naga di Tasikmalaya, juga di Kampung Dukuh dan Kampung Pulo di Garut. Kampung Naga dikenal sebagai komunitas yang menolak segala bentuk modernisasi. Di Kampung Dukuh, rumah adat tersusun bertingkat pada kemiringan tanah. Kampung Pulo dikenal dengan enam rumah adat yang berawal dari satu keluarga pada abad ke-17.
Rumah-rumah adat ini bentuk dan sistem bangunannya mirip. Misalnya lantai rumah panggung setinggi 60-80 sentimeter dari tanah, tiang dari kayu jati atau suren, sambungan yang dikuatkan pen dan pasak, atau diikat tali ijuk maupun rotan. Bahan kayu dan fondasi dari batu kali yang menopang tiang, tanpa direkatkan dengan bahan lain, menjaga rumah tak roboh. Bahkan, seperti kata Ilih, rumah ikut ”menari” bersama gempa. ”Walau gempa melebihi 7,8 skala Richter, saya yakin masih tahan,” kata Sugeng setelah memaparkan penelitiannya di ITB, dua pekan lalu.
Sugeng yakin, arsitektur adat sebenarnya telah melalui uji coba alam hingga diterima masyarakat. Sistematika bangunan, kata dia, utuh dari fondasi hingga atap: menyesuaikan diri dengan material alam sekitar. Kearifan tecermin pada sebutan terhadap rumah dalam bahasa Sunda halus, yaitu bumi. ”Konsep dasar arsitektur masyarakat Sunda adalah menyatu dengan alam,” kata Sugeng.
Bangunan Nusantara, kata pakar arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Josef Prijotomo, tak ditanam ke dalam tanah layaknya rumah modern. Kunci lain yang membuat rumah tradisional tahan gempa adalah bahan kayu yang lentur. Pada sambungan, bahan kayu yang tak dipaku mati sehingga mampu bergoyang. ”Rumah dibiarkan bergoyang mengikuti gempa,” kata Josef.
Josef menyebut warisan tradisi arsitektur ini ”cerlangtara”, singkatan dari ”Cerlang Nusantara”. Ia menolak penyebutan ”kebijakan lokal”. Alasannya, pada masyarakat yang mengidentifikasi diri dengan identitas ”global”, yang lokal itu dipandang tertinggal. ”Padahal warisan tradisi ini menunjukkan kejeniusan kita,” kata Josef.
Salah satu bukti kejeniusan itu, rumah-rumah adat Nusantara terbukti tanggap terhadap gempa. Tak hanya rumah Sunda dan Jawa. Josef menunjuk gempa Tarutung berpuluh tahun lalu. Rumah adat Batak tak hancur. Sebab, rumah itu didudukkan di atas tiang-tiang yang ditanam di kaki rumah, tak disambung. Gempa hanya menggelincirkan bangunan. Seusai gempa, tinggal dikembalikan ke posisi semula.
Josef pun menyarankan untuk kembali membangun dengan cara adat: jangan ditanam ke tanah. Fondasi, dia melanjutkan, adalah ilmu konstruksi Eropa, yang hanya sesuai dengan kebutuhan di sana.
Josef memang dikenal sebagai arsitek yang mengkaji khazanah adat. Dia menjabarkan berbagai bab tentang petungan (perhitungan) dari primbon Jawa yang terkait dengan adat membangun rumah. Petungan itu, misalnya, terkait dengan pemilihan hari, ukuran tiang, jenis kayu, yang disesuaikan dengan hitungan hari lahir pemilik. Maknanya, kata Josef, aturan itu justru tak mengurusi fisik bangunan, tapi manusia yang tinggal dalam bangunan itu, beserta segala cita-cita, mimpi, dan perilakunya.
Perhitungan semacam itu masih relevan hingga kini. Ina Edial, 43 tahun, penduduk Yogyakarta ini, misalnya, usai lindu 2006, memutuskan membangun rumah kedua di Desa Candi, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta, murni berdasar perhitungan primbon. Ina membangun rumah limasan. Diapit rumah tetangga bertembok tinggi, rumahnya yang berwarna cokelat alami dari bahan kayu jati terlihat membumi, meski masih dipadu bangunan semi-modern berbahan beton dan bata.
Rumah limasan itu ”ditebus” Rp 5 juta dari bongkaran rumah warga di Kulon Progo. Ina memilih limasan agar bisa ditambah kamar, kamar mandi, dan dapur sebagai satu kesatuan. Ia tak memilih rumah joglo yang menjulang, karena bangunannya cenderung menyempit.
Lindu memang telah membuat rumah pertama Ina yang berada di pusat kota retak-retak sehingga harus direnovasi. Nah, ketika menjadi relawan gempa itulah, Ina menyadari rumah bertembok bata dan beton justru remuk, sedangkan rumah adat aman karena lebih lentur mengikuti guncangan.
Ina percaya, tradisi tak sekadar mitos. Tetua dulu, dia meyakini, membangun rumah yang strukturnya sesuai dengan kondisi geografis—gempa sudah menggoyang Jawa sejak dulu. ”Rumah seperti joglo, limasan, pasti bukan asal buat, tapi ada alasan kuat,” ujar dia.
Ibnu Rusydi, Anwar Siswadi, Alwan Ridha Ramdani (Bandung), Bernarda Rurit (Yogyakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo