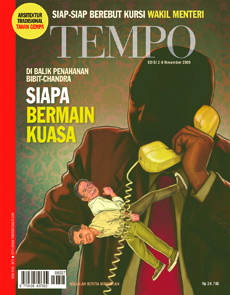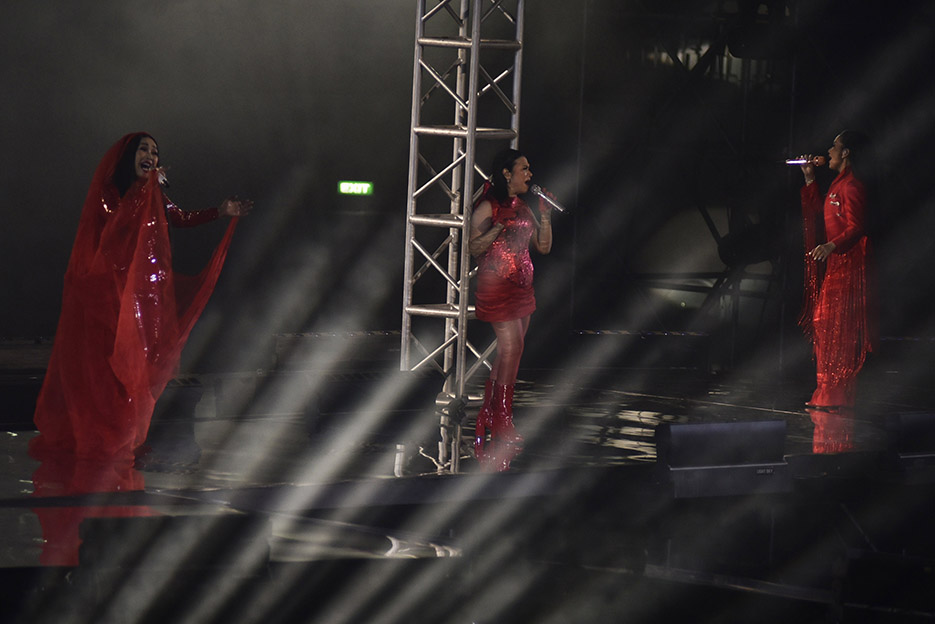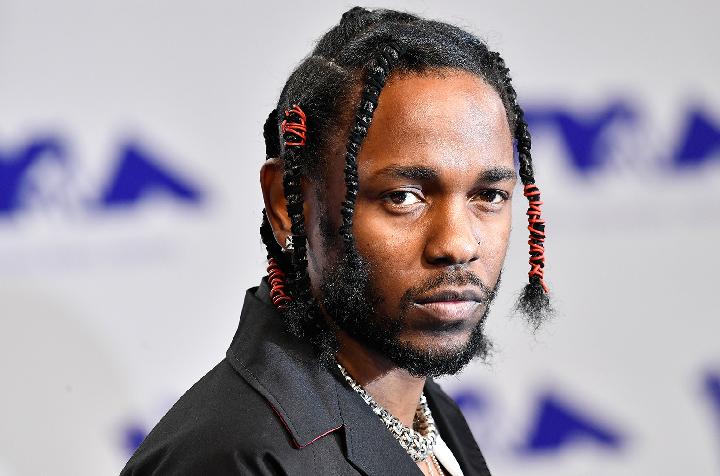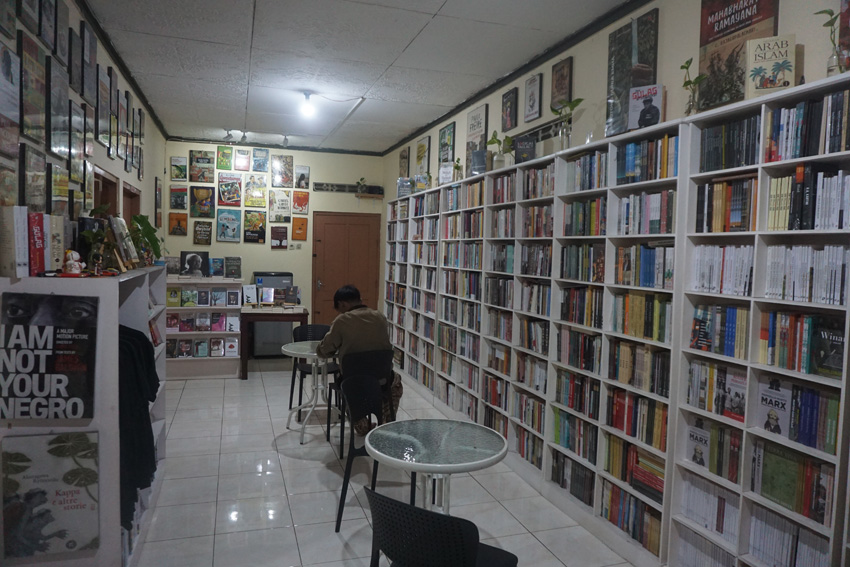Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEMBILAN puluh persen mahasiswa arsitektur semester awal ternyata belum pernah ke Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Itulah fakta yang ditemukan Josef Prijotomo, profesor pengajar arsitektur di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebagai arsitek ahli rumah tradisional, Josef memang sengaja mengajukan pertanyaan sederhana itu kepada mahasiswa semester awal. Dia ingin menakar seberapa banyak pengetahuan mahasiswa tentang arsitektur rumah tradisional.
Setelah mengunjungi Taman Mini, mereka rata-rata berpendapat, rumah asli Indonesia sangat eksotis. Tekniknya pun canggih. Dan, setelah mereka paham pada kelebihan arsitektur lokal, ”Ini memang saatnya mereka dikenalkan pada arsitektur dua musim, bukan yang empat musim,” kata Josef.
Josef, yang sudah mendalami arsitektur tradisional Jawa sejak 1983, punya harapan: jangan sampai calon arsitek lebih mengenal gaya arsitektur Barat, seperti yang banyak dibangun di perumahan mewah,tapi tidak mengenal gaya arsitektur yang selama ini sudah ada di bumi Nusantara.
Pemahaman akan arsitek rumah tradisional makin relevan setelah serial gempa mengempas bumi Indonesia. Topik mengenai bangunan tahan gempa menjadi pembahasan menarik di antara arsitek, juga masyarakat umum. ”Tahan gempakah rumah kita? Apakah bangunan rumah mewah mampu bertahan dari guncangan lindu?” Pertanyaan seperti itu kerap muncul. ”Padahal jawabannya justru ada di sekitar kita, sejak dulu,” tutur Josef.
Rumah tradisional di daerah rawan gempa terbukti tahan gempa. Bangunannya mirip: rumah panggung; penyangga tak ditanam tapi berdiri di atas umpak—tatakan batu berpermukaan rata—terbuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar; sambungan dilekatkan dengan pasak atau tali. Intinya, struktur bangunan dibuat fleksibel sekaligus mampu meredam getaran vertikal, horizontal, dan lateral gempa. ”Bila gempa, rumah menari,” kata Josef.
Sebagai contoh adalah pengalaman Jarimis, penduduk Desa Pisang, Kecamatan Pauh, Padang, yang tidak khawatir rumah gadangnya ambruk meski dihajar gempa 7,9 skala Richter, September lalu. Jarimis menganggap gempa bukan ancaman bagi tempat tinggal yang sudah dibangun sejak 1935 itu. Dia pun tak takut tetap berada di dalam rumah ketika gempa—seperti yang pernah dia alami beberapa kali. ”Rasanya seperti naik kapal laut yang terkena ombak saja,” katanya (lihat ”Belajar dari Omohada dan Gadang”).
Begitu juga ketika lindu mengguncang beberapa daerah di Jawa. Rumah adat Sunda yang terletak di kaki Gunung Tilu, di hulu Sungai Cisangkuy, itu tetap berdiri. Rumah panggung dari bahan kayu puspa, bambu, ijuk, daun kelapa, sirap, dan batu itu masih bertahan meski pernah dihajar gempa ketika Gunung Galunggung meletus pada 1984. ”Bumi (Sunda: rumah) adat bergoyang, tapi goyangannya mengikuti gempa. Tidak roboh, padahal beberapa tiang penyangga sudah dimakan rayap,” kata Ilih Dahsyah, 72 tahun, sesepuh di sana (lihat ”Bumi Kukuh Meski Bumi Guncang”).
Josef yakin, teknologi membangun rumah tradisional yang diajarkan turun-temurun itu tetap relevan dengan kondisi sekarang. Karena bangunan tradisional telah terbukti bisa melewati berbagai zaman hingga kini. Relevansi yang paling mudah, menurut Yori Antar, arsitek yang tekun melestarikan rumah tradisional, adalah nilai ramah lingkungan dan lestari pada rumah tradisional. Ramah lingkungan, karena bangunan menggunakan material lokal yang ada di sekitar; dan lestari karena si pemilik rumah akan menanam pohon atau bambu pada saat membangun rumah untuk bahan baku rumah anak-cucu mereka.
Teknologinyalah yang perlu dipelajari, meski itu tidak mudah. Untuk tiang omohada yang terbuat dari kayu laban, misalnya, pohonnya harus ditebang pada saat bulan muncul. ”Itu menunggu kadar airnya berkurang,” ujar Romo Johannes Hammerle, rohaniwan dari Jerman yang sudah tinggal di Nias selama 38 tahun. Teknik tebang menunggu bulan muncul juga berlaku untuk beberapa jenis kayu lain, termasuk bambu.
Kerumitan rumah Nias terletak pada tiang penyangganya. Ada 35 tiang vertikal dan 12 tiang menyilang, dan masih ditambahkan batu sebagai pemberat. Ada juga, satu tiang utama yang terpasang dari bawah bersama tiang-tiang penyangga, dan berlanjut fungsinya sebagai tiang rumah. Dalam ilmu konstruksi modern, tatanan seperti itu berfungsi sebagai inner core, tiang utama bangunan tinggi yang menjadi pegangan struktur bangunan keseluruhan. ”Rumit,” komentar Yori.
Bila ingin memahami cara membangunnya, kita harus belajar dari penduduk setempat. Menurut Yori, ahli yang lebih tua mengajarkan kepada anak-anak muda. Bila tidak belajar dari ahli setempat yang benar, dipastikan akan terjadi kesalahan dalam membangun rumah tradisional. ”Jadi, butuh penelitian serius untuk memahami rumah tradisional,” kata Josef.
Seperti yang dilakukan dua arsitek Institut Teknologi Bandung, Sugeng Triyadi dan Andi Harapan. Mereka meneliti rumah adat di Jawa Barat, seperti rumah adat Sunda, Kampung Naga di Tasikmalaya, juga di Kampung Dukuh dan Kampung Pulo di Garut. Mereka menemukan kemiripan bentuk dan sistem. Semuanya berupa rumah panggung setinggi 60-80 sentimeter dari tanah, tiang dari kayu jati atau suren, sambungan yang dikuatkan pen dan pasak, atau diikat tali ijuk maupun rotan. ”Walau gempa melebihi 7,8 skala Richter, saya yakin masih tahan,” kata Sugeng setelah memaparkan penelitiannya di ITB, dua pekan lalu
Itulah kearifan lokal: rumah menyesuaikan diri dengan tabiat alam. Materialnya dipilih dari bahan kayu yang relatif ringan dan lentur sehingga tidak akan retak atau runtuh akibat guncangan. Untuk rumah Jawa lain, seperti joglo, limasan, panggangpe, kampung, juga menggunakan materi fleksibel yang tersedia, seperti kayu jati, nangka, tahun, glugu, dan bambu.
Sambungan kayu atau bambu dibuat luwes, sehingga sisi-sisi rumah dapat mengikuti ayunan beban gempa, tidak melawan gaya yang justru memicu kerusakan. Umpak—tatakan batu berpermukaan rata—tempat berdirinya tiang, juga berperan menghindari potensi patah karena gempa. Josef menyebut rumah tradisional itu tidak ditanam di dalam tanah tapi duduk di atas tanah.
Penelitian lain juga dilakukan Departemen Pekerjaan Umum. Ditulis dalam buku tentang rumah tradisional: Konstruksi Indonesia Karya Anak Bangsa Teknologi Rumah Tahan Gempa, yang diterbitkan pada 2007. Di dalamnya dimuat kajian tentang rumah Jawa joglo, rumah gadang, rumah Nias, rumah Bengkulu, rumah bubungan tinggi Kalimantan Selatan, rumah tongkonan Toraja, rumah lawi Minahasa, dan rumah honai Papua.
Semuanya punya keunikan dan kerumitannya sendiri. Arsitek dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yulianto P. Prihatmaji, misalnya, menyumbang kajian tentang joglo di dalam buku tersebut. Kesimpulannya, joglo sangat aman dan stabil terhadap serangan gempa. Teknik sambungan umpak dengan saka guru (tiang besar), dan kaitan bagian atas—saka guru, blandar, sunduk—mampu mengurangi getaran gempa sekaligus menstabilkan bangunan.
Kejeniusan teknik bangunan tradisional itulah yang membuat Yori ingin belajar arkeologi. Apalagi setelah dia menjelajahi beberapa daerah untuk mempelajari dan ikut membangun beberapa jenis rumah adat. ”Sikap arsitektur kita memang harus berubah dari style ke yang berorientasi lingkungan lokal,” kata Yori.
Josef berpendapat serupa. Dia sejak semula yakin bahwa primbon dalam pembuatan rumah di Jawa—biasa disebut petungan atau perhitungan—masih relevan untuk menjawab persoalan arsitektur modern. Itulah mengapa, menurut dia, seorang arsitek harus juga mempelajari cerita rakyat atau folklore. ”Sebelum ada tulisan, ilmu diturunkan melalui cerita,” katanya.
Bina Bektiati
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo