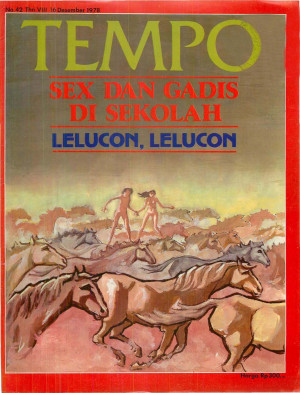SETIAP akhir tahun, baik dosen maupun mahasiswa LPKJ mengadakan
pameran sendiri-sendiri. Tapi kali ini, pameran dua kelompok itu
diadakan persis serentak (5-11 Desember), walaupun tidak di
ruang yang sama. Para dosen di Ruang Pameran TIM dan disponsori
Dewan Kesenian Jakarta. Para mahasiswa di Galeri LPKJ, di
belakang TIM, dengan biaya patungan. Pembukaan kedua pameran ini
hanya terpaut setengah jam: untuk yang mahasiswa jam 19.00,
untuk yang dosen jam 19.30.
Yang Mahasiswa
Dengan sekitar 130 karya seni rupa galeri kecil di belakang TIM
itu tak bisa mewadahi semuanya. Maka ada lukisan yang dipasang
di dinding-luar, ada pula patung yang di plaza. Jadinya suasana
lebih meriah. Tapi ini memang karya para mahasiswa -- yang
pengalaman berkaryanya relatif masih singkat. Di antara 130
karya itu sendiri memang susah dicari yang melegakan. Kalau
tidak karena tekniknya belum memadai, sebuah karya yang nampak
berhasil ternyata banyak sekali mirip dengan karya seniman yang
sudah jadi.
Ada karya non-figuratif dengan teknik mencipratkan cat mirip
karya Jackson Pollock -- jagonya action painting Amerika Serikat
-- yang dibaringkan di lantai. Anehnya, kalau kita sudah nonton
pameran dosen LPKJ di Ruang Pameran, memang bisa ada kesan kalau
lukisan ala Pollock itu seperti mengejek lukisan seorang dosen
yang juga mirip karya Pollock. Ialah lukisan Sardono W. Kusumo
-- bukan dosen seni rupa, memang.
Lalu ada patung yang mirip patung primitif Kalimantan. Bahkan
seorang dosen LPKJ salah anggap: mengira benda itu dibawa
mahasiswa LPKJ yang beberapa bulan lalu mempelajari kesenian
rakyat Kalimantan. Agaknya bakat mahasiswa itu memang besar,
sehingga bisa membuat patung primitif mirip benar dengan
aslinya. Ini harapan pertama.
Harapan kedua bisa dilihat pada sebuah patung bambu: tiga batang
bambu masing-masing terdiri dari tiga-empat ruas, bagian
atasnya dibelah, dibentuk seperti jari-jari tangan mengembang.
Memang tak begitu baik. Tapi ide bahannya -- bambu itu -- unik
jugalah (seingat saya belum pernah ada patung bambu). Dengan
sedikit ketekunan, mungkin bisa ditemukan satu bentuk khas
patung jenis itu -- murah, dan berakar pada budaya kita sendiri.
Yang Dosen
Para dosen tentu saja menyuguhkan karya yang lebih pas, lebih
siap ke "pasaran." Teknis tak perlu lagi diomongkan. Tapi toh
tak ada karya yang menukik dan menyuguhkan kemungkinan yang
jauh. Memang ada Srihadi -- yang sudah kita bicarakan dua minggu
lewat. Ada karya Danarto yang merupakan hiasan murni, yang
menyobek batas antara patung, lukisan dan benda pakai.
Karya yang terdiri dari bidang-bidang putih disusun tiga dimensi
itu, kiranya sangat dipengaruhi pengalaman Danarto membuat
disain panggung sandiwara (untuk Arifin C. Noer atau Rendra).
Lalu ada karya Priyanto S., yang menggambar serangga: rapi,
indah. Ini tentu kelanjutan pameran PERSEGI yang lampau -- yang
mengajukan gagasan bahwa gambar pun patut dihargai setingkat
dengan jenis seni rupa yang lain.
Yang memang pantas diketengahkan karena memang belum pernah
dipamerkan -- di Jakarta paling tidak -- adalah karya G.
Sidharta. Sebuah patung kayu, tinggi sekitar 3 meter, berwarna,
ada bagian yang ditempeli kaca. Menggambarkan seorang dewi lagi
menangis -- judulnya memang begitu Tangisan Dewi Batari
Warna-warna merah-biru-putih, kemulian tangannya yang menyilang
dada, lalu rambutnya yang menjurai ke bawah dan gambar air mata
yang menitik, memang mengesankan seorang yang agung (bukan
manusia) sedang berduka.
Sementara itu Jim Supangkat masih sadis: mengurung patung wanita
telanjang yang dibalut goni dalam sebuah kotak, lalu menggantung
empat kepala manusia yang juga dibalut karung goni pada satu
rantai.
Pameran ini sudah rutin. Itulah barangkali yang menyebabkan para
pesertanya juga tak ingin mengetengahkan karya andalan. Datar
saja.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini