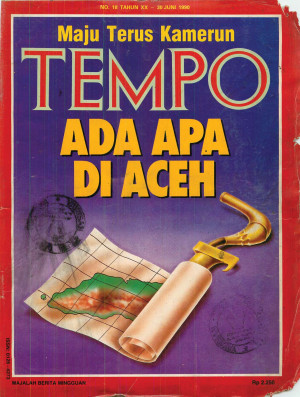SEDHENGING sasi purnama sidhi, Wong Ayu lekas ambathik sinjang. Gawangan alam jembare, bandhul sentiging kalbu, wewajane semuning kandhil, malame rasa jatya, dene lancengipun, manikem paworing rasa, canthing kalamullah kalam kang linuwih, polanipun ingaras ... (Kini saat terang bulan, wahai Putri Ayu, mulailah membatik kain. Gawangan ibarat alam luas, bandul menjadi pedoman hatimu. Wajan menjadi wadah, lilin malam ibarat rasamu sejati. Sedang lilin lanceng bagai manikam yang melengkapi rasa batin. Cantingmu adalah Kalamullah, kalam yang sangat utama, pola itu petunjukmu ...). Suluk Prawan mBatik oleh Astuti Hendrato Darmosugito. MEMBATIK, bagi kalangan wanita keraton di Jawa bukanlah sekadar mencoretkan lilin malam cair di atas sehelai kain dengan pola-pola yang sudah tersedia. Membatik tanpa memahami kawruh kajaten atau ilmu hidup, konon, tidak bisa menghasilkan apa-apa selain menggambar belaka di atas kain mori. Karenanya, seperti juga seni sastra, karawitan dan seni tari yang menekankan keselarasan, membatik bagi orang Jawa lebih merupakan olah batin sebagai sarana kesempurnaan hidup mereka. Pada pembuatan pola-pola sakral, misalnya Parang Barong, yang diperuntukkan bagi Sultan dan leluhurnya, setiap tarikan garis harus ditulis dengan satu tarikan napas, yang membutuhkan pemusatan daya lahir dan batin yang luar biasa, agar tak terputus. Kesempurnaan penggarapan dari kedalaman rasa seperti itulah memancar dari pameran "Sekaring Jagad Ngayogyakarta Hadiningrat" yang disuguhkan oleh Himpunan Pencinta Kain Batik dan Tenun Wastraprema, bekerja sama dengan pihak Keraton Yogyakarta, 19-23 Juni yang lalu di Manggala Wana Bhakti, Jakarta. Orang memang masih boleh meributkan asal usul batik. Kemungkinan dari India atau Cina, bahkan Afrika. Namun, kenyataan yang tak bisa dipungkiri adalah batik menemukan kesempurnaan teknik garapan dan kecanggihan polanya di tanah Jawa. Memasuki ruang pameran yang ditata dengan titik pusat pandangan pada koleksi dari Keraton Yogyakarta, dengan koleksi Pura Pakualaman dan pribadi di luar keraton sebagai pendampingnya, terasa suatu penyuguhan materi yang langka. Di situ dihadirkan kain-kain adati yang tidak bisa begitu saja dikatakan anggun dan indah. Tepat di titik pusat ruang tergelar sebuah kain Kampuh atau sering juga disebu Dodot (buatan sekitar 1939), yang merupakan unsur terpenting dari busana Sultan dalam upacara jumenengan atau pada pisowanan agung untuk dikenakan di sekitar pinggang, di atas celana dari kain cindai. Berwarna cokelat soga dan latar putih terang dalam motif Parang Rusak Barong berukuran 4 kali 3 meter, kain ini memilik tengahan berwarna biru kelam, berhiaskan tepi pola cemukiran yang seakan ratusan mata keris menghunjam ke pusatnya. Garang dan menggetarkan, namun sekaligus berwibawa dan terkendali. Kendali emosi yang tinggi juga tercermin pada kain-kain milik dari kerabat keraton, seperti Ceplok Nitik Kasatriyan yang serba rumit koleksi B.R.Ay. Murdaningrat, menantu Hamengku Buwono VIII. Juga pada Parikesit, yang kelihatannya bersahaja yaitu kain motif parang tanpa bunga, namun sangat bersih hingga pengulangannya terasa memiliki irama yang "hidup", koleksi R.Ay. Hambardjan, cucu Hamengku Buwono VII. Meski kita kenal bahwa ciri khas dari kain batik Yogya adalah latarnya yang putih bersih dan polanya yang cenderung geometrik, kalau tidak bisa disebut kaku -- bila diban- dingkan dengan batik gaya Surakarta, misalnya, yang lebih luwes dan floral dengan latar kuning gading -- ternyata hal itu tidak berlaku bagi kain yang berasal dari Pura Pakualaman. Pertautan kerabat dengan Keraton Surakarta Hadiningrat dengan menikahnya Sri Paku Alam VII dengan putri dari Susuhunan Paku Buwono X, yang konon berkepribadian kuat, memberi warna tersendiri pada kain dari Pura Pakualaman yang merupakan paduan dari gaya Yogyakarta dan Surakarta, yaitu serba bersih dan manis, misalnya kain Putri Sekar Kepel dengan garis-garisnya yang serba meliuk, buatan sekitar 1930. Bahkan sebuah kain kampuh yang sakral dalam upacara perkawinan, Bangun Tulak Pradan Alas-alasan, dengan gambar dari prada emas binatang seisi hutan seperti banteng, kijang, dan sebagainya, tampil ringan dan manis pula. Seni batik tulis klasik yang diwarisi oleh keraton memang masih berfungsi dalam alam kehidupan yang masih berupaya memegang teguh adat-istiadat itu. Terutama berhubungan dengan daur hidup seperti upacara khitanan ataupun pernikahan -- seperti yang dipergelarkan sebagai kegiatan pendamping pameran -- serta tata kehidupan seremonial di situ, kendati berkecamuk budaya baru yang lebih bebas menggelora di luar benteng keraton. Menjadi pertanyaan sekarang adalah, masihkah bisa dilahirkan karya-karya dengan restraint dan yang begitu tinggi, sebagai semangat pengabdian dan penyerahan yang total pada "hukum alam" bila titik orientasi telah bergeser. Ananda Moersid
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini