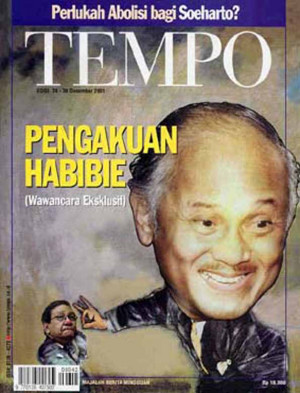SEBUAH kamera di balik mata Kemal Jufri akan meniupkan roh keberanian. Hasilnya adalah rekamannya yang berbicara dengan lantang di dalam dan di kulit muka media kaliber internasional seperti Time, Newsweek, Asiaweek, The New York Times, Business Week, dan Far East Economic Review.
Rekaman itu berupa tubuh-tubuh tanpa nyawa, darah yang mengalir, suara-suara yang mengerang, pertikaian demi pertikaian etnis di Sampit, Timor Timur, Jakarta, Ambon. Semua melibatkan darah dan peluru, dan juga luka-luka serta setumpuk energi untuk berlari karena dikejar milisi. Tapi kamera itu seolah menjadi sebuah tameng bagi Kemal untuk mampu merekam di balik lensa. Tanpa kamera itu, ”Saya pasti pusing dan pingsan. Biasanya, saya lemas melihat darah,” tuturnya jujur kepada TEMPO, ”Tapi, jika ada di balik lensa, aku tak merasa begitu. Enggak tahu kenapa.”
Karena kamera itu adalah nyawa bagi dirinya, tak aneh jika pada 1999 Kemal diganjar Award of Excellence dari Picture of the Year (POY) di Amerika Serikat—organisasi yang berpusat di Missouri yang memberikan penghargaan semacam World Press Photo (versi AS).
Lahir di Jakarta pada 7 Juni 1974 sebagai anak kedua pasangan Fikri dan Annisa Jufri, Kemal menemukan kamera dan fotografi sebagai sebuah takdir. Lulus sekolah menengah di Hawaii, AS, Kemal berkunjung ke Galeri Foto Jurnalistik Antara pada 1994 dan bertemu dengan kuratornya saat itu, Yudhi Soerjoatmodjo. Fotografer Oscar Motuloh-lah yang memperkenalkan kamera dan foto jurnalistik melalui buku-buku karya fotografer internasional. ”Aku itu sebelumnya sama sekali buta memotret,” ujarnya.
Bermodalkan kamera klasik Pentax 4000 dengan satu lensa f50, tanpa flash (lampu kilat/blitz), Oscar menugasi Kemal menyusuri jalan-jalan Jakarta untuk sebuah masa magang di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Hasilnya memuaskan dan anak magang ini malah menerima honor dari foto-foto buatannya. Berikutnya, Kemal menimba ilmu dengan mengikuti workshop esai foto bimbingan Yudhi Soerjoatmodjo di Galeri Foto Jurnalistik Antara. Dari sini, Kemal mulai ikut pameran. Garapannya untuk pameran kedua Kota Kita adalah tentang para profesional muda di luar topeng-topeng kerjanya. Kemal, yang mestinya pulang ke Hawaii untuk melanjutkan pendidikannya, malah larut dalam dunia foto jurnalistik.
Apalagi, bersama Rama Surya, ia kemudian mendapat kesempatan menjadi asisten Sebastio Salgado. Saat itu, fotografer legendaris asal Brasil ini berkesempatan mengambil gambar di Jakarta. ”Aku praktis jadi translator, researcher, porter, jadi macam-macam, deh,” demikian ia mengenang. Pengalamannya selama satu bulan membawanya ke sebuah kesimpulan, ”Cara Salgado memotret sih sama aja dengan aku atau fotografer lainnya. Tapi dia itu gigih betul dalam bekerja.” Ia menambahkan, ”Aku belajar bahwa untuk mendapatkan karya yang benar-benar baik, kita harus bekerja keras.”
Pengagum fotografer James Natchwey, Sebastio Salgado, Eugene Richards, dan—tentu saja—Oscar Motuloh ini sesungguhnya masih dihinggapi keinginan untuk menempuh pendidikan formal dalam fotografi di New York. Tapi, ketika ia memperbincangkan niatnya itu dengan fotografer termasyhur James Natchwey, yang diajak ngobrol malah bingung. Natchwey mengatakan, ”But Kemal, you are already beyond that!” Menurut dia, Kemal harusnya malah mengajar di sana. Natchwey malah menyarankan agar Kemal terus berkarya dan belajar lewat buku.
Sebagai fotografer, Kemal mengaku lebih senang bekerja freelance ketimbang menjadi pegawai tetap. Sekalipun tidak saban bulan menerima gaji, ia merasa lebih bebas dalam memilih berita yang hendak ia garap. Saat ini, bersama Dina Purita Antonio—jurnalis asal Filipina—Kemal mendirikan agen foto Imaji, yang bercita-cita mengumpulkan fotografer dan penulis freelance dalam sebuah wadah, sejak Maret 2001. Proyek yang sedang mereka garap berdua adalah buku mengenai ”Children of East Timor”, yang akan diluncurkan pada pertengahan 2002.
Yusi A.P., Gita W.L.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini